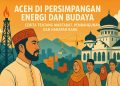Oleh: Juanda Djamal
Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Besar (2019-2024).
Meneropong Aceh dari Tugu Monumen Nasional, ribuan mil jauhnya, di ujung gugusan kepulauan Sumatera-Nusantara, namun kalau kita berdiri tegak di depan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, maka tampak “Aceh” begitu megah dan beradab, bahwa kita berada pada geografis yang strategis yang dikelilingi oleh Selat Malaka dan Samudera Hindia. Dua perairan ini selain menjadi lalu lintas dunia yang dilayari ratusan dan bahkan ribuan kapal setiap harinya, juga memiliki potensi perikanan yang sangat kaya. Potensi sumber daya laut dengan beragam jenis ikan dan biota, memiliki pantai yang bersih nan indah, juga memiliki potensi sumber daya mineral dalam lautan biru.
Gugusan kepulauan sepanjang Samudera Hindia, pulau Banyak, Simeulue, Pulo Aceh, dan Pulau Weh merupakan jalur migrasi ikan tuna sebelum kembali ke perairan Samudera Pasifik, sehingga keberadaan kepulauan Andaman yang berbatasan langsung dengan Pulau Weh memiliki kandungan ikan yang sangat kaya. Selain memiliki potensi laut juga memiliki potensi sumber daya mineral, minyak dan gas, terdapat beberapa blok minyak lepas pantai (offshore) di sepanjang perairan Pidie sampai ke perbatasan Sumatera Utara dan perairan pantai Barat Selatan memiliki kandungan yang jauh lebih tinggi. Demikian pula di daratan (onshore), potensi sumber daya minyak dan gas jauh tersebar di kawasan Timur, Tengah-Tenggara, dan Barat-Selatan. Selain kandungan sumber daya mineral dilautan, daratan Aceh juga sangat kaya minyak dan gas serta tambang lainnya seperti biji besi, emas, tembaga, batu bara, nikel, dan sebagainya. Termasuk potensi sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti lahan persawahan, perkebunan dan memiliki hutan lebat. Bahkan hutan Aceh masuk dalam dua hutan dunia yang dilindungi yaitu pegunungan Leuser Aceh.
Kebijakan Pengelolaan SDA Aceh
Rezim Suharto mengisolasi Aceh dengan menghapuskan status Sabang sebagai free port dan dipindahkan ke Pulau Batam. Selanjutnya pembagian hasil migas Arun tidak jelas, gap sosial yang terlalu timpang menyebabkan perlawanan rakyat Aceh tidak dapat dihindari, rakyat Aceh kembali memanggul senjata, Suharto meresponnya dengan memberlakukan daerah operasi militer (DOM) awal tahun 1990.
Presiden BJ Habibie memiliki kebijakan yang demokratis, dengan menetapkan kebijakan membangun kembali fondasi “Kebangkitan Aceh” setelah 30 tahun terpuruk dalam dinamika kegelapan politik yang luar biasa. BJ Habibie mencabut status DOM Aceh pada 8 Agustus 1998, selanjutnya membentuk desk Aceh yang bertugas untuk menyelesaikan konflik Aceh. Salah satu kebijakannya adalah mengesahkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh pada 4 Oktober 1999. Pada BAB II diatur tentang kewenangan. Meski pun kewenangan yang diberikan hanya untuk mengatur keistimewaan, namun undang-undang ini memberikan kanal baru regulasi Aceh. Kita dapat bayangkan, ikrar Lamteh di pengujung berakhirnya pergerakan DI/TII baru diundangkan setelah hampir 40 tahun.
Selanjutnya, BJ Habibie juga mengubah nomenklatur daripada pergerakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang semasa Suharto menghakimi sebagai gerombolan liar dan pemberontak, namun BJ Habibie menghormati dan menghargai perjuangan GAM sebagai perjuangan rakyat Aceh dalam menuntut keadilan dan kedaulatannya. Presiden BJ Habibie telah membuka jalan terhadap “Kebangkitan Aceh” di awal abad milenium. Langkah konstruktif penyelesaian perjuangan bersenjata rakyat Aceh di bawah komando GAM diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan meminta Hendry Dunant Centre (HDC) menjadi fasilitator dalam perundingan perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia.
Namun, Aceh kembali masuk masa gelap saat Presiden Megawati merusak proses negosiasi damai, padahal proses negosiasi sedang berlangsung secara konstruktif meskipun terjadi perdebatan-perdebatan berkenaan dengan keamanan. Megawati kembali membawa Aceh dalam masa kegelapan, yaitu Darurat Militer (2003). Megawati mengulang langkah gelap yang dilakukan bapaknya di era Orde Lama. Presiden Sukarno tidak menjalankan janjinya saat awal Aceh menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, bahkan dia menjadikan Aceh bagian dari Provinsi Sumatera Utara.
Alhamdulillah, kekuatan Allah berkehendak untuk memberikan kembali kesempatan pada rakyat Aceh untuk menata negeri kaya ini, namun jalannya berliku. Allah berikan ujian gempa dan tsunami yang dahsyat. Negara dan masyarakat Internasional yang tadinya dibatasi oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengunjungi Aceh maka dengan momentum tersebut pintu Aceh terbuka lebar. Solidaritas internasional datang dari seluruh dunia, kekuatan laut dan langit yang Allah berikan membawa rahmat-Nya bagi negeri aulia dan syuhada ini.
Perjanjian damai 15 Agustus 2005 di Helsinki dan pengesahan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh tanggal 1 Agustus 2006 memberikan pesan kuat, bahwa Aceh segera masuk babak baru pembangunannya. Kegelapan dan kegemilangan yang dirasakannya rakyat Aceh selama ratusan tahun seakan membuka jalan baru terhadap kebangkitannya. “Kebangkitan Aceh” dapat terjadi jika rakyat Aceh menyadari beragam peluang dan kesempatan sudah Allah Swt berikan melalui berbagai peristiwa. Allah telah mendatangkan masyarakat dunia dengan beragam budaya bangsa, Allah telah memberikan kanal kebijakan yang lebih jelas melalui tangan BJ Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Kuntoro Mangkusubroto, yang seolah memberikan pembanding atas langkah gelap yang dilakukan oleh Sukarno, Suharto dan Megawati.
Harapan baru, cita-cita baru, dan perilaku baru harus ditumbuhkan seiring dengan kewenangan UU No. 11/2006 terutama berkenaan dengan kewenangan membangun perekonomian Aceh. Bab XXII Pasal 155 – Pasal 173, yang meliputi prinsip dasar, arah perekonomian, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas, perikanan dan kelautan, perdagangan dan investasi, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang, dan infrastruktur ekonomi. Kewenangan yang kita miliki dalam membangun perekonomi Aceh dan mengelola potensi sumber daya alam kita sangat luas dan menguntungkan kita. Hanya saja, 15 tahun terakhir kita belum menyadari atas peluang ini, kontradiksi internal Aceh, diskursus yang tidak berujung, dan semangat “politik kekuasan” belum dapat kita arahkan dalam sebuah kerangka politik-ekonomi Aceh yang berpegang teguh pada “Aceh national interest” sebagaimana yang dicita-citakan oleh yang mulia wali Aceh, Tgk. Muhammad Hasan di Tiro, beliau maklumatkan dalam bukunya Aceh Bak Mata Donya.
Kemakmuran Aceh
Tgk. Hasan Muhammad di Tiro menuliskan, kemerdekaan adalah dasar kemakmuran, kalau Aceh tidak merdeka maka Aceh tidak mungkin mewujudkan kemakmuran itu. Penggalan kalimat ini disampaikan dalam Aceh Bak Mata Donya yang dituliskan puluhan tahun yang lalu dan menjadi rujukan pergerakan perjuangan GAM. Namun demikian, realitas hari ini setelah bencana dahsyat gempa dan tsunami, maka Allah berkehendak Aceh menjadi negeri yang damai. Karena, rakyat Aceh sudah berperang panjang, sejak maklumat perang Belanda dikumandangkan 1873, maka perjalanan Aceh selalu dalam era perjuangan bersenjata. Perjanjian Helsinki menciptakan momentum politik penting, ada pesan politik yang kuat, “sementara hentilah berperang, siapkan dan kuatkan kapasitas sumber daya manusia generasi Aceh, kelola sumber daya alamnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Aceh”. Kita harus mampu membaca tanda-tanda zaman, agar Aceh dapat menyusun kembali langkah dan strategi menuju “Kebangkitan Aceh” tersebut.
Untuk itu, pertanyaan penting kita, dapatkah kita wujudkan kemakmuran Aceh meskipun kita belum memperoleh kemerdekaan, sedangkan saat ini kita hanya memiliki UU No. 11/2006, dimana telah diatur beragam kewenangan, baik tata kelola pemerintahan maupun politik, budaya, dan bahkan perekonomian serta pengelolaan sumber daya alam. Berapa persenkah kemerdekaan yang dimiliki Aceh diatur dalam UU No. 11/2006 tersebut? Dapatkah kita kapitalisasikan menjadi modal untuk mewujudkan Aceh yang berperadaban, dan menjadi titik baru pertumbuhan ekonomi regional dan bahkan dunia.
Tentunya, kita mesti mengubah perilaku politik kita, perilaku politik yang berfikir dan bermental yang sempit “merebut kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok” ke perilaku politik yang negarawan “merebut kekuasaan untuk menguatkan posisi tawar politik Aceh, menguatkan kebudayaan dan budaya Aceh, membangun ekonomi untuk kesejahteraan rakyat Aceh, sehingga Aceh kembali menjadi pusat peradaban dunia”.
Inilah tantangan besar kita, bukanlah dana otonomi khusus yang mesti kita ributkan dan perebutkan, akan tetapi kewenangan pengelolaan sumber daya alam kita atur dan kelola sesuai dengan cita-cita besar perjuangan Aceh “kemerdekaan dan kemakmuraan”.
Dari Mana Kita Mulai?
Memang UU No. 11/2006 punya keterbatasan, maka demikian perjuangan kita belum berakhir dengan adanya perjanjian damai Helsinki maupun UU No. 11/2006. Sebaliknya perjuangan baru dengan mengedepankan diplomasi baru saja kita mulai. Kita masih perlu turunan hukum peraturan pemerintah maupun peraturan presiden ketentuan UU tersebut dapat dijalankan. Kita sadari selama ini banyak bertabrakan antar undang-undang maupun peraturan lainnya. Namun demikian, kita juga harus menyadari bahwa era perjuangan diplomasi ini, pola pikir dan langkah politik akan selalu beradu kepentingan antara kepentingan Aceh dengan Jakarta. Tentunya Jakarta juga memiliki kepentingan mereka. Namun demikian, Aceh semestinya mempersiapkan diplomat-diplomat yang handal, pintar, energik, berwawasan dan visioner agar mampu meyakinkan Jakarta untuk mempertemukan kepentingan dalam kerangka strategis bersama. Sehingga kemajuan Aceh juga kemajuan republik, begitu pula sebaliknya.
Selanjutnya, 15 tahun damai dan 13 tahun dana otonomi khusus diluncurkan, banyak dampak positif yang sudah terjadi, misalnya angka kemiskinan Aceh memiliki penurunan yang luar biasa dari 32,60 % (2005) turun ke angka 15,01 % (2019). Tentunya, situasi demikian menjadi kapital terhadap “kebangkitan Aceh” meskipun investasi untuk merehabilitasi, merekonstruksi dan membangun perdamaian dan pembangunan berkelanjutan (sustainable peace and development) sangat besar yaitu mencapai Rp. 178 triliun.
Untuk angka kemiskinan yang masih pada level 15,01 % harus dapat menjadi sasaran, tentunya mayoritas mereka adalah masyarakat pedesaan (rural) yang berprofesi sebagai petani dan juga sudah banyak juga menjadi kaum miskin kota (urban poor) karena beranggapan migrasi kekota untuk mencari pekerjaan. Maka sisa dana otsus (sampai 2027), Pemerintah Aceh harus melakukan terobosan dan langkah fundamental, tentunya bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk fokus pada pengembangan sektor riil terutama pertanian, perikanan dan peternakan. Upaya pencegahan penguasaan lahan oleh orang kaya baru di pedesaan harus dihentikan pula agar alat produksi masyarakat pedesaan tidak dirampas.
Selanjutnya, anak-anak dari keluarga miskin diberikan beasiswa dan makanan tambahan yang bergizi agar mereka memiliki pertumbuhan otak yang stabil dan jiwa yang sehat. Kemudian bagi remaja dan pemuda (SMU dan mahasiswa) sudah harus disiapkan sebagai generasi pelapis Aceh (2020 – 2040) dengan mengarahkan mereka untuk memiliki dana menguasai bidang keilmuan berdasarkan potensi sumber daya alam, seperti ahli perminyakan, ahli tambang, ahli industri, ahli biji besi dan sebagainya.
Dana otsus yang tersisa tujuh tahun kedepan (2021-2027) dapat diarahkan untuk memastikan keberlanjutan produksi dan peningkatan hasil produksi di sektor riil dengan secara terencana dapat mempersiapkan berdirinya industri pengolahan untuk hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan. Manfaatkan SDM yang sudah tersedia untuk mewujudkaan produksi sektor riil secara berkelanjutan dan perindustrian/manufaktur.
Meskipun Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) sudah terbentuk, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Aceh dan sedang melakukan eksplorasi dan eksploitasi di beberapa lokasi, akan tetapi dalam 2-5 tahun kedepan, ada bagusnya BPMA menyelesaikan ketentuan hukum dan aturan sampai memiliki kejelasan dalam pembagian hasil antara Aceh-Jakarta. Ketentuan ini sangat penting, mengingat dan mempertimbangkan masa lalu kita, saat ketentuan dan aturan tidak berpihak pada kepentingan Aceh maka konflik bersenjata tidak dapat dihindari. Jadwal eksploitasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan eksploitasi kedepan, baik mempersiapkan sumber daya manusia Aceh yang ahli dibidang perminyakan dan gas maupun kebutuhan terhadap anggaran Aceh itu sendiri. Sehingga begitu selesai kerangka pendataan melalui anggaran otonomi khusus, kita pun sudah memiliki exit strategy untuk menjadi negeri yang mandiri dan berdaulat.
Pemerintah Aceh, baik eksekutif dan legislatif, harus mempunyai road map pengelolaan SDA karena SDA adalah kedaulatan Aceh, menguasai SDA maka Aceh sudah memiliki kemerdekaannya, sehingga SDM Aceh dapat mengelola dengan baik, benar dan berkelanjutan. Adalah tantangan besar menjaga jangan sampai kita masuk dalam perangkap penguasaan SDA global.
Pertarungan global hari ini sudah pada level mendominasi, terutama kekuatan China dan Amerika, keduanya bersaing untuk menguasai energi, menguasai tambang, menguasai tanah dan lainnya sehingga mereka menjadi negara yang super power.
Hanya ada satu kunci bagi Aceh, menjaga SDA yang dimilikinya dengan menyiapkan kapasitas SDM yang kuat. Kemampuan SDM-lah yang menjadi kekuatan untuk melakukan berbagai komunikasi, negosiasi dan diplomasi agar tata kelola pemerintahan Aceh, tata kelola pengelolaan SDA Aceh dapat dimanfaatkan untuk “kebangkitan Aceh” sehingga Aceh kembali dapat berinteraksi dengan bangsa dan budaya dunia.
[Sumber: Buku “Aceh 2021: Sumber Daya Alam dan Politik”, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020”]