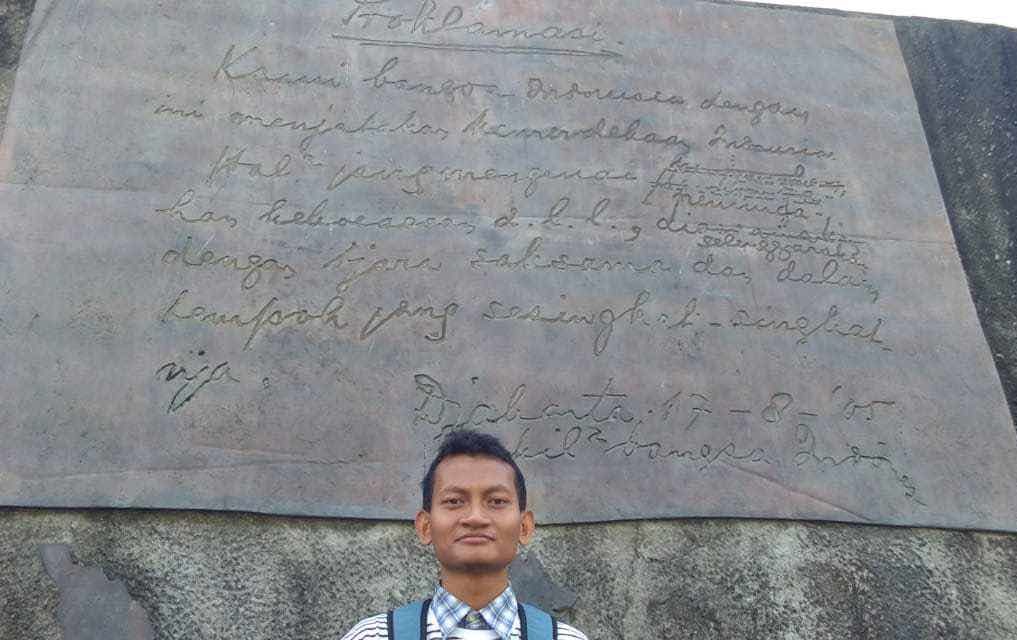Oleh: Zulfikar RH Pohan.
Mahasiswa Magister di Center for Religious and Cros-Cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
David Graeber telah meninggal pada 2 September 2020 lalu dalam usia terbilang muda. Kematian Graeber menyisakan satu lubang tersendiri mengenai corak antropologi yang jarang digunakan di Indonesia, yaitu antropologi anarkis.
Graeber menuliskan risalah mengenainya dengan judul ‘Fragments of an Anarchist Anthropology’ menyoroti sistem dalam kebudayaan masyarakat, demokrasi dan kritiknya terhadap pemikiran ekonomi klasik dan modern terutama dalam analisis nilai dalam ‘Anthropological Theory of Value’.
Dua nama yang sering disandingkan dengan tokoh anarkis adalah Noam Chomsky dan David Graeber, mereka berdua adalah akademisi yang berjuang di jalanan sebagai aktivis anarkis dan bertarung dalam wacana intelektual. David Graeber sebagai akademisi anarkis menjelaskan dengan kapasitas intelektualnya mengenai kebudayaan masyarakat melalui antropologi. Jadi, kata anarkis tak mesti selalu dilekatkan dengan tindakan kericuhan polisi, ormas atau konser dangdut.
Antropologi anarkis berasal dari pertanyaan-pertanyaan teoritis yang bertujuan untuk mengangkat praktik politik di jalanan. Antropologi bagi Graeber adalah corong radikal bagi pengabdiannya sebagai akademisi, teori-teori Graeber adalah teori radikal yang melacak sistem nilai dalam kebudayaan yang berbeda-beda, munculnya pasar, neolibralisme, sampai pekerjaan sia-sia/bullshit jobs (persis skripsi mahasiswa). Dari antropologi anarkis Graeber, setidaknya kita menemukan satu kekhusuan bahwa tanpa pengalaman praktis, mustahil dapat mendalami bahkan membangun epistemologi keilmuan radikal.
Dalam Antropologi anarkis, Graeber berkontribusi pada praktik yang terjadi di sekeliling kita, perampasan tanah, perbudakan, genosida, PHK, raja-raja, dan kebudayaan populer. Jika antropologi yang selama ini kita anggap sebagai ilmu memahami manusia, Graeber justru memposisikannya sebagai alat untuk mengubah sistem. Idealnya, dalam logika antropologi anarkis, menghadapi kenyataan bahwa akumulasi kapital yang menyusupi daerah-daerah Aceh karena penjajahan dan peperangan yang panjang dan bertanggung jawab atas kerusakan hutan, konflik tanah, kemiskinan dan lain-lain. Maka tugas antropolog/akademisi bukan untuk menjelaskannya, tapi untuk mengubah bahwa sebenarnya masyarakat industrial, masyarakat yang tersekat oleh partai politik, dan perlombaan kekayaan bukanlah ciri khas Aceh atau bahkan ciri khas setiap bangsa-bangsa pra-kapital (atau biasa disebut oleh ilmu antropologi/etnografi mainstream sebagai ‘primitif’) manapun.
Tentu mengubah hal tersebut membutuhkan taktik dan strategi, itulah tugas akademisi sebagai aktivis dan memberikan sentuhan aksi dalam setiap wacana intelektual. Dari pengantar singkat bagaimana Graeber membangun paradigma antropologi anarkis, meningatkan saya pada akademisi Aceh.
Sangat sedikit akademisi kampus berperan dalam praktik-praktik radikal perihal sosial, hukum, pendidikan, dan kebudayaan. Bahkan seringkali tidak ada penyambung kesepatakan dan komitmen politik bersama antara akademisi dan aktivis. Hal ini merupakan kecendrungan yang timbul belakangan, atau sebuah hasrat ‘memejakan’ akademisi sehingga menjadi pasif. Beberapa teori bahkan tidak bekerja dengan baik atau gagal diterapkan sebagai alternatif dalam merubah kebijakan pemerintah yang cacat, meminjam bahasa Marvin Harris; ‘Why Nothing Works,”. Sekian, akademisi yang demikian cenderung menciptakan jarak dengan kenyataan riil.
Dari pergulatan akademik yang memang berasal dari jalanan, mudah sekali bagi mereka menginjak-injak rasionalitas, humanisme dan omong-kosong tradisi pencerahan. Foucault, Irigaray, Derrida, Camus, dan lainnya sebagai biang dari musuh-musuh bagi tradisi-tradisi kalangan akademisi konservatif, sebab mereka menyandarkan teorinya sesuai dengan praktik politik di jalanan, penjara, bom, maupun selangkangan. Bahkan sesama akademisi yang bergelut dengan politik, kerapkali melihat tindakan politik adalah salah-satu dari keabsahan teori. Sebagaimana cibiran Camus terhadap Sartre dan Marleu-Ponty yang menikmati privilese sebagai akademisi, alih-alih ambil bagian dalam disipilin organisasi jalanan, dan tekanan-tekanan dari pergulatan radikal dalam faksi-faksi politik radikal kala itu.
Mutu dari akademisi kita yang jalan di tempat adalah dampak dari industrialisasi pendidikan. Selama ini, hanya mahasiswa yang dicibir bakalan menjadi pekerja-pekerja cadangan di perusahaan dengan upah murah. Kita juga harusnya menyentil dampak industrialisasi institusi pendidikan pada para akademisi sebagai pendidik. Industri pendidikan dilengkapi dengan standar-standar publikasi, untung besar bagi lembaga jurnal, penerbit parasit, dan tawaran penelitian yang menggiurkan.
Kita tidak menyadari bahwa tulisan-tulisan akademik dan jurnal-jurnal penelitian mentereng manapun, di dunia nyata akan kalah saing dengan berita clickbait tentang pemuda yang memperkosa ayam. Ada jarak yang serius antara kepekaan masyarakat dan peran akademisi di tengah-tengah kenyataan riil. Bahwa akademisi telah terlalu lama bergelut dengan hal-hal ilmiah di singasana yang tak tersentuh oleh masyatakat secara luas.
Masyarakat harus tau hal ini; lingkungan akademis juga tak steril-steril amat dari institusi kekuasaan yang menindas.
Tidak sedikit akademisi di Aceh benar-benar berjarak dengan kenyataan hanya karena terlalu nyaman dengan privilese sebagai dosen tetap, profesor terhormat, atau peneliti belakang meja. Namun, kenyataan bersifat dinamis, belum lagi konstruksi-konstruksi sosial yang terlalu rumit jika dibawa dalam meja kampus. Kita bisa menyaksikan bagaimana wacana akademis di Aceh, di pusat kota, di universitas ternama para akademisi mengajar, akademisi besar dikelilingi oleh akademisi minion, mereka saling mendukung, menertawakan, serta menyoraki satu-sama lain kalangan akademisi lain, persis ormas atau geng anak SMA. Menjadi akademisi di Aceh, kita harus memasuki pintu-pintu otoritas agar dikenali, untuk sekadar mendapatkan tempat sebagai ‘kakanda’ dan ‘abangda’.
Kita boleh memperhatikan secara seksama, beberapa akademisi Aceh yang kian getol menerbitkan buku atau antologi. Harapannya adalah nama mereka ada dalam sampul, dengan tulisan-tulisan yang hanya dibaca dalam sekali lirik. Dibaca hanya oleh kalangan dan jajaran mereka sendiri dan mengunggahnya di akun media sosial sembari menunggu komentar bernada monoton seperti ‘mantap’, ‘keren’, ‘luar biasa’ dan sebagainya. Sejak awal, tradisi tulis-menulis hanya milik kaum menengah ke atas, hanya mereka yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang bisa dekat dengan tulisan, penerbitan, buku, les menulis berbayar dan apa yang mereka sebut ‘literasi’.
Menulis memang baik dan keren, tapi menulis hanya upaya menyingsingkan lengan baju, untuk benar-benar menjadi kerja yang bermanfaat, akademisi memang benar-benar harus menggeluti problem-problem praktis secara riil.
Belajar dari intelektual anarkis seperti Graeber yang menjangkarkan ilmunya dari problem-problem riil yang mereka perjuangkan, menujukkan identifikasi politik adalah cara mengetahui kawan dan lawan. Tak sedikit para akademisi yang tak menunjukkan tabiat politik mereka dengan alasan bahwa politik akan mencoreng kredibilitas mereka sebagai profesor atau dosen. Karena politik telah dikonstruksi oleh budaya populer menjadi alam liar yang tak dapat diprediksi, penuh tipu daya dan tak seharusnya akademisi yang suci dan bersih untuk terjun ke dalamnya seperti mengadvokasi kebutuhan masyarakat, mematangkan gerakan rakyat, bahkan berdemontrasi.
David Graeber hanyalah manusia yang dapat mati, kita masih menjumpai banyak akademisi yang menjadi aktivis dalam keilmuan yang mereka geluti. Sebagai antropolog, Graeber tidak ingin terjebak dalam pikiran-pikiran konservatif dan essensialisme dalam setiap identitas-identitas, sejarah, kebudayaan, dan kerja pada setiap lapisan masyarakat.
Para akademisi sepeti Graeber percaya bahwa substansi dari kontribusi seorang intelektual adalah ketika ia memposisikan diri sebagai teoritikus yang ulet dan praktikus yang radikal di tengah-tengah masyarakat. Tidak lupa rumusan anarkis: aksi! []