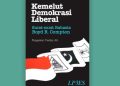Aceh kini memasuki babak baru dalam perjalanan otonomi dan pembangunan ekonominya. Dengan terpilihnya Muzakkir Manaf (Mualem) sebagai Gubernur, publik berharap ada gebrakan nyata di sektor industri sebagai tulang punggung kemandirian ekonomi. Dalam berbagai kesempatan, Mualem menyuarakan pentingnya industrialisasi Aceh yang berbasis potensi lokal dan nilai-nilai keacehan. Harapan ini bukan tanpa dasar. Dengan kekayaan sumber daya alam, posisi strategis di jalur pelayaran Selat Malaka, dan semangat pascarekonsiliasi yang masih menyala, Aceh memiliki modal kuat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Namun, sebagaimana daerah lain di Indonesia, industrialisasi Aceh membutuhkan arah yang jelas, konsistensi kebijakan, dan keberanian politik.
Misi Industri Aceh di Tangan Mualem
Pasangan Mualem–Fadhlullah mengusung visi “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.” Di dalamnya, termuat misi memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Tak sekadar jargon, visi ini dijabarkan ke dalam langkah konkret seperti pendirian pabrik minyak goreng dari sawit Aceh, pembangunan industri farmasi di Pulo Breuh, dan perencanaan kawasan industri baru di Lhokseumawe.
Sektor industri yang menjadi fokus tidak hanya bertumpu pada kekayaan alam yang selama ini diekspor mentah, tapi juga diarahkan pada hilirisasi. Jika berhasil, pendekatan ini akan membawa dampak besar dalam membuka lapangan kerja, menambah nilai ekonomi, dan memperkuat daya tawar Aceh dalam jejaring ekonomi nasional dan global.
Potensi Strategis Aceh: Alam, Akses, dan Kekhususan
Keunggulan Aceh bukan hanya pada cadangan minyak, gas, dan sawit. Provinsi ini memiliki potensi agro yang luar biasa: dari kopi Gayo yang mendunia, nilam Aceh sebagai bahan utama parfum global, hingga potensi rumput laut dan hasil laut lainnya. Di sektor energi, Aceh memiliki potensi panas bumi, air, dan energi surya yang belum tergarap maksimal. Posisi geografis Aceh juga sangat strategis, dengan pelabuhan-pelabuhan yang bisa dijadikan simpul perdagangan internasional.
Namun yang paling unik adalah status kekhususan Aceh. Dalam konteks industri, kekhususan ini seharusnya diterjemahkan dalam bentuk regulasi yang memberikan insentif investasi, perlindungan sumber daya, dan peran lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola hasil bumi. Sayangnya, keistimewaan ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Tantangan Nyata di Lapangan
Walau peluang terbuka, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan. Pertama, infrastruktur industri Aceh belum memadai. KEK Arun yang sempat digadang-gadang sebagai motor industri kawasan, justru stagnan karena tumpang tindih kepentingan dan lemahnya tata kelola.
Kedua, sumber daya manusia (SDM) teknis yang siap pakai masih minim. Banyak industri enggan masuk karena harus mengimpor tenaga kerja dari luar, padahal pengangguran lokal masih tinggi.
Ketiga, iklim investasi Aceh masih dianggap belum ramah. Proses perizinan yang lambat, ketidakpastian hukum, serta kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan masih membayangi persepsi calon investor, baik domestik maupun luar negeri.
Keempat, minimnya riset dan hilirisasi inovasi lokal. Dunia akademik, industri, dan pemerintah daerah belum terhubung dalam satu ekosistem inovasi yang mendorong penciptaan produk berbasis riset, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan herbal.
Arah Baru: Industrialisasi yang Islami dan Berkeadilan
Untuk keluar dari jebakan industrialisasi konvensional yang hanya berorientasi pada eksploitasi, Aceh perlu menawarkan model industrialisasi alternatif: Islami, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Artinya, pembangunan industri harus menghormati nilai-nilai syariat, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, dan ramah terhadap lingkungan. Sebagai contoh, industri farmasi yang direncanakan di Pulo Breuh bisa menjadi pionir dalam produksi obat halal berbasis tanaman lokal. Industri pangan pun bisa diarahkan pada sertifikasi halal internasional, menjadikan Aceh sebagai pusat produksi produk halal dunia.
Sedikit catatan kritis perlu disinggung berkaitan dengan rencana pembangunan industri rokok di Aceh. Ditinjau dari sudut nilai-nilai syariat kebijakan ini cukup bernuansa paradoksal. Islam menanamkan faham yang menafikan aktifitas yang memudharatkan. Merokok adalah salahsatu perbuatan yang melalaikan dan memudharatkan sehingga sebagian besar ulama menolaknya. Jika ada kebijakan yang mendorong tumbuhnya aktifitas mudharat tentu harus juga ditolak. Karena justru bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada butir visi misi yang telah dideklarasikan sebelumnya.
Selain itu, kehadiran industri harus benar-benar memperkuat UMKM dan ekonomi rakyat. Jangan sampai investasi besar justru menyingkirkan pengusaha lokal. Mualem dan timnya harus memastikan adanya kemitraan antara investor besar dengan koperasi lokal, pesantren, dan pelaku ekonomi desa.
Mendorong KEK Arun dan Zona Industri Baru
Revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun harus menjadi prioritas. KEK ini memiliki potensi menjadi pusat industri gas-to-chemical, pengolahan hasil laut, dan logistik ekspor. Untuk itu, perlu ada pembenahan manajemen, keterlibatan BUMD, dan kebijakan afirmatif yang mempermudah pelaku usaha lokal masuk ke dalam ekosistem KEK.
Selain itu, zona industri baru perlu dirancang di wilayah barat dan tengah Aceh, seperti Meulaboh, Takengon, dan Bener Meriah. Ini akan memicu pertumbuhan industri agro dan hilirisasi kopi serta pertanian organik.
Jalan Panjang Menuju Kemandirian Ekonomi
Masa depan industri Aceh sangat ditentukan oleh kemauan politik pemimpinnya. Mualem punya sejarah panjang dalam perjuangan Aceh, dan kini saatnya menerjemahkan semangat itu dalam bentuk pembangunan yang mensejahterakan. Langkah-langkah konkret seperti pembentukan badan promosi industri, reformasi pendidikan vokasional, dan insentif fiskal untuk investor strategis perlu segera dirumuskan.
Kebijakan industrialisasi juga harus memperhatikan ketimpangan regional di Aceh. Daerah pesisir timur sering lebih berkembang, sementara wilayah barat dan pedalaman tertinggal. Maka pembangunan industri harus berbasis pemerataan dan konektivitas lintas wilayah.
Penutup: Momentum yang Tak Boleh Terlewat
Aceh sedang berada di persimpangan sejarah. Kegagalan industrialisasi selama dua dekade pasca-MoU Helsinki bukan hanya karena keterbatasan sumber daya, melainkan karena absennya arah dan komitmen. Kini, dengan kepemimpinan baru, momentum itu kembali datang.
Mualem punya modal legitimasi, pengalaman, dan visi. Tinggal bagaimana ia dan timnya bisa membangun tata kelola industri yang bersih, partisipatif, dan berpihak pada rakyat. Industri bukan hanya tentang mesin dan pabrik, tapi tentang harapan, kerja, dan martabat. Dan Aceh layak untuk mendapatkannya.***
Banda Aceh, 2 Juni 2025
Dr. Ir. Dandi Bachtiar, M. Sc.
Penulis adalah dosen di Departemen Teknik Mesin dan Industri – Universitas Syiah Kuala (USK). dandibachtiar@usk.ac.id