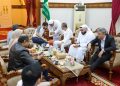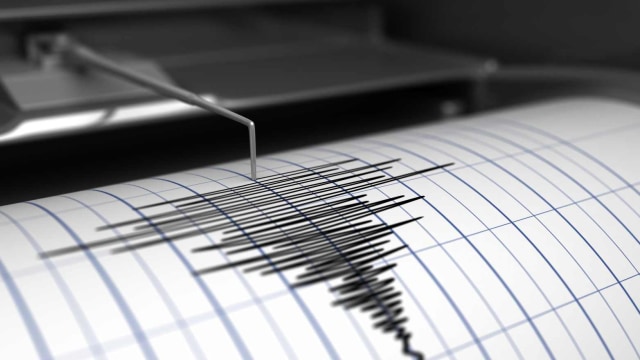Abstrak: Setelah reformasi 1998, desentralisasi menjadi dasar untuk memperbarui pemerintahan Indonesia. Untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memindahkan banyak urusan pemerintah dari pusat ke daerah. Namun, lebih dari sepuluh tahun pengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang daerah sering menghadapi masalah, seperti tumpang tindih kewenangan, ketidakseimbangan dalam kapasitas fiskal dan sumber daya manusia, dan kurangnya mekanisme pengawasan. Artikel ini menelaah bagaimana kewenangan pemerintahan daerah digunakan dan menemukan masalah utama. Ini juga memuat saran tentang cara otonomi daerah menjadi memberdayakan daripada membebani.
Setelah rezim Orde Baru runtuh pada tahun 1998, reformasi birokrasi yang bergulir menjadi momentum penting dalam mengubah tata kelola pemerintahan Indonesia. Perubahan ini disebabkan oleh tuntutan kuat masyarakat untuk sistem pemerintahan yang lebih transparan, demokratis, dan berfokus pada kebutuhan lokal. Penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan tonggak penting dari reformasi tersebut. Kebijakan ini memberikan pemerintah daerah kewenangan yang lebih besar untuk mengelola masalah nasional.
Otonomi daerah adalah solusi untuk berbagai masalah umum, seperti sentralisasi kekuasaan di Jakarta selama bertahun-tahun. Ini juga merupakan cara untuk mengatasi masalah abadi seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan akses layanan publik di daerah terpencil, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Gagasan utamanya adalah bahwa daerah lebih memahami kebutuhan dan potensi daerah mereka, sehingga pelimpahan sebagian kewenangan dari pusat ke daerah dapat menghasilkan pemerataan pembangunan, peningkatan efisiensi pemerintahan, dan penguatan demokrasi lokal.
Desentralisasi ini kemudian diformalkan dalam kerangka hukum oleh berbagai undang-undang. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan undang-undang sebelumnya, berfungsi sebagai dasar hukum utama untuk mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam hal pembagian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pengawasan dan pembinaan. Dengan pembagian kewenangan yang jelas antara otoritas pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, UU ini menetapkan otonomi daerah berdasarkan prinsip pembantuan, desentralisasi, dan dekonsentrasi.
Pemerintah daerah diberi hak dan tanggung jawab yang lebih besar oleh UU tersebut dalam hal menyelenggarakan pelayanan publik, merencanakan pembangunan daerah, dan mengelola sumber daya lokal. Pada akhirnya, tujuan adalah untuk membuat sistem pemerintahan yang lebih sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi, dan budaya di daerah tersebut. Pada saat yang sama, mereka juga ingin memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi.
Namun, pelimpahan otoritas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak selalu berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan dari desentralisasi. Meskipun biasanya pemerintah daerah diberi wewenang yang cukup besar untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat, masih ada beberapa masalah penting yang belum diselesaikan yang berdampak pada kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah salah satu masalah besar yang sering terjadi. Kebingungan tentang batas tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan masih sering terjadi dalam beberapa bidang, seperti perizinan usaha, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, dan kesehatan. Tidak jarang ketidakjelasan ini menyebabkan konflik kebijakan, penundaan pengambilan keputusan, dan penundaan program pembangunan. Sebagai contoh, izin pemerintah daerah untuk pengelolaan kawasan hutan atau tambang dapat bertentangan dengan kebijakan kementerian terkait di tingkat pusat. Akibatnya, investor dan masyarakat lokal akan dirugikan.
Selain itu, pelaksanaan otonomi menghadapi tantangan besar karena kapasitas birokrasi lokal yang tidak merata. Banyak daerah, terutama yang berstatus tertinggal atau di luar Jawa, masih mengalami kekurangan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang berpengalaman dan berkualitas tinggi. Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam membuat kebijakan yang berbasis bukti dan memberikan pelayanan publik yang responsif karena faktor-faktor seperti tingkat pendidikan dan pelatihan pegawai yang rendah, keterbatasan akses ke teknologi dan data, dan budaya organisasi yang tidak fleksibel. Ini diperparah oleh kualitas birokrasi yang buruk di beberapa tempat, yang memungkinkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, ada masalah kualitas pelayanan publik yang berbeda di antara wilayah, yang justru menambah disparitas sosial dan ekonomi. Layanan publik yang relatif memadai, cepat, dan terukur dapat diberikan di daerah dengan kemampuan fiskal besar dan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti DKI Jakarta, Kota Surabaya, atau Kabupaten Banyuwangi. Sebaliknya, banyak daerah lain masih menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti air bersih, layanan medis, dan pendidikan yang baik. Kesimpangan ini menunjukkan bahwa pemberian wewenang saja tidak cukup tanpa diikuti dengan peningkatan kekuatan fiskal, teknis, dan kelembagaan.
Selain itu, ada kecenderungan bahwa elit lokal mengambil alih kekuasaan daerah untuk kepentingan politik jangka pendek. Dalam beberapa situasi, desentralisasi malah menghasilkan oligarki lokal, di mana sekelompok kecil politisi memegang kendali atas anggaran dan sumber daya lokal. Hal ini menyebabkan proses pengambilan kebijakan menjadi transaksional dan tidak inklusif. Otonomi daerah akhirnya berubah menjadi alat untuk pelanggengan kekuasaan lokal yang tidak berpihak pada kepentingan publik, alih-alih menjadi alat untuk pemberdayaan masyarakat lokal.
Banyak masalah ini menunjukkan bahwa desentralisasi bukanlah kebijakan yang dapat diterapkan secara instan. Kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia yang baik, sistem akuntabilitas yang kuat, dan koordinasi yang jelas antara pusat dan daerah adalah syarat untuk pelimpahan wewenang kepada daerah. Otonomi daerah hanya akan menjadi formalitas hukum yang tidak dapat membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan berpihak pada rakyat jika tidak memenuhi persyaratan ini.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bagaimana pemerintahan pusat dan daerah berurusan. Menurut undang-undang ini, wewenang pemerintah daerah terbagi menjadi tiga kategori besar: urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Sektor-sektor penting yang berhubungan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar. Bidang-bidang lain, seperti tenaga kerja, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, lingkungan hidup, juga termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar. Sementara itu, daerah memiliki kewenangan untuk melakukan urusan pilihan berdasarkan potensi dan kekhasan lokal dalam bidang seperti pariwisata, perikanan, pertanian, dan kebudayaan.
Pembagian urusan ini seharusnya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan program yang berbasis pada kebutuhan lokal dan prospek masing-masing wilayah. Oleh karena itu, daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan prioritas pembangunan, mengelola sumber daya, dan menyediakan layanan publik yang lebih partisipatif dan adaptif. Konsep ini sesuai dengan prinsip desentralisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan otonomi daerah secara substansial daripada hanya administratif.
Namun, pelaksanaan wewenang tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Menurut sejumlah penelitian dan evaluasi kebijakan, banyak daerah di Indonesia belum mampu menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka secara optimal. Ini adalah hasil dari sejumlah variabel teknis dan struktural yang saling berkaitan. Pertama dan terpenting, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah terus menjadi masalah penting. Banyak aparatur sipil negara (ASN) di daerah, terutama di luar Pulau Jawa, kurang profesional dan teknis untuk merancang kebijakan, mengelola program pembangunan, dan melakukan evaluasi berbasis data dan hasil. Hal ini menyebabkan birokrasi daerah yang responsif, kreatif, dan akuntabel menjadi terhambat.
Kedua, pemerintah daerah tidak memiliki banyak sumber daya fiskal, yang berarti mereka tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan secara mandiri. Banyak pemerintah daerah tidak memiliki fleksibilitas anggaran yang diperlukan untuk membiayai program pembangunan lokal secara berkelanjutan karena mereka sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya PAD di sebagian besar kabupaten dan kota, terutama di daerah terluar dan tertinggal. Akibatnya, meskipun daerah memiliki otoritas, tanpa dukungan fiskal yang memadai, otoritas tersebut menjadi tidak signifikan.
Ketiga, pelaksanaan otonomi daerah menjadi kurang efektif karena intervensi pemerintah pusat yang terus berlanjut dalam beberapa sektor penting. Misalnya, bidang-bidang seperti pendidikan tinggi, energi, pengelolaan sumber daya alam, dan perizinan investasi masih sangat ditangani oleh kementerian atau lembaga teknis pusat, meskipun secara formal diberikan sebagian kepada daerah. Hal ini menyebabkan perbedaan otoritas dan kebingungan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Tidak jarang inisiatif kebijakan lokal atau peraturan daerah harus diubah atau dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan kebijakan nasional. Intervensi seperti ini dapat melemahkan semangat inovasi di daerah dan membuat pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana program pusat.
Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara kewajiban dan kemampuan pemerintah daerah. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menjalankan berbagai urusan pemerintahan dengan baik; di sisi lain, tidak ada pendanaan yang cukup, regulasi yang konsisten, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Akibatnya, banyak daerah hanya menjalankan tugas pemerintahan secara administratif dan formal, tetapi tidak mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.
Pengelolaan urusan wajib pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, adalah contoh nyata dari kesulitan dalam menerapkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini karena, secara normatif, kedua bidang ini merupakan urusan wajib yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah karena berkaitan dengan hak dasar masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam kenyataannya, sektor ini masih sangat bergantung pada kebijakan, program, dan dana pemerintah pusat.
Misalnya, dalam bidang pendidikan, kabupaten dan kota telah diberi wewenang untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah. Namun, kurikulum nasional, standar nasional pendidikan, pengelolaan tunjangan guru, dan dana BOS semuanya ditetapkan oleh pusat. Pemerintah daerah seringkali hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis dari program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, tanpa memiliki kemampuan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal yang signifikan. Hal serupa terjadi dalam sektor kesehatan. Meskipun pemerintah daerah memiliki otoritas atas fasilitas kesehatan tingkat dasar seperti puskesmas, pemerintah pusat—melalui Kementerian Kesehatan—tetap memiliki kendali atas kebijakan strategis seperti pengadaan vaksin, pengendalian wabah, dan pembagian tenaga medis. Pelayanan publik di sektor-sektor ini tidak merata dan tidak responsif terhadap masalah lokal khusus karena tidak ada keseimbangan antara tanggung jawab yang diberikan kepada daerah dan sumber daya yang mereka miliki.
Pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah salah satu urusan strategis dalam pembangunan daerah, dan masalah ketidaksesuaian kewenangan jelas terlihat dalam bidang ini selain urusan pelayanan dasar. Mayoritas pemerintah kabupaten dan kota memiliki otoritas untuk mengelola sumber daya alam, terutama di bidang pertambangan, kehutanan, dan kelautan, sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah. Namun, setelah revisi, sebagian besar otoritas tersebut dipindahkan ke tingkat provinsi atau bahkan langsung ke pemerintah pusat. Misalnya, izin usaha pertambangan (IUP) sekarang dikeluarkan oleh provinsi atau Kementerian ESDM, bukan lagi oleh pemerintah kabupaten. Begitu pula untuk wilayah pantai dan laut di bawah 12 mil, yang kini dimiliki provinsi dan bukan lagi kabupaten atau kota.
Meskipun pengalihan otoritas ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah kepala daerah menyalahgunakan izin, itu telah menyebabkan ketidaksesuaian kebijakan, masalah administratif, dan bahkan konflik antarwilayah. Sekarang, pemerintah kabupaten dan kota yang sebelumnya telah membangun rencana pembangunan daerah yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengontrol situasi tersebut. Sebaliknya, pemerintah provinsi seringkali kekurangan informasi rinci atau pemahaman yang memadai tentang kondisi lapangan di tingkat kabupaten. Akibatnya, proses perizinan menjadi lebih lambat, tumpang tindih kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan menjadi lebih umum, dan risiko investasi di sektor strategis meningkat.
Fakta ini menunjukkan bahwa mencapai otonomi daerah tidak hanya memerlukan pelimpahan kewenangan secara formal, tetapi juga membutuhkan peran yang jelas, kemampuan untuk bekerja sama, dan dukungan sistem yang memadai untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan dapat diterapkan dengan baik di semua tingkat pemerintahan. Kebingungan struktural dan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah terjadi ketika kewenangan ditarik secara vertikal tanpa dibarengi dengan sinergi antarpemerintah. Oleh karena itu, masalah utama di masa depan adalah bagaimana membagi wewenang tersebut sehingga tidak hanya sah secara hukum tetapi juga masuk akal, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, menghadapi banyak masalah yang berbeda dari perspektif geografis, sosial, dan ekonomi. Tingginya ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah salah satu tantangan struktural yang paling mencolok. Ini termasuk ketimpangan dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, kapasitas fiskal, dan akses ke layanan dasar. Ini tidak hanya terjadi antara Jawa dan luar Jawa, tetapi juga antara provinsi, bahkan antara kabupaten dan kota dalam satu provinsi. Dalam situasi seperti ini, kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang hampir sama kepada seluruh daerah tanpa mempertimbangkan kapasitas sebenarnya dan karakteristik masing-masing wilayah dapat memperburuk perbedaan pembangunan yang sudah ada.
Di satu sisi, daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, banyak sumber daya alam, dan birokrasi yang mapan dan kompeten, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, atau Kalimantan Timur, dapat memanfaatkan otonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, dan mengembangkan berbagai inovasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Mereka tidak hanya memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang besar, tetapi mereka juga memiliki kekuatan institusional yang memungkinkan mereka untuk mengelola anggaran dan program pembangunan dengan baik. Pemerintah daerah di wilayah-wilayah ini dapat menjalankan wewenang mereka secara optimal dan mandiri, bahkan berdampak positif pada daerah lain, dengan dukungan SDM yang memadai dan akses teknologi yang baik.
Sebaliknya, sejumlah besar wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan kecil menghadapi tekanan yang sama. Mereka ditugaskan untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan, tetapi mereka kekurangan sumber daya fiskal dan kapasitas administratif yang diperlukan untuk memenuhi tugas tersebut. Karena mereka sangat bergantung pada dana transfer pusat seperti DAU dan DAK, mereka tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk inovasi atau mengubah kebijakan sesuai dengan situasi lokal. Bahkan dalam situasi tertentu, dana yang ada hanya cukup untuk membiayai belanja rutin daripada pembangunan yang bersifat strategis dan berjangka panjang.
Selain itu, disparitas kapasitas ini menyebabkan ketimpangan ekonomi dan ketidaksetaraan dalam pelayanan publik. Misalnya, orang di daerah maju seperti Yogyakarta atau Bandung memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi, sementara orang di Kabupaten Intan Jaya, Papua, atau Pulau Simeulue, Aceh, menghadapi kekurangan fasilitas dasar, tenaga medis, guru, dan bahkan akses jalan yang buruk. Akibatnya, tujuan utama desentralisasi—mempercepat pemerataan pembangunan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat—tidak tercapai. Sebaliknya, otonomi memperkuat daerah yang sudah kuat dan melemahkan daerah yang sudah lemah.
Situasi ini juga mempengaruhi hubungan antara pusat dan daerah. Dalam situasi di mana daerah-daerah memiliki kapasitas yang lebih rendah, pemerintah pusat seringkali dipaksa untuk kembali mengambil alih beberapa fungsi strategis yang telah diberikan sebelumnya kepada mereka, yang menimbulkan kesan “desentralisasi semu”. Sebaliknya, pemerintah daerah yang tidak melaksanakan fungsinya dengan benar dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat, menumbuhkan ketidakpercayaan publik, dan meningkatkan kemungkinan konflik sosial.
Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan metode yang lebih kontekstual dan adaptif untuk menerapkan otonomi daerah di Indonesia. Pembagian wewenang harus didasarkan pada kemampuan spesifik setiap daerah—termasuk kapasitas ekonomi, geografis, dan sosial-budaya. Desentralisasi asimetris, juga dikenal sebagai “asymmetric decentralization”, memungkinkan solusi di mana otoritas dan tanggung jawab dibagi sesuai dengan tingkat kesiapan daerah. Daerah yang lebih maju mungkin memiliki lebih banyak otonomi, sementara daerah yang masih berkembang dapat mendapat bantuan teknis, penguatan kapasitas kelembagaan, dan distribusi fiskal yang lebih progresif dari pusat.
Sangat penting untuk melakukan evaluasi yang terus-menerus dan menyeluruh terhadap sistem desentralisasi saat ini. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ada ketimpangan dalam pelaksanaan otonomi daerah serta berbagai hambatan yang menghalangi pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah. Dalam konteks kebijakan publik, desentralisasi adalah sistem yang terus berubah yang perlu dipertimbangkan dan disesuaikan dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan geografis yang terjadi di tingkat nasional dan lokal. Oleh karena itu, pemerintah pusat, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan lembaga pengawas independen seperti BPK dan KPK, harus secara aktif mendorong evaluasi berkala terhadap pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Tidak mungkin evaluasi ini bersifat administratif hanya berdasarkan tingkat serapan anggaran atau dokumen pelaporan. Sebaliknya, evaluasi ini harus substantif dan menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai metrik kinerja pemerintahan daerah, partisipasi publik, tingkat kepuasan masyarakat, dan efektivitas layanan publik. Selain itu, evaluasi harus mempertimbangkan apakah pembagian urusan pemerintahan saat ini benar-benar mendorong desentralisasi atau justru memperkuat sentralisasi yang tersembunyi melalui mekanisme regulasi dan keuangan yang menghalangi upaya daerah. Dalam situasi ini, penyesuaian kebijakan desentralisasi harus didasarkan pada fakta-fakta lapangan, bukan hanya asumsi teoritis yang umum.
Sangat penting bagi pemerintah untuk secara konsisten menggunakan tiga asas utama UU 23/2014 sebagai dasar etika dan normatif dalam menilai dan mengubah pembagian kewenangan. Asas-asas ini adalah Rekognisi, Subsidiaritas, dan Diferensiasi. Namun, ketiga prinsip tersebut masih belum digunakan sepenuhnya. Meskipun tantangan dan kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, banyak kebijakan masih berusaha untuk mencapai keseragaman. Misalnya, daerah tertinggal, juga dikenal sebagai “3T” (terdepan, terluar, tertinggal), tetap diberi wewenang yang sama dengan daerah metropolitan, tanpa mempertimbangkan bahwa mereka menghadapi masalah infrastruktur, aksesibilitas, dan sumber daya manusia yang terbatas. Sementara itu, daerah yang memiliki kapasitas tinggi sering merasa dibatasi oleh peraturan pusat yang terlalu ketat.
Dengan demikian, dua hal utama harus menjadi fokus reformasi kebijakan desentralisasi. Pertama, penataan ulang urusan pemerintahan berdasarkan analisis kontekstual dan evaluasi data. Kedua, meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah melalui pelatihan karyawan, peningkatan transparansi, dan peningkatan sistem penganggaran. Ini adalah satu-satunya cara agar prinsip-prinsip dasar otonomi daerah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari orang, bukan hanya menjadi kata-kata di kertas kebijakan.
Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu contoh terbaik dari inovasi pemerintahan daerah. Banyuwangi telah mengembangkan berbagai inovasi berbasis digital di bawah pimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas sejak 2010. Ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu inisiatif utamanya adalah “Bling”, yang merupakan singkatan dari Banyuwangi e-Planning, sebuah sistem e-government yang bertujuan untuk mendigitalisasi seluruh proses perencanaan pembangunan, mulai dari musyawarah desa hingga penganggaran dan pelaporan kinerja.
Menurut evaluasi internal Pemkab Banyuwangi (2023), program ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD dan mengurangi kemungkinan korupsi proyek hingga 35% dalam lima tahun terakhir. Selain itu, Bling memungkinkan orang mengakses dan berpartisipasi secara daring dalam rencana pembangunan daerah untuk meningkatkan partisipasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan daerah dapat berjalan dengan sangat efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat jika didukung oleh teknologi, kepemimpinan yang visioner, dan sumber daya manusia yang memadai.
Prestasi di Banyuwangi terus berlanjut. Kabupaten ini juga mengembangkan sektor pariwisata berbasis komunitas, sistem layanan kesehatan berbasis mobile, dan pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan industri. Semua temuan ini menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat jika kewenangan otonomi daerah diterapkan dengan prinsip efisiensi, inovasi, dan inklusi.
Sebaliknya, beberapa kabupaten di wilayah Indonesia Timur, terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT), menghadapi masalah besar dalam menjalankan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Meskipun memiliki sumber daya alam dan budaya yang luar biasa, daerah-daerah ini menghadapi kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan modern karena berbagai keterbatasan struktural.
Jumlah tenaga teknis yang rendah dan kapasitas yang rendah dari aparatur sipil negara (ASN) merupakan masalah utama. Banyak karyawan strategis ASN memiliki pendidikan yang buruk, kurangnya pelatihan rutin, dan kurangnya akses ke teknologi informasi. Hal ini menyebabkan pelayanan publik tetap tradisional, lambat, dan tidak responsif terhadap kebutuhan warga. Selain itu, implementasi sistem e-government menjadi sulit karena infrastruktur digital yang tidak merata dan akses internet yang terbatas.
Akibatnya, program pembangunan biasanya tidak berbasis data, seringkali reaktif, dan tidak berkelanjutan. Tidak ada pengawasan anggaran yang memadai dan program wajib seperti pendidikan dan kesehatan masih tertinggal dalam kualitas. Dalam situasi seperti ini, pelaksanaan otoritas pemerintahan daerah cenderung bersifat administratif dan simbolik daripada strategis dan solutif. Kasus ini menunjukkan bahwa kesenjangan kapasitas di antara daerah dapat menjadi tantangan besar untuk mencapai otonomi yang merata dan efektif.
Perbandingan antara Banyuwangi dan beberapa kabupaten tertinggal di NTT menunjukkan bahwa desentralisasi sangat bergantung pada keadaan lokal, terutama dalam hal sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, metode otonomi asimetris—yang menyesuaikan wewenang dengan kemampuan masing-masing daerah—harus dipertimbangkan dengan lebih serius dalam kebijakan nasional. Pemerintah pusat tidak dapat membuat satu kebijakan untuk seluruh daerah. Sebaliknya, pemerintah pusat harus memberikan dukungan yang afirmatif bagi daerah dengan kapasitas rendah, membantu mereka mengejar ketertinggalan dan mendapatkan otonomi secara substansial, bukan hanya formalitas hukum.
Evaluasi menyeluruh dari pembagian urusan akan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan memperkuat integrasi nasional melalui pemerataan pembangunan dan penguatan kepercayaan publik terhadap negara. Indonesia akan lebih siap menjawab tantangan masa depan seperti globalisasi, perubahan iklim, dan transformasi digital dengan menjadikan desentralisasi sebagai proses yang responsif dan adaptif. Tantangan-tantangan ini akan berdampak langsung pada pemerintahan dan layanan publik.
Serangkaian strategi kebijakan yang tidak hanya normatif tetapi juga praktis, terukur, dan berbasis data diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dan menjawab berbagai tantangan yang telah disebutkan sebelumnya. Ke depan, rencana untuk memperbarui otonomi daerah dapat dimulai dengan tiga pendekatan utama yang saling melengkapi.
Pertama dan terpenting, kapasitas institusi dan aparatur pemerintah daerah harus ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan. Tidak hanya struktur pemerintahan daerah yang dimaksudkan, kapasitas kelembagaan juga mencakup kualitas sumber daya manusia, kemampuan manajemen, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan LAN harus memperkuat sistem pelatihan dan pendidikan aparatur lokal. Kepemimpinan strategis, perencanaan pembangunan partisipatif, pengelolaan keuangan daerah, dan transformasi digital pemerintahan harus menjadi bagian dari pelatihan yang diperlukan, bukan hanya instruksi prosedural teknis. Selain itu, sistem pengembangan karier ASN di daerah harus didasarkan pada meritokrasi dan bukannya hubungan politik atau kekerabatan yang sering mengurangi profesionalisme birokrasi lokal.
Selain itu, pendekatan pemerintahan yang baik—yang menjunjung tinggi prinsip efisiensi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan inklusi—sangat penting untuk memperbaiki tata kelola organisasi pemerintahan daerah. Selain itu, pemerintah daerah harus diberikan akses yang lebih luas ke inovasi digital dalam administrasi publik seperti e-government, e-budgeting, dan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). Ini diperlukan untuk membuat proses pelayanan publik lebih cepat, responsif, dan dapat dilacak.
Kedua, untuk menjamin bahwa tujuan desentralisasi dipenuhi dengan benar, diperlukan peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data (data-driven governance), yang dikenal sebagai pemerintahan yang didorong oleh data. Selama ini, evaluasi kinerja daerah biasanya hanya dilakukan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban tahunan atau LKPJ, yang hanya bersifat naratif dan seringkali tidak mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, sistem pengukuran kinerja daerah yang komprehensif harus dibuat. Sistem ini harus mencakup pengukuran input, output, dan hasil dari semua tugas pemerintahan yang diberikan. Untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan sosial, pengumpulan data harus sistematis, terintegrasi, dan terbuka untuk umum.
Selain itu, peran lembaga pengawasan internal daerah seperti Inspektorat Daerah dan lembaga pengawasan eksternal seperti BPK, KPK, dan Ombudsman harus diperkuat agar evaluasi kinerja daerah tidak hanya administratif tetapi juga substantif, dan untuk mencegah kemungkinan penyimpangan. Jika daerah tidak mencapai kemajuan dalam pengelolaan urusan desentralisasi, pemerintah pusat juga dapat memberikan insentif dan disinsentif berbasis kinerja, seperti memberikan DID atau membatasi dana transfer umum.
Ketiga, peningkatan otonomi daerah harus dibarengi dengan partisipasi publik yang lebih besar dalam perumusan dan pengawasan kebijakan lokal. Demokrasi lokal tidak akan berhasil jika warga hanya menjadi objek pembangunan dan tidak berpartisipasi secara aktif dalam menyuarakan aspirasi mereka dan mengawasi bagaimana pemerintah beroperasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pemerintah daerah untuk memfasilitasi partisipasi publik yang nyata, seperti forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), kanal aduan publik digital, dan penguatan peran lembaga lokal seperti BPD, LPM, RT/RW, dan organisasi masyarakat sipil.
Selain berfungsi sebagai alat untuk mengontrol masyarakat, partisipasi ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan meningkatkan kemampuan politik warga negara. Selain itu, setiap proses pengambilan keputusan di daerah harus melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan masyarakat adat secara aktif. Pada akhirnya, tata kelola daerah yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan akan dihasilkan melalui partisipasi publik yang kuat.
Pada akhirnya, keberhasilan otonomi daerah tidak ditentukan oleh jumlah kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada mereka; lebih baik, itu harus diukur berdasarkan seberapa banyak perda yang dikeluarkan, anggaran yang dikelola, atau seberapa banyak urusan yang ada di daerah. Apakah kebijakan daerah benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi lokal dan melindungi kelompok rentan?
Memperpendek rantai birokrasi, mendekatkan negara kepada warga negara, dan meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik adalah tujuan utama desentralisasi dan otonomi daerah. Namun, banyak hambatan lapangan menghalangi tujuan ini. Ini termasuk ketidaksesuaian regulasi dengan keadaan lokal, birokrasi daerah yang lemah, dan tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa standar hukum dan praktik implementasi selaras. Regulasi yang mengatur kewenangan pusat-daerah harus fleksibel dan memberi ruang untuk inovasi kebijakan lokal tanpa mengabaikan prinsip negara kesatuan.
Selain itu, harmonisasi ini mencakup penggabungan strategi pembangunan daerah dan visi pembangunan nasional. Pemerintah pusat tidak cukup hanya menjadi pengawas dan pemberi mandat; mereka juga harus menjadi mitra strategis bagi daerah dalam membangun kapasitas, memberikan data yang akurat, dan mendorong kolaborasi antarwilayah. Pemerintah daerah, di sisi lain, harus berani mengembangkan kebijakan yang berbasis pada potensi lokal dan kebutuhan warganya daripada terjebak dalam mentalitas administratif semata.
Praktik desentralisasi yang efektif dalam tata kelola publik kontemporer tidak hanya mencakup pembagian kekuasaan secara vertikal; itu juga mencakup sistem pengawasan dan keseimbangan (check and balances), transparansi anggaran, keterbukaan data, dan akuntabilitas publik. Tanggung jawab yang besar diperlukan untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada daerah dan melibatkan pihak non-pemerintah seperti perguruan tinggi, media, masyarakat sipil, dan dunia usaha. Dengan demikian, pemerintahan daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana regulasi dari atas, tetapi juga berfungsi sebagai pembawa perubahan sosial dan pembangunan inklusif dari bawah ke atas.
Akhirnya, keadilan sosial, demokrasi partisipatif, dan pemerataan pembangunan adalah pilar dari otonomi daerah yang efektif. Kewenangan yang diberikan kepada daerah bukan sekadar alat administratif; itu adalah kepercayaan konstitusional negara kepada daerah untuk mengelola urusan internalnya sendiri. Karena itu, semua pihak—baik pusat maupun daerah, birokrat maupun warga negara—memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa otonomi benar-benar menjadi jalan menuju kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat.
Oleh: Lidia
Mahasiswa Universitas Bangka Belitung
lidiaamanda39@gmail.com