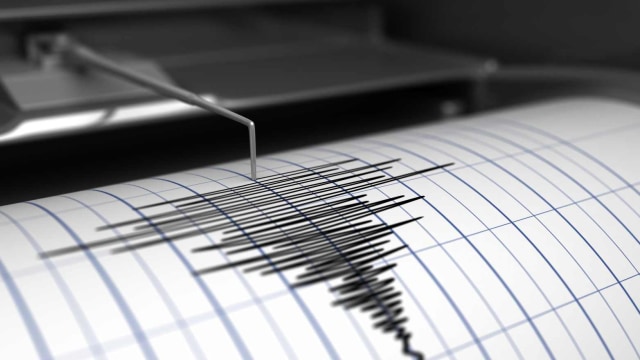Oleh: Sahlan Hanafiah
Sosiolog UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Pendahuluan
Pemilihan umum 2024 di Aceh diramaikan oleh partai politik lokal pendatang baru, yaitu Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh dan Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha’at dan Taqwa (Gabthat). Dua partai politik lokal tersebut melengkapi empat partai politik lokal lainnya yang sudah terlebih dahulu eksis dan berpengalaman bertarung dalam pemilu sebelumnya, yaitu Partai Aceh (PA), Partai Darul Aceh (PDA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh SIRA).
Kehadiran dua partai politik lokal baru itu tentu saja menggembirakan dan harus disambut positif, karena selain akan membawa warna dan alternatif baru bagi demokrasi di Aceh, juga membuat persaingan dalam perebutan kursi legislatif di level kabupaten, kota, dan provinsi semakin seru dan meriah. Namun pertanyaannya, sejauhmana partai politik lokal, baik baru maupun lama mampu bersaing pada Pemilu 2024 dan pemilu-pemilu berikutnya?
Pertanyaan tersebut patut diajukan mengingat trend perolehan kursi partai politik lokal pada dua periode pemilu sebelumnya (2014 dan 2019).
Seperti diketahui, pada Pemilu 2009, pemilu pertama yang digelar pasca Perjanjian Damai Helsinki, partai politik lokal secara keseluruhan menguasai 49% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Namun Pemilu 2014, perolehan kursi partai politik lokal turun menjadi 40%. Begitu pula Pemilu 2019, perolehan kursi partai politik lokal kembali turun hingga tersisa 34%. Fenomena yang sama turunnya dukungan terhadap partai politik lokal juga terjadi merata di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Aceh.
Para peneliti telah berupaya mencari tahu penyebab turunnya dukungan terhadap partai politik lokal, terutama Partai Aceh. Namun mereka umumnya memberikan perhatian pada kinerja partai di parlemen, kurangnya sumber daya, dan pengelolaan partai yang dianggap lemah (Zulfan, dkk, 2023; Ikramatoun, dkk, 2023). Sementara calon legislator yang diusung dan dalam arena politik seperti apa caleg itu bertarung luput dari perhatian para peneliti sebelumnya. Padahal dalam sistem pemilu keterwakilan proporsional dengan daftar terbuka, persaingan terjadi antar calon legislator, baik calon legislator antar partai maupun di dalam partai. Persaingan tersebut terjadi dalam iklim politik patronase (Aspinall, 2014), yaitu politik natulak natarek (Hanafiah, 2021), politik saling memberi dan menerima. Karena itu, kemampuan calon legislator beradaptasi dengan iklim politik seperti itu sebenarnya menjadi kunci keme-nangan partai. Dengan kata lain, yang menentukan meningkat atau berkurangnya jumlah peroleh kursi partai di parlemen bukan sepenuhnya terletak pada kinerja partai politik di parlemen, qanun yang dihasilkan, program yang ditawarkan, dan bagaimana partai politik dikelola, melainkan pada kemampuan calon legislator beradaptasi dalam lingkungan politik patronase.
Dengan demikian, peluang partai politik lokal memenangkan kursi legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota pada Pemilu 2024 sangat tergantung pada seberapa banyak partai lokal memasang calon legislator yang memiliki bakat, hasrat, dan kemampuan menjadi ”sosok yang dermawan”–istilah lain untuk praktek politik saling memberi dan menerima. Untuk mengurai argumen tersebut, berikut ini akan dijelaskan dan digambarkan apa itu politik patronase, mengapa politik semacam itu berkembang dan bagaimana dipraktekkan. Pembahasan tersebut diharapan dapat membe-rikan gambaran tentang medan yang bakal dihadapi oleh para calon legislator, terutama dari partai politik lokal di Aceh.
Apa Itu Politik Patronase?
Para ilmuan sosial dan politik cenderung menggunakan istilah patronase untuk menggambarkan praktik memberi dan menerima dalam politik perebutan kekuasaan. Secara literal, patronase adalah hubungan antara patron dan klien. Kata patron berasal dari Bahasa Latin: patronus, yang bermakna pelindung atau pembela, sementara klien (Latin: cliens) artinya bersandar atau bergantung. Jadi, secara sederhana patronase dapat diartikan sebagai hubungan antara pihak yang kuat (mampu memberikan perlindungan) dengan pihak yang lemah (membutuhkan perlindungan). Model hubungan terse-but umumnya mengakar dalam masyarakat yang memiliki kelas sosial.
Mengutip Alex Weingrod, Theobald (1983) membedakan patronase ke dalam dua jenis, yaitu patronase sosial dan patronase politik. Patronase sosial erat kaitannya dengan masyarakat yang hidup dalam sistem tradisional seperti feodalisme, yaitu sistem dimana yang berkuasa adalah yang menguasai tanah. Dalam sistem tersebut tuan tanah bertindak sebagai patron, sementara buruh tani dalam posisi sebagai klien. Sebagai patron, tuan tanah memberikan lahan untuk digarap oleh petani berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti loyalitas dan kejujuran. Sementara petani, sebagai bentuk terima kasihnya memberikan pelayanan kepada tuan tanah dalam bentuk membantu tuan tanah menjaga keamanan keluarga mereka, membersihkan rumah, menjaga kebun dan hewan peliharaan. Hubungan yang dijalin bersifat saling menguntungkan, namun posisi mereka tidak setara dan cenderung eksploitatif.
Sementara patronase politik menurut Theobald (1983) adalah hubungan antara pihak yang memiliki akses politik dan kekuasaan atau memiliki kewenangan mendistribusikan sumber daya yang mereka kuasai berdasarkan mandat yang mereka terima dengan pihak yang membutuhkan atau menginginkan akses dan sumber daya tersebut. Jadi, pandangan Theobald dapat disederhanakan seperti berikut: patronase politik terjadi di dalam institusi formal pemerintahan, sementara patronase sosial terjadi di dalam institusi informal masyarakat.
Konsep patronase politik yang ditawarkan oleh Theobald (1983) di atas tidak berbeda jauh dari yang diajukan oleh beberapa ahli politik lainnya. Aspinall dan Sukmajati (2015:3) misalnya dengan merujuk pada Shefter mendefinisikan patronase sebagai ”pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individu kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.
Definisi yang lebih sederhana diajukan oleh Ananstasi Piliavsky. Menurut Piliavsky (2014:5), patronase adalah hubungan antara dua orang yang tidak berimbang, salah satu diantara mereka berperan memberi, sementara yang lainnya menerima. Pihak yang memberi (patron) secara ekonomi lebih makmur, secara politik lebih berkuasa atau memiliki keistime-waan dan mereka mengontrol apa yang pihak lain (klien) butuh atau inginkan, sehingga membuat mereka tergantung atau tertekan.
Konsep dan istilah patronase juga seringkali tumpang tindih dengan klientelisme. Stokes (2009, 604-627) misalnya cenderung menggunakan istilah klientelisme. Menurutnya, klientelisme adalah memberikan barang atau jasa sebagai ucapakan terima kasih atas dukungan yang diberikan, dimana kriteria yang dipakai oleh patron adalah: apakah Anda mendukung atau nantinya akan mendukung saya dalam pemilu?
Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa politik patronase merupakan praktek politik saling memberi dan menerima yang dilakukan dalam posisi tidak setara, tidak sukarela, tidak ikhlas, melainkan terpaksa dan eksploitatif di mana satu pihak (patron) memberi sesuatu (barang, uang atau jasa) dengan harapan menerima balasan dalam bentuk dukungan politik, sementara di pihak yang lain (klien) menerima barang dan jasa akan tetapi mereka merasa berkewajiban, kadangkala terpaksa mengembalikan pemberi-an tersebut dalam bentuk dukungan politik. Hubungan tersebut bisa saja terjadi dalam konteks sosial (sedang tidak menjabat atau bukan pejabat publik), namun di balik itu tersimpan agenda politik.
Kondisi-kondisi yang Menyuburkan Praktik Politik Patronase
Mengapa politik patronase tumbuh subur di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia? Di sini paling tidak dapat dijelaskan lima faktor pendorong terjadinya praktek politik tersebut, yaitu: (1) usia demokrasi masih terlalu muda; (2) pemerintah tidak efektif menjalankan fungsinya; (3) norma sosial; (4) angka kemiskinan tinggi; dan (5) sistem pemilu dengan daftar calon legislator terbuka.
Demokrasi baru berkembang
Hagopian (2009:582-603) berargumen bahwa praktek politik patronase memiliki korelasi erat dengan negara yang demokrasinya baru tumbuh. Menurut Hagopian (2009:582-603), negara sedang berkembang umumnya mempraktekkan sistem demokrasi setelah mereka keluar dari sistem lama yang sebelumnya jauh berbeda. Misalnya beberapa negara di Eropa Timur, sebelumnya mereka terpasung cukup lama dalam sistem komunisme di bawah Uni Soviet. Sementara itu, sebagian besar negara di Afrika dan Asia rata-rata baru melepaskan diri dari cengkraman kolonialisme Barat. Demo-krasi juga baru berkembang karena sebelumnya terhalang oleh konflik bersaudara seperti umumnya terjadi di Afrika.
Adapun negara lain, seperti Indonesia dan Filipina baru saja menumbangkan rezim otoritarian. Karena itu menurut Hagopian (2009:582-603), usia demokrasi menentukan kualitas. Jika usia demokrasinya terlalu muda maka tingkat kematangan dalam mempraktekkan demokrasi cenderung rendah. Sebaliknya, semakin tua dan lama sebuah negara mempraktekkan demokrasi maka semakin berpengalaman dan matang demokrasi dipraktekkan.
Negara yang sistem demokrasinya telah lebih maju, strategi mobilisasi pemilih tidak lagi dilakukan melalui pendekatan transaksional, melainkan lebih berbasis pada ideologi atau program. Dalam rangka merebut suara, partai atau kader partai memperkenalkan program, kebijakan atau ”menjual” ideologinya kepada para pemilih. Program, kebijakan atau ideologi yang ditawarkan antar partai politik memiliki perbedaan yang mudah dikenali. Sebagai contoh, partai A yang mengidentifikasikan dirinya sebagai partai liberal mendukung kebijakan pernikahan sesama jenis, semen-tara partai B sebagai partai konservatif melarang pernikahan sesama jenis. Contoh lain yang tidak terlalu ekstrem seperti: partai A mendukung pemberian izin usaha ritel skala nasional seperti usaha toko swalayan masuk ke daerahnya, sementara partai B menolak dan lebih mementingkan pengembangan usaha lokal.
Di negara yang demokrasinya lebih maju, seperti Finlandia, satu partai politik dengan partai politik yang lain memiliki garis damarkasi yang jelas. Misalnya Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (Partai Sosial Demokrasi Finlandia) yang dipimpin oleh Sanna Marin (2019-2023) menawarkan konsep kesejahteraan egalitarian untuk semua warga yang menetap di Finlandia tanpa memandang latar belakang agama, bahasa, dan etnik, sementara Perussuo-malaiset (Partai Finns) lebih memprioritaskan kesejahteraan warga lokal dan mengesampingkan para pendatang. Contoh lain, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue mendukung kebijakan inklusi sosial dan politik, termasuk memberikan ruang yang lebih luas kepada kelompok minoritas seperti LGBTQ untuk mengekspresikan haknya sama dengan kelompok mayoritas lain, sementara Perussuomalaiset membatasi ruang bagi kelompok tertentu.
Di negara dengan demokrasi lebih maju, hubungan antara pemilih dengan kader partai politik relatif setara dan stabil. Pemilih memiliki tingkat independensi dan kemandi-rian yang tinggi sehingga keputusan pemilih tidak dapat dipengaruhi dengan pendekatan transaksional. Di negara yang demokrasinya lebih maju, praktek politik patronase dikate-gorikan sebagai praktek korupsi dan bisa diganjar dengan hukuman yang sangat berat, di mana hal ini bertolak belakang dengan negara yang demokrasinya masih muda seperti Indonesia.
Pemerintah Tidak Efektif
Selain faktor demokrasi yang belum matang, politik patronase juga terjadi karena pemerintah tidak efektif dan maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Misalnya, tugas pemerintah memberikan pelayanan publik secara cepat, murah, dan mudah kepada masyarakat. Namun hal tersebut seringkali tidak terjadi sehingga masyarakat mencari cara lain, jalan pintas untuk mewujudkan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, masyarakat harus melewati prosedur yang panjang dan rumit. Dari pada menunggu terlalu lama, keluarga pasien menghubungi pihak-pihak yang mereka kenal dengan harapan dapat membantu mempercepat proses pelayanan terhadap keluarga mereka. Pihak ketiga yang dihubungi biasanya memiliki pengaruh, mampu menekan pihak rumah sakit agar pelayanan terhadap keluarga mereka dipercepat dan diper-mudah. Pihak ketiga yang membantu keluarga pasien tentu saja memanfaatkan momentum tersebut untuk menun-jukkan pengaruhnya, menciptakan ketergantungan, dan tentu saja berharap dipilih pada saat ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Kelemahan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kehendak politik kekuasaan. Sebagai contoh, seringkali keluarga pasien mengeluh kesulitan mendapatkan akses mobil ambulan untuk membawa keluarga mereka ke rumah sakit atau mobil pengantar jenazah. Momentum seperti itu dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan menyediakan mobil ambulan gratis, lengkap dengan foto, nama, dan lambang partai di sekujur dinding mobil. Aksi tersebut tentu saja sangat manusiawi, namun tidak menyele-saikan masalah struktural pelayanan kesehatan masyarakat di daerah setempat.
Pola yang sama juga terjadi pada sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, atau pendi-dikan. Karena pemeritah tidak efektif memberikan pelayanan, maka masyarakat mencari bantuan pihak ketiga yang memiliki modal ekonomi atau mempunya akses politik ke dalam pemerintah yang menguasai anggaran publik, sementara di sisi lain pihak ketiga juga menanti-nanti momentum tersebut sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan dan pengaruh politik dan dipandang layak menjadi patron yang baik untuk menjadi wakil mereka di parlemen.
Kemiskinan
Kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi juga merupakan salah satu faktor pendorong suburnya politik patronase. Menurut Shin (2015), kemiskinan sebagai faktor terjadinya politik patronase dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi permintaan (demand side) dan penawaran (supply side). Dari sisi permintaan, masyarakat diposisikan sebagai penyebab dari terjadinya praktik patronase karena mereka cenderung pragmatis dan lebih memilih bantuan langsung tunai dibanding program atau kebijakan yang berdampak jangka panjang. Akibatnya para politisi tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti irama masyarakat.
Stoke (2009) misalnya menjelaskan bahwa salah satu karakter masyarakat miskin dan kurang terdidik adalah tidak mau mengambil risiko. Artinya, jika mereka diminta memilih antara bantuan langsung atau kebijakan yang berdampak jangka panjang maka mereka lebih memilih bantuan langsung. Sebab, dalam pandangan masyarakat miskin, memilih kebijak-an akan berhadapan dengan ketidakpastian, belum tentu berdampak langsung terhadap mereka, sementara kebutuhan yang mereka hadapi bersifat harian (daily basis). Karena itu masyarakat miskin tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi pada hari esok. Bagi mereka, memastikan kebutuhan hari ini jauh lebih penting dari pada hari esok.
Sementara dari sisi penawaran (supply side), politisi (yang sedang menjabat maupun tidak) diposisikan sebagai pihak yang sengaja menciptakan iklim ketergantungan dengan membiarkan masyarakat miskin tetap miskin sehingga mereka selalu membutuhkan uluran tangan dari para politisi. Dengan demikian, para politisi lebih mudah mendapatkan dukungan politik karena mereka dipandang sebagai ”patron yang baik” yang suka menolong.
Shin (2015) dari hasil penelitiannya di Jakarta berkesimpulan bahwa praktek politik patronase lebih banyak disebabkan oleh faktor permintaan dari masyarakat miskin dan kurang terdidik (demand side). Hal itu dibuktikan dari partai yang menawarkan program dan kebijakan perolehan suaranya lebih rendah dibanding dengan partai yang menawarkan bantuan langsung. Akibatnya, semua partai politik pada akhirnya menempuh jalan politik patronase. Namun kesimpulan Shin di atas bersifat kasuistik.
Norma dan tradisi
Norma yang berkembang dalam masyarakat juga merupakan salah satu faktor tumbuh suburnya politik patronase. Di daerah tertentu masyarakat memegang norma seperti, ”tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah”. Artinya, orang yang memberi lebih baik dan lebih terhormat di mata masyarakat dan Tuhan dibanding orang yang menerima. Norma tersebut pada prinsipnya baik, khususnya dalam masyarakat yang belum mengenal sistem pemerintahan demokratis, namun dalam masyarakat yang telah menerapkan sistem pemerintahan demokratis, norma semacam itu menjadi kurang relevan, sebab posisi tangan di atas telah diambil alih oleh pemerintah. Pemerintah dibentuk dan diberikan mandat untuk memfasilitasi terciptanya lingkungan dan masyarakat mandiri, independen, dan tidak tergantung pada pihak lain, karena ketergantungan cenderung akan mendorong terjadinya eksploitasi (perbudakan). Akan tetapi seperti telah dibahas di atas, pemerintah seringkali tidak efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga masyarakat mencari bantuan pihak lain atau sebaliknya, situasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sedang mencari dukungan politik. Akibatnya, norma tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah tetap hidup dalam masyarakat meskipun mereka menetap di bawah pemerintahan demokratis.
Ketika norma dan politik patronase saling berkelindan maka di sana terjadi proses reduksi esensi dan manipulasi tujuan. Artinya, prinsip yang awalnya berbasis pada keikh-lasan berbalik tujuan menjadi alat politik mencari dukungan. Nilai ketulusannya hilang. Pihak pemberi memberikan sesuatu, baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa tidak lagi berdasakan pada ketulusan dan keiklasan, melainkan untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk dukungan politik. Artinya, relasi tidak lagi terjadi satu arah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat yang belum mengenal sistem pemerintah demokrasi, melainkan dua arah, dalam bentuk timbal saling memberi dan menerima.
Uniknya kedua belah pihak sadar atau barangkali berpura-pura tidak sadar tetap menilai praktek seperti itu sebagai praktek yang sakral, sehingga semua orang (terutama yang memilikini hasrat berkuasa) berlomba-lomba menjadi pihak yang memberi. Namun pada saat yang sama, keberada-an pihak yang menerima juga menjadi sangat penting. Sebab, jika tidak ada yang menerima, relasi tersebut tidak akan terjadi. Karena itu, sebagai penerima mereka tidak mengang-gap posisinya rendah dan hina, melainkan sebaliknya, merasa terhormat karena telah membantu terjadinya sebuah relasi yang sakral. Akibatnya, jumlah penerima selalu stabil, tidak pernah berkurang. Fenomenan ini menjelaskan mengapa jumlah masyarakat miskin di daerah tertentu tidak pernah berkurang.
Selain norma, tradisi juga menjadi faktor yang memberi tempat bagi tumbuh suburnya politik patronase. Di daerah tertentu misalnya masyarakat memiliki tradisi mentraktir, yaitu membelikan atau membayar makanan dan minuman di warung atau rumah makan untuk orang lain. Pihak yang mentraktir biasanya secara ekonomi lebih mapan dan secara sosial lebih berpengaruh. Sebaliknya, pihak yang ditraktir secara ekonomi dan sosial lebih lemah. Dalam skala yang lebih luas, tradisi semacam itu disebut kenduri, yaitu memberikan atau menyediakan makan dan minuman untuk merayakan atau mengenang peristiwa tertentu—baik susah maupun senang– kadangkala diiringi pembacaan doa. Basis dari tradisi traktir dan kenduri berasal dari norma yang sama: tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah.
Namun ketika bersentuhan dengan politik, esensi dari tradisi tersebut telah bergeser maknanya. Jika sebelumnya untuk membantu yang lemah dan mendapatkan keberkahan dari Tuhan, kini kenduri telah menjadi intrumen memobilisasi suara politik. Akibatnya muncul konstruksi sosial baru di mana pihak yang sering mentraktir dan melaksanakan kenduri dipandang lebih mampu secara ekonomi, sosial dan politik. Mereka juga dipandang lebih pantas mewakili masyarakat di parlemen. Tragisnya, tidak ada yang mempertanyaakan dari mana asal usul sumber dana yang dipakai oleh para politisi dalam menggelar kenduri yang frekwensinya semakin sering dilakukan menjelang pemilu.
Sistem Pemilu
Faktor lain yang menyebabkan tumbuh suburnya politik patronase adalah sistem pemilu (Aspinall, 2014; Shin, 2013: 101-119). Sistem pemilu sebenarnya tidak terlalu problematis jika kualitas demokrasi lebih matang. Namun ketika usia demokrasi masih seumur jagung, sistem pemilu rentan dibajak. Sebagai contoh, sistem pemilu yang berpusat pada partai seperti sistem dengan daftar tertutup dimana pemilih memilih partai politik, bukan kandidat maka politik patronase dilakukan oleh partai politik. Partai politik yang mendistri-busikan barang, uang dan jasa ke konstituennya berdasarkan preferensi tertentu. Sasaran yang dituju biasanya terbatas dan tidak masif karena posisi massa dengan partai berjarak. Sebaliknya, jika sistem pemilu berpusat pada kandidat seperti daftar terbuka maka patronase dilakukan berbasis pada personal. Artinya, masing-masing kandidat bekerja memo-bilisasi suara untuk dirinya, bukan untuk partai. Akibanya praktik politik patronase menjadi sangat massif karena setiap kandidat berupaya mempengaruhi pemilih untuk memilih dirinya.
Strategi Politik Patronase
Bagaimana kursi legislatif dipertahankan dan dimenangkan di dalam demokrasi patronase? Di sini akan dideskripsikan minimal tiga strategi yang sering dipakai, yaitu pork-barrel, patronase, dan serangan fajar.
Pork-barrel adalah sebuah istilah yang mengandung makna negatif. Istilah tersebut merupakan metafora dari praktek pengalokasian anggaran publik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif (terutama yang sedang menjabat) untuk proyek pembangunan yang khusus diperuntukkan bagi daerah pemilihan atau daerah basis dukungan (Sidman, 2019:42-43). Tujuan dari proyek pembangunan tersebut selain untuk mengambil keuntungan finansial dalam bentuk fee juga untuk menyenangkan konstituen sebagai bentuk balas jasa atas dukungan yang pernah atau akan diberikan pada saat pemilu. Praktek semacam itu lazim dilakukan oleh pemerintah sebagai pengguna anggaran bekerjasama dengan partai politik pendu-kung di parlemen. Proses pengalokasian anggaran biasanya dilakukan dengan sangat rapi dan proyek yang dipilih juga sangat selektif sehingga tidak menimbulkan kesan proyek titipan, seperti membangun jembatan, jalan, terminal, sekolah, toilet umum, wastafel, atau irigasi. Namun lokasi proyek yang dibangun dipilih berdasarkan pertimbangan daerah basis dukungan.
Tidak hanya lembaga eksekutif, lembaga legislatif atau anggota legislator juga melakukan strategi pork barrel, yaitu dengan cara ’menitipkan anggaran’ di lembaga eksekutif untuk mendanai proyek pembangunan di daerah pemilihannya. Proyek yang dibangun biasanya tidak berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan masyarakat, melainkan atas pertimbangan menyenangkan para pendukung dan pemilih. Karena itu, kualitas proyek yang dibangun biasanya rendah, tidak berta-han lama, dan cepat rusak.
Di daerah tertentu, pork barrel dikenal dengan istilah dana aspirasi atau dana pokok-pokok pikiran. Pemerintah maupun anggota legislator setiap tahun mengalokasikan ’jatah anggaran’ yang kemudian digunakan untuk membangun daerah basis suara (eksekutif) atau daerah pemilihan (legislatif) masing-masing. Praktek ini dipandang negatif dan dikritik karena pemerintah eksekutif maupun legislatif hanya memberikan perhatian pada daerah ’kantong suara’ atau basis dukungan mereka, sementara daerah di luar basis dukungan diabaikan sehingga pembangunan menjadi tidak merata. Padahal dalam demokrasi, politisi yang terpilih harus mengabdi untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pendukungnya saja. Pork barrel juga dikecam karena strategi tersebut lebih menguntungkan para petahana (yang sedang menjabat) secara ekonomi dan politik dalam menghadapi pemilihan umum.
Patronase
Jika pork barrel dilakukan oleh dan lebih mengun-tungkan para petahana, maka strategi patronase (tentunya dengan varian yang beragam) dilakukan oleh petahana maupun non-petahana. Seperti telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini, patronase adalah hubungan dua pihak, dimana satu pihak (politisi/kandidat) berperan sebagai patron, sementara pihak yang lain (pemilih) sebagai klien. Patron selalu menunjukkan posisinya secara ekonomi lebih makmur dan secara politik lebih kuat, lebih berkuasa, lebih berpengaruh. Sementara klien merupakan pihak yang lemah, yang membutuhkan perlindungan dan bantuan. Dengan kata lain, patron tangannya berada di atas, sementara klien tangannya di bawah.
Petahana atau politisi yang sedang menjabat biasanya lebih mudah menjalankan perannya sebagai patron karena mereka memiliki kewenangan dan akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik yang dikelola oleh pemerintah, seperti akses terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Mereka dapat merancang program atau proyek pembangunan, mengalokasikan anggaran, lalu mengimple-mentasikan sesuai dengan kepentingan politiknya, seperti dalam kasus proyek pork barrel. Namun demikian, posisinya yang strategis sebagai petahana tidak berarti menjamin mereka menang pada pemilu berikutnya. Sebab, yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang bukan pada siapa yang menguasai aset dan akses ke pemerintah, melainkan siapa yang paling terbuka dan luas dalam mendistribusikan aset dan akses yang mereka kuasai tersebut kepada masyarakat.
Jika patron mendistribusikan materi dan jasa hanya untuk kelompok tertentu (disebut patronase sempit), seperti kepada kader partai, tim sukses atau tim pemenangannya saja maka kemungkinan mereka untuk terpilih kembali lebih kecil dibanding yang menggunakan strategi patronase luas, yang menjangkau tidak hanya para pendukungnya, melainkan semua pemilih yang berada di daerah pemilihan tanpa membedakan latar belakang mereka.
Sementara itu, para patron non-petahana atau politisi yang baru pertama sekali bertarung dalam pemilu memiliki tantangan yang jauh lebih berat dari pada para petahana dalam memenangkan kursi legislatif. Sebagai pendatang baru, mereka harus bekerja lebih keras, mengandalkan personalitas dan kapasitas pribadi untuk menyakinkan pemilih bahwa mereka pantas dan mampu menjadi patron yang dapat diandalkan.
Dalam konteks politik patronase di era yang pragmatis, memiliki modal kharismatik, religius, santun saja tidak cukup potensial untuk dipilih. Namun lebih dari itu, seorang politisi juga harus (1) memiliki dan menunjukkan adanya pengaruh dan akses politik yang luas dan (2) sikap kedermawanan yang tinggi terhadap masyarakat. Dua kriteria tersebut merepresen-tasikan sosok ”patron yang baik” di mata masyarakat. Dan tentu saja untuk membangun reputasi sebagai ”patron yang baik” tidak dapat dilakukan dalam waktu satu malam menjelang pemilu, melainkan membutuhkan waktu yang relatif lama, jauh sebelum pemilu digelar, dimulai dari unit masyarakat paling kecil hingga paling besar. Misalnya dimulai dari individu, keluarga, komunitas, organisasi, desa, kecamatan hingga kabupaten dan provinsi. Prinsipnya, semakin luas sasaran pemilih yang berhasil dijangkau maka semakin besar peluang dukungan diperoleh.
Praktik membangun reputasi sebagai patron yang dapat diandalkan sangat beragam. Sebagai contoh, untuk mendapat-kan reputasi sebagai ”patron yang baik” di mata individu tidak cukup sekedar mengajak mereka minum kopi di warung. Namun harus lebih dari itu, membantu mencarikan pekerjaan atau memberikan modal usaha. Begitu pula, agar memperoleh citra yang baik di mata satu keluarga tidak cukup sekedar menanyakan kabar melalui media sosial atau berkunjung ke rumah pada saat hari besar keagamaan, tapi lebih dari itu, berkunjung sekaligus menjadi orang pertama yang memberikan bantuan dalam bentuk jasa, barang maupun uang terutama pada saat-saat tertentu seperti saat sedang ditimpa musibah atau momentum hari bahagia seperti saat menggelar pesta perkawinan, kenduri dan perayaan kelulusan. Bentuk bantuan yang diberikan bisa sangat beragam, seperti menanggung biaya pengobatan bagi yang sakit, membantu biaya pemulangan jenazah keluarga yang meninggal, mengirimkan papan bunga sebagai ucapan selamat–lengkap dengan foto dan logo partai politik, menyumbang makanan, tenda, dan kebutuhan lainnya.
Pada unit yang lebih luas seperti komunitas dan organisasi, patron menawarkan pendanaan kegiatan atau membantu sebagian dari kebutuhan kegiatan. Selain dalam bentuk dana dan barang, patron juga mengambil peran sebagai penghubung (broker politik), menghubungan kelom-pok komunitas dan organisasi dengan patron lain yang lebih tinggi dan lebih berpengaruh. Demikian juga, jika sasaran yang dituju adalah desa atau kemukiman, maka bantuan barang dan jasa yang diberikan bernilai dan berdampak luas bagi masyarakat, seperti menyumbang kursi, tenda, sajadah, alat dapur, dan perlengkapan kenduri. Dengan demikian, semakin tinggi dan besar unit masyarakat yang disasar, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan, dan semakin besar pula peluang memenangkan dukungan politik.
Serangan fajar
Langkah lain yang dilakukan dalam rangka merebut dukungan pemilih biasanya adalah melakukan ”serangan fajar”. Serangan fajar merupakan istilah lain untuk politik bagi-bagi uang yang dilakukan menjelang waktu pemungutan suara. Strategi ini biasanya dilakukan di waktu fajar atau sebelum pemilih keluar dari rumah masing-masing menuju tempat pemungutan suara.
Serangan fajar biasanya menyasar pemilih yang belum menentukan pilihan (swing atau floating voters) atau dilaku-kan sebagai ’tanda jadi’ supaya pilihannya tidak berubah lagi terutama bagi yang telah memberikan komitmen awal. Di luar itu, serangan fajar tidak banyak membantu mendulang suara. Sebab, seperti telah didiskusikan pada bagian sebelumnya, dalam arena demokrasi patronase, yang menentukan kemenangan bukan pada seberapa banyak dan tebal ’amplop’ dibagikan dalam satu momen, melainkan terletak pada kemampuan para politisi (patron) membangun loyalitas dan ketergantungan pemilih (klien) secara terus menerus terhadapnya.
Tiga strategi di atas tentu saja tidak cukup mewakili gambaran umum praktek mobilisasi pemilih yang dilakukan dalam rangka memenangkan kursi legislatif di level kabupaten, kota, dan provinsi yang menjadi arena partai politik lokal. Masih banyak strategi mobilisasi pemilih lainnya yang lebih sophisticated.
Nasib Parlok dalam Arena Politik Patronase
Jika skenarionya seperti digambarkan di atas maka bagaimana kira-kira nasib partai politik lokal, baik baru maupun lama dalam perebutan kursi legislatif di level kabupaten-kota dan provinsi? Seperti telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini, jawabannya sangat tergantung pada kemampuan caleg beradaptasi dengan lingkungan politik patronase dan seberapa banyak partai politik lokal mengusung ”caleg dermawan” yang mampu dan mau menggunakan strategi patronase luas.
Bagi parlok lama, seperti PA, PNA, PDA, dan barangkali juga Partai SIRA, mereka sedikit banyak diuntungkan oleh pengalaman bertarung dalam pemilu sebelumnya, memiliki petahana di parlemen dan struktur jaringan politik yang relatif mapan. Berbekal pengalaman sebelumnya, PA misalnya mulai menyadari pentingnya menjadi partai politik terbuka dengan membuka diri, menampung serta merangkul tokoh-tokoh yang dinilai ”dermawan” untuk dipasang sebagai caleg pendulang suara (Serambi Indonesia 27 Februari 2023). Dalam menghadapi Pemilu 2024, PA juga memasang kader mereka yang pernah menjadi pejabat publik, seperti mantan bupati dan wali kota (Serambi Indonesia, 2 Mei 2023). Strategi tersebut barangkali sedikit banyak akan membantu, minimal mempertahankan perolehan jumlah kursi seperti pada pemilu sebelumnya.
Lalu bagaimana dengan nasib partai politik lokal pendatang baru? Jika parlok pendatang baru hanya mengandalkan modal semangat, mengusung ”caleg dhuafa”, dan tidak menjadikan partai lebih terbuka dengan menyasar segmen yang lebih luas maka kemungkinan untuk dapat bersaing dengan partai politik lokal lainnya, apalagi bersaing dengan partai politik nasional akan lebih sulit. Dengan kata lain, parlok pendatang baru bisa jadi akan bernasib sama dengan parlok yang pernah bertarung pada Pemilu 2009. Jika Pemilu 2009 parlok berguguran karena mereka tidak memiliki identitas dan modal politik ”terlibat dalam perjuangan”, maka Pemilu 2024, parlok tumbang karena mereka tidak memiliki modal menjadi”politisi dermawan”.
Sementara itu, partai politik nasional lebih diuntungkan dengan sistem politik patronase, sebab mereka memiliki potensi modal ekonomi yang lebih besar dan jaringan yang lebih luas. Meskipun caleg dari partai nasional secara personal tidak memiliki modal ekonomi untuk memodali dirinya menjadi ”politisi dermawan”, mereka masih memiliki banyak sumber, cara dan jalan lain yang dapat ditempuh, misalnya berperan sebagai broker politik, menghubungkan pemilih dengan para patron yang lebih tinggi dan besar pengaruhnya di level nasional. Atau mereka membawa pulang proyek pork barrel yang bersumber dari dana yang dikelola oleh pemerintah pusat ke daerah pemilihannya dan mengambil keuntungan dari perannya tersebut. Posisi istimewa seperti itu tidak dimiliki oleh caleg dari partai politik lokal.
Penutup
Tulisan ini tentu saja tidak sedang bermaksud mendorong prakter politik patronase di Negeri Syariat, melainkan berupaya menggambarkan sebuah tantangan politik sekaligus realitas politik yang tidak sehat. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hakikat dari politik patronase adalah ekploitatif, menciptakan ketergantungan dan ketimpangan, melanggengkan kemiskinan, melemahkan institusi demokrasi dan pemerintahan serta mendorong perilaku koruptif para elit. Satu-satunya nilai positif yang dapat dilihat dari model politik patronase adalah mampu meningkatkan partisipasi pemilih datang ke bilik suara. Karena itu untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik maka sistem politik yang dipraktekkan harus direfleksikan kembali.
Daftar Pustaka
Aspinall, E. Mada Sukmajati. (2015) Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia, dalam Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (Ed). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pemilu Legislatif 2014, Penerbit PolGov UGM.
Aspinall, E. (2014). Indonesia’s 2014 Elections: Parliament and Patronage. Journal of Democracy, 25(4).
Hagopian, Frances (2009). Parties and Voters in Emerging Democracies, dalam Carles Boix dan Susan C Stokes (Ed). The Oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford University Press.
Hanafiah, S. (2022). Politik Natulak Natarek. Politik Natulak Natarek – Sagoe.ID
Ikramatoun, S., Zulfan, Z., & Aminah, A. (2023). The Decline of Local Political Parties in Post-Conflict Aceh: A Qualitative Study. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), 4(1), 41-57. https://doi.org/10.22373/jsai.v4i1.2644
Piliavsky, A. (2014). Patronage as Politics in South Asia, Cambridge University Press.
Serambi Indonesia (2023). “Partai Aceh Prioritaskan Calon Incumbent dan Mantan Bupati 2 Periode sebagai Caleg DPRA 2024.” Partai Aceh Prioritaskan Calon Incumbent dan Mantan Bupati 2 Periode sebagai Caleg DPRA 2024 – Serambinews.com (tribunnews.com)
Serambi Indonesia (2023). “Sulaiman Abda Gabung ke Partai Aceh, Dapat Jabatan Ketua Dewan Pakar.” Sulaiman Abda Gabung ke Partai Aceh, Dapat Jabatan Ketua Dewan Pakar – Serambinews.com (tribunnews.com)
Shin, J. Hyeok. (2015). Voter Demands for Patronage: Evidence from Indonesia. Journal of East Asian Studies 15.
Shin, J. Hyeok (2013). Electoral system choice and parties in new democracies: Lessons from the Philippines and Indonesia, dalam Dirk Tomsa dan Andreas Ufen (Ed). Party Politics in Southeast Asia: Clientelism and electoral competition in Indonesia, Thailand and the Philippines. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
Sidman, A. H. (2019). Pork Barrel Politics: How Government Spending Determines Elections in A Polarized Era. New York, Columbia University Press.
Stokes, C. Susan (2009). Political Clientelism, dalam Carles Boix dan Susan C Stokes (Ed), The Oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford University Press.
Theobald, R. The Decline of Patron-Client Relations in Developed Societies. European Journal of Sociology, 24, pp 136-147 doi:10.1017/S0003975600003994
Zulfan, Z., Ikramatoun, S., & Aminah, A. (2023). Aceh Local Political Party: The rise, victory, and decline. Multidisciplinary Science Journal, 5, 2023018. https://doi.org/10.31893/multiscience.2023018
NB: Artikel ini telah publis dalam buku “Aceh 2024: Membangun Martabat Politik Dengan Politik Bermartabat”. Banda Aceh, Bandar Publishing, Desember 2023.