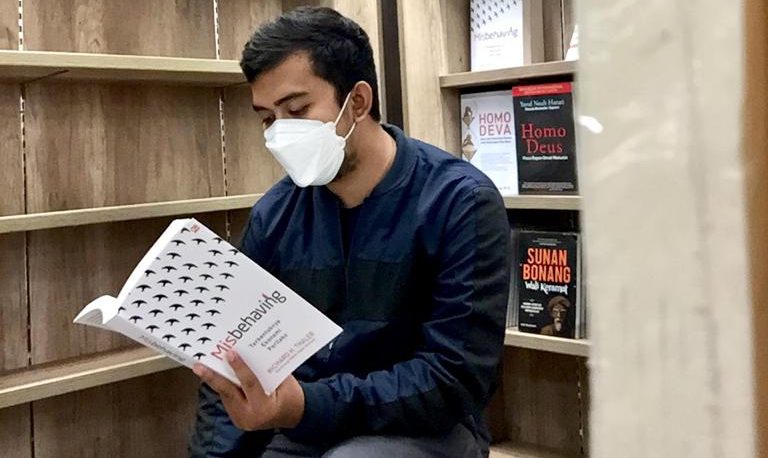Oleh: Rahmat Fahlevi
Mahasiswa Ilmu Politik Fisip Universitas Syiah Kuala
Beberapa kali media dihebohkan dengan berita terkait pemerintah Aceh yang tetap mempertahankan status quo sebagai provinsi termiskin.
Pada tulisan kali ini, saya tidak mengadvokasi pihak tertentu karena saya tidak dibayar untuk menjadi buzzer, troll atau bots pemerintah maupun oposisi.
Marshall plan yang penulis maksud adalah sebagaimana yang dilakukan AS terhadap beberapa negara di dunia untuk melakukan pembagunan sekaligus merecovery kerusakan akibat perang dunia ll. Perang menghasilkan hal yang sangat destruktif baik dari sisi ekonomi, psikologi, politik dan multi dimensi lain yang bahkan sifatnya bisa berkelanjutan.
MoU Helsinki merupakan sebuah traktat internasional yang perfeksionis, multidimensi untuk memperbaiki serangkaian impact destruktif dari perang beberapa dekade antara GAM dan RI.
Namun sayang jauh panggang dari api, point-point tersebut sangat utopia untuk di aktualisasikan.
“Kita tidak memiliki blueprint yang baik”
Saat Indonesia di hebohkan dengan omnibus law hampir semua orang berpikir bahwa RUU sejenis itu hanya pusat yang memiliki wewenang untuk membuatnya.
Nyatanya tidaklah demikian, mengutip dari bukunya Prof. Jimly assiddiqie yang berjudul “Omnibus law” dalam buku tersebut Prof. Jimly mengutarakan bahwa omnibus bahkan bisa di terapkan di tingkat daerah sekalipun. Pemerintah Aceh beserta legislatifnya hanyut dalam konflik interest partai, isu simbol sehingga tidak memiliki alternatif berpikir menyusun blueprint untuk memajukan Aceh yang multi-dimensi.
Saya sangat yakin, sebodoh-bodohnya pemimpin atau legislator pastinya ia memiliki staf ahli yang membisikkan apa yang seharusnya harus dilakukan jika berkaca pada masalah Aceh terkini.
Komitmen pemerintah Aceh terhadap transparansi dan akuntabilitas sangatlah minus yang bahkan membuat saya harus banting stir ke DKI Jakarta untuk membuat analisis APBD tahunan. Proses industrialisasi sangat minim jika pun ada dampak dari corporate social responsibility tidak begitu terasa yang bahkan pemerintah tidak bisa membedakan mana CSR dan corporate philanthropy.
Pemerintah Aceh tidak bisa dijadikan pemegang tongkat tunggal untuk memajukan Aceh, ia hanya sebagai desicion making dan seharusnya pemerintah harus mampu menjadikan korporasi sebagai badan hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan CSR nya disamping program pemerintah sendiri.
Pendidikan Aceh sangat tertinggal jika dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia, hukum yang hanya berfokus pada perihal remeh temeh yang tidak memuat problem utama Aceh kini.
Saya belum pernah melihat upaya pembangunan kolosal ataupun rekayasa konstruksi di Aceh yang sifatnya signifikan yang bertujuan akses untuk distribusi komoditas, bahkan tol pun adalah upaya pemerintah pusat yang membangunnya. Pemerintah Aceh beserta legislatif hanya mandek pada budaya hedonis birokrasi yang selalu mendandadi SKPA, menyusun inventarisir pembangunan berorientasi pada austerity yang setiap tahunnya mengalami proses pembugaran.
Kita selalu dalam delusi “Aceh bangsa teuleubeh ateuh rhueng donya” dan mengidentifikasi diri sebagai Aceh yang kaya akan sumber daya alam sehingga tidak ada upaya untuk selangkah lebih maju beralih ke industrialisasi.
Kegagalan pemerintah dalam mengidentifikasi virtue yang dimiliki Aceh sangatlah fatal akibatnya.
Saya tidak memperpanjang sub tulisan saya ini karena akan berujung kepada ajang curhat.
Semua elemen dalam masyarakat dan civil society mampu mendeteksi patologi di Aceh saat ini yang sifatnya multidimensional mulai dari supremasi hukum, budaya, ekonomi, politik dan lainnya.
“Marshall plan yang saya tawarkan”
Aceh sudah belasan tahun dalam gelimangan dana otonomi khusus yang nominalnya triliunan. Tapi sayangnya Aceh tidak mampu melakukan industrialisasi secara signifikan.
Sebagai anti-tesis, saya pernah membaca beberapa model atau desain negara kesejahteraan dan negara-negata Nordik sangat menarik atensi saya.
Proposisi pertama, yang akan saya susun adalah Aceh sama statusnya seperti negara Irlandia yang berdiametral dengan Inggris.
Irlandia mendapat otonomi khusus sebagaimana Aceh. Terbukti saat Inggris melakukan Brexit tahun 2019 lalu, Irlandia mengeluarkan satu paket kebijakan yang bernama “Withdrawal of the united kingdom from the european union consequential provisions bill 2019” yang dalam RUU tersebut Irlandia menyatakan sikap tetap bergabung ke Uni Eropa walaupun secara teritorial Irlandia bersama Inggris.
Memiliki hak otonomi khusus yang sama seperti Irlandia pertanyaannya, mengapa Aceh tidak ada upaya yang sama untuk itu. Tidak mesti persoalan geografis dan regionalisme ekonomi, bisa saja Aceh menggunakan UUPA/Qanun-nya dengan mengakumulasi beberapa problem utama Aceh serta menuangkan dan memformulasikannya dalam Hukum.
Proposisi yang kedua, di Nordik terkumpul beberapa negara seperti Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark dan Islandia.
Negara-negara tersebut mempunyai desain negara kesejahteraan yang sangat hebat. Mereka meningkatkan pajak progresif dengan mencekik kapitalisme, menciptakan sistem tripartit yaitu sistem yang terkoordinasi antara Pemerintah, korporat dan buruh sehingga tidak menciptakan sistem yang anarki dan terbuka untuk apapun data.
Sistem tripartit ini mengakumulasikan pajak yang cukup besar yang memampukan negara mensubsidi buruh dan masyarakatnya dalam jaminan sosial meliputi pendidikan, kesehatan, jaminan hari tua, yang bahkan pengangguran pun mendapatkan gaji.
Keberhasilan negara-negara Nordik mendamaikan kapitalisme dan buruh ini diabadikan oleh Sosiolog Denmark Gosta esping andersen dalam bukunya yang berjudul “The three world of welfare capitalism”
Aceh memiliki populasi yang relatif sama dengan negara-negara Nordik. Dengan populasi sekecil ini, di stimulus oleh dana otsus triliunan lalu mengapa Aceh tidak mampu melakukan manuver seperti itu? Apakah ada obstacle besar untuk mewujudkan Aceh setara negara-negara Nordik?
Saya tidak menganggap Aceh itu benar-benar miskin walau statistik berkata demikian sekalipun. Karena bicara realitas tidak selalu bisa di kuantifisir oleh per-angka-an. Dan pun saya tidak menganggap otsus itu sebagai significant predictor kemajuan. Masyarakat modern memang demikian selalu berkubang dalam rasio dan data alih-alih kenetralan namun tidak punya alternatif pemikiran yang lain.
Perjanjian Plaza yang dilakukan beberapa negara sekutu cukup membuat para ekonom barat terkejut. Pisau paradigma ekonomi barat mengalami kemandulan eksplanasi untuk menjelaskan keadaan Jepang yang tetap stabil pasca intervensi keuangan/depresiasi secara sengaja terhadap dollar yang dilakukan di hotel Plaza, Prancis.
Pemimpin yang tidak MEMBACA itu sangat BERBAHAYA sebenarnya, ia tidak pernah belajar dari sejarah, tidak punya stok planning dalam upaya replikasi pembangunan ekonomi politik yang baik. Mahatma gandhi adalah contoh upaya pembangunan ekonomi bersifat buttom up. Andai otsus digunakan dengan master plan dan planning function cukup baik, tidak ada budaya hedonis birokrasi serta supremasi UUPA layaknya Irlandia. Mungkin Aceh akan segemilang negara-negara Skandinavia.
Kita semua sangat berharap agar pemerintah Aceh beserta DPRA mempunyai roadmap kerja yang bagus dan tidak hanya menghasilkan kebijakan publik yang bersifat kosmetik atau temporer melainkan kebijakan yang bersifat sustainable development.