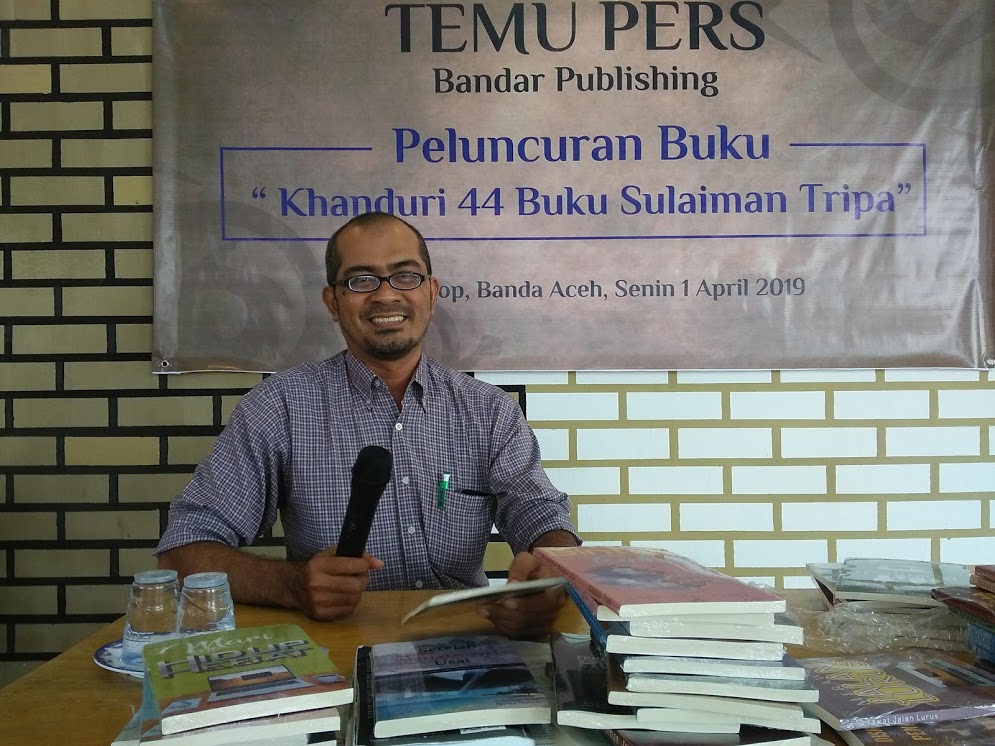Oleh: Sahlan Hanafiah
Staf Pengajar Program Studi Sosiolog Agama UIN Ar-Raniry
Pertanyaan ini sudah lama didiskusikan, tapi tetap saja tidak berujung. Setiap kali musim politik tiba, orang-orang akan mengajukan pertanyaan yang sama: Layak dan patutkah ulama (ahli agama) terlibat dalam politik praktis?
Lebih lagi ketika seorang ulama kharismatik memutuskan untuk terjun langsung ke dunia politik, bertarung dalam Pemilu legislatif maupun Pilkada, maka gema dari pertanyaan itu makin nyaring terdengar. Tentu saja masyarakat terbelah dalam memberikan pandangannya. Paling tidak terbelah ke dalam dua kubu, yaitu yang menolak dan mendukung.
Suara kubu yang menolak biasanya lebih nyaring terdengar karena mereka merasa dalam posisi menjaga kesucian pewaris para nabi (al-ulama waratsatul anbiya’) dari pengaruh buruk politik. Sementara suara kubu yang mendukung acapkali terdengar sayup-sayup. Barangkali karena mereka khawatir dicela dan dihujat.
Argumen kubu yang menolak
Kubu yang menolak ulama terlibat dalam politik praktis umumnya menyodorkan empat argumen. Argumen pertama, ulama adalah milik umat.
Mereka berpandangan, ketika ulama bergabung ke dalam partai politik, maka ulama tersebut tidak lagi menjadi milik umat, melainkan milik partai politik. Begitu pula ketika ulama maju sebagai kepala daerah, maka ulama akan menjadi kepala daerah dari partai politik pengusung dan pendukungnya.
Argumen kedua mengapa mereka menolak biasanya didasari pada rasa khawatir jika nanti umat tidak terurus. Mereka berasumsi bahwa ulama diutus untuk melayani umat, khususnya memimpin ritual agama dan memberikan pengajaran agama.
Namun jika ulama terjun ke dunia politik, mereka khawatir kegiatan keagamaan tidak terurus dan tidak ada lagi yang mengajarkan hukum agama serta memimpin ritual keagamaan. Alasan ketiga mereka menolak ulama terlibat dalam politik praktis adalah karena menilai ulama tidak memiliki pengalaman politik dan kemampuan mengelola pemerintahan. Dalam pandangan mereka, politik dan pemerintahan lebih banyak berurusan dengan kebijakan, administrasi dan birokrasi yang sifatnya sangat teknis. Sementara ulama tidak memiliki kemampuan teknis sedetil itu.
Jika ulama dipaksakan memimpin pemerintahan tanpa pengalaman dan skill yang mumpuni, maka dikhawatirkan pemerintahan yang ia pimpin akan salah urus serta dapat berakibat fatal terhadap dirinya dan hajat hidup orang banyak.
Terakhir yang sering dijadikan alasan menolak ulama terlibat dalam politik adalah karena politik dan agama dilihat sebagai dua dunia yang berbeda. Politik dinilai sebagai dunia yang kotor, sementara agama identik dengan urusan yang suci.
Dalam pandangan mereka, politik cenderung memecah belah, saling sikut, penuh intrik, konflik kepentingan, identik dengan deal-deal politik yang tidak sehat, korupsi, kolusi, nepotisme dan semacamnya. Sementara agama adalah dunia yang jujur, Ikhlas, mempersatukan, harmoni, merangkul, sejuk, dan damai. Karena itulah kelompok yang menolak tidak rela jika ulama sebagai panutan dan teladan terjebak di dalam sebuah dunia yang mereka anggap kotor.
Argumen kubu yang mendukung
Sementara itu, kubu yang mendukung ulama terjun ke dunia politik memiliki argumen sebaliknya. Mereka berpandangan, ulama pada kenyataannya bukan milik umat secara keseluruhan, melainkan milik jama’ah (kelompok, rombongan, kumpulan orang-orang).
Mereka mencontohkan, ulama terbagi ke dalam mazhab tertentu dan tidak seluruhnya diikuti oleh pengikut mazhab lainnya. Ulama terbelah ke dalam organisasi keagamaan tertentu dan tidak seluruhnya dijadikan panutan oleh anggota organisasi keagamaan lainnya. Demikian juga, ulama terbagi ke dalam afiliasi pesantren tertentu dan tidak seluruhnya dijadikan pedoman oleh kalangan pasantren lainnya.
Pada saat yang sama, ulama juga berusaha menambah jumlah jamaahnya, memperluas pengaruhnya dalam masyakat. Karena itu menurut kubu ini, ulama sebenarnya tidak berbeda dari para politisi yang juga mewakili kelompok masyarakat (jamaah) tertentu dan berusaha memperluas pengaruhnya.
Dengan demikian, mengatakan ulama milik umat, lalu menuntut para ulama bersikap netral, tidak memihak atau berdiri di tengah-tengah umat, menurut kubu ini sama sekali tidak realistis.
Kedua, terkait kekhawatiran jika ulama terjun ke dunia politik lalu umat tidak terurus, kubu ini berpandangan sebaliknya. Justru dengan terlibatnya ulama ke dalam dunia politik, kesempatan mengurus umat terbuka lebih luas.
Mereka mencontohkan, jika sebelumnya seorang ulama hanya mengurus pesantren dan santri yang ia pimpin, setelah terlibat dalam politik, ulama dapat mengurus seluruh pesantren dan santri yang ada di wilayah politiknya, baik melalui kebijakan maupun program yang dianggap baik untuk kemajuan pesantren secara keseluruhan.
Begitu pula, jika sebelumnya ulama hanya berkiprah di satu masjid, maka setelah terjun ke dunia politik, mereka dapat berkontribusi melakukan pengembangan terhadap semua masjid yang masuk dalam wilayah politiknya.
Ketiga, soal tidak memiliki pengalaman politik dan kapasitas mengelola pemerintahan. Kubu yang mendukung ulama berpolitik dan terlibat dalam pemerintahan berpandangan bahwa pada dasarnya tidak ada orang yang ujuk-ujuk langsung memiliki pengalaman politik sebelum mereka terlibat dan mengalaminya.
Mereka juga berpandangan bahwa politik bukan profesi yang diperoleh dari jalur pendidikan formal,
seperti jurusan ilmu politik. Menurut mereka, politik adalah arena terbuka bagi siapa saja, dari latar belakang profesi apapun yang memiliki keinginan berkhidmat memperjuangkan sesuatu yang dianggap baik bagi masyarakat dan alam beserta seluruh isinya.
Karena itu melalui sistem politik demokrasi, kubu ini berpandangan, siapa saja boleh bahkan didorong untuk berpolitik praktis untuk memperjuangkan sesuatu yang dianggap baik berdasarkan keahlian yang dimilikinya.
Terakhir, soal politik itu kotor dan agama bersih. Menurut kubu ini, dunia politik dan pemerintahan pada dasarnya tidaklah kotor. Sama halnya dengan agama, tujuan politik adalah baik, yaitu untuk mengurus hajat hidup orang banyak, menjadikan masyarakat dan kehidupan di sekitarnya lebih baik.
Adapun yang membuat politik menjadi kotor menurut kubu ini adalah segelintir oknum politisi busuk yang berkhianat terhadap mandat rakyat dan berkhidmat untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Perilaku kotor mereka itu biasanya terjadi karena lemahnya sistem hukum dan tidak berdayanya masyarakat akibat kemiskinan yang dipelihara dan pendidikan yang tersandra.
Penutup
Lalu di mana posisi saya dalam debat ini? Saya berada di antara dua pandangan kubu ini.
Pada satu sisi saya setuju bahwa politik demokratis merupakan arena yang terbuka bagi semua elemen masyarakat, termasuk para ulama. Artinya, ulama juga berhak terlibat dalam politik, baik langsung (seperti maju pilkada, pileg, mendirikan parpol) maupun tidak langsung.
Namun pada sisi lain harus disadari bahwa arena politik kita saat ini berada di lingkungan dan budaya politik patronase, yaitu pulitek natulak-natarek, pulitek na fee na proyek, pulitek na ureung dalam, pulitek balah jasa. Tradisi politik destruktif semacam ini membuat siapa pun yang berada dalam jabatan politik rentan terseret arus politik negatif yang menghalalkan segala cara.
Oleh karena itu, jika pun ulama hendak terlibat politik praktis, maka selemah-lemah iman yang harus dilakukan pertama adalah membangun budaya politik konstruktif yang tidak meukusuem-kusuem, terbuka dan akuntabel. []