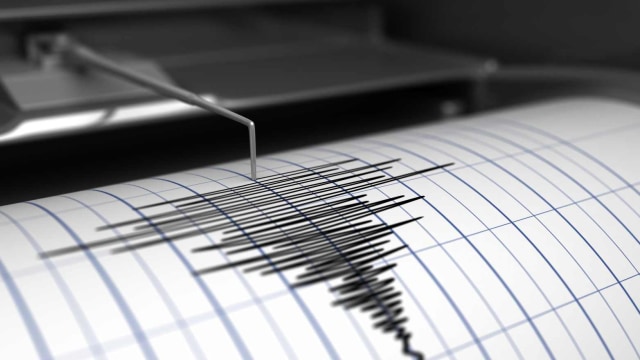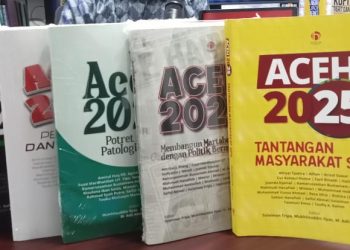Oleh: Fairus M. Nur Ibrahim.
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Kopelma Darussalam, Banda Aceh.
Kita perlu mengubah gaya komunikasi. Jika tidak, pada 2020 atau bahkan setelah itu, orang tua di Aceh pun bisa trauma datang ke masjid.
“Masjid kok gitu sih,” tanya putra bungsu saya tiga tahun lalu. Pertanyaannya muncul, jauh sebelum Wali kota Banda Aceh, Aminullah Usman, mendeklarasikan program “Masjid Ramah Anak” sebagaimana diberitakan media lokal Serambi Indonesia pada pengujung Agustus 2019. Namanya Althaf Ahmadi Nouval. Saat itu ia masih berusia 9 tahun dan tercatat sebagai murid kelas 4 salah satu sekolah dasar di pinggiran Kota Banda Aceh.
Bukan sekali dua Althaf berkeluh-kesah dan menumpahkan kekecewaannya “diusir” dari shaf yang ditempatinya bersama orang dewasa. Padahal, sepulang sekolah, apalagi pada masa-masa libur, ia kerap kali kepincut melaksanakan salat fardu berjamaah di masjid. Semangat ini membuncah di hatinya pasca-booming demam tilawah Muzammil yang sempat melanda Banda Aceh ketika itu. Masjid-masjid yang suara imannya merdu dalam salat bertipe jahar, seperti subuh, magrib, dan isya, sering dikehendakinya untuk disambangi.
Kala Ramadan, semangatnya beribadah pun tak pudar. Namun, di masjid pula ia menemukan masalah. Waktu itu, saat baru saja mengucapkan salam, menyudahi dua rakaat pertama qiyamul lail pada tujuh malam terakhir Ramadan 1439 H, seorang jamaah usia 50-an beranjak dari tempatnya bersimpuh lalu mengham- piri. “Pindah ke sana, ke saf anak-anak yang di belakang,” perintahnya sembari mengisi saf yang ditempati Althaf. Padahal, “Di (saf) belakang nggak bisa dengar suara imam karena ada anak-anak bercanda dan tak serius menger- jakan salat. Udaranya pun panas karena kipas angin tidak dihidupkan,” cerita Althaf kepada saya usai kami melaksanakan ibadah pada dini hari itu.
Sejak kejadian tersebut, Althaf lebih memilih tidur di rumah daripada melakukan salat malam di masjid, baik yang di dekat rumah maupun di tempat lain yang suara imamnya ia gandrungi. Sikap Althaf jadi ibarat langit dan bumi. Semangatnya menuju masjid melorot tajam. Pada- hal, sungguh tak mudah mengajak anak-anak melakukan salat kala dini hari, apalagi pukul 02.30-04.30 waktu barat Indonesia (WBI), ketika serangan kantuk sedang menghujam dengan berat. Alih-alih membuat Althaf lebih dekat kepada masjid, teguran dan cara tak ramah yang ditunjukkan jamaah dewasa terhadapnya menjadi kontra- produktif.
Rupanya tak cuma Althaf. Hampir setiap waktu salat berjamaah di masjid, ada saja anak-anak yang terluka hatinya. Syukri Syamaun adalah contoh lain. Ia memang bukan anak-anak lagi, tapi ayah dari seorang anak yang kecewa akibat mendapat hardikan dan lakap tak patut dari seorang takmir suatu masjid. “Masa, pengurus masjid menyebut anak saya najis, ini sangat merendah- kan,” tuturnya kepada saya saat menceritakan kembali pengalamannya. Ketika bercerita, ekspresi wajah Syukri jelas mengisyaratkan pikiran dan perasaan negatif. Tutur katanya seirama dengan gerak tangan dan perubahan raut muka, termasuk pengecilan pupil dan senyum yang tidak simetris ketika menekankan hal-hal tertentu di dalam kisahnya. Dalam koteks keilmuan komunikasi, aspek kinesik Syukri–seperti kontraksi otot wajah, postur, dan gestur–dapat menggambarkan apa yang sedang ia pikir dan rasa. Tubuh Syukri, sebagaimana tubuh manusia lain, memiliki lebih 600 otot.
Semua itu bekerja bersama-sama secara harmonis sehingga memungkinkan manusia berjalan, duduk, berbicara, atau mengerdipkan mata kepada seseorang. Gerakan-gerakan tubuh ini memiliki potensi sebagai isyarat atau penyampai pesan tertentu. Senyuman yang tulus atau benar-benar senyum sebagai penyampai pesan bahagia, misalnya, hanya akan terjadi bila melibatkan otot mulut, telinga, tulang pipi, dan kerutan di sekitar mata. Sebaliknya, senyuman palsu atau senyum yang dipaksakan hanya melibatkan bibir semata, tidak mengikutsertakan mulut, kerutan mata, telinga, dan tulang di pipi.
Wajah dan gestur Syukri saat bercerita seirama dengan apa yang diucapkannya ketika itu: kecewa. Saking kecewa, pegawai satu instansi vertikal di Aceh ini bahkan menyatakan menaruh “dendam” dan berketetapan hati tidak bakal mengunjungi masjid itu lagi. Syukri tak terima sang anak sibiran tulang dicap begitu rupa.
Apa yang sebenarnya dialami Syukri? Suatu siang menjelang zuhur, ia memutuskan membelokkan motor yang dikendarai ke halaman suatu masjid di bilangan kota Banda Aceh. Bersama sang anak yang baru saja dijemputnya di salah satu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Syukri berniat menunaikan salat zuhur secara berjamaah.
Tak dinyana. Niat baik Syukri rupanya tak menemu- kan ulam. Ibarat kata pepatah, “pucut dicinta, ulam tak tiba-tiba”. Bukannya beroleh suasana hangat saat mengerjakan ibadah, perasaannya malah diaduk-aduk usai menjalani ibadah fardu di siang hari itu.
Ketika iqamah mulai dikumandangkan, kata Syukri, ia beranjak menempati saf kedua. Di depannya, puluhan lelaki dewasa telah membentuk barisan pertama. Imam pun telah tegak di mihrab. Posisi paling ujung di saf kedua sengaja ia pilih agar dapat menempatkan sang anak di sisi kirinya sehingga tak memungkinkan bakal ada jamaah lain yang berdiri setelah itu. Di sebelah kanan Syukri, lelaki dewasa dalam ragam usia–mulai belasan hingga yang berkepala enampuluhan–telah berdiri memenuhi saf.
Seorang takmir rupanya memerhatikan bocah lelaki Syukri. Meski sang anak berdiri di ujung saf, ia merasa tak elok jika ada anak kecil berada di deretan orang dewasa. Sebelum imam melakukan takbir, dengan agak menghardik ia meminta Syukri memindahkan sang bocah dari saf. Si anak terkejut. Syukri pun sama, bahkan merasa malu akibat suara “nyaring” takmir membuat banyak orang melirik ke arahnya. Pun begitu, ia memilih menurut dan tak ingin berdebat: bergeser menuju saf paling belakang.
Di masjid tersebut, saf paling belakang diperuntuk- kan bagi anak-anak. Karena tak ada kelompok anak yang salat di sana siang itu, Syukri dan bocah lelakinya saja yang akhirnya menempati saf tersebut. Syukri sengaja melaksanakan salat di “saf anak-anak” ini, selain karena kecewa kepada takmir, juga untuk menemani dan menyemangati kembali bocah lelakinya yang baru saja dihardik.
Syukri mengaku kecewa berat siang itu. Ucapan takmir yang sengaja mendatanginya usai salat ditunaikan kian menambah luka di hati. “Anak-anak yang belum SD (sekolah dasar) harusnya tak dibawa masuk ke masjid, apalagi berada di saf orang dewasa, mereka itu bernajis.”
Pengganggu Jamaah Senior
Bukan rahasia lagi kalau sebagian orang mengang- gap kehadiran anak-anak di masjid sebagai biang pengganggu kekhusyukan ibadah orang dewasa. Seperti dialami Syukri, ada pengurus masjid yang bahkan menganggap anak-anak membawa najis jika berada di dalam masjid sehingga masjid itu menjadi “zona terlarang” bagi mereka.
Ada pula orang dewasa yang tak segan menghardik dan mengancam secara kasar jika ada anak yang bermain dan bercanda di dalam masjid. Akhirnya masjid menjadi tempat menyeramkan bagi anak-anak. Bagi mereka, sifat Allah yang mahakasih dan sayang tidak terlihat muncul pada perilaku sebagian takmir dan jamaah dewasa. Tak salah jika akhirnya anak-anak lebih mengenal Allah yang mahakeras siksanya dibandingkan maharahim-Nya akibat cenderung dihukum dan diomeli jika bermain-main di dalam rumah Allah itu. Jikapun ada yang sungguh- sungguh beribadah seperti Althaf, mereka pun dianggap tak layak berada di saf terdepan meski datang lebih awal dibanding jamaah dewasa. Padahal, dalam batas-batas tertentu, berada di saf depan merupakan hak bagi siapa yang datang lebih dulu; bukan hak yang didasarkan atas usia.
Sikap “alergi” terhadap kehadiran anak-anak di rumah Allah ini patut kita sayangkan. Apalagi, dalam banyak hal kita kerap berucap secara verbal bahwa anak- anak merupakan aset yang sejak dini semestinya didekatkan kepada masjid.
Akibat perilaku tak ramah dari jamaah yang lebih senior, jangan salahkan bila akhirnya anak-anak mencari lokasi alternatif sebagai tempat beraktivitas. Pilihannya bisa saja ke kafe, game online, atau warkop ber-WiFi. Di sana suasananya lebih menyenangkan, penjaganya pun cantik-cantik dan ramah pula. Di tempat-tempat seperti ini mereka merasa diterima dan dihargai. Sebaliknya, karena representasi sebagian takmir dan jamaah senior, mereka tidak mendapatkan hal itu di masjid. Padahal, masjid sebagai pusat display agama semestinya menjadi tempat mengajarkan Islam, keramahan, dan kasih sayang.
Ahistoris
Perilaku tak ramah sebagian orang terhadap kehadiran anak-anak di masjid tampaknya ahistoris dengan teladan yang pernah ditunjukkan Nabi. Kasus Umamah bisa kita jadikan contoh. Nabi pernah memba- wanya ke masjid dan kemudian melaksanakan salat di sana.
Umamah yang kita sebut adalah cucu perempuan Rasulullah. Selain Hasan dan Husain yang dihasilkan dari perkawinan Fatimah dan Ali Ibn Abi Thalib, Nabi pun memiliki empat cucu lain. Salah satunya Umamah yang lahir dari rahim Zainab, putri sulung sang Nabi.
Para sahabat pernah melihat Rasulullah keluar rumah sambil menggendong Umamah dan membawanya serta saat menunaikan salat. Bahkan, relasi Umamah dan Nabi dalam salat inilah yang kemudian menjadi panduan fikih tentang kebolehan melaksanakan salat sembari menggendong anak.
Sahabat-sahabat yang makmum kepada Rasulullah pernah pula menceritakan peristiwa lain. Nabi melakukan sujud lebih lama dibanding sujud-sujud dalam salat berjamaah sebelumnya.
Usai salat, mereka mempertanyakan situasi itu. Sujud dilakukan dalam durasi lama, ujar sebagian di antara mereka, karena saat itu Allah sedang menurunkan wahyu.
“Tidak,” tutur Nabi dalam hadis yang diriwayatkan An-Nasai. “Itu tidak terjadi (turunnya wahyu), tetapi anakku (maksudnya Hasan dan Husain) menunggangiku. Aku tidak ingin terburu-buru agar mereka puas bermain.”
Para sahabat pernah pula dibuat kaget oleh tindakan Nabi yang tiba-tiba menuruni mimbar. Penyebabnya tak lain kecuali perilaku Hasan dan Husain. Sebagaimana lazim dilakukan anak-anak di dalam masjid, bermain bahkan menangis, kedua cucu Nabi pun berperilaku sama.
Nabi menghampiri dan berupaya menenangkan dua cucunya itu. Sesudah keduanya menurut, Nabi pun kembali menaiki mimbar, melanjutkan khutbah yang tadi tertunda.
Sikap Nabi kepada cucu yang “mengusilinya” kala mengimami salat atau bermain-main di masjid dapat dirujuk pada sejumlah hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Abi Syaibah, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Baihaqi, Abu Ya’la, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, dan Hakim. Hadis-hadis ini, ada yang bersumber dari Buraidah, ada pula dari Abu Hurairah. Didasari atas kodifikasi sejumlah hadis tersebut, maka takmir dan jamaah dewasa mestinya bisa lebih toleran kepada anak- anak yang berada di dalam masjid.
Pun begitu, tentu saja toleransi ini tidak serta merta melepaskan orangtua dari tanggung jawab membawa anak ke masjid. Mereka tidak boleh cuek, tetapi mesti menjaga kesucian dan mengajarkan adab berada di masjid. Jangan diam saja jika anaknya membuat ribut, jangan pula tak melengkapinya dengan popok agar tak membuat masjid terkotori oleh kotoran sang anak.
Well. Belajar dari sikap Nabi terhadap ketiga cucunya, agaknya kita memang perlu lebih ramah terhadap anak-anak agar tak ada lagi orangtua yang perasaannya teraduk-aduk seperti Syukri atau yang motivasi ke masjid terdegradasi seperti Althaf.
Karena itulah, kita mengapresiasi, mendoakan, dan memberi standing applause terhadap pimpinan daerah, petua masyarakat, tokoh keagamaan maupun aktor-aktor politik, yang menyampaikan gagasan dan kemudian benar-benar berupaya mewujudkan gagasan menjadikan masjid–melalui jamaah dan takmir-nya–menaruh peduli terhadap anak dan bersikap ramah kepada mereka. Secara khusus saya ingin memberi apresiasi terhadap Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, yang pada 2019 telah secara eksplisit menyampaikan komitmen menjadikan seluruh masjid di Banda Aceh dalam kondisi ramah anak.
Saya haqqul yaqin, Pak Wali tak bakal sekadar melengkapi aneka fasilitas, tapi dengan berbagai cara akan pula meng-up-grade karakter, pemahaman, serta gaya komunikasi sebagian takmir maupun jamaah senior terhadap anak-anak yang notabene menjadi jamaah yunior di lingkungan masjid. Di luar itu, Pak Walikota pun–tentu saja termasuk pula para pemangku kepentingan di seluruh kabupaten/kota di Aceh–perlu care serta mau meningkatkan awareness-nya bahwa untuk maksud seperti itu, tak boleh ada pembiaran terhadap tindakan-tindakan radikal dan tak ramah seperti merebut, mengganggu, bahkan berbuat anarkis di dalam masjid.
Jika Pak Wali, Pak Bupati, dan para stakeholder membiarkan ini terjadi; jangankan anak-anak, pada 2020 atau bahkan setelah itu, orang tua dan orang tua-tua di Aceh pun bakal trauma datang ke masjid. Nah! [Sumber: Sebagian dari isi buku “Aceh 2020, Diskursus Sosial, Politik, dan Pembangunan”)