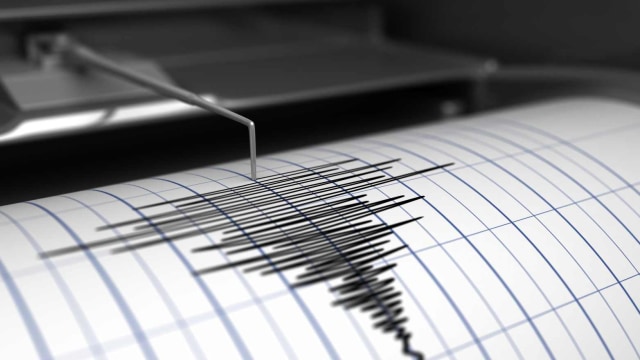Pada tanggal 18-19 Agustus 1998, ada hajatan penting yang dilaksanakan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, United Nation Development Program (UNDP), dan Ford Foundation, yakni Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Hadir sebanyak 15 pakar waktu yang menjadi pembicara, antara lain Prof. Dr. Muladi, S.H., Dr. Ir. Muslimin Nasution, Mas Ahmad Santosa, S.H.,LLM., Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H.,MCL.,MPL., Arie Suganti Hutagalung, S.H.,LLM., Prof. Dr. Hasanu Simon, Sulaiman N. Sembiring, S.H., Dr. Setijati D. Sastradipradja, TA. Nurwinakun, S.H., Chalid Muhammad, S.H., Ir. Budiman Arief, Ir. Sudar D. Armando, M.Agr., Dr. Etty R. Agoes, S.H., Gayatri L. Lilley, M.Sc., dan Prof. Dr. TO. Ihromi, S.H.
Ada dua hal yang menarik –sekaligus penting dan strategis—terkait kegiatan ini. Pertama, dengan coba melirik kembali situasi sosial-ekonomi-politik pada tahun 1998 yang tidak baik-baik saja, masih ada sekelompok orang memikirkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. Saya kira, kondisi dan situasi tersebut tidak mudah untuk direspons, saat sedang gejolak yang terjadi saat pergantian kepemimpinan nasional setelah melalui demo mahasiswa: tanggal 21 Mei 1998. Setelah mundurnya Presiden Soeharto, Wakil Presiden BJ. Habibie naik menjadi presiden Indonesia yang ketiga.
Walau ada angin segar yang dibangun Habibie, gejolak masih terasa. Belum lagi ada banyak persoalan bangsa dan daerah yang muncul ke permukaan, selain masalah SDA, misal gugatan sejumlah daerah terkait negara kesatuan, serta hal-hal substansi dan hakikat kenegaraan dibicarakan secara bebas.
Kedua, inisiatif untuk merekam berbagai hasil lokakarya tersebut dalam sebuah buku yang berjudul Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dokumen buku ini menjadi sangat penting bagi proses pembelajaran –kalaupun tidak sampai pada upaya melihat bagaimana politik hukum yang dijalankan negara dan pengelolanya terkait SDA. Makanya saya akan melihat tiga makalah saja yang terkait dengan apa yang mau saya tuliskan, yakni Muladi, Mas Achmad Santosa, dan TO Ihromi.
Buku ini sendiri diterbitkan pada April 1999. Dengan demikian ada jeda sekitar setengah tahun dari pelaksanaan lokakarya hingga terbitnya buku. Dan saya tahu, tradisi semacam ini –baik dulu maupun sekarang—tidak dimiliki oleh semua komunitas ilmiah. Hanya sedikit saja yang berpikir jauh semacam ini, dan salah satunya, saya kira ICEL ini.
Dalam pengantar buku, Mas Achmad Santosa menyebut dengan tegas bahwa politik hukum SDA di Indonesia sampai saat ini (1999) lebih didasarkan pada kepentingan kebutuhan investasi dalam rangka pemulihan ekonomi pada awal Orde Baru (setelah 1966). SDA (hutan, tambang, air, dan mineral) dipandang serta dipahami dalam konteks economic sense dan belum dipahami sebagai ecological and sustainable sense.
Ada keseyogiaan yang idealnya harus dilihat dalam konteks perkembangan kebijakan di Indonesia. Diperkenalkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN Tahun 1973), seharusnya kebijakan dalam memahami SDA sudah berubah. Kebijakan yang lahir setelah Deklarasi Stockholm Tahun 1972. Nyatanya juga tidak berubah. Padahal Indonesia sendiri ikut terlibat secara aktif dalam pertemuan penting tersebut (Salim, 2010). Secara pemahaman, sudah diperkenalkan bahwa SDA tak semata mempertimbangkan economic sense, melainkan juga lingkungan, lingkungan sosial, dan keberlanjutannya.
Dalam makalahnya, Muladi mengutip isu GBHN 1973 yang menyebut, “… dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan menyeluruh dan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang”.
Realitasnya waktu itu, dalam pemanfaatan SDA lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi. SDA semata-mata dilihat sebagai aset untuk mengeruk devisa sebesar-besarnya dan kurang mempertimbangkan kelestariannya (Muladi, 1999).
Kondisi tersebut, turut disampaikan pula Mas Achmad Santosa dalam makalahnya dalam lokakarya, “Reformasi Hukum dan Kebijaksanaan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam”. Ia menulis, kondisi kebijakan Orde Baru demi kepentingan kebutuhan investasi. Sejumlah UU yang lahir waktu itu, misal Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, dikeluarkan sebagai paket pembuka pintu bagi penanaman modal asing dan dalam negeri melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pengelola negara tidak mempertimbangkan keterbatasan daya dukung dan kerentanan dari SDA (Santosa, 1999).
Ada satu paparan yang waktu terkait masyarakat hukum adat disampaikan oleh Prof. TO. Ihromi, terkait bagaimana harusnya MHA harus mendapat tempat dalam pembangunan. MHA mengandalkan SDA untuk sumber kehidupan, namun memiliki cara yang baik dalam pengelolaannya. SDA itu menjadi lebensraum bagi mereka dengan menggunakan aturan-aturan adat sebagai aturan mainnya (Ihromi, 1999).
Saya membayangkan, apa yang didiskusikan hampir tiga dasawarsa sebelumnya, ternyata diulangi lagi dalam ulang tahun ke-28 ICEL, di Jakarta tanggal 22 Juli 2021. Salah satu simpulan penting, titik balik hukum lingkungan di Indonesia, yang dulu termasuk dalam jajaran negara yang menjadi pionir dalam menunjukkan keberpihakan pada lingkungan hidup dan gagasan pembangunan berkelanjutan, kini justru regulasinya mengalami kemunduran.
Perbedaannya, dulu awal Orde Baru yang dikritik adalah orientasi investasi, kini dengan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi titik baliknya. Pendiri ICEL, Mas Achmad Santosa menyebut, lengkah progresif di bidang hukum lingkungan mengalami kemunduran dengan UU Cipta Kerja. UU ini mengubah berbagai peraturan terkait dengan SDA, tidak ada referensi pembangunan lingkungan berkelanjutan dalam konsiderans dan batang tubuhnya. Padahal UU sektoral saja memberi referensi pada perlindungan lingkungan (Arif, 2021).
Hadir dalam diskusi penting tersebut, Prof. Emil Salim –seorang tokoh ekonomi dan lingkungan hidup Indonesia yang secara langsung menjadi saksi dalam Pertemuan Stockholm dan sesudahnya. Menurutnya, kepentingan antargenerasi, generasi 2045 harus kita selamatkan dengan menyelamatkan lingkungannya. Dengan hukum lingkungan yang tegak dan diakui, bahwa lingkungan bukan hanya dipidatokan, tetapi dihidupi sebagai bagian Tanah Air Indonesia.
Wallahu A’lamu Bish-Shawaab.
[es-te, Kamis, 17 April 2025]