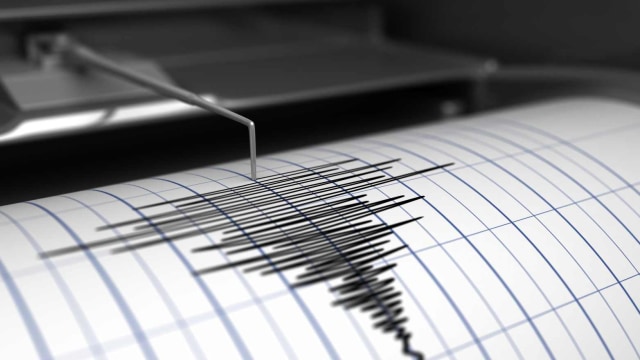Oleh: Ari J. Palawi
Ketika saya menulis artikel “Industri Kreatif Aceh: Panggung Kosong, Sistem Palsu“, yang memantik banyak reaksi dan debat, satu hal yang terus mengemuka adalah bahwa kita sedang mengobati gejala, tetapi mengabaikan akar. Persoalan industri kreatif Aceh tidak berdiri sendiri. Ia terhubung langsung dengan lemahnya posisi pendidikan seni, baik secara struktural dalam sistem pendidikan, maupun secara kultural dalam cara pandang masyarakat terhadap seni itu sendiri.
Padahal jika kita jujur membaca sejarah, seni dan kebudayaan bukan sekadar pelengkap pembangunan, melainkan fondasi peradaban. Bangsa-bangsa besar di dunia—dari peradaban Islam klasik hingga Eropa pasca-Renaissance—bertumbuh di atas pemuliaan terhadap karya seni, pemikiran simbolik, dan ekspresi budaya. Sayangnya, di Aceh hari ini, warisan budaya yang kaya belum diiringi dengan sistem pendidikan seni yang kuat dan berkelanjutan.
Teknik dan Kedokteran Dihormati, Mengapa Seni Tidak?
Kita hidup di masyarakat yang menghormati profesi dokter dan insinyur. Mengapa? Karena hasil kerjanya terlihat: rumah sakit berdiri, jembatan menghubungkan, penyakit sembuh. Tapi seni juga menghasilkan—ia menciptakan harmoni sosial, pemulihan psikologis, dan jati diri kolektif. Bedanya, hasilnya tidak selalu berbentuk bangunan atau alat, melainkan makna, kesadaran, dan relasi antarmanusia.
Kita lupa bahwa bendera, lagu kebangsaan, arsitektur masjid, hingga motif-motif ukiran adat yang kita banggakan—semuanya adalah hasil kerja artistik. Bahkan UNESCO mengakui bahwa pendidikan seni berkontribusi signifikan pada penguatan kompetensi sosial dan budaya anak (UNESCO, 2006 – Road Map for Arts Education) [Sumber: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384200]
Hilangnya Seni dari Ruang Hidup Aceh
Namun hari ini, nilai seni perlahan menghilang dari ruang-ruang kehidupan di Aceh. Kota dibangun dengan beton, tanpa konsep estetika atau simbol budaya lokal. Sekolah-sekolah umum tak lagi menyediakan guru seni yang kompeten atau ruang praktik yang layak. Dalam dokumen anggaran publik Aceh (APBA/APBK), pendidikan seni nyaris tak disebut—jika pun ada, sering kali hanya untuk kegiatan seremoni atau lomba-lomba tahunan.
Sementara itu, Data Kemendikbudristek menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, usulan formasi ASN untuk guru seni budaya dari pemerintah daerah sangat minim, yang berdampak pada terbatasnya rekrutmen pengajar seni budaya.
Lebih memprihatinkan, program studi seni di kampus-kampus Aceh bertahan dengan sumber daya terbatas. Mahasiswa yang sebenarnya punya talenta luar biasa seringkali dinilai dengan standar akademik formal yang tak memahami laku seni sebagai proses, bukan sekadar angka.
Mengubah Cara Pandang: Pendidikan Seni adalah Pendidikan Manusia
Sudah saatnya kita mengubah cara pandang. Pendidikan seni harus diposisikan sejajar dengan kedokteran, teknik, dan hukum. Karena seni mendidik bukan hanya kemampuan, tetapi kemanusiaan. Ia menumbuhkan empati, keberanian menafsirkan zaman, dan kecakapan mencipta makna di tengah kekacauan sosial.
Beberapa negara telah menunjukkan jalan. Finlandia telah mengintegrasikan seni dan kreativitas ke dalam kurikulum pendidikan dasar melalui pendekatan pembelajaran interdisipliner dan kompetensi transversal, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kreatif dan ekspresi diri.” (OECD, 2015) [Sumber: Future of Education and Skills 2030/2040 | OECD]. Di Jepang, pendidikan budaya lokal diwajibkan untuk menjaga identitas daerah sekaligus membangun apresiasi lintas generasi. Di Kuba, sekolah seni menjadi episentrum produksi budaya nasional.
Apa yang Bisa Kita Lakukan di Aceh?
Berikut beberapa langkah konkret yang bisa ditempuh untuk membangun pendidikan seni di Aceh sebagai bagian dari pembangunan peradaban:
- Masukkan pendidikan seni ke dalam kebijakan prioritas pembangunan daerah – tidak hanya di dinas kebudayaan, tetapi juga di pendidikan dan perencanaan.
- Bangun ekosistem sekolah seni yang terintegrasi dengan komunitas dan warisan budaya lokal.
- Perkuat posisi program studi seni di perguruan tinggi dengan dukungan infrastruktur, beasiswa, dan pelatihan dosen.
- Dorong kemitraan antara media, seniman, akademisi, dan pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan seni.
- Evaluasi ulang pendekatan MBKM atau program sejenis agar benar-benar menyentuh nilai dan praktik budaya lokal.
Seni, Martabat, dan Masa Depan Aceh
Tulisan ini bukan nostalgia budaya, bukan juga romantisasi masa lalu. Ini adalah seruan agar kita tidak kehilangan fondasi kebudayaan kita sendiri. Karena jika pendidikan seni terus dipinggirkan, maka kita sedang melemahkan akar peradaban kita secara perlahan.
Saya mengajak pemerintah daerah, institusi pendidikan, orang tua, komunitas budaya, dan media seperti Sagoe TV untuk bersama-sama mengangkat martabat pendidikan seni. Bukan sekadar mengisi acara atau menampilkan hiburan, tapi membentuk manusia-manusia yang utuh: sadar akar, terbuka nalar, dan berani bermakna.
Jika kita ingin Aceh yang adil, cerdas, dan bermartabat di masa depan—maka pendidikan seni bukan tambahan, melainkan keharusan. []
Penulis adalah Pendiri Geunta Seni Jauhari (sejak 2022); Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Seni Universitas Syiah Kuala (2010-2020; Ketua Jurusan Pendidikan Seni (2017-2020). Ia menulis, meneliti, dan mencipta karya yang menghubungkan penciptaan artistik, pengabdian budaya, dan kebijakan publik. Fokusnya banyak pada wilayah-wilayah non-sentral dan suara komunitas.