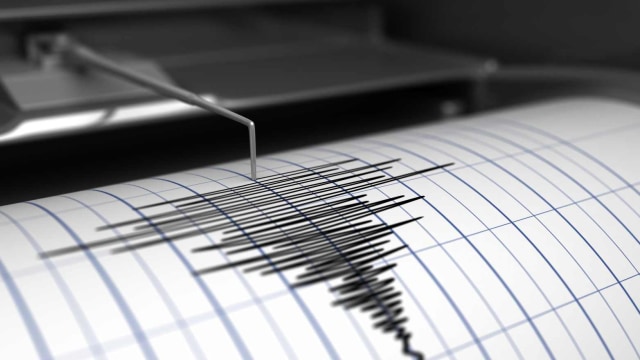Oleh: Harjoni Desky
Ketua Prodi S2 Ekonomi Syariah UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
“Abang, bisa bantu desain logo untuk usaha saya?” tanya seorang pemilik Keude sembako di Lhokseumawe. Yang ditanya bukan mahasiswa desain grafis atau lulusan politeknik, melainkan santri dayah yang baru saja menyelesaikan kursus daring tentang Canva dan pemasaran digital. Ia belajar secara otodidak, di sela waktu mempelajari kitab kuning. Inilah potret baru generasi muda Aceh – santri yang bukan hanya ahli fikih, tapi juga mulai memahami dunia digital.
Aceh, daerah yang dikenal dengan identitas keislamannya dan basis pendidikan dayah (pesantren tradisional), kini tengah menghadapi tantangan besar: tingginya pengangguran muda dan stagnasi ekonomi lokal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda usia 15–24 tahun mencapai 14,8%, salah satu yang tertinggi di Sumatera. Di sisi lain, ribuan santri lulus dari dayah setiap tahunnya, namun sebagian besar menghadapi keterbatasan akses ekonomi dan lapangan kerja.
Apakah mungkin santri menjadi ujung tombak kebangkitan ekonomi Aceh melalui dunia digital?
Dayah selama ini dikenal bukan hanya sebagai pusat pengajaran ilmu agama, tetapi juga sebagai benteng moral dan pembentuk karakter generasi muda Aceh. Pola pendidikan di dayah menanamkan disiplin tinggi, ketekunan, kesabaran, serta kesungguhan dalam menuntut ilmu. Nilai-nilai ini terpatri kuat dalam kehidupan santri sehari-hari, membentuk pribadi yang tangguh, sederhana, dan berjiwa mandiri. Inilah yang menjadikan dayah sebagai institusi pendidikan berbasis nilai yang tetap relevan di tengah perubahan zaman.
Ketika para santri diberi akses terhadap teknologi dan literasi digital, mereka menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Kemampuan memahami alat dan platform digital tumbuh cepat, terlebih karena mereka terbiasa belajar secara mandiri dan intensif. Santri yang terbiasa membaca kitab kuning kini mulai terbiasa pula membaca data, mengolah visual, bahkan memproduksi konten dakwah yang menarik melalui media sosial.
Modal sosial yang telah dibangun dayah selama ini, jika disinergikan dengan keterampilan digital, akan melahirkan generasi baru santri yang tidak hanya saleh secara spiritual, tetapi juga produktif secara ekonomi.Beberapa inisiatif telah dimulai. Di Bireuen, misalnya, sebuah lembaga pelatihan informal bekerja sama dengan dayah untuk mengajarkan dasar-dasar desain grafis dan pengelolaan media sosial. Hasilnya, santri tidak hanya bisa mengelola akun dakwah di TikTok atau Instagram, tapi juga mulai menerima pesanan desain, editing video, bahkan membuat konten promosi UMKM lokal. Ini adalah lompatan penting menuju integrasi ke ekonomi digital.
Meski potensinya besar, tantangan juga tidak kecil. Pertama, akses infrastruktur digital di banyak daerah Aceh masih sangat terbatas. Koneksi internet yang lambat atau tidak stabil menjadi penghalang utama untuk pembelajaran daring dan praktik keterampilan digital.
Kedua, kurikulum dayah umumnya belum mengintegrasikan aspek literasi teknologi. Fokus utama masih pada penguasaan ilmu-ilmu agama klasik. Meskipun penting, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan wawasan dunia modern agar lulusannya relevan dengan kebutuhan zaman.
Ketiga, masih ada resistensi dari sebagian kalangan yang memandang bahwa keterlibatan santri di dunia digital bisa mengganggu keikhlasan dalam belajar agama atau bahkan membawa pengaruh buruk dari luar. Ini adalah tantangan kultural yang perlu dijawab dengan pendekatan bijak, bukan konfrontatif.
Untuk menjawab tantangan transformasi digital di lingkungan dayah, diperlukan pendekatan yang kolaboratif dan lintas sektor. Tidak mungkin beban ini ditanggung oleh dayah seorang diri. Pemerintah daerah perlu mengambil peran sebagai fasilitator utama dengan merancang kebijakan afirmatif yang mendorong integrasi teknologi dalam pendidikan tradisional. Ini bisa diwujudkan melalui penganggaran program literasi digital untuk dayah, penyediaan infrastruktur internet di lingkungan pesantren, hingga pelatihan guru-guru agama agar mampu mengakses dan mengelola sumber-sumber pengetahuan digital.
Di sisi lain, sektor swasta, khususnya perusahaan-perusahaan teknologi dan lembaga keuangan syariah, dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan ekosistem talenta digital berbasis dayah. Melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), mereka bisa mendanai pelatihan keterampilan digital, mentoring wirausaha berbasis teknologi, serta menyediakan akses perangkat lunak atau perangkat keras yang dibutuhkan. Dengan keterlibatan swasta, proses transformasi ini tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga tumbuh dari sinergi kebutuhan industri dan potensi lokal.
Institusi pendidikan tinggi juga memiliki peran penting sebagai katalisator inovasi. Kolaborasi antara kampus dengan dayah dapat membuka ruang transfer pengetahuan dan teknologi secara terstruktur. Mahasiswa dan dosen bisa dilibatkan sebagai pendamping atau pelatih dalam program digitalisasi pesantren. Bahkan, dengan model pengabdian masyarakat yang terintegrasi, perguruan tinggi dapat menjadikan dayah sebagai laboratorium sosial untuk mengembangkan pendekatan pendidikan yang berbasis nilai, teknologi, dan pemberdayaan ekonomi. Bila semua pihak bergerak bersama, maka visi membangun talenta digital dari dayah bukan hanya wacana, melainkan agenda strategis pembangunan Aceh.
Bayangkan jika dalam lima tahun ke depan, dari 1000 dayah di Aceh, masing-masing meluluskan minimal 5 talenta digital. Itu berarti 5000 santri digital yang siap masuk ke pasar kerja global – mulai dari content creator, social media manager, UI/UX designer, hingga web developer. Lebih dari sekadar keterampilan teknis, santri digital juga membawa etika kerja dan nilai-nilai Islam yang menjadi pembeda – tanggung jawab, kejujuran, dan niat untuk maslahat.
Aceh tidak kekurangan sumber daya. Yang kurang adalah desain strategis untuk mengoptimalkan potensi manusianya. Santri, yang selama ini hanya ditempatkan sebagai penjaga tradisi, sebenarnya memiliki daya dorong besar sebagai agen perubahan.
Jika selama ini Aceh dikenal karena warisan ulama, maka kini saatnya melahirkan generasi santri teknokrat – mereka yang mampu berdakwah lewat platform digital, membangun usaha lewat jejaring daring, dan membawa wajah baru Islam Aceh yang progresif dan solutif.
Digitalisasi bukan ancaman bagi nilai-nilai keislaman. Justru sebaliknya, ia bisa menjadi kendaraan dakwah dan penguatan ekonomi umat – bila dipandu dengan visi yang benar. Talenta digital dari dayah bukan lagi mimpi. Ia sedang tumbuh. Tinggal apakah kita mau menyiramnya, atau membiarkannya layu karena ketidakpedulian.
Karena pada akhirnya, masa depan Aceh tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang terus terkikis, melainkan oleh sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dan menciptakan nilai. Santri yang mampu membaca zaman, bukan hanya kitab; yang fasih berdakwah di mimbar, tapi juga di dunia maya. Inilah generasi yang kita tunggu – generasi yang akan menulis ulang narasi pembangunan Aceh, dengan tangan-tangan yang terampil, hati yang bersih, dan visi yang bercahaya. Jika dayah mampu melahirkan ulama besar masa lalu, maka ia juga mampu melahirkan arsitek peradaban digital masa depan. Semoga.