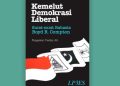Oleh: Ari J. Palawi
“Mate aneuk meupat jeurat, gadoh adat pat tamita?!”
(Biarlah anak mati terbunuh, tapi adat jangan sampai hilang?!)
— Penegasan adat dalam hikayat Sultan Iskandar Muda, dikutip dalam buku “Inilah Pesan-Pesan Indatu (Nenek Moyang) Orang Aceh”
Dari Legitimasi Simbolik ke Legitimasi Sosial
Keberadaan Wali Nanggroe saat ini sah secara hukum. Ia dilembagakan melalui Qanun, diakui dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), dan dijalankan dalam struktur resmi Pemerintah Aceh. Tetapi sah secara hukum belum tentu berarti legitim secara sosial. Banyak masyarakat — terutama generasi muda, pelaku seni budaya, akademisi, dan masyarakat adat non-dominan — yang masih bertanya: apa arti kehadiran Wali Nanggroe dalam hidup kami?
Pertanyaan ini bukan bentuk perlawanan, melainkan isyarat bahwa legitimasi simbolik tidak cukup. Penghormatan kultural tidak lahir dari struktur formal, tetapi dari hubungan hidup antara lembaga dan masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif, tanpa kehadiran nyata di tengah peristiwa sosial dan dinamika kebudayaan sehari-hari, simbol akan kehilangan makna, dan legitimasi akan merosot menjadi seremonial belaka.
Artinya, Kelembagaan Wali Nanggroe perlu melampaui batas-batas protokoler. Ia harus menyeberang dari ruang formal ke ruang sosial — dari podium ke panggung rakyat, dari seremoni ke aksi. Legitimasi sosial hanya akan tumbuh bila masyarakat merasa bahwa lembaga ini mendengar mereka, memahami mereka, dan memperjuangkan apa yang mereka nilai penting.
Langkah-langkah berikut dapat menjadi penanda pergeseran tersebut:
- Menginisiasi dialog publik rutin lintas etnis dan generasi di seluruh wilayah Aceh.
- Terlibat langsung dalam mediasi konflik berbasis adat dan budaya yang kerap muncul di komunitas.
- Menyusun laporan tahunan kebudayaan Aceh yang merangkum tantangan dan harapan masyarakat adat secara partisipatif, dan menyampaikannya ke publik sebagai bentuk akuntabilitas sosial.
- Memfasilitasi representasi komunitas minoritas budaya dalam pengambilan keputusan strategis, agar suara-suara yang jarang terdengar bisa ikut menentukan arah kebijakan budaya di Aceh.
Dalam proses ini, kepercayaan masyarakat tidak bisa diminta, tapi harus dibangun dan dirawat. Ia tumbuh dari konsistensi dan kesediaan untuk bekerja dalam diam, mendengarkan dalam kerendahan hati, dan mengambil sikap ketika nilai-nilai bersama terancam — bahkan jika itu berarti bersikap berbeda dari arus kekuasaan.
Wali Nanggroe bukan sekadar lembaga yang dipajang dalam konstitusi lokal. Ia hanya akan berarti jika menjadi tempat berpulangnya harapan budaya rakyat. Dan untuk itu, ia harus hidup, bukan hanya hidup-hidupan.
Evaluasi Kritis: Simbolisme Tinggi, Akses Publik Rendah
Sudah hampir dua dekade sejak lembaga Wali Nanggroe secara resmi dilembagakan dalam sistem pemerintahan Aceh pasca-Helsinki. Namun, alih-alih menjadi lembaga yang dekat dengan denyut hidup masyarakat, ia justru kerap dipersepsikan sebagai institusi “di atas sana” — megah dalam seremoni, kuat dalam simbol, tapi jauh dari ruang interaksi publik yang hidup dan dinamis.
Kesan ini bukan semata tuduhan. Ia tumbuh dari pengalaman sehari-hari publik yang jarang merasakan kehadiran lembaga ini secara langsung — terutama di kalangan muda, pelaku seni, penggerak komunitas, serta masyarakat adat non-dominan. Dalam wawancara informal maupun diskusi komunitas, berulang kali muncul keluhan bahwa Wali Nanggroe tidak hadir dalam program-program transformasi budaya akar rumput, tidak terlibat dalam inisiatif seni kontemporer yang progresif, dan tidak memberikan dukungan nyata terhadap gerakan pelestarian budaya lokal yang dilakukan secara mandiri oleh komunitas.
Dari sisi komunikasi publik, kehadiran Wali Nanggroe masih sangat terbatas di ruang-ruang strategis zaman ini: tidak aktif di media sosial, tidak terlihat dalam diskusi kebudayaan lintas generasi, dan jarang berkolaborasi dengan komunitas seni, sastra, atau pendidikan yang selama ini justru menjadi ujung tombak revitalisasi budaya. Padahal, di era digital dan desentralisasi informasi, transparansi, aksesibilitas, dan keterlibatan langsung adalah syarat utama legitimasi moral.
Publik masa kini tidak cukup diyakinkan dengan pidato adat atau prosesi seremonial. Mereka ingin melihat pemimpin adat yang mau berdialog, mau dikritik, mau belajar bersama, dan mau terlibat dalam kerja nyata di tingkat komunitas. Tanpa ini, simbolisme Wali Nanggroe akan tetap tinggi, tapi daya jangkaunya rendah. Relevansinya akan tergerus bukan karena serangan, tapi karena ketiadaan jembatan yang menjangkau publik secara horizontal.
Di sisi lain, posisi Wali Nanggroe dalam peta kekuasaan lokal juga menyimpan dilema yang tak kunjung selesai. Kedekatannya — secara struktural maupun genealogis — dengan satu poros politik tertentu (yang sebagian besar berasal dari eks-GAM) membuat sebagian masyarakat ragu untuk melihatnya sebagai lembaga pemersatu. Bahkan dalam beberapa kasus, pesan-pesan budaya yang dikeluarkan oleh Wali Nanggroe dicurigai memiliki agenda partisan, sehingga kehilangan bobot kulturalnya yang seharusnya netral dan memayungi semua.
Masalah ini bukan hanya persoalan persepsi, tapi soal konsistensi sikap kelembagaan. Bila Wali Nanggroe ingin benar-benar menjadi pelindung marwah budaya dan pemersatu sosial, maka ia harus menunjukkan jarak kritis terhadap kepentingan politik jangka pendek. Ia tidak boleh menjadi bagian dari satu barisan kekuasaan. Sebaliknya, ia harus menjadi rujukan etis yang berdiri di atas semua pihak, meskipun itu berarti mengambil posisi yang tidak populer.
Simbolisme budaya hanya akan kuat bila didukung oleh praktik yang terbuka dan inklusif. Dan legitimasi kultural tidak bisa hidup dalam ruang tertutup. Tanpa keterbukaan terhadap kritik, kolaborasi lintas sektor, serta keberanian menjaga jarak dari politik praktis, Wali Nanggroe akan sulit mengembalikan dirinya sebagai jangkar moral dan pelindung kearifan yang benar-benar dipercaya.
Pertanyaannya hari ini bukan apakah lembaga ini masih sah, tetapi apakah ia masih dirasakan sebagai milik bersama?
Bila jawabannya tidak, maka saatnya dilakukan reposisi mendalam — bukan dengan mengubah namanya, tetapi dengan menyegarkan ruh dan menegaskan misinya dalam lanskap sosial Aceh kontemporer.
Agenda Reposisi: Dari Figur-Sentris ke Sistem-Sentris
Salah satu tantangan utama dalam kelembagaan Wali Nanggroe hari ini adalah kecenderungan figur-sentrisme — sebuah kondisi di mana identitas lembaga terlalu lekat dengan satu sosok personal. Dalam budaya simbolik seperti Aceh, ini memang sulit dihindari. Namun jika tidak disertai dengan pembentukan sistem yang kuat dan kolektif, risikonya sangat besar: ketika figur tersebut dipersoalkan secara politik, dipersepsi tak netral, atau dianggap tidak mewakili aspirasi luas, maka kepercayaan publik terhadap lembaganya pun ikut tergerus.
Oleh karena itu, reposisi kelembagaan dari figur-sentris ke sistem-sentris bukan hanya penting, tapi mendesak. Wali Nanggroe tidak bisa terus bergantung pada kharisma individu. Ia harus tumbuh menjadi institusi yang berdaya karena sistem nilai, struktur partisipatif, dan kapasitas kelembagaannya. Dan itu artinya, ada beberapa agenda transformasi strategis yang bisa segera dimulai:
- Bangun Tim Kultural Multietnik
Reformasi pertama yang paling mendasar adalah membentuk Dewan Kultural Wali Nanggroe yang representatif dan inklusif. Dewan ini bukan hanya pelengkap seremonial, tapi harus berfungsi sebagai think tank budaya Aceh, tempat bertemunya:
- tokoh adat lokal dari seluruh etnis di Aceh,
- seniman muda dan penggerak komunitas kreatif,
- ulama perempuan dan cendekia lintas generasi,
- serta perwakilan dari kelompok adat minoritas dan komunitas terpencil.
Mereka bersama-sama merumuskan agenda kebudayaan kolektif yang tidak elitis, tidak sentralistik, dan tidak eksklusif. Dengan melibatkan beragam suara, Wali Nanggroe tidak lagi menjadi juru tafsir tunggal nilai-nilai Aceh, tetapi fasilitator dialog antartradisi dalam satu ruang kebangsaan yang utuh.
- Desentralisasi Peran melalui Forum Adat-Gampong
Alih-alih menjadi pengontrol dari atas, Wali Nanggroe sebaiknya memposisikan diri sebagai penggerak dari bawah. Salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan adalah memfasilitasi terbentuknya Forum Adat Gampong se-Aceh — ruang horizontal tempat para pemangku adat dari berbagai wilayah saling berbagi praktik, tantangan, dan solusi.
Forum ini bisa menjadi wahana bagi:
- penguatan hukum adat lokal,
- pengarsipan praktik kultural berbasis komunitas,
- serta penyusunan rekomendasi kebijakan budaya lokal kepada pemerintah daerah.
Dengan langkah ini, Wali Nanggroe akan menjadi katalisator transformasi adat, bukan pusat komando. Desentralisasi seperti ini juga akan memperluas legitimasi sosial lembaga karena melibatkan partisipasi riil masyarakat adat di tingkat akar rumput.
- Digitalisasi Warisan Budaya dan Partisipasi Publik
Zaman berubah, dan cara mewariskan budaya pun harus berubah. Di era digital, Wali Nanggroe memiliki peluang besar untuk menjadi pionir transformasi pengetahuan adat ke dalam bentuk-bentuk baru yang mudah diakses generasi muda.
Bayangkan jika:
- manuskrip kuno, hikayat, syair, dan hukum adat terdokumentasi dalam bentuk digital terbuka,
- cerita rakyat Aceh diolah menjadi podcast, kanal YouTube, atau gim naratif,
- atau ritus adat diabadikan dalam seri dokumenter interaktif yang bisa diakses dari Sabang sampai Pulau Banyak.
Semua ini bisa diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan universitas, sekolah adat, rumah kreatif, startup lokal, hingga kreator konten digital. Jika ini dilakukan, maka warisan budaya tidak akan mati di laci, tapi hidup di ponsel anak-anak muda Aceh — dan di situ, Wali Nanggroe bukan lagi institusi yang dilihat dari jauh, tapi dirasakan langsung sebagai pelindung pengetahuan dan penggerak imajinasi budaya.
Reposisi ini bukan tentang merendahkan peran figur Wali Nanggroe, tetapi menyelamatkan lembaganya dari kebergantungan yang rapuh. Di atas semua itu, ini adalah soal menghidupkan kembali mandat moral kelembagaan melalui struktur yang sehat, keterlibatan yang luas, dan sistem yang tangguh.
Jika langkah-langkah ini dijalankan dengan konsisten, maka Wali Nanggroe bukan hanya akan tetap relevan — tetapi akan menjadi model kelembagaan budaya masa depan, yang mampu menjaga marwah sambil menumbuhkan inovasi, dan merawat masa silam sambil memeluk masa depan.
Menjadi Mitra Strategis Pemajuan Kebudayaan Aceh
Dalam konteks kebijakan nasional, pemajuan kebudayaan tidak lagi dimaknai semata sebagai pelestarian warisan masa lalu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan secara tegas menempatkan kebudayaan sebagai strategi pembangunan nasional. Artinya, aktor-aktor kebudayaan — baik negara maupun non-negara — memiliki tanggung jawab untuk merancang masa depan dengan berpijak pada nilai, pengetahuan, dan praktik budaya yang hidup.
Dalam semangat ini, Wali Nanggroe tidak cukup hanya menjadi simbol pelindung adat. Ia harus hadir sebagai mitra strategis dalam mengorkestrasi kerja-kerja pemajuan kebudayaan di Aceh, baik dengan pemerintah daerah, lembaga legislatif, komunitas akar rumput, maupun dunia pendidikan. Posisi moral dan simboliknya harus diterjemahkan dalam tindakan-tindakan taktis dan kolaboratif.
Ada empat hal strategis yang bisa menjadi titik tolaknya:
- Inisiator Riset Budaya Berbasis Komunitas
Kekayaan budaya Aceh tidak hanya terletak pada artefak atau seremoni, tapi pada pengetahuan hidup yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat adat. Sayangnya, banyak di antaranya belum terdokumentasi dengan baik — bahkan terancam hilang. Di sini, Wali Nanggroe dapat mengambil peran sebagai inisiator riset budaya berbasis komunitas, yang melibatkan:
- masyarakat adat sebagai subjek pengetahuan,
- mahasiswa dan dosen dari berbagai kampus lokal sebagai mitra ilmiah, dan
- pemerintah sebagai pendukung kebijakan dan pembiayaan.
Dengan pendekatan ini, riset budaya tidak lagi eksklusif milik akademisi, tapi menjadi alat pemberdayaan masyarakat adat sendiri.
- Mendorong Pengarusutamaan Kebudayaan dalam RPJMA dan APBA
Kebudayaan sering kali tertinggal dalam agenda pembangunan karena tidak dianggap “ekonomis” atau “produktif”. Padahal, justru dari kerja budaya lahir fondasi sosial, kohesi komunitas, dan etika pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Wali Nanggroe perlu terlibat aktif dalam mendorong agar kebudayaan diarusutamakan dalam:
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA),
- struktur kelembagaan pemerintah daerah,
- serta prioritas anggaran di berbagai sektor — dari pendidikan hingga pariwisata.
Dengan cara ini, budaya tidak hanya hadir di acara formal, tapi menjadi kerangka berpikir dan arah kerja pembangunan itu sendiri.
- Pelindung Pekerja Budaya dan Adat
Selama ini, pelaku budaya — dari penjaga naskah kuno, penutur bahasa lokal, perajin tradisional, hingga perempuan adat — sering kali bekerja dalam sunyi tanpa perlindungan sosial maupun ekonomi. Padahal merekalah yang menjaga jantung kebudayaan Aceh tetap berdetak. Wali Nanggroe dapat mendorong lahirnya kebijakan perlindungan bagi pekerja budaya, termasuk:
- pengakuan status sosial-hukum mereka,
- skema insentif dan jaminan kerja budaya,
- serta ruang afirmatif untuk kelompok rentan dalam tradisi: perempuan adat, penyandang disabilitas, atau pemuda komunitas terpencil.
Ini bukan sekadar pemberdayaan, tapi keadilan kultural.
- Suara Moral dalam Isu Sosial Kontemporer
Kebudayaan tidak berhenti di museum atau prosesi adat. Ia harus menanggapi tantangan zaman: perusakan lingkungan, radikalisme agama, konflik lahan, urbanisasi paksa, hingga diskriminasi etnis. Dalam semua ini, Wali Nanggroe harus menjadi suara moral dan kultural yang tegas menyuarakan nilai-nilai keacehan yang adil, moderat, dan menghargai keragaman. Sikap ini harus hadir:
- dalam pernyataan publik,
- dalam advokasi kebijakan,
- dan dalam langkah-langkah nyata membantu komunitas yang terdampak.
Dengan kata lain, Wali Nanggroe bukan hanya menjaga budaya, tetapi menafsirkan ulang budaya — agar ia tetap hidup, relevan, dan menyala. Kebudayaan Aceh tidak boleh membeku sebagai simbol purba; ia harus menjadi daya gerak untuk menjawab persoalan dunia kontemporer.
Kelembagaan yang Etis dan Adaptif: Rekomendasi Jalan Tengah
Di tengah tarik-menarik antara nilai adat, syariat Islam, dan kerangka hukum negara, lembaga Wali Nanggroe berada dalam posisi yang sangat unik sekaligus rawan. Ia bisa menjadi jembatan nilai — perekat antara akar kultural dan struktur modern. Tapi jembatan hanya kuat jika dua hal terpenuhi: fondasi yang kokoh dan fleksibilitas untuk menyesuaikan beban zaman.
Artinya, untuk tetap relevan dan dihormati, Wali Nanggroe tidak cukup hanya dengan warisan historis dan legalitas formal. Ia perlu melembagakan diri secara etis dan adaptif. Etis, artinya menjunjung akuntabilitas dan keberpihakan pada kepentingan publik. Adaptif, artinya mampu membaca arah zaman dan menyesuaikan cara kerja tanpa kehilangan ruh keacehan. Beberapa langkah penting dalam kerangka ini adalah:
- Keterbukaan dan Akuntabilitas Publik
Di era yang menuntut transparansi, lembaga budaya tidak boleh menutup diri. Wali Nanggroe perlu mulai menerapkan standar akuntabilitas modern — tidak hanya pada aspek keuangan, tetapi juga pada aspek kerja budaya.
Beberapa langkah minimal yang bisa ditempuh:
- Menyampaikan laporan tahunan kelembagaan yang dapat diakses publik,
- Mengadakan forum pertanggungjawaban tahunan, baik secara offline maupun daring, di mana masyarakat adat, akademisi, dan pelaku budaya bisa memberi masukan dan kritik terbuka,
- Membangun kanal pengaduan dan konsultasi daring untuk menampung aspirasi dari komunitas, terutama generasi muda dan kelompok minoritas budaya.
Keterbukaan seperti ini akan menjadi jembatan kepercayaan. Lembaga yang mendengar akan lebih mudah dipercaya. Dan kepercayaan adalah fondasi utama legitimasi moral.
- Otonomi dari Politik Praktis
Kita tentu sadar bahwa tak ada lembaga yang sepenuhnya steril dari politik. Tapi independensi tetap harus dijaga sebagai prinsip dasar. Jika Wali Nanggroe terlalu dekat dengan satu partai, satu figur, atau satu jaringan kekuasaan tertentu, maka fungsinya sebagai penjaga nilai bersama akan terancam.
Oleh karena itu, diperlukan:
- Etika kelembagaan yang menegaskan batas peran politik dan budaya,
- Kode etik internal yang melarang afiliasi politik aktif dalam struktur kultural,
- serta penguatan posisi non-partisan Wali Nanggroe dalam konstitusi lokal melalui revisi qanun bila diperlukan.
Masyarakat butuh juru nilai, bukan juru kampanye. Dan Wali Nanggroe hanya bisa memainkan peran itu jika ia menjaga jarak sehat dari arus pragmatisme politik.
- Pembaruan Kaderisasi Kepemimpinan
Salah satu kelemahan struktur budaya di banyak tempat — termasuk Aceh — adalah ketergantungan pada satu generasi, atau bahkan satu garis keturunan. Akibatnya, terjadi stagnasi pemikiran dan eksklusi terhadap anak muda yang sebenarnya memiliki kapasitas dan semangat besar untuk terlibat.
Wali Nanggroe perlu secara sistemik:
- membuka ruang kaderisasi tokoh adat muda,
- mengembangkan program magang, pelatihan, dan mentoring kebudayaan lintas disiplin,
- serta mengintegrasikan warisan adat dengan nalar intelektual generasi digital.
Pembaruan bukan berarti meninggalkan tradisi, tapi membawa tradisi berjalan bersama masa depan. Karena sejatinya, adat bukan soal tua atau muda — tapi tentang siapa yang peduli, siapa yang belajar, dan siapa yang siap melanjutkan.
Jika langkah-langkah ini dijalankan, maka lembaga Wali Nanggroe akan menemukan jalan tengah yang sehat: tidak terjebak dalam beban simbolik masa lalu, tapi juga tidak larut dalam arus populisme hari ini. Ia akan menjadi institusi yang membumi dalam nilai, tapi terbangun dalam sistem; bersahaja dalam etika, tapi progresif dalam strategi.
Dan di situlah ia bisa benar-benar menjadi penjaga masa depan budaya Aceh — bukan sekadar nama, tetapi ruh yang hidup.
Akhirul Kalam: Lembaga yang Dirindukan, Bukan Sekadar Dihormati
Aceh hari ini tidak hanya membutuhkan identitas, tetapi juga arah. Arah yang tidak dapat lahir dari strategi politik semata, tapi dari nilai-nilai hidup yang telah tumbuh dalam adat, kesenian, bahasa, dan syariat — nilai-nilai yang menuntun, bukan memaksa; yang menghidupkan, bukan membekukan.
Dalam masyarakat yang pernah terluka oleh konflik, disilaukan oleh politik praktis, dan dihadapkan pada tantangan globalisasi yang menggerus akar, adat dan budaya adalah jaring pengaman terakhir sekaligus kompas etis bersama. Namun, kompas itu hanya berguna jika dipegang dan dipakai untuk bergerak. Artinya, nilai adat tidak cukup dihormati — ia harus dijalani. Dan lembaga Wali Nanggroe, bila ingin tetap bermakna, harus menjelma sebagai penjaga nilai yang dinamis, bukan penjaga monumen yang beku.
Kelambagaan Wali Nanggroe akan menemukan kekuatannya yang sejati ketika kemuliaannya:
- dapat lebih bebas dari bayang-bayang seremonial,
- mendengar lebih banyak,
- dan hadir lebih banyak di tengah rakyat.
Hanya dengan itulah ia akan berubah dari lembaga yang hanya dihormati karena keharusan, menjadi lembaga yang dirindukan karena kehadiran. Rindu bukan karena megahnya pakaian adat, panjangnya gelar, atau tingginya podium — tapi karena maknanya terasa sampai ke hati masyarakat, dari desa ke kota, dari etnis dominan sampai yang terlupakan.
Aceh tidak kekurangan sejarah. Yang ia butuhkan adalah langkah baru — lembut namun tegas, dari lembaga yang tak hanya berjalan di atas jalan adat, tetapi juga menuntun arah masa depan. Bila Wali Nanggroe mampu melembagakan dirinya bukan sekadar sebagai simbol, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup dan bekerja — maka ia akan menjadi jangkar di tengah gelombang, cahaya di antara simpang jalan, dan rumah kultural yang membuat rakyat ingin pulang, bukan menjauh.
Kini, tugas besar itu terbuka luas. Tinggal satu hal yang ditunggu rakyat Aceh:
Kemudahan Wali Nanggroe melangkah ke terang peran baru sebagai penjaga hidup bersama yang sesungguhnya? [TAMAT]
_____
Penulis adalah peneliti dan pendidik di bidang seni, budaya, dan masyarakat di Universitas Syiah Kuala. Ia aktif menulis tentang relasi budaya, Islam, dan peradaban lokal. Menyelesaikan studi di Banda Aceh, Hawai‘i, dan Australia, ia terus belajar dari masyarakat akar rumput dan para ulama yang menjaga warisan dengan hati.