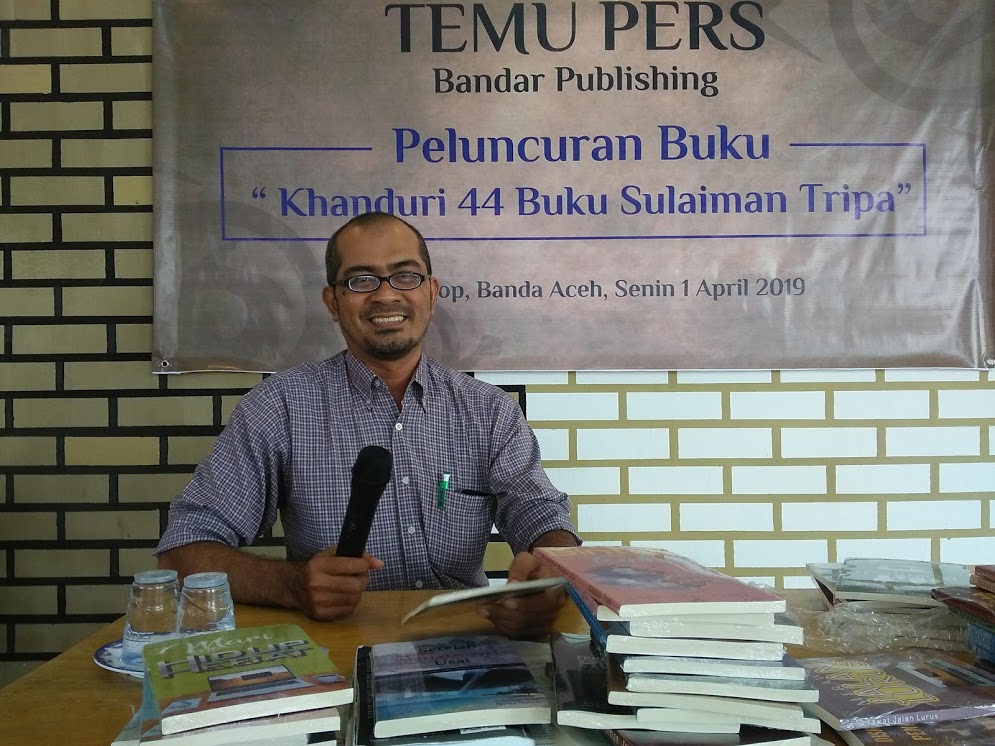Oleh: Ari J. Palawi
Dalam dunia yang kian terkoneksi, berbicara tentang budaya tak lagi cukup berhenti pada pelestarian. Ia kini menuntut kehadiran yang bermartabat dan berdaya dalam percakapan global. Aceh, dengan sejarah panjang dan warisan spiritual yang kaya, menghadapi tantangan penting dalam hal ini. Apakah seni tradisinya masih memiliki daya tawar? Apakah ia masih tumbuh sebagai kekuatan kultural yang hidup, atau hanya tinggal sebagai simbol seremonial yang tampil di panggung, tapi tak lagi terdengar?
Aceh sejatinya tidak pernah hilang dari peta. Namun, terlalu sering ia hanya hadir sebagai bayangan: diingat lewat citra, bukan suara. Ia tampil di berbagai forum kebudayaan, namun jarang menjadi subjek yang menentukan narasi. Pertanyaan “bagaimana Aceh hadir di dunia?” menjadi kunci penting dalam refleksi kebudayaan hari ini. Untuk menjawabnya, kita perlu menengok ke belakang, membaca kenyataan hari ini, dan membayangkan jalan ke depan.
Dalam sejarahnya, Aceh pernah menjadi simpul diplomasi dan pertukaran budaya di Asia Tenggara. Salah satu simbol kuat dari masa itu adalah surat Sultan Aceh kepada Ratu Elizabeth I dari Inggris pada abad ke-16. Surat itu bukan sekadar dokumen politik, melainkan cermin dari peradaban yang sadar akan representasi dan martabat budaya. Seni dalam konteks ini bukan hiasan, melainkan bagian dari diplomasi itu sendiri. Tari, musik, sastra, dan arsitektur digunakan untuk menyampaikan nilai, bukan sekadar untuk dikagumi. Ia adalah bahasa politik, spiritual, dan sosial dalam satu kesatuan. Warisan ini menunjukkan bahwa Aceh tidak hanya pernah dikenal, tetapi juga dihormati sebagai entitas kultural yang aktif dan sejajar dalam dunia Islam dan Asia.
Namun, kenyataan kontemporer menunjukkan jurang yang makin menganga antara sejarah dan praktik hari ini. Seni tradisi Aceh masih kerap tampil, tetapi dalam format yang makin dangkal. Ia hadir dalam seremoni resmi, menjadi pembuka atau pelengkap acara, tetapi jarang menjadi ruang pendidikan atau refleksi. Di balik panggung megah itu, kita menyaksikan ketimpangan: dokumentasi yang lemah, regenerasi yang minim, dan institusi seni yang berjalan tanpa arah. Budaya makin terjebak dalam logika proyek, bukan proses. Seni direduksi menjadi “tugas” untuk memenuhi agenda tertentu, bukan kebutuhan untuk memahami dan menghidupkan nilai-nilai bersama.
Kondisi ini memunculkan krisis representasi. Siapa yang menampilkan seni Aceh, untuk tujuan apa, dan dalam narasi siapa? Representasi yang tidak berakar pada kesadaran historis dan konteks sosial bisa dengan mudah menjelma menjadi bentuk eksotisme baru. Seni ditampilkan karena “unik”, bukan karena bermakna. Ia dipilih karena “menghibur”, bukan karena mendidik atau menggerakkan. Dalam situasi seperti ini, seni tradisi tidak lagi berfungsi sebagai ruang spiritual, sosial, dan pedagogis seperti dulu. Ia berubah menjadi panggung kosong yang hanya memenuhi harapan visual penonton, bukan kebutuhan batin masyarakat.
Regenerasi menjadi titik krusial dalam upaya membalik arah. Tetapi regenerasi bukan hanya soal mengganti pemain lama dengan yang baru. Lebih dari itu, regenerasi harus mencakup perluasan peran—bukan hanya seniman atau penampil, tetapi juga penulis, peneliti, kurator, dan mediator budaya. Aceh perlu menumbuhkan generasi muda yang bukan hanya bisa menari dan menyanyi, tetapi juga menafsir, menulis, dan berbicara tentang makna dari apa yang mereka lakukan. Tanpa ini, seni tradisi akan terus berada di tangan pihak luar yang mendefinisikannya dari kejauhan.
Dalam konteks ini, arsip hidup menjadi penting. Bukan sekadar menyimpan dokumen, melainkan menjaga ruang-ruang praktik agar tetap berdenyut. Meunasah, dapur, kolong rumah, ladang, dan lapangan adalah ruang-ruang arsip itu. Di sanalah ingatan dan pengetahuan budaya dipertukarkan, diajarkan, dan diperbarui. Maka yang kita butuhkan bukan hanya teknologi dokumentasi, tetapi juga kebijakan dan gerakan komunitas yang menjaga agar ruang-ruang ini tetap hidup dan dimaknai bersama.
Diplomasi budaya pun harus dimaknai ulang. Selama ini, ia lebih sering dikelola dari atas ke bawah—ditentukan oleh lembaga, digerakkan oleh agenda luar, dan dipentaskan oleh kelompok resmi. Padahal, seni tradisi Aceh tumbuh dari komunitas. Maka, panggung dunia harus diisi oleh mereka yang hidup dan terlibat langsung dalam tradisi itu. Diplomasi bukan tentang memperlihatkan eksotisme, tetapi membuka percakapan. Ia adalah ruang pertemuan yang saling belajar, bukan pertunjukan satu arah.
Namun semua ini tak akan bermakna tanpa kesadaran etis dalam representasi. Di tengah arus pariwisata massal, digitalisasi, dan komodifikasi budaya, kita perlu bertanya: ketika seni Aceh ditampilkan, siapa yang diuntungkan? Apakah komunitasnya dilibatkan? Apakah narasinya jujur terhadap sejarah dan konteks sosial? Seni tradisi Aceh tidak hanya berisi keindahan bentuk, tetapi juga sejarah penjajahan, pengalaman bencana, dan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Menampilkannya secara asal-asalan bukan saja mereduksi makna, tapi juga mengkhianati ingatan kolektif.
Esai ini tidak menutup dengan jawaban final, melainkan ajakan terbuka untuk menata ulang ekosistem budaya. Kita perlu memperkuat pendidikan seni yang berpihak pada refleksi dan kreativitas lokal. Kita harus mengembangkan arsip budaya yang hidup dan terhubung dengan komunitas. Kita perlu menumbuhkan generasi penulis dan penafsir dari dalam. Dan yang terpenting, kita harus memastikan bahwa setiap panggung yang kita bangun berdiri di atas nilai keadilan, keterlibatan, dan kesadaran historis.
Menempatkan Aceh di peta bukan soal tampil lebih sering, tetapi hadir lebih utuh. Bukan tentang menjadi “dikenal dunia”, tetapi tentang menyuarakan nilai dan martabat dari dalam diri sendiri. Dunia tidak butuh lebih banyak pertunjukan. Ia butuh lebih banyak kejujuran kultural. Aceh bisa hadir di sana—bukan sebagai ingatan masa lalu, tapi sebagai kekuatan kultural yang bergerak, bernapas, dan hidup bersama zaman. []
Ari Palawi
Jembatan Bunyi antara Tradisi dan Inovasi
Dari pesisir Banda Aceh hingga panggung akademik di Melbourne dan Hawai‘i, Dr. Ari Palawi adalah kekuatan budaya yang menjembatani masa lalu dan masa depan melalui senar gitarnya—yang bergetar dalam warisan ratusan tahun tradisi Melayu dan Aceh. Sebagai Dosen Senior Etnomusikologi di Universitas Syiah Kuala, Ari bukan sekadar pendidik, melainkan juga strategi kebudayaan, perancang pertunjukan, dan penggerak komunitas. Entah saat ia membaca makna adat melalui musik, merancang pertukaran lintas budaya, atau mengarahkan kebijakan kebudayaan Aceh, seluruh karyanya berpijar dengan tujuan dan ketulusan.