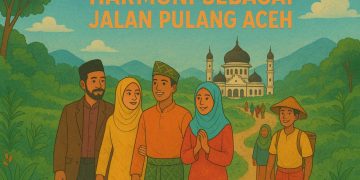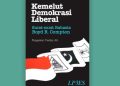Oleh: Ari J. Palawi
Musisi dan Akademisi Seni Aceh
Setiap kali sebuah acara musik diumumkan di Aceh, reaksi publik nyaris dapat ditebak: protes, kecemasan moral, hingga pembatalan. Kasus konser Dewa 19 di Lhokseumawe baru-baru ini bukan pengecualian, melainkan pola berulang (AJNN, 12 November 2025). Syariat kembali dijadikan batas terakhir untuk menilai pantas-tidaknya bunyi diperdengarkan di ruang publik. Namun ketika saya mencermati ulang perdebatan ini, terutama melalui penelitian saya tentang musik dan syariat di Banda Aceh (Palawi, Implementasi Syariat Islam dalam Program Penyiaran Musik dan Nyanyian…, 2004), terlihat jelas bahwa persoalannya jauh lebih rumit daripada sekadar “musik haram” atau “acara maksiat”.
Dalam penelitian itu, radio-radio lokal tetap menyiarkan musik pop, dangdut, jazz, keroncong, hingga musik daerah. Tidak ada tentangan berarti, selama tidak menampilkan konten yang dianggap berlebihan atau melanggar etika publik. Artinya, musik pada dasarnya bukan masalah di Aceh; yang diperdebatkan adalah bentuk kerumunan dan ekspresi publik yang dianggap rawan ketika dibungkus format konser modern.
Ironisnya, penolakan terhadap konser-konser ini muncul bersamaan dengan ritual lain yang justru berlangsung dengan megah: festival budaya, perayaan institusi, hingga acara hiburan internal yang digelar oleh lembaga pemerintahan sendiri. Inilah ketidakseimbangan yang perlu disorot: standar moral tidak boleh berubah hanya karena berubahnya panggung.
Di Mana Syariat Ditempatkan dalam Perdebatan Musik?
Perdebatan konser sering berhenti pada slogan, bukan pada keilmuan. Padahal tradisi Islam sendiri menyediakan perangkat analitis yang sangat kaya. Hamka (1983) menjelaskan bahwa syariat merupakan keseluruhan hukum yang Allah tetapkan untuk membimbing manusia menuju kemaslahatan. Al-Syathibi, jauh sebelumnya, menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—bukan membatasi kreativitas manusia, melainkan mengarahkannya agar bermanfaat.
Dalam kerangka itu, musik bukanlah entitas yang otomatis bermasalah. Justru sejarah intelektual Islam memperlihatkan penghargaan tinggi terhadap suara. Ikhwan al-Shafa menggambarkan musik sebagai harmoni kosmik—gema gerakan alam semesta yang menyenangkan jiwa. Rumi menyebutnya “makanan bagi pecinta Tuhan”, medium yang memperhalus batin dan membangkitkan cinta Ilahi (Muhaya, 2003).
Sejarah juga mencatat betapa Islam pernah menjadi pusat teori musik dunia lewat karya Al-Masudi, Al-Ashfahani, Safi al-Din al-Urmawi, hingga Maulana Mubarak Syah (Rozak, 2001; Bakri, 1987). Tidak ada satu pun yang menempatkan musik sebagai lawan moral, melainkan sebagai disiplin ilmu, estetika, bahkan spiritualitas.
Yusuf al-Qardlawi (2001) merumuskan empat batas fiqh musik yang sangat praktis:
- syair tidak melanggar syariat;
- cara menyajikannya tidak memancing maksiat;
- tidak disertai hal yang diharamkan;
- tidak berlebihan.
Empat rambu ini bersifat proporsional. Ia tidak menutup pintu kreativitas, tetapi memberi kerangka etis agar musik menghadirkan maslahat.
Perspektif serupa muncul dalam diskusi di kanal Sagoe TV bersama Dr. Sehat Ihsan Shadiqin (14 November 2025). Ia menegaskan bahwa banyak kekeliruan publik lahir dari penafsiran sepihak, bukan dari ajaran itu sendiri. Musik, dalam tradisi tasawuf dan dalam sejarah Islam, adalah ruang kontemplasi dan penyucian jiwa—bukan pemicu kerusakan moral.
Karena itu, menjadikan syariat sebagai dasar pembatalan konser perlu kehati-hatian metodologis. Sebab syariat sendiri menuntut keadilan, proporsionalitas, dan maslahat.
Yang Dibutuhkan Aceh Bukan Pelarangan, tetapi Penataan
Jika kita kembali membaca dinamika penolakan konser dalam beberapa tahun terakhir, terlihat bahwa penolakan lebih sering lahir dari kecemasan abstrak: kekhawatiran kerumunan, asumsi potensi maksiat, atau ketakutan terhadap “budaya luar”. Padahal di kota-kota muslim lain, konser dapat berlangsung tertib melalui regulasi yang jelas: kurasi konten, pengawasan, panduan etika penonton, serta koordinasi keamanan.
Masalah utamanya bukan pada musik, tetapi ketiadaan standar tata kelola konser di Aceh. Ketika pedoman tidak disebutkan secara eksplisit, keputusan akhirnya bergantung pada tafsir moral yang berubah-ubah. Ini berbahaya karena menempatkan ekspresi seni sebagai sasaran empuk bagi ketidakpastian.
Penelitian saya pada radio Banda Aceh (2004) memperlihatkan gejala yang sama: lembaga penyiaran cenderung “mengunci diri” lebih ketat daripada aturan formal demi menghindari tafsir negatif publik. Jika pola ini dibiarkan merembes ke dunia pertunjukan, Aceh berisiko kehilangan ruang kreasi publik. Padahal ruang itu penting, terutama bagi anak muda, pelaku seni, dan ekosistem ekonomi kreatif yang terus berkembang.
Aceh memiliki warisan musik yang kuat—Rapa’i Pase, Saman, Seudati—yang tumbuh berdampingan dengan nilai keislaman masyarakat. Jika yang tradisional bisa diatur dengan tertib dan terhormat, mengapa yang modern tidak bisa?
Yang dibutuhkan bukan pelarangan, tetapi pedoman yang eksplisit:
- standar izin,
- mekanisme pengawasan,
- keterlibatan ulama,
- kurasi artistik,
- dan kode etik penonton.
Dengan pedoman yang adil, syariat tidak lagi menjadi alasan untuk menutup ruang publik, tetapi menjadi fondasi moral untuk menata dan memperindahnya.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana: Apakah Aceh akan terus mencurigai setiap bunyi, atau mulai menata ruang bagi musik yang terhormat dan bermanfaat?
Sebagai wilayah dengan tradisi intelektual Islam yang kaya dan warisan seni yang dalam, Aceh sesungguhnya memiliki semua modal untuk menjawabnya dengan lebih arif. []