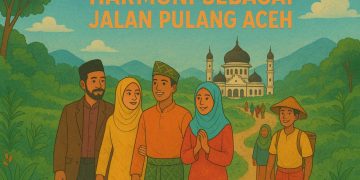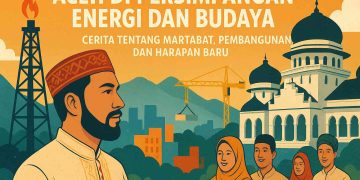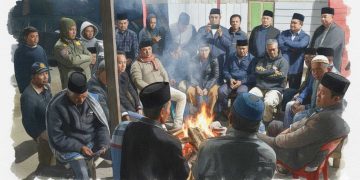Oleh: Ari J. Palawi
Musisi dan Akademisi Seni Aceh
Dalam bahasa Aceh, ada sebuah hadih maja yang bunyinya keras dan getir, tapi sarat kebijaksanaan: “Agam hana raba krèh.” Secara harfiah, artinya laki-laki tidak meraba buah pelirnya sendiri — kalimat yang kasar di telinga, tapi luhur di makna. Ia bukan bicara tentang tubuh, melainkan tentang harga diri, keberanian, dan rasa malu yang menjaga manusia dari kehinaan.
Peribahasa ini lahir dari masa ketika kata masih berarti. Ketika lelaki tidak hanya dinilai dari seberapa kuat fisiknya, tapi dari seberapa teguh ia memegang kebenaran. Laki-laki sejati adalah yang tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus berdiri di tempat yang benar — meski sendirian.
Sekarang, gema itu nyaris hilang. Kita punya banyak laki-laki dengan jas rapi, jabatan tinggi, dan gelar panjang, tapi sedikit yang masih punya malu. Banyak yang pandai berbicara, tapi takut menegakkan kebenaran. Banyak yang tampak gagah, tapi sebenarnya hanya penakut yang pandai bersembunyi di balik rapat dan kesepakatan palsu. Aceh kini seperti rumah besar yang masih berdiri, tapi kehilangan isi moralnya.
Nada Keberanian yang Hilang
Laki-laki Aceh dulu adalah penggubah keberanian. Mereka menyusun hidup seperti melodi — jujur, seimbang, dan tegas. Tgk. Chik di Tiro berjuang bukan untuk nama, tapi untuk kebenaran yang ia yakini. Teuku Umar menulis strategi dengan darahnya sendiri. Dan di antara mereka berdirilah seorang perempuan, Laksamana Keumalahayati, pemimpin armada laut pertama di dunia, yang berperang bukan demi gengsi, tapi demi kehormatan bangsanya. Ia adalah teguran abadi bagi para laki-laki yang kehilangan marwah. Ketika perempuan bisa berdiri di garis depan dengan keberanian, mengapa laki-laki hari ini justru berlindung di balik alasan dan kompromi?
Kini, banyak pemimpin yang lebih sibuk menjaga posisi daripada menjaga kebenaran. Banyak yang terlihat bekerja, padahal hanya sibuk mempercantik laporan. Ada yang berani bersuara, tapi hanya ketika aman. Mereka seperti gitar tanpa senar — tampak utuh, tapi tak lagi bersuara. Lebih menyedihkan lagi, sifat pengecut itu kini diwariskan kepada generasi muda. Banyak yang sudah akil balig tapi belum matang pikir. Tubuhnya dewasa, tapi jiwanya masih ringkih. Mereka ingin disebut laki-laki, tapi takut menjadi manusia yang bertanggung jawab.
Anak Muda dan Lagu yang Patah
Di kampus, di warung kopi, di ruang kerja, dan di forum publik, kita melihat wajah-wajah muda yang kehilangan arah moral. Mereka hafal teori dari luar negeri, tapi tak bisa membaca luka di sekitar. Pandai berbicara di media sosial, tapi gagap ketika harus turun tangan di dunia nyata. Mereka ingin tampil, bukan tumbuh; berani karena ramai, bukan karena benar.
Sekarang ini, di banyak kampus dan sekolah, banyak anak muda laki-laki yang kehilangan daya tahan batin. Badannya besar, tapi pikirannya rapuh. Sudah akil balig, tapi belum dewasa. Gampang menyerah, cepat bosan, dan malas berpikir panjang. Mereka lebih percaya diri berdebat di media sosial daripada berani menyentuh persoalan di lapangan. Banyak yang kuliah hanya untuk gelar, bukan untuk ilmu. Banyak juga yang jadi guru atau pemimpin muda, tapi bekerja dengan semangat “yang penting jalan.”
Fenomena ini bisa kita lihat di mana-mana — dari ruang kelas sampai lembaga pemerintahan. Budaya tanggung jawab makin tipis, sementara budaya cari aman makin tebal. Dulu, pemuda Aceh dikenal kuat hati, peka, dan berani berdiri di barisan depan. Kini banyak yang terjebak pada gaya hidup kosong — sok modern tapi rapuh, sok paham tapi malas belajar.
Syekh Abdurrauf dan Tafsir Keberanian
Namun sejarah Aceh tidak hanya diwarnai perang dan darah. Ada juga keberanian yang ditulis dengan pena dan ilmu.
Syekh Abdurrauf as-Singkili, ulama besar abad ke-17, menulis Tafsir Tarjuman al-Mustafid — tafsir Al-Qur’an lengkap dalam bahasa Melayu-Jawi. Karya itu bukan sekadar kitab tafsir, melainkan pernyataan moral: bahwa ilmu harus berpihak pada masyarakat, bukan pada kekuasaan. Di masa Sultanah Safiatuddin, beliau berani menegaskan pentingnya agama yang mencerahkan, bukan menakut-nakuti. Ia hidup di tengah politik istana, tapi tidak kehilangan arah spiritual. Syekh Abdurrauf mengajarkan bahwa keberanian sejati bukan pada siapa yang kita lawan, tapi pada seberapa jujur kita terhadap nurani sendiri. Ilmu tanpa keberanian hanyalah hiasan. Keberanian tanpa ilmu hanyalah kebodohan yang bersuara keras.
Hari ini, kita punya banyak orang pintar, tapi sedikit yang benar-benar berani jujur. Banyak yang mengajar tapi tak mendidik, berdakwah tapi menakuti, memimpin tapi tak memelopori. Semua sibuk memainkan peran, tapi lupa memainkan hati.
Kehilangan Malu, Hilangnya Musik Nurani
Malu adalah irama dasar dalam kebudayaan Aceh. Tanpa malu, hidup menjadi fals — seperti lagu yang kehilangan nada.
Dulu, orang Aceh menjaga malu sebagaimana menjaga iman. Kini, banyak yang menganggap malu sebagai penghalang karier. Pejabat bisa tersenyum di tengah kebusukan. Guru bisa membiarkan muridnya malas tanpa rasa bersalah. Mahasiswa bisa menyontek tanpa merasa hina. Semua tampak wajar — bahkan dianggap pintar mencari celah. Inilah hakikat dari hadih maja itu: agam hana raba krèh — laki-laki yang tidak lagi tahu di mana letak kehormatannya.Ia tak lagi meraba marwahnya, tak lagi memeriksa hatinya, tak lagi mendengarkan suara nuraninya. Dan ketika rasa malu mati, maka keberanian pun ikut terkubur bersama harga diri.
Menemukan Kembali Irama Diri
Aceh tidak butuh lebih banyak pidato, tapi lebih banyak teladan. Laki-laki sejati tidak harus berteriak lantang; cukup tegak di tempat yang benar. Ia tidak menjilat ke atas dan tidak menindas ke bawah. Ia tidak menjual prinsip demi proyek, dan tidak menukar ilmu dengan tepuk tangan.
Sudah cukup kita menonton lakon kepemimpinan palsu yang berulang setiap lima tahun. Sudah cukup kita mendengar pidato yang indah tapi hampa. Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian moral — keberanian untuk malu, untuk belajar, untuk menolak kebodohan yang dibungkus kepintaran, dan untuk hidup jujur di tengah dunia yang pura-pura. Sebagaimana genderang dan rapa’i Aceh hanya berbunyi indah bila dipukul dengan ritme yang tepat, demikian pula hidup ini. Bila tidak jujur, ia hanya akan jadi bunyi tanpa makna.
Laki-laki Aceh — dari pejabat hingga mahasiswa, dari guru hingga seniman, dari dosen hingga pemimpin gampong — semua harus kembali mendengar gema hadih maja itu. Karena bila keberanian terus kita abaikan, kita bukan lagi agam, hanya gema kosong yang menunggu senyap. []