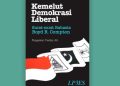Oleh: Affan Ramli.
Master Sosiologi Pendidikan International Islamic University Malaysia (IIUM) dan Tenaga Ahli Pendidikan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
WS Rendra mungkin tidak serius bertanya, tapi saya masih memikirkannya sampai sekarang. Di ujung puisi ‘Seonggok Jagung di Kamar’, ia melempar gugatan penutup, apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastera, tehnologi, kedokteran, atau apa saja, bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya, lalu berkata ‘di sini aku merasa asing dan sepi!’
Di kampus pertama tempat saya belajar ragam teori pendidikan, pertanyaan reflektif ini tidak punya tempat. Bukan tidak ada yang mampu memberi jawaban, lebih tragis dari itu tidak satupun orang mampu mengajukan pertanyaan jenis itu, dari dosen atau mahasiswa. Orang-orang tidak sempat berpikir ulang kenapa mereka harus berada di kampus. Tekadnya sudah terlanjur jelas dari awal, kebanyakan orang ingin tersertifikasi sebagai tenaga kerja, guna mudah mengakses pekerjaan di kantor-kantor negara dan swasta. Sejumlah kecil orang ingin berkarir di dunia keilmuan.
Teori sosiologi klasik juga mengajarkan demikian. Kampus dianggap bertugas menyediakan tenaga kerja terampil ‘siap pakai’, yang dibutuhkan masyarakat industri modern. Ini mensyaratkan dua premis saling bergantungan. Pertama, industri kita harus mengalami perkembangan pesat. Kedua, kampus-kampus kita harus membekali mahasiswa dengan jenis dan skill yang relevan sesuai perkembangan industri. Indonesia belum memenuhi keduanya. Industri kita menampung terlalu sedikit dari total tenaga kerja yang dihasilkan kampus setiap tahunnya. Pada awal 2020, lebih 12 persen dari total pengangguran adalah pemegang ijazah kampus. Itu angka tertinggi, disusul SMK 8.49 persen dan SMA 6,77 persen (BPS, 2020).
Ahli kapitalisme pendidikan asal Amerika, Samuel Bowles dan Herbert Gintis membantah doktrin klasik itu. Lembaga-lembaga pendidikan termasuk kampus, merujuk Bowles dan Gintis, tidak berfungsi menyiapkan tenaga kerja terampil. Kampus bekerja menyiapkan kondisi mental (pikiran, kesadaran, dan pola tingkah laku) yang diperlukan dunia kerja. Perkara keterampilan, mudah dipelajari dalam waktu singkat di dalam dunia kerja itu sendiri. Melalui magang dan jenis kursus lainnya yang hemat waktu.
Faktanya, para sarjana yang telah menghabiskan waktu 4-5 tahun di kampus harus dilatih ulang keterampilannya oleh pihak yang mempekerjakan mereka. Seringkali harus dilatih dari awal. Beberapa sarjana yang lebih unggul dari sisi teknis dibanding seangkatan mereka kebanyakan karena mendapat pengalaman dan pengetahuan di luar kampus dan di luar program studi mereka. Ahli mesin dengan pengalaman kerja puluhan tahun di perbengkelan, meski berijazah SMA, jauh lebih terampil dibanding sarjana teknik mesin jebolan universitas, bila hanya mengandalkan sepenuhnya pengetahuan yang disediakan kampusnya.
Nadiem Makarim, Mendikbud kita kurang menyadari kenyataan ini. Ia masih meyakini teori klasik sosiologi pendidikan yang telah dibantah Bowles dan Gintis. Proses pembelajaran di kampus-kampus Indonesia saat ini di mata Nadiem, kurang relevan dengan jenis dan tingkat keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Lebih-lebih kurang relevan dengan perkembangan industri global generasi 4.0 yang bertumpu pada teknologi informasi dan serba digital. Nadiem memaksa, tugas kampus haruslah mempersiapkan tenaga kerja terampil siap pakai. Ini mitos lama.
Belajar dari Cina, kiblat ekonomi Asia. Perkembangan industri mereka begitu pesat dalam seperempat abad terakhir bukan bertumpu pada keterampilan dan teknologi hasil ramuan kampus-kampus dalam negeri. Cina mengandalkan transfer teknologi dari perusahaan-perusahaan multinasional yang memenangkan tender proyek-proyek pemerintah. Ditambah kontribusi pusat-pusat riset teknologi milik perusahaan-perusahaan asing yang berbisnis di negeri tirai bambu. Singkatnya, penguasaan skill dan teknologi tinggi dilakukan di dalam zona industri itu sendiri, bukan di kampus.
Penilaian Nadiem memang keliru, tetapi pilihan kebijakannya entah bagaimana cukup jitu. Nadiem adalah contoh dimana pemikiran-pemikiran yang keliru terkadang bisa juga berujung pada keputusan yang tepat. Strateginya memperbaiki proses belajar mengajar di perguruan tinggi layak diapresiasi. Terutama pilihannya mengembangkan program Kampus Merdeka. Dalam Kampus Merdeka, mahasiswa diberikan hak belajar satu semester di luar program studi dan dua semester di luar perguruan tinggi. Mahasiswa berhak belajar merdeka selama 3 semester dengan hitungan bobot total setara 60 SKS.
Selama 2 semester di luar perguruan tinggi, mahasiswa didorong bergelut dengan pengalaman di dunia nyata dibawah bimbingan supervisor. Terdapat 8 jenis kegiatan yang ditawarkan dalam program ini: pertukaran pelajar, magang (praktik kerja), asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, dan membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik (lebih lengkap lihat juknis pelaksanaan Kampus Merdeka Kemendikbud). Diasumsikan, mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka akan lebih survive di dunia nyata dan dunia kerja setelah kuliah.
Dunia Nyata
‘Dunia nyata’ dan ‘dunia kerja’, dua istilah ini digunakan sebagai konsep kunci dalam gagasan Kampus Merdeka Kemendikbud. Keduanya (dunia nyata dan dunia kerja) dipahami sebagai realitas faktual di luar kampus. Ini suatu penegasan, bahwa realitas yang dihadirkan dalam proses pembelajaran di kampus-kampus ‘bukan dunia nyata’. Dengan kata lain, ‘dunia keilmuan’ dan ‘dunia nyata’ diletakkan dalam dua ketegori dikotomis.
Secara epistemologis, ‘bukan dunia nyata’ punya beberapa kemungkinan makna. Bisa jadi realitas itu wujud opinian, dongeng, hoaks, atau ketiadaan (nothingness). Filsafat realisme berpandangan, bahwa wujud-wujud dalam realitas mental, seperti ide, konsep-konsep, argumentasi masih merupakan dunia nyata sejauh ide-ide itu merepresentasikan atau diabstraksikan dari realitas faktual (nyata). Bahkan mental sebagai realitas sama faktualnya dengan benda-benda terinderawi. Tetapi banyak juga ide manusia bukan berasal dari ‘dunia nyata’ dan tidak merepresentasikan dunia faktual.
Kita ambil beberapa kemungkinan makna dari anggapan bahan pembelajaran kampus bukan dunia nyata. Kemungkinan makna pertama, mahasiswa belajar dari realitas opinian. Wujud realitas opinian bergantung pada kesepakatan (konsensus), seperti keberadaan sistem tanda dan bahasa. Implikasi dari kemungkinan makna pertama ini berat, seluruh pembelajaran termasuk tema-tema kesejahteraan, keadialan sosial, baik- buruk, dan benar-salah yang dihadirkan di kampus semuanya merupakan realitas opinian, tidak faktual.
Kemungkinan makna kedua, mahasiswa di kampus-kampus Indonesia kebanyakan disuguhkan bahan pembelajaran berkualitas dongeng. Artinya realitas yang dihadirkan di ruang-ruang belajar seputar politik, ekonomi, dan isu lainnya hanya menarik disusun dalam cerita fiksi, tetapi tidak ditemukan basis realitas eksternalnya dalam kehidupan harian. Kemungkinan ketiga, bahan pembelajaran banyak hoaksnya. Berbeda dari dongeng, hoaks selain tidak berbasis kenyataan, jenis ini menyisipkan suatu intensi (niatan) merusak dan mengganggu situasi.
Proses belajar mengajar di kampus-kampus Indonesia memang seringkali gagal menghadirkan dunia nyata. Dosen dan mahasiswa sama-sama terpuaskan dan orgasme dengan tradisi penghapalan dan pengutipan (quotation) teks, ditambah seni tingkat tinggi kompilasi teks, tanpa pertanggungjawaban epistemologis dan metodologis. Teori bergudang-gudang yang disajikan untuk konsumsi warga kampus hampir seluruhnya barang impor dari peradaban lain di masa lampau, lalu dipaksakan cocok menjadi pisau bedah dan alat pemandu arah pembangunan dunia sosial dan dunia kerja Indonesia kontemporer.
Kegagagalan kampus menghadirkan dunia nyata adalah sebuah tragedi. Usulan Kampus Merdeka mengeluarkan mahasiswa dari perguruan tinggi selama dua semester untuk belajar dunia nyata juga sama konyolnya. Bukankah jika demikian Kemendikbud seperti ingin mengatakan, silakan belajar dongeng selama 6 semester tetapi nanti mahasiswa perlu belajar dunia nyata selama 2 semester sisanya. Dibanding memberi hak mahasiswa belajar 2 semester di luar kampus, Nadiem dan Kemendikbud sepatutnya memastikan pada semua semester perguruan tinggi, berkeharusan dan berkemampuan menghadirkan dunia nyata kedalam sistem pembelajaran kampus.
Dunia Kerja
Nadiem dan timnya percaya dunia keilmuan kampus tidak mendekatkan mahasiswa pada realitas dunia nyata. Terutama pada realitas dunia kerja. Tapi apa itu realitas dunia kerja? Realitas pada dirinya sendiri memiliki banyak lapisan-lapisan makna. Seperti itu pula, dunia kerja memiliki lapisan-lapisan realitas yang mungkin tak pernah dipahami oleh Kemendikbud, mahasiswa, sarjana, bahkan oleh para dosen mereka.
Realitas dunia kerja tidak sepermukaan menjelaskan barang apa yang anda produksi, jasa apa yang anda jual, siapa konsumen pengguna jasa anda, dan siapa konsumen barang-barang yang anda produksi, keterampilan apa yang harus anda miliki untuk memproduksi barang-barang itu dan bagaimana memasarkan jasa anda kepada pengguna (negara atau swasta).
Realitas dunia kerja belum terjelaskan sama sekali—seperti diingatkan Marx, Gramsci, aliran ilmu sosial kritis Frankfurt, dan para cendikia posmarxis—tanpa pemahaman akurat pada akumulasi primitif, akumulasi modal, realasi kuasa dalam hubungan sosial produksi dan bentuk-bentuk eksploitasi rakyat pekerja yang semakin maju dari waktu ke waktu. Dunia kerja yang sangat dehumanis.
Nadiem sendiri dan Kemendikbud tidak punya penjelasan tentang realitas dunia kerja Indonesia, selain himbauannya saban waktu agar skill siap pakai harus dibekali pada mahasiswa sebagai calon tenaga kerja, kebutuhan teknologi industri (manufaktur dan jasa) terkini yang serba digital, dan persaingan peluang kerja yang semakin mengglobal. Mas Mendikbud lupa mengingatkan di masa depan tenaga kerja Indonesia harus bersaing dengan pekerja asing yang lebih terampil menguasai teknologi tinggi.
Ketidakmampuan menjelaskan realitas dunia kerja dalam narasi Kampus Merdeka berawal dari kategori dualitas ‘dunia keilmuan kampus’ dan dunia nyata-dunia kerja’ yang dibangun Nadiem dan Kemendikbud. Padahal realitas dunia kerja sebagai dunia nyata pun, hanya dapat dijelaskan dengan benar dan utuh melalui aktifitas keilmuan, tentu dari sudut pandang kritis dan progresif.
Perspektif teknokratik dan liberal yang digunakan Kemendikbud dalam menjelaskan dunia kerja mendorong kita melacak kembali darimana asal muasal ide merdeka dalam program Kampus Merdeka. Ada dua kemungkinan, pertama, Kampus Merdeka terinsipirasi dari paradigma pendidikan kritis Freirean. Setengah abad lalu Freire dan mazhab pedagogi kritis merupakan corong utama gagasan ‘merdeka belajar’ dan ‘belajar untuk merdeka’. Kemungkinan ke dua, Nadiem berangkat dari penalaran sebaliknya, liberalisasi dunia pendidikan. Benar, liberal secara harfiah juga sepadan dengan kata merdeka. Kampus Merdeka dalam hal ini adalah kampus liberal.
Meski sama-sama menggunakan istilah merdeka, mazhab kritis dan liberal keduanya meniupkan penalaran berbeda dan berlawanan. Paradigma kritis akan memaknai Kampus Merdeka sebagai perjuangan emansipatoris (pembebasan dari relasi kuasa timpang dan eksploitatif). Paradigma liberal memaknai Kampus Merdeka sebagai usaha maksimal melayani kepentingan pasar, dunia kerja, dunia usaha atau dunia industri. Kampus Merdeka Nadiem berangkat dari pemikiran liberalisasi pendidikan.
Pembongkaran bangunan nalar di belakang konsep Kampus Merdeka tadi sekaligus menggugurkan klaim sepihak Kemendikbud, bahwa gagasan itu diturunkan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kampus-kampus yang ditugaskan menyiapkan tenaga kerja jinak untuk kebutuhan dunia industri tidak mungkin punya spirit sebagus dengan Dewantara, yang sepenuh-penuh hati mementingkan mental kemerdekaan dan kemandirian kaum terpelajar.
Kampus Merdeka Nadiem, pada akhirnya bertugas memperkuat selangkah lagi lebih serius upaya penjinakan orang-orang terdidik kita. Itu sebabnya gugatan sastrawan WS Rendra masih relevan setengah abad kemudian, sejak puisi itu dibacakan.
Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi pada akhirnya menghasilkan “kebutaan massal” pada realitas dunia sosial dan dunia kerja tempat kaum terpelajar tumbuh dan mati.[]