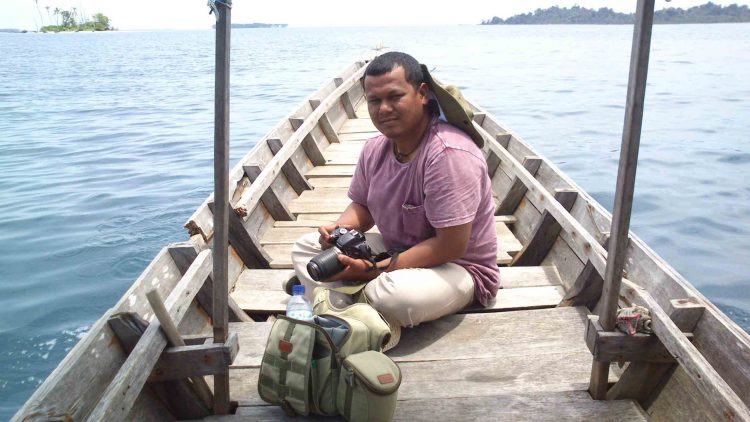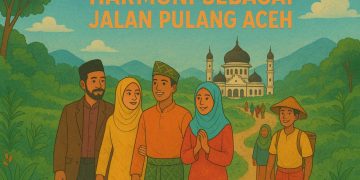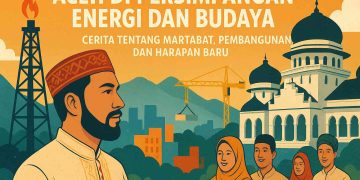Oleh: Ari J. Palawi
Seni di Aceh tidak lahir dari ruang kelas. Ia tumbuh dari kesenyapan dapur, dari detak tanah saat hujan pertama turun, dari tubuh yang menari bukan untuk panggung, tapi untuk bertahan. Dari segala sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh silabus, tapi justru menyusun keberadaan kita sebagai manusia yang utuh.
Maka ketika hari ini lembaga-lembaga pendidikan tinggi mulai membuka program studi seni—ada yang tergesa, ada yang sambil lalu—kita patut berhenti sejenak. Bukan untuk menolak, tapi untuk bertanya: seni macam apa yang hendak dihidupkan? Dan dari ruang hidup siapa ia akan tumbuh?
Karena membuka jurusan seni bukan seperti membuka jalur baru di kampus teknik. Ia bukan sekadar menambahkan satu entri di borang akreditasi. Seni butuh roh. Butuh niat. Butuh alasan yang lebih dalam dari sekadar “menyesuaikan kebutuhan zaman.” Karena seni itu sendiri adalah cara zaman berbicara—dan itu hanya bisa dipahami bila kampus mau mendengarkan.
Sayangnya, yang kita lihat justru kebalikannya. Kampus demi kampus berlomba membuka program studi, tapi jarang yang berani membuka dialog. Tidak semua, tentu. Tapi cukup banyak yang menjadikan seni sebagai urusan birokrasi, bukan sebagai medan penciptaan.
Ada yang berkilah, bahwa seni kontemporer biar jadi ranah institusi X saja. Ada yang merasa cukup dengan tetap di jalur pendidikan. Ada yang bangga membuka prodi baru, tapi bingung menghidupkan ruang belajar. Mereka yang sudah mapan, kadang justru merasa tak perlu berubah. Mereka yang baru, sibuk membenahi syarat administratif ketimbang mencari arah.
Lalu di tengah semua itu, mahasiswa datang. Dengan tubuh yang ingin bergerak. Dengan kepala yang masih ragu, tapi menyala. Dan mereka duduk di kelas yang kadang terlalu sunyi untuk disebut ruang seni. Tidak salah siapa-siapa. Tapi jika dibiarkan, ini akan jadi warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya: kampus seni yang hadir, tapi tidak hidup.
Kita tidak sedang menagih kesempurnaan. Tapi barangkali, sudah saatnya kita tidak memaafkan keterbiasaan. Sudah cukup banyak ruang belajar yang kita bangun tanpa menyiapkan tanah tempat tumbuh. Kampus seni bukan sekadar lembaga. Ia seharusnya menjadi ruang batin bersama, tempat gagasan tidak ditertawakan, tubuh tidak disuruh diam, dan sejarah tidak disembunyikan di balik modul.
Karena kalau tidak, kita sedang menyiapkan panggung tanpa naskah. Gelar tanpa makna. Gedung tanpa kehidupan.
Realitas Terkini: Siapa yang Sudah Ada, dan Apa yang Sebenarnya Mereka Tawarkan?
Aceh tak kekurangan lembaga. Dalam beberapa tahun terakhir, program studi seni tumbuh di beberapa titik: dari ISBI Aceh di Jantho yang punya mandat khusus untuk memajukan seni dan budaya, hingga FKIP di Universitas Syiah Kuala yang sudah lebih dulu mengelola jalur pendidikan seni untuk guru. Beberapa kampus swasta juga mulai ikut membangun ruang akademik untuk seni pertunjukan, seperti UBBG di Banda Aceh, dan UNIKI di Bireuen.
Di atas kertas, kita seperti sedang menuju musim subur. Nama-nama prodi bertambah. Mahasiswa baru berdatangan. Brosur dibagikan, spanduk dibentang. Tapi di balik semua itu, pertanyaan pentingnya belum dijawab: apa sebenarnya yang sedang ditawarkan oleh kampus-kampus ini kepada dunia seni di Aceh?
Apakah mereka sekadar menyelenggarakan pendidikan tinggi, atau sungguh-sungguh berupaya menciptakan ekosistem belajar yang hidup?
ISBI Aceh, misalnya. Berdiri dengan semangat besar dan cita-cita menjadi pusat seni budaya regional, kampus ini punya ruang untuk lebih banyak prodi dan keleluasaan dalam menjangkau lintas kompetensi. Tapi di tengah potensi itu, masih terasa longgar hubungan antara kampus dan masyarakat seni akar rumput. Banyak potensi belum tersentuh. Banyak ruang kerja kolaboratif yang masih berupa rencana. Sebagian besar program masih berjuang meraih akreditasi dasar. Tak sedikit mahasiswa yang merasa belum ditantang untuk benar-benar mencipta dari ruang hidup mereka sendiri.
FKIP di USK pun memiliki sejarah panjang. Dari satu-satunya prodi seni di Aceh selama bertahun-tahun, mereka telah meluluskan banyak guru seni yang tersebar di berbagai kabupaten. Tapi kita juga harus jujur: jalur keguruan ini sering kali dibatasi oleh cara pandang administratif. Seni diajarkan sebagai teknik mengajar, bukan sebagai laku hidup yang reflektif dan penuh daya cipta. Sementara kampusnya sendiri—yang punya sembilan fakultas dan potensi interdisipliner yang sangat luas—belum tampak sebagai motor penggerak utama bagi inovasi seni di wilayah ini.
Di sisi lain, kampus-kampus yang lebih muda seperti UBBG atau UNIKI berupaya menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal. Beberapa dosen muda dan alumni mulai membawa gagasan baru. Tapi infrastruktur, jejaring, dan arah kelembagaan masih jauh dari kokoh. Tanpa dukungan yang serius, upaya mereka bisa berakhir sebagai proyek jangka pendek.
Bukan maksud tulisan ini untuk mencatat siapa unggul dan siapa tertinggal. Justru sebaliknya, inilah saatnya kita jujur dan terbuka: bahwa pertumbuhan institusi seni di Aceh tidak serta-merta berarti perkembangan nilai-nilai seni itu sendiri.
Bertambahnya kampus bukan jaminan bertumbuhnya keberanian berpikir. Bertambahnya mahasiswa bukan bukti bertambahnya peradaban.
Apa yang kita butuhkan hari ini bukan lomba membuka prodi. Tapi keberanian setiap institusi untuk menjawab ulang pertanyaan ini: seni seperti apa yang sedang kami bentuk? Dan manusia macam apa yang ingin kami tumbuhkan di dalamnya?
Kalau pertanyaan ini belum bisa dijawab jernih, barangkali yang sedang kita bangun bukan lembaga pendidikan seni, melainkan struktur kosong yang sibuk mencatat data, tapi lupa mendengar dunia.
Apa yang Tidak Pernah Disentuh: Harta Karun dari Tanah Aceh
Kita kerap terburu-buru mengadopsi istilah-istilah besar: seni pertunjukan kontemporer, riset penciptaan, interdisiplin, revitalisasi budaya. Tapi kita jarang berhenti untuk bertanya—apa sebenarnya yang kita miliki di sini, yang bisa menjadi fondasi kuat untuk membentuk metode, orientasi, dan visi pendidikan seni di Aceh?
Aceh tidak miskin bahan ajar. Justru sebaliknya, yang miskin adalah keberanian untuk menjadikannya sebagai sumber pengetahuan utama. Di tanah ini, suara bukan sekadar bunyi. Ia menyimpan sejarah. Tubuh bukan hanya gerak, tapi bahasa sosial dan spiritual. Warna, motif, pakaian adat, dan pola lantai dalam tari rakyat bukan sekadar estetika, tapi peta nilai yang menghubungkan manusia dengan alam, dengan sejarah, dan dengan Tuhan.
Tapi semua itu nyaris tidak masuk kelas. Banyak kampus seni di Aceh masih bergantung pada referensi luar—entah dari pusat seni nasional, atau dari pendekatan-pendekatan akademik barat yang tidak selalu cocok dengan karakter pengalaman lokal.
Buku-buku ajar yang digunakan tidak bicara tentang Rapai Pase, Seudati di Lhokseumawe, tari Nandong di Simeulue, atau struktur bunyi dalam Doa-doa Laut masyarakat pesisir barat. Praktik seni dari komunitas masih dilihat sebagai “kegiatan kebudayaan,” bukan sebagai pengetahuan yang setara dengan teori koreografi atau desain visual modern. Banyak tradisi hanya menjadi bahan dokumentasi, tapi tidak pernah diajak bicara dalam proses penciptaan.
Padahal kita tahu, dunia seni tidak tumbuh dari teks saja. Ia tumbuh dari laku hidup. Dari pengalaman langsung. Dari tubuh yang menyimpan trauma, harapan, dan kegigihan. Dan Aceh—dengan seluruh bentang sejarahnya yang penuh luka dan daya tahan—menyimpan harta karun artistik yang seharusnya menjadi laboratorium pembelajaran paling kuat.
Sayangnya, kampus-kampus seni kita belum cukup membuka diri untuk itu. Kurikulum masih kaku. Dosen tidak diberi ruang cukup untuk meriset hal-hal lokal yang dianggap “kurang akademik.” Mahasiswa tidak ditantang untuk berpikir dengan bahasa rumahnya sendiri. Padahal justru di situlah pintu pembaruan bisa dibuka.
Jika kita ingin membentuk kampus seni yang benar-benar hidup, maka kita perlu membalik cara pandang ini. Bukan sekadar membawa teori dari luar ke dalam ruang kelas, tapi membawa ruang hidup masyarakat masuk ke dalam kampus. Menjadikan suara nenek, gerakan tukang sulam, warna dari anyaman laut, atau cerita dari ritual laut sebagai sumber dan metode pembelajaran.
Harta karun tidak selalu harus ditemukan. Kadang ia hanya perlu diakui.
Kampus Seni Ideal: Peka, Lentur, dan Hidup
Jika kita bicara kampus seni yang ideal, jangan bayangkan bangunan megah dengan studio ber-AC dan pencahayaan panggung tiga dimensi. Kampus seni yang kita butuhkan di Aceh bukan hanya ruang fisik—tapi ruang yang peka, lentur, dan hidup. Tiga kata itu bukan sekadar slogan, tapi pijakan untuk menilai: apakah kampus itu sungguh-sungguh hadir bagi zaman, bagi tempat di mana ia berdiri, dan bagi manusia yang tumbuh di dalamnya?
Peka berarti kampus sanggup mendengar. Ia tidak berjalan sendiri dalam menara gading. Ia membaca lingkungan, mendengar masyarakat, mencatat perubahan, dan memetakan kebutuhan. Kampus seni yang peka tidak sibuk mengejar akreditasi hingga lupa pada anak-anak muda yang masuk dengan bahasa tubuh dan latar yang sangat beragam. Ia tahu bahwa mahasiswa dari pesisir Aceh Barat tidak bisa diperlakukan sama dengan mahasiswa dari perkotaan. Ia sadar bahwa perbedaan bukan ancaman, tapi bahan baku pendidikan seni itu sendiri.
Lentur berarti mampu berubah. Bukan berubah karena tekanan pasar atau kebijakan yang terus berganti, tapi karena kampus memahami bahwa zaman tidak diam. Kampus seni yang lentur sanggup mengintegrasikan teknologi, sains, ekologi, bahkan praktik penyembuhan, ke dalam pembelajaran seni tanpa kehilangan arah. Ia tidak terjebak antara “tradisi” dan “kontemporer” sebagai dua kubu yang bertentangan, karena ia tahu bahwa yang penting adalah relevansi dan kebermaknaan, bukan kategori.
Hidup berarti kampus itu bukan tempat menyimpan naskah, tapi tempat melahirkan pertanyaan. Bukan ruang untuk menghafal sejarah seni, tapi tempat mencipta sejarah baru. Kampus seni yang hidup terasa denyutnya—di kelas, di halaman, di luar pagar. Ia menjadi tempat orang ingin belajar karena tahu bahwa yang mereka dapat bukan sekadar ijazah, tapi cara memahami hidup dengan lebih jujur, lebih halus, dan lebih kuat.
Kita tidak butuh kampus seni yang seragam. Yang kita butuhkan adalah kampus yang sanggup menumbuhkan karakter. Di mana mahasiswa tidak diajari menjadi “seniman profesional” dalam pengertian formal yang sempit, tapi menjadi manusia yang tahu bagaimana menjadikan seni sebagai cara untuk hidup, berpikir, merawat, dan bergerak.
Dan itu tidak akan tercapai kalau kampus hanya sibuk menyusun borang dan mengejar akreditasi. Kampus seni tidak seharusnya hanya jadi perpanjangan tangan dari sistem pendidikan nasional yang seragam dan birokratis. Kampus seni harus berani jadi ruang alternatif—yang memadukan pengalaman, pertanyaan, penciptaan, dan keberanian.
Seni bukan pelajaran biasa. Dan kampus seni bukan kampus biasa.
Jalan Kritis: Apa yang Harus Kita Perbaiki Bersama
Kampus seni bukan tanggung jawab satu institusi. Ia adalah cermin dari cara kita memperlakukan seni secara kolektif. Maka jika ada yang perlu dibenahi, itu bukan hanya soal kurikulum atau fasilitas. Tapi cara berpikir kita. Cara kita menempatkan seni di dalam kehidupan, dan cara kita memahami pendidikan sebagai proses membentuk manusia, bukan hanya mengisi gelar.
Mari kita mulai dari para pemimpin kampus. Mereka yang hari ini menduduki kursi tertinggi di universitas atau sekolah tinggi seni, perlu berhenti berpikir seolah-olah seni itu wilayah. Bukan waktunya lagi menyatakan: “ini bagian kami, yang itu biar ditangani kampus sebelah.” Seni tidak mengenal pagar institusi. Ia bukan peta administratif. Kalau kita masih melihatnya begitu, kita sedang mengkerdilkan sesuatu yang justru bisa menjadi jalan keluar dari stagnasi berpikir di pendidikan tinggi.
Lalu dosen. Dosen bukan hanya pengajar. Ia pembelajar pertama. Jika dosen tak lagi penasaran, maka mahasiswa kehilangan arah. Jika dosen hanya hadir untuk mengisi jam, maka kampus kehilangan jantung. Sudah waktunya dosen seni, siapa pun dia—entah dari kampus besar atau kecil, negeri atau swasta—kembali menyelami seni sebagai pengalaman hidup, bukan hanya sebagai tanggung jawab profesi.
Mahasiswa juga perlu diajak untuk tidak sekadar menunggu. Mahasiswa seni harus mulai sadar bahwa belajar seni bukan menunggu diinstruksikan. Ia adalah latihan panjang untuk berpikir dan merasakan. Banyak dari mereka datang dengan semangat yang utuh, tapi lalu diluruhkan oleh sistem yang dingin. Kita harus kembali menyemangati mereka untuk bergerak: menulis, mencipta, mengkritik, mengorganisasi, dan mencari bentuk belajar yang bermakna.
Pegawai kampus, staf teknis, tata usaha—sering luput dari perhatian, padahal mereka bagian dari wajah lembaga. Budaya pelayanan, etos kerja, dan kepekaan mereka terhadap suasana pembelajaran sangat memengaruhi kualitas hidup kampus seni. Tidak ada alasan untuk memisahkan kerja teknis dari misi artistik. Semua harus saling menopang.
Dan tentu saja, pemerintah. Pemerintah daerah dan pusat harus berhenti menjadikan seni sebagai bahan pelengkap acara. Tidak cukup dengan mendanai festival atau menetapkan hari budaya. Pendidikan seni butuh keberpihakan yang lebih dalam: dalam pendanaan riset, dalam kebijakan rekrutmen dosen, dalam distribusi sumber daya, dan terutama dalam kebijakan yang memberi ruang kepada pendekatan lokal dan ragam praktik budaya yang ada.
Yang paling penting: kita semua harus berani mengakui bahwa ada yang belum selesai. Ada hal-hal yang selama ini kita maklumi, padahal tak seharusnya. Ada sistem yang terus berulang, padahal kita tahu arahnya tak ke mana-mana.
Membenahi kampus seni bukan soal revolusi besar. Ia dimulai dari cara kita duduk bersama. Dari keberanian untuk saling mendengar. Dari kesediaan untuk mengubah logika “yang penting berjalan” menjadi “apa yang sedang kita bangun bersama.”
Sebab kalau tidak, kita hanya akan punya lebih banyak kampus seni yang berdiri—tanpa betul-betul hadir.
Kalau Kita Tahu Kita Bisa Lebih Baik, Kenapa Tidak?
Esai ini bukan untuk memperdebatkan siapa yang paling dulu hadir, siapa yang paling banyak prodi, atau siapa yang paling sering tampil di panggung seremonial. Ini bukan soal senioritas lembaga atau siapa yang lebih dekat ke pusat kekuasaan. Ini tentang pertanyaan yang sangat mendasar, dan karenanya sangat penting: untuk apa kampus seni kita hadir di Aceh?
Kalau tujuannya hanya agar kita punya institusi yang bisa mencetak lulusan dengan gelar sarjana seni, ya itu sudah tercapai. Tapi kalau yang kita inginkan adalah ruang belajar yang membentuk manusia—yang peka, lentur, dan hidup—maka pekerjaan kita masih jauh dari selesai.
Kampus seni harus bisa lebih dari sekadar pelengkap sistem pendidikan tinggi. Ia harus menjadi ruang tumbuh nilai-nilai hidup. Tempat di mana gagasan bisa lahir tanpa takut diadili. Tempat di mana tubuh bisa bergerak tanpa ditertawakan. Tempat di mana siapa pun—dari mahasiswa, dosen, petugas keamanan hingga rektor—merasa bahwa keberadaannya punya makna bagi proses belajar dan penciptaan bersama.
Dan ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu kampus. Atau satu kementerian. Ini kerja panjang, kerja lintas. Antara institusi, antara generasi, antara gagasan dan tindakan.
Aceh tidak sedang menunggu kampus seni yang sempurna. Tapi Aceh membutuhkan kampus seni yang tahu ke mana ia ingin pergi. Yang bisa berdiri dengan keberanian, dengan arah, dengan visi yang tidak mudah dibelokkan oleh kepentingan jangka pendek atau kekuasaan administratif.
Kalau hari ini kita sudah tahu bahwa kita bisa membenahi, bisa memperbaiki, bisa menata ulang—maka pertanyaannya tinggal satu:
Kenapa tidak?
________
Tentang Penulis:
Ari J. Palawi lahir dan tumbuh di Banda Aceh. Ia menempuh pendidikan seni di ISI Yogyakarta, melanjutkan studi ke University of Hawai‘i at Mānoa, dan meraih gelar doktor di Monash University. Sampai tulisan ini hadir ke pembaca, ia masih tercatat sebagai lektor di Universitas Syiah Kuala, sembari menimbang langkah baru dalam perjalanannya. Ia menulis karena gelisah—dan karena percaya, bahwa perubahan adalah hak semua orang, baik yang tinggal, maupun yang memilih berjalan.