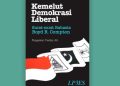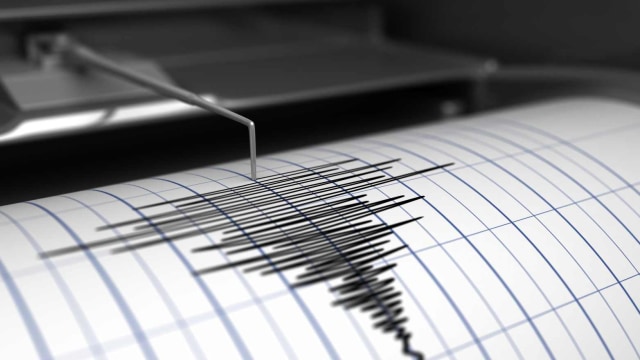Oleh: Muhammad Jais, S.E., M.Sc.IBF.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dan Alumni S2 Islamic Banking and Finance di International Islamic University Malaysia (IIUM).
Isu razia kendaraan berplat BL (Aceh) di Sumatera Utara baru-baru ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan luas. Kebijakan yang dikaitkan dengan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menuai kritik tajam, termasuk dari kalangan DPR RI asal Aceh.
Tindakan ini dinilai tidak sekadar soal penertiban pajak atau administrasi kendaraan, melainkan menyentuh relasi historis dan ekonomi antara Aceh dan Sumut. Fakta bahwa sebagian besar masyarakat Aceh masih sangat bergantung pada Medan dalam hal distribusi barang, perdagangan, hingga layanan perbankan menunjukkan adanya persoalan struktural yang sudah berlangsung lama. Aceh yang kaya sumber daya alam ironisnya tetap berperan hanya sebagai pasar konsumen.
Jejak ketergantungan Aceh terhadap Medan sesungguhnya telah terbentuk sejak lama, terutama pasca-konflik dan tsunami yang melemahkan infrastruktur ekonomi daerah. Secara geografis, Medan memang strategis sebagai kota besar terdekat yang sekaligus menjadi pusat distribusi logistik Sumatera bagian utara. Tidak heran jika bahan makanan, produk manufaktur ringan, hingga kebutuhan pokok Aceh sebagian besar dipasok dari Medan. Kondisi ini membuat pasar Aceh sangat rentan terhadap dinamika pasokan dari luar, bahkan muncul ungkapan bahwa jika Medan menghentikan suplai barang hanya dalam seminggu, pasar Aceh akan mengalami kekosongan.
Selain sektor konsumsi, ketergantungan itu terlihat jelas dalam aspek otomotif dan perbankan. Ribuan kendaraan di Aceh masih menggunakan plat BK (Sumut) atau plat B (Jakarta) dengan alasan harga lebih murah dan fasilitas kredit lebih mudah. Konsekuensinya, pajak kendaraan bermotor yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh justru mengalir ke provinsi lain. Pada saat yang sama, sebagian masyarakat Aceh lebih memilih menyimpan dana mereka di bank-bank konvensional di Medan dibanding Bank Syariah Aceh dan BSI. Aliran uang ini semakin memperkuat perputaran ekonomi di Sumut, sementara potensi ekonomi Aceh sendiri melemah karena dana masyarakat tidak berputar di dalam daerah.
Kelemahan terbesar Aceh sebenarnya terletak pada ketiadaan industri pengolahan dan hilirisasi. Meski memiliki potensi besar dari hasil pertanian, batu bara, gas bumi Arun, kopi Gayo, hingga hasil laut, komoditas tersebut masih dijual dalam bentuk mentah tanpa nilai tambah berarti. Nilai ekonomi justru dinikmati di luar daerah, sementara Aceh hanya menjadi penonton. Sejak masa Gubernur Irwandi Yusuf hingga kini, pola konsumsi masyarakat Aceh tidak banyak berubah, lebih banyak belanja ke Medan daripada membangun pusat belanja dan industri sendiri. Hal ini menunjukkan kegagalan kebijakan ekonomi daerah dalam mendorong produktivitas dan kemandirian.
Melihat kondisi tersebut, solusi yang ditawarkan bukan sekadar perdebatan soal razia plat kendaraan, tetapi bagaimana Aceh mampu membalikkan arus ketergantungan. Pemerintah daerah perlu memperkuat sektor pariwisata, membangun pusat perbelanjaan modern, serta melengkapi fasilitas publik seperti hotel, tempat hiburan, dan rekreasi keluarga agar masyarakat tidak selalu berbelanja keluar daerah. Di sisi lain, pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal harus menjadi prioritas, sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati di Aceh sendiri. Dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan penerapan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan kemandirian, Aceh berpeluang keluar dari ketergantungan struktural terhadap Sumatera Utara dan menguatkan posisinya dalam perekonomian nasional.
Razia plat BL, fenomena permukaan dari masalah struktural
Kontroversi razia kendaraan berplat BL di Sumut sesungguhnya hanya fenomena permukaan. Di satu sisi, Gubernur Sumut mengklaim razia dilakukan demi kepatuhan aturan dan optimalisasi PAD. Namun di sisi lain, kebijakan ini menyinggung rasa keadilan masyarakat Aceh. Secara hukum, memang ada ketentuan bahwa kendaraan yang digunakan secara terus-menerus di luar wilayah registrasi lebih dari tiga bulan wajib melaporkan atau mutasi. Namun, implementasi aturan ini sering dianggap diskriminatif ketika hanya menyasar kendaraan Aceh di Sumut. Kritik pun mengalir: bukankah banyak kendaraan berplat BK juga bebas berkeliaran di Aceh tanpa razia serupa?
Dari perspektif ekonomi, razia ini mengungkap realitas pahit, Aceh belum mampu mandiri dalam menciptakan ekosistem kendaraan dan logistiknya sendiri. Selama masyarakat Aceh masih berbelanja barang kebutuhan pokok, membeli mobil di luar daerah dan menaruh uang di bank luar Aceh, wajar jika Sumut menganggap Aceh sebagai “pasar” yang perlu dimaksimalkan. Dengan demikian, persoalan plat nomor hanyalah cermin dari persoalan struktural yang lebih dalam dari lemahnya basis produksi dan distribusi Aceh, serta absennya strategi kemandirian ekonomi.
Konsekuensi ketergantungan, dari harga diri hingga kerentanan ekonomi
Ketergantungan ekonomi Aceh terhadap Medan tidak hanya berkaitan dengan persoalan angka-angka statistik, melainkan juga menyentuh aspek harga diri dan kedaulatan daerah. Kerentanan ini tampak jelas ketika rantai pasok kebutuhan pokok sepenuhnya bergantung pada Medan. Sedikit saja terjadi gangguan distribusi, pasar Aceh akan langsung goyah karena tidak memiliki cadangan industri pangan yang memadai. Di sisi lain, ribuan kendaraan berplat BK yang beroperasi di Aceh menciptakan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), sebab pajak kendaraan bermotor mengalir ke kas Sumatera Utara, sementara infrastruktur jalan yang digunakan kendaraan tersebut justru dibiayai dari APBA.
Selain itu, potensi ekonomi lokal ikut tergerus karena aliran dana masyarakat Aceh yang lebih banyak tersimpan di bank-bank di Medan. Kondisi ini menyebabkan likuiditas yang semestinya dapat menggerakkan ekonomi daerah malah memperkuat perekonomian luar. Ketidakmampuan Aceh membangun pusat produksi dan perdagangan sendiri semakin menegaskan keterpinggirannya dalam sistem kapitalisme nasional, di mana daerah ini hanya berfungsi sebagai pasar konsumen. Meskipun dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, posisi Aceh tetap rapuh secara struktural karena nilai tambah ekonomi justru dinikmati di luar daerah.
Jalan keluar, dari retorika perlawanan ke kemandirian nyata
Menyikapi kondisi ketergantungan yang berlangsung lama, Aceh tidak bisa terus-menerus terjebak dalam retorika perlawanan yang bersifat emosional. Ancaman boikot, razia balasan, atau jargon anti-Medan hanya memberikan kepuasan sesaat tanpa menyentuh akar masalah. Yang dibutuhkan adalah strategi kemandirian ekonomi jangka panjang yang terukur dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Reformasi kebijakan pajak kendaraan, misalnya, dapat menjadi langkah awal dengan menurunkan atau menghapus biaya balik nama kendaraan dari luar daerah. Insentif fiskal ini akan mendorong masyarakat untuk memutasi kendaraan ke plat BL sehingga pajak kembali masuk ke kas daerah dan meningkatkan PAD.
Lebih jauh, kemandirian Aceh juga bergantung pada penguatan industri berbasis sumber daya alam lokal, pemanfaatan pelabuhan strategis seperti Sabang, Krueng Geukuh, Kuala Langsa serta revitalisasi sistem perbankan syariah agar dana masyarakat berputar dalam skema produktif di dalam daerah. Hilirisasi produk unggulan seperti kopi, hasil laut, dan CPO akan memberi nilai tambah sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan luar. Di sisi lain, pembangunan ekonomi kreatif dan UMKM berbasis inovasi digital, pariwisata halal, dan industri kreatif harus menjadi prioritas untuk mendorong lahirnya generasi wirausaha baru. Dengan sinergi langkah-langkah tersebut, Aceh dapat bergerak dari sekadar simbol perlawanan menuju kemandirian nyata yang berdaulat secara ekonomi.
Perspektif Ekonomi Syariah, kemandirian sebagai jalan tengah
Ekonomi syariah menekankan pentingnya kemandirian (istiqlal iqtishadi) agar umat tidak terjerumus dalam ketergantungan yang melemahkan. Al-Qur’an secara tegas mengingatkan bahwa kaum beriman tidak boleh membiarkan dirinya berada dalam posisi yang mudah ditekan pihak lain. Firman Allah dalam QS. An-Nisa: 141 menegaskan bahwa orang beriman tidak boleh memberi jalan bagi pihak kafir untuk memusnahkan mereka. Dalam konteks modern, ayat ini dapat dimaknai sebagai larangan membiarkan ketergantungan ekonomi yang berpotensi merugikan dan merendahkan martabat umat. Artinya, kemandirian ekonomi bukan hanya isu teknis, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga harga diri dan kedaulatan.
Dalam kerangka itu, tradisi ekonomi Islam menawarkan dua prinsip penting yang relevan bagi Aceh. Pertama, prinsip produksi dan hilirisasi (al-intaj wa al-tasni’) yang menekankan pentingnya mengolah sumber daya lokal—seperti kopi Gayo, hasil bumi, hasil laut, dan CPO—di dalam negeri sehingga memberi nilai tambah dan tidak sekadar diekspor mentah ke luar daerah. Kedua, prinsip keadilan distribusi (al-‘adalah al-iqtisadiyah) yang menuntut pemerintah daerah menciptakan mekanisme perdagangan yang adil agar masyarakat tidak terus-menerus membeli barang dari luar dengan harga lebih mahal. Jika kedua prinsip ini dijalankan, Aceh dapat keluar dari peran pasif sebagai “pasar” dan menempatkan diri sebagai pelaku aktif dalam jaringan ekonomi yang lebih setara.
Razia plat BL di Sumatera Utara hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih mendasar, yakni ketergantungan struktural ekonomi Aceh terhadap Medan. Selama Aceh hanya berperan sebagai pasar dan konsumen, persoalan serupa akan terus muncul dalam berbagai bentuk. Karena itu, Aceh perlu melakukan transformasi menuju kemandirian dengan membangun industri berbasis lokal, memperkuat basis fiskal, memanfaatkan infrastruktur laut, dan mengoptimalkan potensi ekonomi syariah. Pada akhirnya, martabat Aceh tidak diukur dari plat nomor kendaraan yang melintas di jalan, melainkan dari sejauh mana rakyatnya mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri. Transformasi menuju kemandirian ekonomi berbasis syariah bukan hanya jalan keluar dari konflik sosial, tetapi juga kunci peningkatan kesejahteraan dan keadilan dalam bingkai NKRI.[]