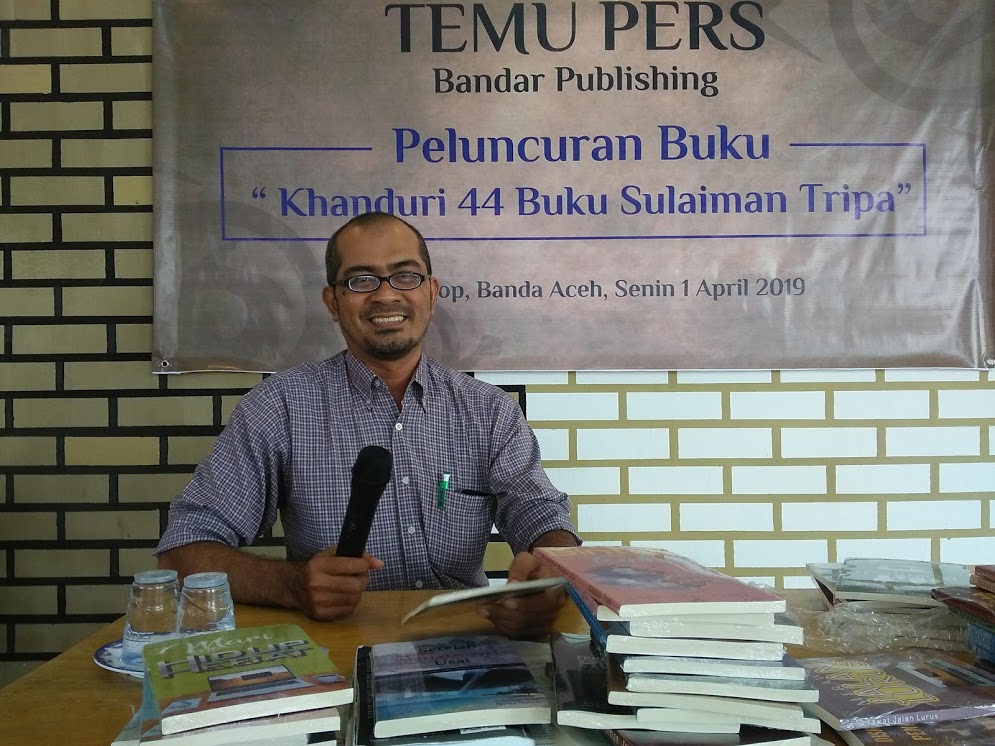Oleh: Arfiansyah.
Pengajar di Prodi Sosiologi Agama, UIN Ar-Raniry.
Artikel ini tidak memuji Snouck Hurgronje dan tidak pula ikut-ikutan marah terhadapnya seperti Kebanyakan orang Aceh. Artikel ini berangkat dari rasa penasaran saya kenapa Snouck begitu lekat dalam imajinasi masyarakat di Aceh melebihi ingatan mereka terhadap Belanda sendiri. Untuk Snouck, orang Aceh mengkonstruksi cerita yang menjadikannya bak legenda sehingga membuatnya sebagai orang kulit putih yang paling membekas di dalam benak dan imajinasi masyarakat di Aceh. Cerita-cerita itu menghadirkan sosok Snouck di tengah masyarakat Aceh dari masa-masa. Snouck begitu hidup dan terus menerus dihidupkan meski interaksi orang Aceh terakhir dengan Snouck terjadi lebih dari satu abad berlalu.
Kebencian orang Aceh terhadap Snouck melebih kebencian mereka kepada Belanda dan semua bangsa yang berhadapan dengan Aceh di medan perang. Hampir semua masyarakat di Aceh generasi pasca kemerdekaan seperti memberi goresan luka kepada setiap bayi yang mereka lahirkan. Goresan yang mengingatkan bayi tersebut kepada Snouck ketika mereka besar dan terus berputar demikian dari generasi ke generasi berikutnya. Kebencian tersebut melewati ubun-ubun mereka yang kemudian memberikan kesan penghormatan yang luar biasa terhadap Snouck. Secara harfiah, penghormatan itu setidaknya mereka berikan kepada karya Snouck tentang Orang Aceh yang menjadi adikarya untuk dunia pengetahuan (antropologi dan etnografi) dan juga kebijakan kolonial.
Di Aceh, Snouck kerap hadir dalam percakapan sehari-hari dalam bentuk idiom dan sindiran. Snouck terkadang dijadikan ungkapan untuk memuji kawan yang sekaligus bermakna kewaspadaan. “jangan seperti Snouck” adalah ungkapan yang kerap saya dengar dari orang-orang tua di Aceh ketika masih belajar di Universitas Leiden, kampusnya Snouck. Ungkapan yang bermakna kewaspadaan, kehati-hatian, kebencian dan juga terkadang menjurus pada kesan penghormatan karena kebencian yang terlalu besar terhadap seseorang adalah dampak dari ketidakmampuan orang tersebut menandingi dan menundukkan yang dibenci.
Begitu lekatnya Snouck pada lidah orang Aceh membuat semua orang Belanda yang berkunjung ke Aceh selalu merasa was-was. Mereka khawatir, peristiwa masa lalu masih dapat memicu kekerasan terhadap mereka. Pada tahun 2006 pasca Tsunami, misalnya, saya bekerja dengan beberapa orang Belanda di sebuah INGO. Semuanya, ketika pertama sekali ke lapangan akan bertanya apakah mereka akan baik-baik saja?
Namun Snouck memiliki tempat sendiri. Orang Aceh memisahkannya dari Belanda. Karenanya kawan-kawan Belanda saya kemudian mendapati orang Aceh fair menepatkan masa lalu pada tempatnya. Apalagi orang Aceh merasa tak pernah dikalahkan oleh Belanda, yang membuat orang Aceh selalu bangga berhadap-hadapan dengan Belanda hingga saat ini. Tetapi berbeda dengan Snouck, Orang Aceh begitu murka. Mereka ditaklukkan oleh satu kepala, kepala Snouck.
Merawat Ingatan Kelam
Tidak ada manusia yang berhasil menghantam orang Aceh begitu kuat, sadis dan memalukan selain Snouck. Dari ribuan orang yang datang ke atau ditantang oleh Aceh, hanya Snouck lah seorang yang kemudian hari benar-benar diperhitungkan dan diingat sampai sekarang.
Setelah kemerdekaan Indonesia, sepertinya orang Aceh mengevaluasi kenapa mereka harus lari ke gunung dan membiarkan orang Belanda membangun rel kereta api, membuka perkebunan hingga ke pedalaman Aceh seperti pabrik kopi dan teh, membiarkan Belanda berada di tengah hutan pinus untuk menderes getah dan membiarkan mereka mengumpulkan pundi-pundi Golden dari hasil hutan Aceh. Orang Aceh pasca kemerdekaan sepertinya terus berpikir, kenapa Belanda yang jumlah sedikit itu berhasil membangun jalan ke pedalaman rimba Gayo dan lintasan pesisir timur hingga Selatan Aceh.
Mereka sepertinya sepakat berkesimpulan bahwa Snouck adalah biang kemunduran mereka. Snouck adalah garis batas antara perlawanan senjata yang heroik dan tak terkalahkan dengan pelarian ke hutan belantara membangun strategi perang baru. Snouck adalah batas antara tetap bertahan di Kuta Raja dengan pindah ke hutan belantara. Pahitnya hasil evaluasi terhadap Snouck ini membuat orang Aceh merawat segala sesuatu tentangnya. Banyak cerita tentang Snouck yang begitu merakyat yang membuatnya melekat.
Orang Aceh, baik di pesisir maupun di pedalaman tengah Aceh saat ini tidak pernah mengetahui secara persis kalau Snouck pernah memberikan ceramah agama kepada indatu mereka dahulu. Snouck pun tidak membuat catatan dan pengakuan yang mengatakan bahwa dia pernah berdiri di atas mimbar Masjid Raja. Namun, orang Aceh begitu yakin, Snouck telah memberikan sejuta petuah agama kepada orang Aceh melalui mimbar-mimbar masjid dan kedai kopi serta tausiah dari rumah ke rumah. Mereka begitu yakin kalau Snouck telah mengelabui keyakinan mereka terhadap agama, yang merupakan biang keterpurukan mereka.
Snouck sendiri memang mengaku selama di Kuta Raja dan pesisir Aceh dia bertemu dengan orang di tempat-tempat umum dan pergi ke desa-desa. Dia berdiskusi dengan para arisktrokrat, guru agama dan orang biasa. Dia menginterogasi para tahanan dan dengan terang-terangan dia berlalu lalang antara pasar dan kantor kolonial. Dia tidak bekerja secara sembunyi-sembunyi seperti yang telah dilakukan di Mekkah dengan berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Kegiatan dan afiliasinya yang jelas kepada kolonial Belanda menyisakan tanya apakah orang Aceh dulu tidak menaruh curiga dan mempertanyakan identitas Snouck dan misinya di Aceh? Sepertinya, orang Aceh pasca kemerdekaan mengabaikan semua pertanyaan yang dapat mengurangi kepedihan terhadap Snouck. Cerita Snouck sebagai biang keterpurukan harus terus dibangun dan dirawat. Harus ada satu yang disalahkan atas kemunduran Aceh dalam peperangan, bukan Belanda tetapi Snouck.
Satu hari di Aceh Tengah saya bahkan mendapatkan cerita bahwa Snouck mengajarkan kepada orang Gayo tentang bagaimana menghormati Al-Quran. Menurut cerita itu, Snouck mengatakan bahwa Al-Quran harus diletakan di tempat tertinggi seperti dipan atau di atas lemari. Al-Quran itu suci dan mulia karenanya harus dibalut dengan kain putih bersih untuk menjaganya. Orang Gayo begitu yakin dengan ucapkan Snouck yang mereka beri gelar Tengku Puteh (Ulama Putih) dan melakukan apa yang diajarkan tentang etika terhadap Al-Quran.
Generasi berikutnya menyalahkan Snouck atas nasehatnya karena ternyata itu adalah upaya Snouck menjauhkan orang Gayo dari Al-Quran, sumber pengetahuan dan kekuatan. “Kalau kita temui saat ini banyak A-Quran bersampul debu yang tebal, itu disebabkan ajaran Snouck yang berhasil memanipulasi keyakinan orang Gayo terhadap Islam”, begitu ujar salah seorang orang tua di Aceh pedalaman. Snouck lah yang telah menjauhkan mereka dari ajaran Islam. Karenanya orang Aceh mundur dalam peperangan dengan Belanda.
Snouck begitu bebas berkeliaran tanpa dicurigai sama sekali akan misinya. Penampilannya yang serba putih, ghamis putih, sorban putih dan dibalut dengan kecakapannya akan agama Islam dan hukum Islam telah membutakan mata masyarakat di Gayo dan pesisir Aceh tentang identitas dan misi Snouck sesungguhnya. Namun, identitas Snouck yang non Muslim pada akhirnya ketahuan. Suatu hari, dia terlihat sedang buang air kecil berdiri di sisi sungai Peusangan, di sekitar kota Takengon. Orang yang melihatnya terkejut tak kepalang. Bagaimana mungkin seorang ulama kencing berdiri dan belum dikhitan. Berita itu tersebar cepat. Snouck lari ke pesisir. Dia kemudian tak berjejak.
Snouck sendiri sebenarnya mengaku di dalam bukunya tentang Tanah Gayo dan Penghuninya bahwa dia tidak pernah menapakkan kaki ke wilayah tengah Aceh. Tapi mengonstruksi Snouck dalam imajinasi mereka begitu penting. Penting karena mereka tak pernah dikalahkan senjata, tapi ditaklukan pengetahuan yang bangun oleh Snouck untuk Belanda.
Aceh, Snouck dan Pengetahuan
Memori yang begitu dalam tentang Snouck bukanlah sebatas memori tentang sakit hati dan dendam. Meskipun Snouck sering ditepatkan sebagai papan dart untuk melemparkan semua amarah masa lalu, tapi Snouck juga dipuja oleh orang Aceh untuk hasil karyanya tentang budaya dan masyarakat Aceh dan Gayo masa lalu. hasil karyanya tentang orang Aceh yang kini berjudul “Aceh di Mata Kolonialisme” sempat menjadi buku paling dicari di Aceh beberapa tahun lalu. Merujuk pada tulisan Snouck terkadang lebih terasa hebat, ilmiah dan berkualitas daripada merujuk pada ribuan manuskrip yang ditulis oleh Ulama Aceh sendiri.
Memori dan konstruksi cerita tentang Snouck adalah memori dan cerita tentang penyebab keterpurukan terbesar dalam sejarah Aceh dihadapan orang luar. Orang Aceh tentu menolak kata “kalah” apalagi “menyerah”. Sebagian besar orang Indonesia juga sepakat dengan mereka, Aceh tak pernah dikalahkan Belanda. Benar, Aceh tak pernah mengalah apalagi menyerah dihadapan senjata siapa pun; tidak kepada Belanda, Jepang dan tidak pula kepada tentara Indonesia pada masa pemberontakan ulama dan kelompok etno-nasionalist Aceh. Tapi mereka ditaklukan hanya oleh satu orang, hanya Snouck Hurgronje seorang.
Snouck pada konteks ini tidak lagi digambarkan sebagai sosok manusia. Tapi dia sering digambarkan sebagai simbol kekalahan pada pengetahuan. Snouck tidak pernah digambarkan berada di medan perang dan memegang senjata. Dia hanya bermodal tanya dan pena. Sosoknya baru dimunculkan pasca kemerdekaan. Dia diceritakan dengan simbol-simbol emosional akan ketertinggalan dalam pengetahuan dan kecerdikan. Kedua hal ini yang menaklukkan semua gerakan bersenjata Aceh semenjak abad ke 18 hingga abad 21 ini.
Orang Aceh, dalam semua sejarah lisan yang saya dengar sejak kecil hingga kini, selalu bangga akan kegigihan mereka melawan Belanda jika berhadap-hadapan senjata dan strategi perang. Banyak cerita tentang strategi perang yang terkadang terkesan tak masuk akal, seperti menungging di bibir pantai dan kemudian pantat mereka dicat hitam agar dikira barisan meriam. Atau memanjat pohon kelapa, membawa serta cermin agar pantulan cahaya dikira selaksa perwira yang bersiap menyambut perang. Dalam banyak cerita, Belanda selalu menunda bahkan membatalkan serangan akibat kecerdikan strategi orang Aceh. Dari cerita-cerita melegenda yang beredar, menurut orang Aceh bahkan Belanda sendiri, peperangan Belanda dengan Aceh adalah peperangan paling mahal dalam sejarah kolonial Belanda. Frustasi melawan kecerdikan dan strategi perang orang Aceh, Belanda mengutus Snouck Hurgronje, seorang antropolog yang ahli Islam dan Hukum Islam. Di sini Belanda tidak mengutus manusia, tetapi mengutus pengetahuan.
Sebelum ke Aceh, Snouck belajar banyak hal tentang Islam dan Aceh baik ketika dia di Mekkah maupun di Batavia (Jakarta saat ini) sebagai penasihat kolonial. Dia adalah orang Eropa non Muslim pertama yang berhasil masuk ke Mekkah. Dan orang kulit putih pertama pula yang mengambil foto-foto Mekkah. Untuk belajar, dia bahkan rela disunat dan kabarnya juga mengucapkan dua kalimat syahadat agar bisa menjadi bagian dari masyarakat yang dia pelajari. Untuk itu dia mengubah diri menjadi Abdul Ghaffar.
Kepiawannya dalam membangun pengetahuan (meneliti) dan pengorbanannya demi menjadi bagian sebuah komunitas diajungkan jempol oleh semua antropolog dan etnografer. Menjadi bagian penting dari masyarakat yang harus ditaklukkan bukanlah perkara mudah untuk saat itu bahkan untuk saat ini. Dengan catatan etnografisnya yang lengkap dan menyeluruh serta analisa-analisanya tentang struktur budaya dan masyarakat di Aceh, dia telah meletakan fondasi antropologi masyarakat Muslim dan hukum Islam untuk pertama kali. Dia kemudian dikenang oleh antropolog dan etnografer sebagai salah seorang maha guru antropologi. Perkerjaannya membangun pengetahuan pada masa lalu terus menjadi rujukan dan diskusi hingga saat ini. Baik di Belanda maupun di Indonesia, dirinya dan hasil karyanya dibicarakan kembali setiap tahunnya.
Sebenarnya, ketika Snouck datang ke Aceh, masyarakat Aceh telah lama terpuruk dan menjauh dari ilmu pengetahuan. Catatan-catatan kejayaan Aceh yang ditopang oleh semarak pengetahuan terakhir sekali direkam hingga akhir abad ke 17, ketika masa Ratu Syafiatuddin berkuasa. Setelahnya, kekuatan kesultanan Aceh menurun drastis. Ulee Balang atau aristokrat kemudian mengamankan kekuasaan mereka di wilayah kemukiman masing-masing. Membuat Kesultanan Aceh secara teknis terpecah-pecah menjadi kecil. Semenjak itu, Sultan hanyalah simbol pemersatu saja tanpa kekuatan ril.
Keterpurukan yang memalukan tidak pernah terjadi ketika Aceh menjadi kesultanan kosmopolit. Kebebasan berpikir dijamin. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Para ulama giat menulis, memperkenalkan ragam pengetahuan baru mulai dari pertanian, astronomi, budaya dan kelautan. Mereka bahkan melatih perang. Mesjid Raja Baiturrahman adalah sebuah pusat studi terkemuka, sebuah kampus yang melahirkan cendekia dan pejuang-pejuang seperti Laksamana Malahayati. Alih-alih diserang, Aceh selalu menyerang dan memperluas kekuasaannya di wilayah Asia Tenggara sekarang.
Menurunnya semangat pengetahuan mulai terjadi ketika kesultanan tidak lagi ditopang oleh ulama besar. Dengan kata lain, Aceh terpuruk ketika kekuasaan/penguasa mulai mengangkangi dan mengatur kemajuan pengetahuan. Ketika perut mulai menguasai pikiran. kehilangan kelompok pelajar di lingkaran kesultanan menurunkan pengaruh dan kekuatan, bahkan kekuatan militernya. Belanda datang pada masa-masa Aceh sebenarnya telah lama tenggelam. Melepaskan diri dari semarak dan semangat berpengetahuan.
Dengan sisa-sisa kejayaan kesultanan tersebut, Aceh masih sulit ditaklukan oleh senjata Belanda hingga Snouck datang dengan semangat penelitian dan mengali pengetahuan untuk kebijakan kolonial. Aceh kemudian takluk meski kata “kalah” dan “menyerah” tidak pernah diterima oleh mereka. Tetapi dengan kepedihan, mereka menyaksikan dari kejauhan bagaimana Belanda membangun rel kereta api antara provinsi, membangun jalan yang begitu panjang, membangun perkantoran, membuka puluhan area perkebunan, membangun sekolah-sekolah dan rumah sakit, membangun museum yang hingga puluhan tahun berikutnya menjadi museum satu-satunya di Aceh. Semuanya terjadi semenjak Snouck memperkenal kebijakan etis di Aceh yang kemudian menjadi panduan untuk kebijakan kolonial di Indonesia.
Penutup
Artikel ini tidak bermaksud meletak Snouck Hugronje pada tempat yang agung di tengah-tengah masyarakat Aceh yang sudah pasti menolaknya mentah-mentah. Artikel ini hanya berusaha mendalami dan memahami kenapa Snouck begitu abadi di dalam imajinasi masyarakat Aceh dan kenapa mereka memisahkan kemarahan terhadap Snouck dari Belanda di dalam cerita sehari-hari mereka. Itu bukanlah kemarahan semata, tetapi juga rasa hormat yang tak mungkin diperikan ke alam semesta bahwa dalam amarahnya, orang Aceh mengakui bahwa pengetahuan lah yang menaklukan mereka, bukan senjata. Itu cukup menjadi makna yang dirahasiakan di dalam jiwa dan diturunkan kepada generasi di setiap masa. Tetapi tidak ada yang mengambil hikmah dan menjadikannya pelajaran bangsa.
Semenjak kedatangan Belanda hingga saat ini, pengetahuan tak pernah berkembang di Aceh bahkan mungkin di Indonesia. Penyebab utamanya hanyalah karena kekuasaan mengangkangi pengetahuan. Sejak akhir abad ke 17 hingga kini orang Aceh berebut kekuasaan dan meributkan pembagiannya. Selama pengetahuan di Aceh tidak mendapatkan tempat yang layak di dalam pemerintahan dan masyarakat, barangkali selama itu pula sumpah serapah terhadap Snouck selalu dijaga.[]