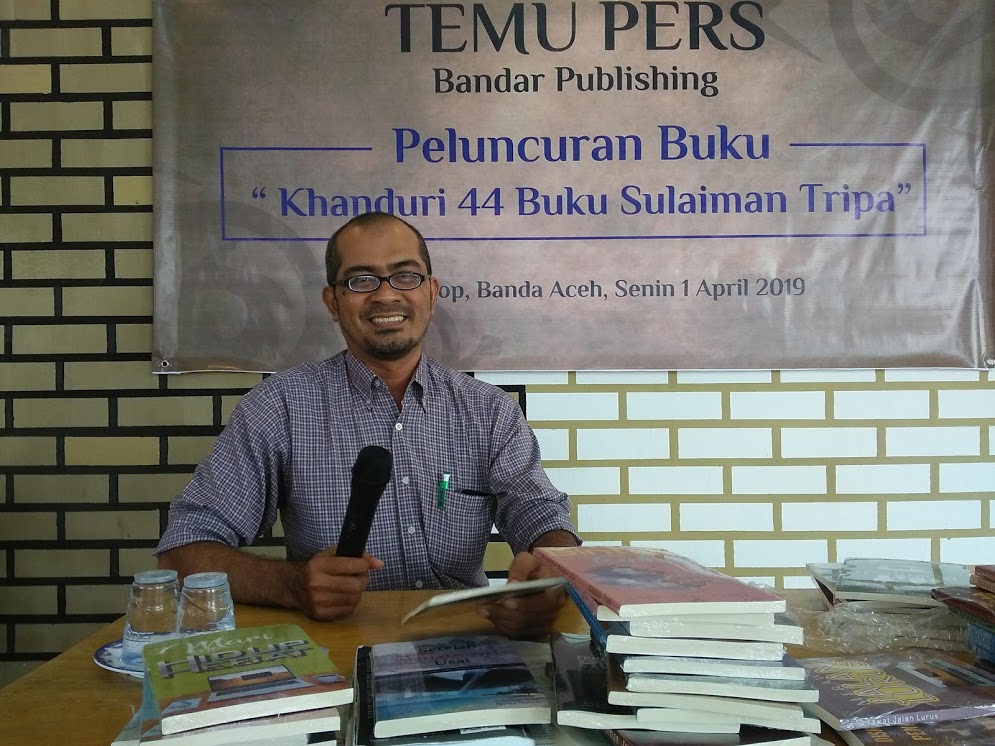Oleh: Sulaiman Tripa
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
“…permasalahan UUPA jangan dipendam terlalu lama, jika ada persoalan maka harus segera diperbaiki, kepada pemerintah pusat diharapkan tidak membuat UU yang menabrak UU Otonomi Khusus.” – Yusril Ihza Mahendra, Republika, 12 Agustus 2023.
Latar Belakang
Dua tahun yang lalu, 2023, saat berkunjung ke Aceh, Profesor Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bagaimana idealnya otonomi khusus dalam republik. Sejumlah kata di atas, antara lain menggambarkan kondisi ideal itu. Namun hal ini masih jauh dalam realitas.
Sejumlah kajian pascakonflik –apalagi konflik bersenjata yang menahun—butuh waktu untuk kembali ke kondisi sedia kala. Bukan soal mudah untuk menyelesaikan konflik. Butuh kerja keras juga untuk merawat perdamaian yang sudah dicapai. Soal pemulihan konflik tidak saja soal reintegrasi, melainkan termasuk bagaimana perempuan yang menjadi korban mendapat perhatian dalam penyelesaiannya (Ulfah, Fedryansyah, & Nulhaqim, 2022). Peran perempuan dalam merawat serta membangun perdamaian dan keamanan, pada dasarnya juga nyata dan tidak mungkin diabai (Ocktaviana & Kamaruzzaman, 2021; sejumlah catatan ini lihat juga: Azizah, Hidayahtulloh, Perwita, & Maksum, 2021).
Dengan demikian, konflik Aceh dan proses penyelesaian harus dilihat secara utuh sebagai satu rangkaian yang saling bertautan (Adryamarthanino & Nailufar, 2021). Selain itu, prosesnya juga melibatkan banyak pihak. Atas dasar itulah, tidak mungkin ada klaim seolah hanya beberapa orang saja yang berperan dalam menyelesaikan Aceh tersebut.
Kesadaran banyak pihak dan banyak faktor yang terlibat, sangat penting sebagai pemahaman bersama. Pemahaman ini akan berdampak pada kekuatan bersama untuk merawatnya dengan baik. Banyak catatan diberikan berkaitan upaya merawat damai, baik melalui buku maupun artikel-artikel jurnal.
Hal ini menandakan pentingnya perdamaian yang dicapai dengan susah payah itu untuk dirawat dengan baik. Bahkan tahun 2012, Pustaka Larasan, ICAIOS, dan KITLV-Jakarta, menggarap satu buku penting, Aceh Pascatsunami dan Pascakonflik. Buku ini disunting oleh Patrick Daly R. Michael Feener Anthony Reid. Salah satu tulisan di dalamnya, Rizal Sukma, “Mengelola Perdamaian di Aceh: Tantangan Pemeliharaan Perdamaan Pascakonflik”, menyebut sejumlah tantangan kunci dalam upaya pemeliharaan perdamaiaan di Aceh, yakni: Pertama, implementasi pasal-pasal kunci dalam MoU yang belum dituntaskan. Kedua, perlu diciptakan mekanisme penyelesaian damai terhadap perbedaan-perbedaan dan konflik. Ketiga, perdamaian yang awet dan berkelanjutan hanya dapat dijamin oleh upaya-upaya sadar untuk menangani akar penyebab yang memicu konflik pada awalnya (Sukma, 2012).
Apa yang diungkapkan Rizal Sukma, juga ditegaskan oleh Yusril Ihza Mahendra. Sebagai ahli hukum tata negara, sebelum mendapat amanah sebagai Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, ia menyebutkan bahwa UUPA masih banyak kekurangan di dalam pasalnya, tidak seluruh hasil kesepakatan Helsinki dapat tertuang dalam UUPA sekarang. Atas dasar itulah, UUPA masih sangat terbuka untuk dilakukan perbaikan. Peraturan ini merupakan salah satu lex spesialis dari semua UU di tingkat nasional (Putra, 2023).
Ada banyak catatan yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra. Merujuk pada proses pembahasan aturan pelaksana dari UUPA, betapa banyak waktu yang dibutuhkan, dengan jumlah pertemuan yang tidak sedikit. Padahal dengan logika lahirnya UUPA sebagai langkah kongkret mengartikulasikan MoU, harusnya akan dibentuk aturan pelaksananya dengan sukarela. Realitas empiris tidak memperlihatkan demikian. Untuk menyelesaikan apa yang harusnya hadir sebagai konsekuensi dari UUPA, butuh energi yang luar biasa untuk bisa mencapai titik temunya.
Saya menganggap UUPA itu sebagai bagian dari produk cinta. Hukum yang lahir juga atas dasar sekaligus konsensus karena cinta, pada dasarnya hukum yang dipenuhi dengan keikhlasan dan kepentingan kebersamaan. Berhukum dengan cinta, harus menjadi jawaban dari komitmen untuk menjaga dan merawat damai. Salah satu saluran menjaga dan merawat ini adalah memastikan semua yang menjadi konsensus –dalam bahasa lain dan dalam bentuk formal MoU – dan telah dikongkretkan dengan UUPA, harus dipastikan semua sudah dituntaskan dengan baik.
Untuk memahami keduanya (MoU dan UUPA), harus berangkat dari konsep dasar hukum (dan berhukum). Untuk semua kepentingan dari hukum tersebut, termasuk bagaimana hukum harus mematikan bagi kebahagiaan rakyatnya, maka berangkat dari konsep hukumnya.
Konsep Hukum dan Berhukum
Semua orang yang belajar hukum melalui jalur formal, tidak mendapatkan konsep hukum dalam satu makna. Dengan demikian, mereka juga tidak mendapatkannya dalam satu wajah, melainkan banyak wajah (multi fased). Menggambar wajah hukum sesungguhnya bukan perkara mudah dan tidak sederhana.
Sejumlah yang bermateri pengantar ilmu hukum, selalu menyertakan ragam konsep hukum dari berbagai sudut dan cara pandang. Kondisi ini sebenarnya dibentuk dari posisinya dalam meyakini aliran atau mazhab yang melatarbelakangi cara pandangnya itu.
Buku Satjipto Rahardjo dan buku Achmad Ali, menyebut sejumlah pendapat terkait apa yang disebut sebagai hukum. Pendapat para sarjana, yang bisa diinventarisasi dalam ragam aliran. Tentu saja, posisi aliran atau mazhab akan berbeda cara melihat lebih jauh terhadap hukum. Sejumlah buku hukum memperlihatkan adanya perbedaan cara memandang hukum dari masing-masing latar belakangnya, baik dari aliran hukum historis, realisme hukum, hukum alam, atau bahkan aliran positivism hukum (Rahardjo, 2006; Ali, 2015).
Konteks berhukum, tersedia satu konsep yang ada dalam buku Satjipto Rahardjo. Cara berhukum akan berhubungan dengan bagaimana cara hukum itu dilaksanakan. Dengan kata lain, bagaimana cara kita menjalankan hukum. Selama ini, jika merujuk pada buku-buku hukum progresif, menjalankan hukum masih didominasi dengan cara-cara berhukum tertentu yang dipaksanakan, terutama dalam bentuk yang didatangkan dan didatangkan dari luas. Satjipto Rahardjo menyebut kata “transformed and imposed”. Apa yang didatangkan tersebut, kemudian diberlakukan dalam tatanan sosial Indonesia yang lebih asli dengan sekalian nilai-nilainya.
Konsep yang lebih kongkret saya baca dari satu artikel Satjipto Rahardjo di Harian Kompas, yang menyebutkan cara berhukum sebagai cara menjalankan hukum. Berhukum memang dimulai dari teks, tetapi sebaiknya tidak berhenti sampai di situ. Teks yang bersifat umum itu memerlukan akurasi atau penajaman yang kreatif saat diterapkan pada kejadian nyata dalam masyarakat, yaitu melalui hukum dengan akal sehat. Hukum menjadi apa yang disebut sebagai institusi akal sehat (reasonable) dan bukan sekadar institusi penerapan teks (Rahardjo, 2008).
Dua konteks makna dari cara berhukum saya temukan dalam buku Ilmu Hukum. Pertama, mendayagunakan hukum dalam hal menyelesaikan berbagai problem dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, hukum yang digunakan berakar pada suatu komunitas, dimana komunitas tersebut dimulai dengan membangun suatu tatanan yang bersifat lebih alami, seperti tradisi dan kebiasaan. Ditegaskan Satjipto Rahardjo, hukum dalam masyarakat kita di Indonesia memiliki tradisi sebagai kontekstualisme, dimana seseorang di dalamnya sociocentric, bukan individual centric. Maka dalam konteks ini, filsafat kehidupan (arena) sosial yang mendasarinya adalah holism. Keterpaduan (cohesion) lebih diunggulkan dari pada konflik. Corak cara berhukum tipe ini, dalam iklim harmoni, maka konflik diredam (Rahardjo, 2006).
Atas penjelasan itulah, sesungguhnya hukum harus dilihat lebih luas dari hanya sekedar teks undang-undang. Konteks berhukum, dengan demikian, melampaui dari apa yang sekadar diatur dalam undang-undang semata.
Ada penjelasan lugas dalam buku Satjipto Rahadjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, bahwa masing-masing bangsa tentu memiliki corak cara berhukum, dimana dalam operasionalnya, ia tidak bisa dilepaskan dari akar-akar sosial dan kulturalnya. Cara berhukum itu bukanlah sesuatu yang masinal dan mekanistis, tetapi merupakan suatu bentuk kehidupan sosial yang khas (a peculiar form of social life) (Rahardjo, 2007).
Pemahaman cara berhukum semacam itu harusnya menjadi arus utama dalam memahami hubungan Aceh dan republik. Harus ada yang mendorong cara berhukum yang lebih dinamis, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial, dan bukan hanya terpaku pada teks aturan-aturan yang seperti hilang ruang sosialnya.
Pemahaman tersebut sangat penting untuk posisi Aceh yang berada pada arena pascakonflik (sekaligus pascatsunami) dan membutuhkan responsivitas yang lebih besar lagi. Apalagi hukum dalam konteks Aceh dalam republik, sebagai wujud dar bentuk yang lebih kongkret dari apa yang disebut sebagai kesepahaman bersama. Jadi bukan hukum yang dilihat secara terpisah dari keberadaan kesepahaman bersama tersebut.
MoU sebagai Titik Temu Moral
Dalam satu diskusi menjelang 20 tahun damai Aceh, salah seorang yang terlibat dalam tim runding Indonesia di Helsinki, Prof. Hamid Awaluddin mengingatkan bahwa MoU itu fondasi yang tidak boleh dianggap tanpa makna. UUPA dan revisi apapun dipandu oleh MoU tersebut sebagai modal dan akar dalam menyelesaikan konflik. Pendapat semacam ini, beberapa kali juga diungkapkan Wakil Presiden waktu itu, HM Jusuf Kalla. Ia mengingatkan agar menjaga rasa saling percaya atas tercapainya damai.
MoU dapat disebut sebagai titik temu dari moral. Ketika membuat konsensus, para pihak utama –Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka—yang bertemu dan berdialog di sudut Helsinki (Finlandia), memiliki pertimbangan mendalam untuk menyetujui hal yang bisa diterima bersama. Pertimbangan ini, secara kongkret bisa dibaca dalam konsiderans menimbang dari UUPA.
Ketika posisi sekarang masih ada yang bermasalah dan mempermasalahkan pada UUPA, secara konsep sepertinya harus dipahami begitu sulit apa yang menjadi titik temu moral itu lalu dirumuskan dalam teks-teks formal yang terukur. Hal ini, menurut tingkatannya dapat dilihat dalam dua masalah. Masalah pertama, ditemui adanya perbedaan cara membaca, cara menerjemahkan, cara memahami, dari teks moral ke teks undang-undang. Apa yang menjadi konsensus dan ada dalam MoU, ternyata tidak semua terbaca dan tertampung secara gambling dalam UUPA. Masalah kedua, pada sisi cara UUPA diimplementasikan. Apa yang sudah ada dalam UUPA saja, masih saja memiliki banyak hambatan dan tantangan untuk terumus secara kongkret dalam aturan pelaksananya.
Dua masalah di atas, bukan perkara sederhana. Butuh keikhlasan dan kelegaan hati untuk memperbaiki diri sebagai konsekuensi dari konsensus moral. Rasa saling percaya, tidak main belakang, dan apa adanya, merupakan sikap-sikap arif yang harus dipupuk dalam rangka merawat damai Aceh yang sesungguhnya masih seumur jagung. Malah seharusnya kedua pihak utama dalam MoU harus bahu-membahu dalam proyek merawat ingatan bagi generasi muda Indonesia agar mereka tahu bahwa di Aceh pernah merasakan kisal kelam yang tidak boleh terulangi di masa mendatang. Merawat ingatan ini tidak sama seperti merawat luka. Merawat ingatan sangat penting agar generasi masa depan tidak mengulang kisah kelam yang sama.
Saya kira, banyak negara beradab di dunia ini dengan bersahaja merawat kisah-kisah kelam negerinya berbagai cara. Mendirikan museum, menghadirkan tugu tertentu, bahkan bangunan tertentu untuk mengingat agar tidak terulangi kisah kelam negeri mereka. Bukan dengan menguburnya dalam-dalam lalu memberi yang tidak masuk akal.
Hadirnya MoU merupakan pengakuan secara langsung bahwa di Aceh pernah terjadi sesuatu yang tidak manusiawi. Dengan MoU, sebagai bentuk tertulis, ingin menjadikannya sebagai perisai agar tidak terulangi. Maka memaknai MoU harus dilakukan sampai ke relung hati.
Mudah-mudahan sudah cukup korban hingga MoU. Tidak muncul lagi konflik yang akan menambah beban bagi generasi Aceh sekarang dan yang belum lahir. Berdasarkan catatan dari buku Al Chaidar, Sayed Mudhahar Achmad, & Yarmen Dinamika, jumlah korban dari rangkaian konflik Aceh mencapai 35 ribu (Chaidar, Achmad, & Dinamika, 1998). VoA Indonesia yang mengutip Amnesty International mencatat 10-30 ribu korban jiwa (Lamb, 2013; BBC, 2023). Bukan soal mudah untuk menghitung-hitung jumlah korban. Pihak yang menjadi korban pun sangat beragam. Sipil yang harus mendapat perhatian utama. Hal yang pasti bahwa setiap konflik pasti akan muncul korban. Dan hal yang harus diingat pula, ingatan tentang konflik akan membekas dalam ingatan.
UUPA sebagai Titik Temu Hukum
Apa yang ada dalam MoU, dikonkretkan dalam UUPA. Tanda tanya tetap saja muncul, misalnya apakah sebuah undang-undang yang berasal dari satu MoU sudah pasti sudah menampung semua hal? Sebagaimana sudah diungkapkan sebelumnya, memungkinkan ada kesenjangan antara apa yang diatur dalam MoU dan UUPA.
Kajian hukum menyebutkan betapa sulitnya konsensus tertentu diaplikasikan dalam pengaturan kongkret. Secara sosiologis pengaturan semacam ini mendapat banyak kendala, namun harus diselesaikan. Kerumitan membentuk UUPA dari basis MoU merupakan pengalaman Aceh dalam NKRI yang sangat bernilai, karena UUPA harus menjamin tertampung dari apa yang disepakati dalam MoU (Sulaiman, 2012).
Atas dasar itulah, MoU dan UUPA harus dilihat secara bersamaan. Keduanya berhubungan erat dan tidak mungkin dipisahkan. Dalam konteks bagaimana hubungan tersebut, paling tidak kita bisa pastikan dengan merujuk pada dua kunci yang selalu harus diingat (dan ini tersurat dalam konsiderans UUPA), yakni: Pertama, bencana yang melahirkan kesadaran untuk perwujudan perdamaian dalam NKRI. Kesadaran ini melahirkan komitmen penyelesaian konflik berkelanjutan “hitam di atas putih” melalui sebuah MoU yang dilanjutkan dengan pembentukan UUPA. Kedua, ihwal UUPA juga harus mengkonkretkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan upaya pelaksanaan pembangunan di Aceh untuk dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia (Tripa, 2024)
Dengan bersandarkan pada dua kunci penting tersebut, ada dua pertanyaan terkait yang juga harus terjawab, yakni:
Pertama, apakah semua isi MoU tertampung dalam UUPA? Dalam hal UUPA, Pemerintah berusaha semua poin dalam MoU yang menjadi konsensus untuk diatur dalam UUPA. Hanya saja sampai sekarang, belum semua poin tersebut berjalan sebagai konsensus. Kondisi ini bisa dipahami karena kewenangan untuk melaksanakan dua hal tersebut berada di dua lembaga berbeda. MoU ditandatangani oleh pemerintah, sementara kewenangan pembentukan UUPA ada pada dua lembaga pembentuk undang-undang, yakni lembaga eksekutif-legislatif. Dengan lembaga yang berbeda, maka tafsir atas apa yang disepakati juga berbeda. Berbagai perbedaan pandang inilah antara lain yang dirasakan hingga sekarang ini, yang harus diselesaikan dengan baik.
Kedua, apakah apa yang diatur dalam UUPA sudah semuanya dituntaskan dalam implemenetasinya? Pertanyaan ini juga sangat penting, karena pada kenyataannya masih ada beberapa ketentuan pelaksana UUPA hingga kini masih belum tuntas. Patut diingat bahwa ketentuan pelaksana tidak hanya apa yang menjadi kewajiban pemerintah (Jakarta). Pada kenyataannya, belum semua qanun diselesaikan tingkat Aceh.
Kedua pertanyaan ini (normatif dan sosiologis) sangat penting untuk dijawab. Konon lagi berbagai kekurangan dalam proses pembentukan hukum akan menjadi masalah hukum tersendiri, terutama bisa memunculkan suasana “kekosongan” hukum. Dalam hal ini, hukum yang seharusnya diatur dengan UUPA, akan tetapi karena belum selesai ketentuan pelaksana, tidak bisa dioperasionalkan. Dalam konteks Aceh, sepertinya dua posisi sekarat juga harus dipahami: antara perbedaan pandang di satu pihak, dan kemauan politik di pihak lain. Baik cara pandang dan kemauan politik adalah dua hal yang sangat terbuka peluang untuk diselesaikan oleh Pemerintah (Jakarta) dan Pemerintahan Aceh. Proses penyelesaian keduanya akan memperlihatkan titik kait terpenting dalam sebuah undang-undang, yakni politik, hukum, dan kepentingan.
Sebuah UU yang lahir dan bertujuan untuk mengatur kekhususan (dan keistimewaan), pada dasarnya memberikan kesempatan bagi Aceh untuk mengatur dirinya. Konsep ini berfungsi untuk memberi keleluasaan walau dalam realitas, keleluasaan itu dipangkas. Padahal seharusnya pemerintah melihat implementasi otonomi khusus sebagai wujud dari pengintegrasian nilai-nilai lokal dengan keutuhan NKRI (Aryana, Choirunnisa, Rahman, & Immanuel, 2024).
Catatan Akhir: Revisi UUPA dan Momentum Batu Uji
Dengan mengingat pentingnya UUPA bagi jalan damai Aceh, maka idealnya proses revisi yang dilakukan pun harus ekstra hati-hati. Program Legislasi Nasional Tahun 2024 yang menyepakati UUPA sebagai salah satu undang-undang yang akan direvisi, jangan sampai melaupakan posisi undang-undang sebagai hukum yang khusus. UUPA bukan undang-undang biasa yang bisa disamakan dengan yang lain.
Realitasnya perhatian orang menjadi sederhana. Salah satu isi UUPA adalah soal dana otonomi khusus dari 2% dan turun menjadi 1% hingga 0% pada 2027. Sepertinya pasal ini yang menjadi perhatian utama saat UUPA direvisi. Idealnya sejumlah hal lain juga harus disentuh. Misalnya bagaimana kewenangan mengelola hasil migas pada wilayah tertentu. Setiap sumber daya harus berdampak bagi daerah penghasil secara signifikan. Hal lain adalah tentu saja soal keberlanjutan damai yang harus menjadi konsensus bersama. Jangan dilupakan penting menegaskan komitmen ini dalam revisi.
Bagi internal Aceh, momentum ini bisa saja menjadi batu uji dalam melihat kekompakan. Dari segi momentum, era revisi dibanding saat UUPA dibentuk, tentu jauh bedanya. Dalam UUPA sendiri sesungguhnya ada kondisi tidak kompak terjadi berulang di Aceh. Eka Januar dan Ainol Marziah, dalam bahasa sederhana menyentil pentingnya momentum tertentu agar Aceh kompak (Januar & Marziah, 2019).
Inilah semacam pesan cinta yang mestinya mendapat tempat di republik. Ketika hukum dibentuk, maka berhukum dengan cinta pun menjadi titik mutlak.[]
Daftar Pustaka
Adryamarthanino, V., & Nailufar, N. N. (2021, 8 2). Gerakan Aceh Merdeka: Latar Belakang, Perkembangan, dan Penyelesaian. Retrieved from Kompas: https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/02/130000979/gerakan-aceh-merdeka-latar-belakang-perkembangan-dan-penyelesaian
Ali, A. (2015). Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Kencana.
Aryana, M. A., Choirunnisa, R. A., Rahman, A., & Immanuel, I. E. (2024). Otonomi Daerah di Aceh: Sinergi atau Tantangan bagi Pemerintah Pusat. Muqoddimah, 8(4). http://dx.doi.org/10.31604/jim.v8i4.2024.2063-2072
Azizah, N., Hidayahtulloh, M. A., Perwita, L. C., & Maksum, A. (2021). ‘Velvet Triangles’ in Women, Peace and Security Agenda in Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional, 10(1). https://doi.org/10.18196/hi.v10i1.12223
BBC. (2023). Rumoh Geudong: ‘Saya disetrum dan digantung dengan kaki di atas’, trauma anak muda Aceh. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-65845473
Chaidar, A., Achmad, S. M., & Dinamika, Y. (1998). Aceh Bersimbang Darah, Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Firmansyah. (2011). Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Januar, E., & Marziah, A. (2019). Tantangan Pemerintah Aceh Dalam Mengimplementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science, 4(2), 195-212. doi:https://doi.org/10.22373/jai.v4i2.457
Lamb, K. (2013, 4 19). Amnesty: Banyak Korban Konflik Aceh Belum Dapatkan Keadilan. https://www.voaindonesia.com/a/amnesty-banyak-korban-konflik-aceh-belum-dapatkan-keadilan-/1644497.html
Ocktaviana, S., & Kamaruzzaman, S. (2021). Women, Peace, and Security Agenda in Aceh, Indonesia. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 23(2), 127-140. doi:10.14203/jmb.v23i2.1403
Putra, E. P. (2023). Yusril Sebut Undang-Undang Pemerintah Aceh Banyak Kekurangan (Antara). https://news.republika.co.id/berita/rz94fw484/yusril-sebut-undangundang-pemerintah-aceh-banyak-kekurangan
Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum, Cetakan 6. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, S. (2007). Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Rahardjo, S. (2008, 12 19). Berhukum dengan Akal Sehat. Retrieved from Kompas.
Sukma, R. (2012). Mengelola Perdamaian di Aceh: Tantangan Pemeliharaan Perdamaan Pascakonflik. In P. Daly, R. M. Feener, & A. Reid., Aceh Pascatsunami dan Pascakonflik (p. 265). Jakarta: Pustaka Larasan.
Sulaiman. (2012). Membentuk Hukum bagi Perdamaian Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 14(1). https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6204
Tripa, S. (2024). Strategi Mengawal Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Banda Aceh: Bandar Publishing.
Ulfah, M. N., Fedryansyah, M., & Nulhaqim, S. A. (2022). Inong Balee dan Pemulihan Pascakonflik di Aceh: Analisis Teori Kekerasan Johan Galtung. Kolaborasi Resolusi Konflik, 4(2). 10.24198/jkrk.v4i2.39989
Unesco. (2012). World Trends in Freedom of Expression and Media Development . Retrieved from Unesco: https://www.unesco.org/en/world-media-trends
Sumber: Artikel ini pernah dipublikasi dalam buku bersama yang berjudul “20 Tahun Damai RI-GAM Dari Senjata, Berkonflik Dalam UUPA” terbitan https://bandarpublishing.com/produk/20-tahun-damai-ri-gam-berdamai-dari-senjata-berkonflik-dalam-uupa/