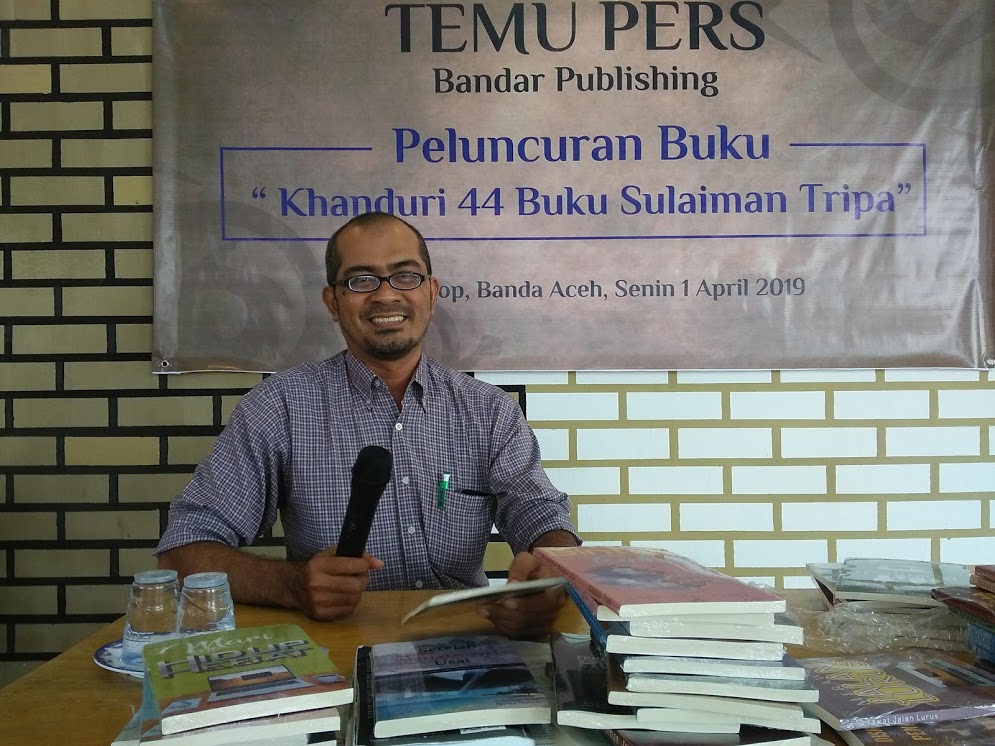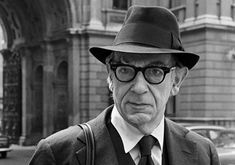Oleh: Ari J. Palawi
Peneliti dan pendidik di bidang seni, budaya, dan masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
Tulisan Dr. Arfiansyah berjudul “Tak Sempat Membawa Terang, AI Membawa Kegelapan” (Sagoe TV, 5 Agustus 2025) menyampaikan kekhawatiran yang perlu kita dengar dan pikirkan bersama. Ia menyoroti penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) dalam dunia akademik—dari mahasiswa yang menyerahkan skripsi kepada mesin, hingga dosen dan institusi yang berbangga dengan karya ilmiah instan. Saya tidak dalam posisi membantah keresahan itu. Tapi izinkan saya menyisipkan satu perspektif: bahwa kegelapan yang kita hadapi hari ini bukan karena AI, melainkan karena redupnya kecerdasan manusia itu sendiri—kecerdasan yang jujur, kritis, dan beretika—yang saya sebut sebagai Human Intelligence (HI).
Kita perlu hati-hati dalam memberi nama pada gejala. Menyebut AI sebagai pembawa kegelapan seolah memberi beban moral pada alat, bukan pada pengguna. Padahal AI hanyalah cermin. Ia tidak menciptakan niat buruk, tidak punya kehendak bebas. Ia bekerja dari perintah, belajar dari data, dan menjawab apa yang diminta. Kalau AI digunakan untuk menipu, menyalin, memalsukan, atau memproduksi kebohongan, maka yang perlu diperiksa bukan alatnya, melainkan manusianya. Masalah bukan pada teknologi, tapi pada nilai dan nalar yang gagal mengiringinya.
Saya tidak ingin membela AI, tapi juga tak ingin menyalahkannya secara serampangan. Sebab dalam banyak hal, AI justru membuka ruang baru bagi kreativitas, kolaborasi, dan efisiensi. Masalah muncul ketika manusia memperlakukannya bukan sebagai alat bantu berpikir, tetapi sebagai pengganti berpikir. Ketika mahasiswa mengganti proses pencarian dengan perintah cepat, ketika dosen mengejar publikasi tanpa melewati perenungan, ketika kampus membanggakan kuantitas tanpa menimbang kualitas, maka AI hanya menjadi katalis dari krisis yang sudah lebih dulu ada. Bukan penyebab, melainkan pemantul.
Dalam tulisan saya di Kompasiana berjudul “Segarkan Dulu Kecerdasan Manusianya” (17 Mei 2025), saya menyampaikan keresahan dari arah yang berbeda. Kita hidup dalam sistem pendidikan yang dibentuk oleh tuntutan administratif, target akreditasi, dan tekanan sosial untuk cepat selesai. Mahasiswa didorong lulus cepat, dosen didesak terbit banyak. Di tengah iklim seperti ini, AI datang bukan sebagai penyelamat atau perusak, melainkan sebagai pengungkap: memperlihatkan sejauh mana kemalasan struktural dan kekosongan intelektual telah menjadi norma yang diterima.
Di banyak kampus, mahasiswa didorong untuk “mengejar publikasi” bukan karena semangat ilmiah, tetapi karena kewajiban administratif. Bahkan di semester awal pascasarjana, tugas-tugas sudah harus diterbitkan di jurnal dengan level tertentu, padahal belum ada kesiapan berpikir atau perangkat metodologis yang memadai. Di sisi lain, dosen pun terburu-buru mengejar angka publikasi demi sertifikasi dan kredit poin. Dalam suasana ini, AI hadir bukan untuk memperdalam ilmu, tetapi menjadi jalan pintas sistemik—dan kita semua membiarkannya karena ikut menikmati manfaat instannya. Maka penyalahgunaan AI tidak terjadi dalam ruang kosong; ia tumbuh subur di antara struktur yang memprioritaskan hasil daripada proses.
Maka solusinya bukan menuduh AI membawa kegelapan, tapi menyadari bahwa kita telah lama memadamkan obor akal sehat kita sendiri. Kampus hari ini bukan lagi ruang tafakur, tetapi pabrik administratif. Ruang kelas kehilangan rasa ingin tahu. Skripsi berubah jadi syarat, bukan proses. Artikel ilmiah dipakai untuk akreditasi, bukan pengetahuan. Dalam konteks seperti itu, AI hanya mempercepat apa yang selama ini kita diamkan. Maka pertanyaannya: masih adakah tempat untuk kejujuran intelektual di dunia yang begitu sibuk memburu format?
Saya sepakat bahwa kita berada dalam situasi genting. Tapi membangun rasa genting saja tidak cukup. Kita perlu arah. Dan arah itu, menurut saya, tidak lahir dari paranoia terhadap teknologi, tapi dari rekonstruksi kesadaran kita sebagai manusia. Apa peran kita dalam dunia yang makin otomatis? Apa yang membuat kita tetap manusia di tengah mesin yang makin canggih? Bukan otak kiri yang cepat menghitung, tetapi hati dan akal yang masih bisa menimbang.
Yang sedang kita pertaruhkan bukan hanya kualitas akademik, tetapi kejujuran eksistensial kita sebagai manusia. Ketika manusia menyerahkan sepenuhnya kerja berpikir kepada mesin, bukan hanya pengetahuan yang dikorbankan, tapi juga rasa tanggung jawabnya. AI bisa membantu menjelaskan data, tapi ia tidak tahu makna air mata. Ia bisa memproses pola, tapi tak bisa merasakan beban keputusan. Maka kalau kita ingin mempertahankan ruang insani dalam pendidikan, kita harus memastikan bahwa mesin tidak menggantikan pengalaman belajar sebagai proses pembentukan moral.
Oleh sebab itu, mari kita dorong kampus untuk tidak alergi pada AI, tetapi justru menjadikannya peluang belajar tentang tanggung jawab. Mari kita gunakan AI sebagai pintu masuk untuk diskusi tentang etika, integritas, dan martabat berpikir. Mari kita buat ruang-ruang di mana mahasiswa tidak hanya diajari menguasai alat, tapi juga diajak menyadari batas dan maknanya. Kita tidak sedang menolak masa depan, tapi sedang berusaha memastikan masa depan itu tetap manusiawi.
AI tidak membawa kegelapan. Kegelapan terjadi ketika kita berhenti menyalakan cahaya dari dalam diri sendiri. Jika kita jujur menatap situasi ini, seharusnya kita tidak sekadar takut, tapi tergerak. Bukan untuk mengubur teknologi, tetapi untuk menyalakan ulang akal sehat. Jika ada krisis hari ini, mungkin inilah kesempatan terbaik untuk meninjau kembali untuk apa sebenarnya kita belajar.
Di sinilah peran para pendidik menjadi amat penting. Kita tak bisa hanya menegur mahasiswa yang memakai AI secara sembrono, tanpa terlebih dahulu menyediakan ruang dialog yang membimbing mereka memahami alat ini secara etis. Kita tak bisa hanya marah pada generasi baru, tanpa menyadari bahwa kadang kita, generasi sebelumnya, juga terlalu sibuk memburu gelar dan jabatan, lalu lupa menjadi teladan berpikir. Alih-alih saling menyalahkan, mari kita mulai dengan saling mendengar—dan dari situ membangun kembali kepercayaan antara ilmu, akal sehat, dan rasa tanggung jawab.
Dan pada titik itu, mungkin kita akan menemukan bahwa harapan bukan datang dari teknologi atau statistik, melainkan dari manusia yang tetap mau bertanya—dan tetap mau jujur dalam menjawabnya. []