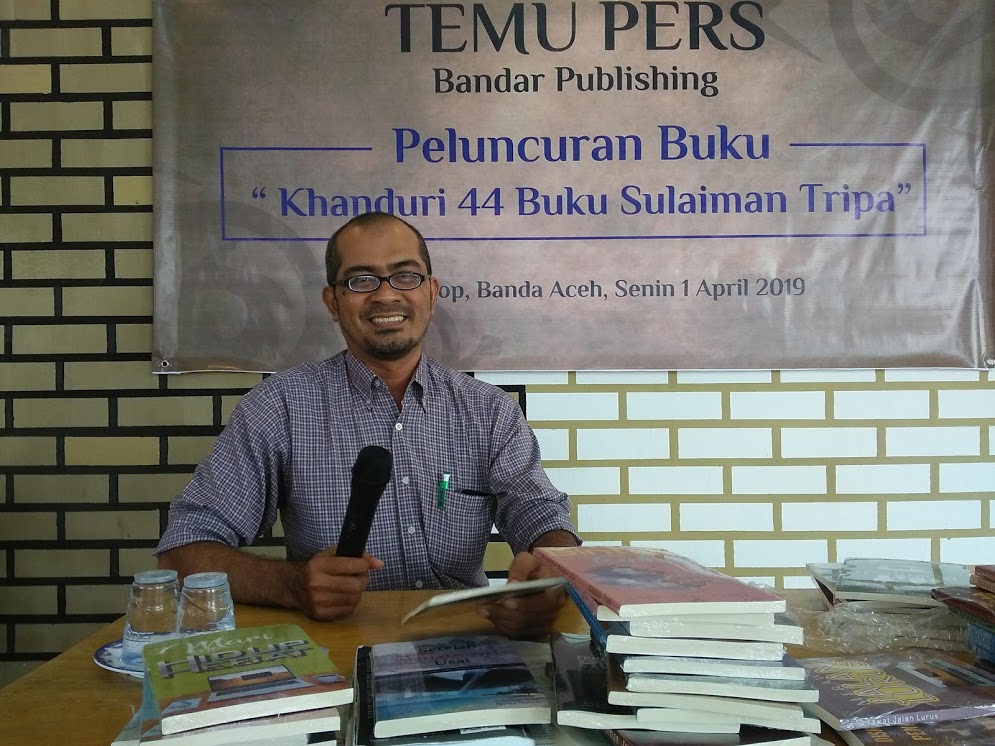Oleh: Dr. Sehat Ihsan Shadiqin.
Dosen Prodi Sosiologi Agama, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
Teman baik saya, seorang Sosiolog dari Universitas Malikussaleh Lhokseumawe bercerita tentang sebuah desa yang pernah menjadi tempat penelitiannya. Saya tidak sebutkan desa apa. Katanya, desa itu sudah lama menjadi pusat peredaran sabu. Pertama kali dibawa oleh seorang perantau asal desa itu dari Malaysia. Ia membangun jaringan yang sangat rapi dengan jaringan Malaysia dan jaringan lokal Aceh, sehingga bisnisnya berjalan lancar. Banyak anak muda desa yang direkrut menjadi agen kecil, tua-muda, laki-perempuan, bahkan anak-anak. Jadinya, desa itu sudah dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai “gampong sabe.”
Kata teman itu, predikat “gampong sabe” memang layak diterima desa itu. Kalau kita jalan di sana, pemandangan orang sakaw sangat lumrah. Transaksi dilakukan terang-terangan, tidak bersembunyi di belakang kandang ayam atau pakai sandi. Di pinggir jalan, di depan warung, di kedai kopi, biasa saja.
Akibatnya banyak orang di sana terjerumus pada tindakan kriminal. Mereka perlu mendapatkan uang cepat dan banyak untuk membeli sabu. Pencurian, perampokan, penodongan sering dilakukan. Bahkan banyak anak gadis menjajakan tubuhnya pada lelaki nakal dengan bayaran receh demi sabu. Ini benar-benar gila! Kita hampir tidak percaya itu ada di Aceh.
Apakah di sana ada camat? Ada! Apakah di sana ada koramil? Ada! Ada kapolsek? Lengkap. Apakah kampung itu ada keuchik? Tidak ada yang kurang, semua posisi jabatan ada orangnya. Tapi mereka semua angkat tangan. Di sana ada invisible hand yang bermain, kuat tapi tak terlihat.
Pada satu waktu, pindah seorang teungku ke desa itu. Ia melihat fenomena rusaknya strata sosial masyarakat karena sabu. Ia bertanya pada keuchik, petua, imum, mengapa ini dibiarkan terjadi. Semua angkat tangan dan berkata: hana mungken tapeuglah, teungku!
Sang teungku berfikir keras, bagaimana menyelesaikan masalah yang sudah mengakar ini. Ia membaca lagi kitab-kitab agama untuk menemukan referensi yang tepat. Ia bertanya lagi kepada gurunya, kepada orang yang paham. Beberapa bulan kemudian ia mengeluarkan fatwa radikal: “Mati karena memerangi agen narkoba adalah mati syahid!”
Banyak orang yang sudah putus asa dengan hidupnya karena pengaruh narkoba melihat fatwa ini sebagai peluang bagus mengakiri hidup. Kehidupannya selama ini sudah dapat dipastikan akan berakir tragis: di dunia maupun akirat. Dengan adanya peluang pahala “syahid” maka semua dapat berakir baik. Meskipun tidak bahagia di dunia, setidaknya bahagia di akirat. Kebahagiaan itu nampak sangat nyata, hanya satu tarikan nafas saja. Hari ini membunuh agen narkoba, ditembak, besok sudah masuk surga. Bukankah sebuah peluang bagus?
Agen narkoba lantas diburu. Siapa saja yang datang ke sana membawa narkoba dikejar ramai-ramai oleh orang kampung. Agen narkoba merasa orang akan membunuhnya. Di sisi lain orang-orang ingin dibunuh oleh agen narkoba agar mendapatkan pahala syahid. Tapi itu tidak terjadi sebab agen narkoba justru lari menghilang ketakutan. Ini terjadi lagi esok harinya, lusa, dan berbulan-bulan kemudian. Agen narkoba sama sekali tidak berani lagi masuk desa, orang desa juga tidak ada yang tewas karena ditembak oleh agen narkoba. Yang terjadi justru hal yang diinginkan teungku: kampung itu bebas narkoba! Sekarang kampung itu sudah jadi pusat produksi kepiting lunak terkenal di Aceh.
Saat birokrat dan aparat tidak mampu menyelesaikan masalah, teungku dengan satu fatwa menuntaskannya. Ia tidak digaji, tidak pakai seragam, tidak diangkat dengan SK, tidak ada senjata, tanda tangannya tidak menentukan apapun. Namun ucapannya pada satu malam setelah magrib mengubah wajah desa untuk selamanya.
Inilah yang kita sebut dengan otoritas keagamaan dalam masyarakat muslim di Aceh. Tidak ada yang lebih dipercaya oleh masyarakat selain teungku. Bukan hanya di desa itu, hampir seluruh daerah di Aceh meyakini pada satu kalimat: “kiban kheun teungku!”
Tidak selamanya baik, tentu saja. Dalam banyak kasus teungku yang diberkan otoritas oleh masyarakat justru menggunakannya untuk meraih kekuasaan politik dan menguasai sumber daya yang lebih banyak. Ada juga yang provokatif menggerakkan pengikut untuk melakukan kekerasan. Namun dalam kasus di atas, ia telah melakukan sebuah langkah yang radikal yang menyelesaikan masalah di desa itu.
Hal yang sama terjadi di sebuah provinsi. Saat covid-19 semakin mengganas, pemerintahnya nampak kelimpungan menangani masalah ini. Dari presiden, gubernur, camat, keuchik, semuanya tidak memiliki satu pandangan yang sama dalam menyelesaikan pandemi. Saboh hue u barat, saboh hue u timu. Apalagi ada masalah internal yang merusak program kampanye dan penanganan covid, termasuk korupsi dana yang berjumlah triliyunan.
Kondisi ini berdampak pada sikap masyarakat yang abai dengan prokes. Setiap hari kita menyaksikan nyaris tidak ada kesan takut dengan pandemi. Pasar ramai, warung kopi penuh, pusat belanja gaduh, perkantoran lengkap. Statistik korban yang semakin menanjak, kematian yang bertambah, stok obat yang menipis, ruang perawatan yang semakin terbatas, sama sekali tidak menjadi pelajaran. Lage na aju. Kahancuran di depan mata.
Masyarakat lebih suka mendengarkan “fatwa media sosial” yang tidak jelas milik siapa. Bukan hanya masyarakat awam, tapi kalangan terdidik. Bahkan nakes! Bit pungo. Saya melihat sendiri banyak akademisi hobi menyebarkan hoax pandemi ini. Aparat pemerintah menganggap sepele pandemi. Nakes meremehkan vaksin. Share sana share sini tanpa saringan. Prinsip-prinsip kecendiaan, memiliki integritas pada ilmu pengetahuan, menyampaikan pendapat berbasis data, melakukan klarifikasi atas fakta yang ada, membaca data dengan kristis, sama sekali diabaikan. Banyak diantara mereka berebut posisi pertama mempublikasi berita hoax di media sosial seolah sebuah pertandingan dengan hadiah milyaran.
Lalu muncullah seorang teungku yang menjadi pahlawan. Ia memberikan beberapa fatwa Radikal yang membuat pemerintah sungguh-sungguh menangani covid, penyebaran hoax keok, nakes semangat, dan masyarakat peduli dengan prokes. Akir tahun semua aspek kehidupan menjadi lebih baik. Alhamdulillah.
Saya tidak tahu apa bunyi fatwa yang dikeluarkan Teungku itu. Sebab itu belum terjadi.[]