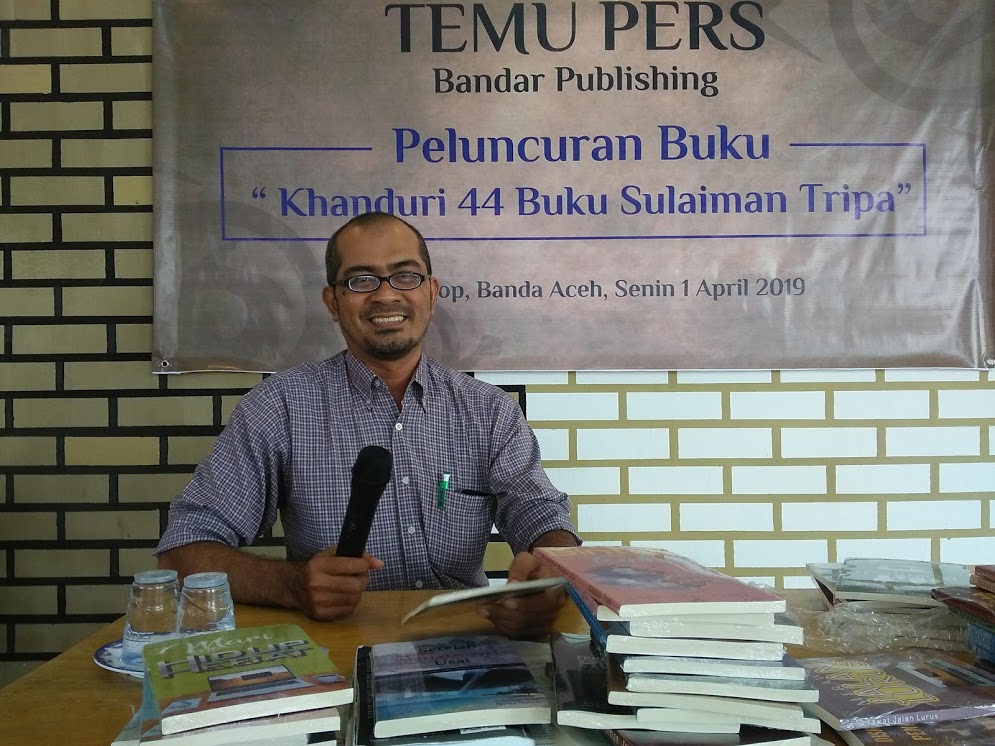Oleh: Ari J. Palawi
Pemerhati Budaya, tinggal di Banda Aceh
Nama almarhum Hasan Tiro tetap hidup dalam memori rakyat Aceh. Ia dikenang sebagai sosok yang mengangkat martabat bangsa Aceh di mata dunia. Terlepas dari jalan yang pernah ditempuh, beliau adalah simbol sejarah. Seandainya beliau masih hadir di tengah kita hari ini, pesannya mungkin sederhana: damai yang telah dicapai adalah titipan, dan kekayaan bumi Aceh, termasuk potensi gas raksasa di Laut Andaman, adalah amanah yang harus dikelola dengan adil demi rakyat.
Dua puluh tahun setelah damai Helsinki, Aceh telah bebas dari dentuman senjata, tetapi tantangan kesejahteraan belum sepenuhnya terjawab. Damai adalah fondasi, tetapi ia harus diisi.
Damai memang membawa ketenangan. Jalanan yang dulu mencekam kini kembali hidup. Namun seperti yang diingatkan Muhammad Jusuf Kalla dalam rapat Baleg DPR RI (11 September 2025), damai bukan garis lurus. Ia menuntut konsistensi, kebijaksanaan, dan komitmen penuh untuk menjaga amanah perjanjian Helsinki. Revisi hukum boleh dilakukan, tetapi hanya untuk memperkuat, bukan mengurangi, dan harus selalu selaras dengan MoU.
Namun data berbicara jujur. Menurut BPS Aceh, pada Maret 2025 terdapat 704,69 ribu jiwa penduduk miskin atau 12,33 persen dari total populasi. Angka ini memang turun sedikit dari 12,64 persen pada September 2024, tetapi masih menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera. Padahal sejak 2008 Aceh telah menerima puluhan triliun rupiah dana Otonomi Khusus—tahun 2025 saja nilainya Rp4,3 triliun. Dana besar itu belum otomatis menjawab problem rakyat. Persoalannya, seperti kata Jusuf Kalla, bukan pada jumlah, melainkan pada governance: tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Aceh juga punya luka sejarah dalam pengelolaan migas. Kilang Arun pernah menjadi salah satu produsen LNG terbesar dunia dengan cadangan 14–15 TCF gas alam. Gas itu diangkat dari bumi Aceh, devisa besar masuk ke pusat, tetapi masyarakat sekitar kilang tetap hidup dalam keterbatasan. Infrastruktur memang ada, tetapi kesejahteraan rakyat tidak sebanding. Arun meninggalkan jejak pahit: potensi besar yang tidak menjadi berkah.
Kini, sejarah memberi kesempatan kedua. Mubadala Energy bersama mitra internasional menemukan cadangan gas besar di Laut Andaman. Pada 2023, sumur Layaran-1 di South Andaman terbukti mengandung lebih dari 6 TCF gas-in-place. Disusul 2024, sumur Tangkulo-1 menemukan cadangan tambahan lebih dari 2 TCF gas-in-place. Kedua temuan ini menempatkan blok Andaman sebagai salah satu potensi gas terbesar di Asia Tenggara dalam dekade terakhir. SKK Migas menyebut bahwa pengembangan lapangan ini menargetkan produksi mulai sekitar akhir 2028.
Namun penting dicatat, “gas-in-place” bukanlah cadangan produksi langsung. Ia adalah potensi sumber daya di bawah tanah yang masih harus dikembangkan, dibuktikan, dan dihitung keekonomiannya. Di sinilah pekerjaan besar dimulai: memastikan cadangan raksasa itu benar-benar menjadi produksi, dan produksi menjadi kesejahteraan rakyat Aceh.
Aceh memiliki dasar hukum yang kuat dalam pembagian hasil migas melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Regulasi ini memberi ruang bagi Aceh mendapatkan porsi signifikan dari hasil pengelolaan migas, meski detailnya bergantung pada kontrak PSC yang berlaku. Namun pembagian angka hanyalah satu sisi. Nilai sejati terletak pada bagaimana gas itu dikonversi menjadi pembangunan nyata: lapangan kerja, industri hilir, dan daya hidup ekonomi rakyat.
Waktu emas masih ada. Produksi Andaman baru dimulai sekitar lima hingga enam tahun ke depan. Itu berarti Aceh punya ruang mempersiapkan sumber daya manusianya. Papua memberi teladan. Ketika BP membangun Tangguh LNG Train 3, anak-anak Papua dikirim belajar dua tahun, mendapat sertifikasi, lalu pulang mengoperasikan kilang sendiri. Aceh harus berani meniru. Dengan universitas, BUMD, dan lembaga pelatihan, anak-anak Aceh bisa disiapkan agar menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton di tanah sendiri.
Gas Andaman bukan semata persoalan teknis. Ia juga etis dan spiritual. Aceh adalah Serambi Makkah. Energi yang ditemukan di lautnya adalah titipan Allah. Karena itu ia hanya akan membawa berkah bila dikelola dengan keadilan, keberlanjutan, dan orientasi pada generasi mendatang.
Namun peluang besar selalu diiringi risiko. Literatur global penuh dengan contoh “kutukan sumber daya”: kekayaan melimpah justru memicu korupsi, ketidakadilan, bahkan konflik baru. Aceh tidak kebal dari bahaya ini. Sengketa wilayah laut, perebutan rente, atau kerusakan lingkungan bisa menjadi ancaman nyata. Tetapi risiko bisa diubah menjadi peluang. Dengan tata kelola yang transparan, partisipasi masyarakat, keterlibatan kontraktor lokal, serta pengawasan publik, gas Andaman bisa menjadi berkah.
Jalan Aceh ke depan harus jelas. Pertama, konsistensi dalam menjalankan MoU Helsinki dan UUPA agar kepercayaan tetap terjaga. Kedua, membenahi governance, menutup ruang kebocoran dan korupsi. Ketiga, menyiapkan SDM lokal agar benar-benar menjadi aktor utama industri migas. Keempat, menjadikan nilai budaya dan agama sebagai fondasi moral. Kelima, membangun hilirisasi agar gas tidak hanya diekspor mentah, tetapi diolah menjadi pupuk, petrokimia, dan energi yang memberi lapangan kerja.
Aceh bisa belajar dari Vietnam. Negara itu pernah berperang hampir dua dekade melawan Amerika. Tetapi setelah perang usai, mereka memilih berdamai dengan masa lalu, merangkul mantan musuh, dan kini menjadi salah satu ekonomi paling cepat berkembang di Asia. Mereka memilih menatap ke depan, bukan tenggelam dalam dendam. Aceh pun harus memilih hal yang sama.
Bayangkan, seandainya Hasan Tiro masih hadir bersama kita, beliau mungkin akan berkata: “Bangsa yang besar bukan hanya yang bebas dari senjata, tetapi yang mampu menyekolahkan anak-anaknya, memberi makan rakyatnya, dan menjaga martabatnya.” Gas Andaman adalah ujian sejarah. Ia bisa menjadi berkah bila dikelola dengan adil, atau menjadi luka baru bila disia-siakan.
Mari kita jaga amanah ini. Mari kita isi damai dengan karya. Mari kita jadikan migas bukan sekadar angka di neraca, tetapi jalan menuju Aceh yang maju, adil, dan bermartabat. []