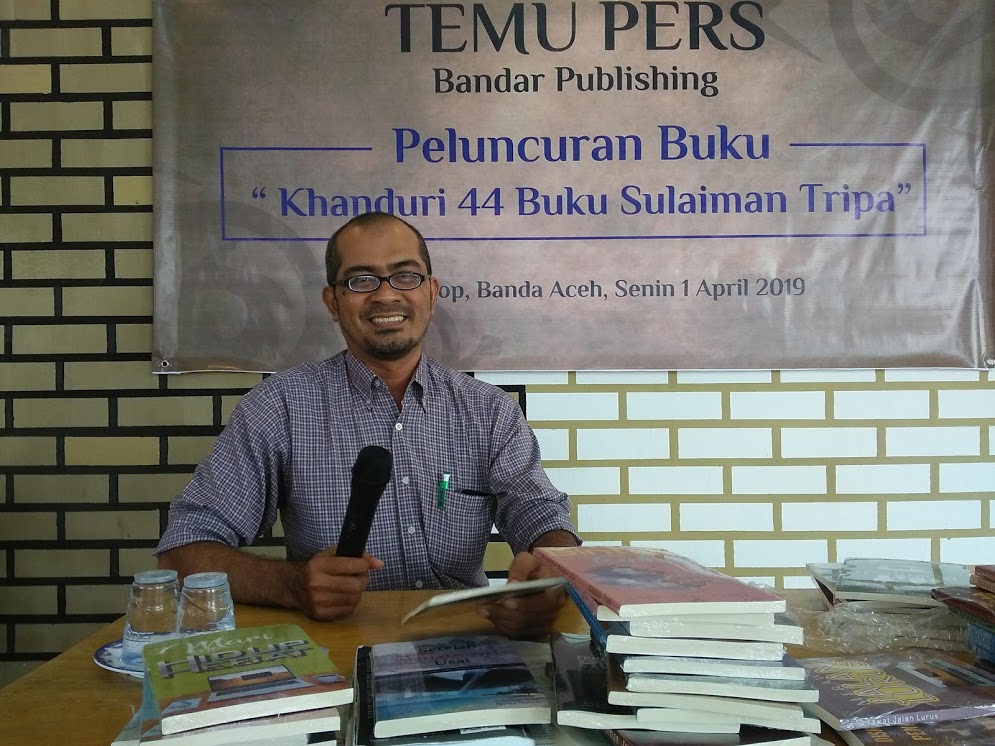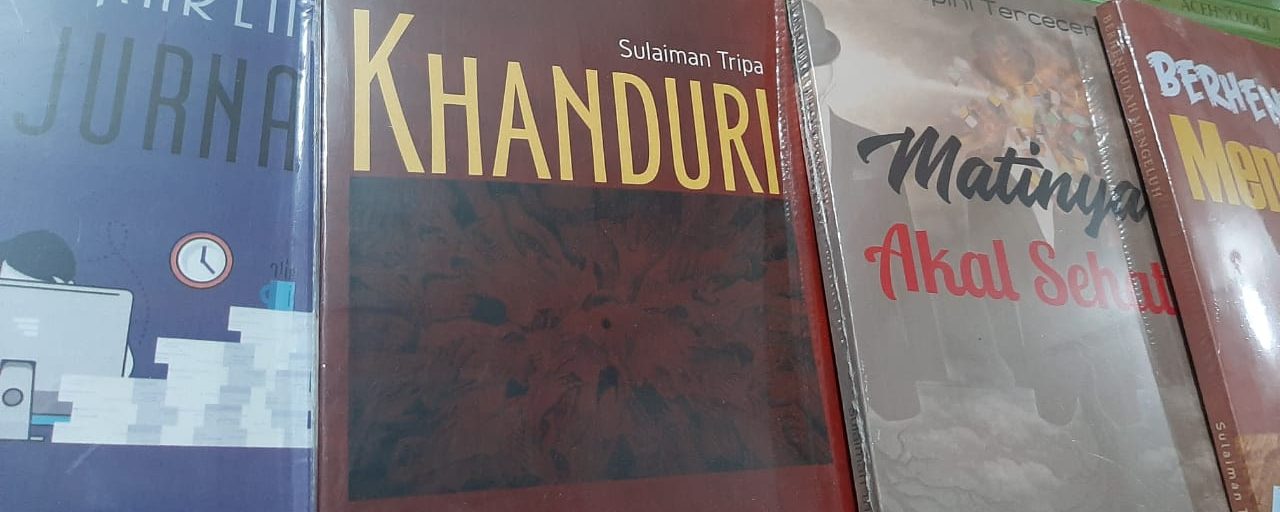Oleh: Ari Palawi
Ada yang sedang tumbuh diam-diam dari janji negara. Program indah yang digagas Presiden Prabowo untuk memanusiakan manusia, terutama anak-anak dan remaja desa, tampak mulai mengakar sebagai niat baik yang perlu kita kawal bersama. Jika benar diniatkan untuk memuliakan hidup, bukan sekadar proyek atau pengulangan dari skema pembangunan lama, maka inilah momen langka yang seharusnya menyentuh nadi keistimewaan Aceh yang sesungguhnya. Tapi pertanyaannya, apakah Aceh berani istimewa?
Yang dimaksud “berani istimewa” bukan hanya soal status administratif sebagai daerah otonomi khusus, tapi tentang keberanian moral dan intelektual untuk membedakan diri secara prinsipil dari arus besar penyeragaman sistemik nasional yang sering kali gagal menjawab kebutuhan lokal.
Momentum Sekolah Rakyat: Kesempatan untuk Menyimpang dengan Bijak
Program Sekolah Rakyat yang kini mulai dirancang dan disebarluaskan ke berbagai daerah, termasuk mungkin di Aceh, adalah titik awal penting. Ia bisa menjadi jalan baru untuk keluar dari kemelut pendidikan dasar-menengah yang selama ini diseragamkan dari Sabang sampai Merauke, namun terus melahirkan masalah-masalah baru: kekeringan makna, keterputusan dengan realitas lokal, dan pendidikan yang lebih menekankan hafalan daripada pengasahan akal dan empati.
Aceh, dengan segala kekhasan sejarah, budaya, dan spiritualitasnya, memiliki tanggung jawab dan peluang untuk menjadikan Sekolah Rakyat bukan sebagai kloning dari pusat, melainkan sebagai antitesis yang sehat dari model pendidikan nasional yang terlalu administratif dan teknokratis. Model yang sering gagal mendidik manusia utuh—yang berpikir, merasa, dan berbuat dalam relasi yang manusiawi dengan sesama dan alam.
Memurnikan Tujuan: Bukan Untuk Ormas, Tapi Untuk Anak Negeri
Yang perlu digarisbawahi sejak awal adalah bahwa sekolah ini bukan milik ormas mana pun. Ia milik rakyat. Milik anak-anak yang kerap dipinggirkan karena tinggal jauh dari kota, atau dianggap hanya sebagai angka statistik dari program-program penanggulangan kemiskinan. Anak-anak yang selama ini hidup dalam bayang-bayang trauma konflik, bencana, atau ketidakpastian masa depan.
Karena itu, pendekatan homogen, terpusat, dan seragam justru berbahaya. Ia menghilangkan konteks. Padahal pendidikan yang baik lahir dari kedekatan dengan bumi tempat ia tumbuh: dari bahasa ibu, dari kisah-kisah lokal, dari tradisi belajar yang tidak harus selalu bernama “kelas”, tapi bisa berbentuk meunasah, bale, atau tumpukan batu di bawah pohon yang rimbun, di mana anak-anak bisa belajar membaca alam, mengenal diri, dan menghargai hidup.
Kalau Aceh sungguh-sungguh mau berani istimewa, maka inilah saatnya untuk tidak tunduk pada model cetak biru dari pusat, apalagi jika model itu menanggalkan nilai-nilai keacehan yang penuh hikmah. Kita butuh lebih dari sekadar sekolah; kita butuh taman kehidupan, tempat anak tumbuh sebagai manusia, bukan sebagai mesin atau pemilih suara di masa depan.
Taman Pengetahuan, Bukan Ladang Politisasi
Sudah cukup lama pendidikan kita dirampas dari marwahnya. Sekolah menjadi tempat menggiring, bukan membimbing. Ia dibangun bukan untuk mencerdaskan, tapi untuk mendisiplinkan, membungkam, atau—pada titik paling kejamnya—mencetak anak-anak untuk kepentingan politik elektoral.
Kini, saat Sekolah Rakyat dirancang kembali, Aceh harus punya nyali untuk tidak menjadikannya perpanjangan tangan dari partai politik atau organisasi tertentu yang ingin mendominasi ruang-ruang sosial. Ini bukan panggung pengaruh, ini adalah ruang kehidupan. Dan kita tahu, sekali ruang kehidupan dijajah oleh kepentingan politik jangka pendek, maka hancurlah generasi yang akan datang.
Sekolah Rakyat di Aceh harus kembali kepada akar: menumbuhkan akal sehat yang merdeka, menjunjung tinggi keberadaban, serta memperkuat jati diri yang selama ini diwariskan para endatu. Di sinilah pendidikan bukan hanya soal kurikulum, tapi soal keberanian untuk menyusun hidup dengan bijak, berani, dan manusiawi.
Tanggung Jawab Kolektif: Anak Cucu Adalah Masa Kini yang Belum Bernama
Kita semua adalah penjaga masa depan. Dan masa depan itu bukan milik siapa-siapa kecuali anak cucu kita yang belum bisa memilih, belum bisa bersuara. Kalau kita diam saat arah pendidikan mereka diseret ke dalam proyek-proyek politik atau program pembangunan yang tak berpijak pada realitas mereka, maka kitalah yang sedang menyiapkan kubur bagi martabat mereka.
Aceh adalah tanah yang penuh kisah. Tapi kisah itu tak akan ada artinya kalau kita tak mampu menyambungnya dengan masa depan. Dan masa depan itu, kini, berada dalam ruang yang bernama Sekolah Rakyat—yang bisa menjadi pintu cahaya, atau jebakan baru yang lebih tersamar.
Maka pertanyaan itu kembali: Apakah Aceh berani istimewa?
Berani memilih jalan yang berbeda.
Berani melindungi anak-anaknya dari penyeragaman yang memiskinkan.
Berani meneguhkan pendidikan sebagai jalan kehidupan, bukan alat kekuasaan.
Jawabannya bukan ada di tangan pemerintah saja.
Jawabannya ada pada kita semua. []
Penulis adalah dosen seni pertunjukan di Universitas Syiah Kuala. Ia menulis, meneliti, dan mencipta karya yang menghubungkan penciptaan artistik, pengabdian budaya, dan kebijakan publik. Fokusnya banyak pada wilayah-wilayah non-sentral dan suara komunitas.