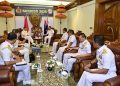Oleh: Galuh Tirta Juan Farera
Pernah nggak sih, lagi galau terus buka TikTok, terus nemu video dengan lagu indie yang kayaknya “gue banget”? Atau tiba-tiba pengen beli jaket oversized gara-gara liat outfit skena anak TikTok yang keren parah? Nah, ini bukan sekadar tren random. Di balik itu semua, Generasi Z lagi membangun budaya baru—dengan gaya, suara, dan caranya sendiri. Scroll terus, karena ini cerita tentang kamu (iya, kamu) dan dunia yang lagi kamu bentuk tiap hari.
Di era digital yang bergerak cepat, budaya populer mengalami perubahan yang nyaris tak terbendung. Salah satu pergeseran paling mencolok tampak pada bagaimana Generasi Z membentuk identitas dan mengekspresikan diri melalui media sosial, terutama TikTok. Platform ini bukan sekadar tempat untuk hiburan ringan atau tren sesaat. Ia telah menjelma menjadi ruang budaya baru—tempat tren fashion, musik, dan nilai sosial tidak hanya dibagikan, tetapi juga dikonstruksi ulang dengan cara yang segar dan sering kali mengejutkan.
Dengan konten yang mudah dibuat dan algoritma yang gesit menyebarkan video ke berbagai penjuru, TikTok memberi peluang luas bagi siapa pun untuk tampil, bersuara, dan menciptakan makna. Di dalamnya, anak muda bukan hanya penonton pasif; mereka adalah aktor utama yang aktif mengolah, merespons, dan membentuk budaya populer hari ini. Di kamar-kamar mereka, saat suasana hati berubah-ubah—sedih, riang, murung, atau galau—mereka memutar lagu-lagu indie, mengenakan outfit skena, dan merekam tarian sebagai bentuk pelampiasan emosi dan pencarian makna personal. Lagu-lagu indie, meski sederhana secara teknis, kerap membawa emosi yang lebih kuat dan autentik, lengkap dengan estetika vintage, minimalis, atau artsy yang sangat dekat dengan selera visual mereka.
TikTok telah menjadi panggung budaya tempat identitas dinegosiasikan secara terbuka. Melalui tarian, lip-sync, gaya berpakaian, maupun cerita-cerita pendek yang dibagikan, generasi ini membentuk narasi mereka sendiri, lepas dari dominasi media arus utama. Berkat algoritma yang demokratis—di mana siapa pun bisa viral tanpa perlu modal besar—mereka menciptakan ekosistem budaya yang sangat cair, cepat, dan sering kali tidak terduga. Di titik ini, kita menyaksikan bagaimana ekspresi diri bukan lagi produk institusi besar, melainkan hasil dari interaksi harian yang spontan dan kreatif.
Salah satu ekspresi paling menonjol yang hidup dalam ruang ini adalah streetwear—gaya berpakaian yang awalnya lekat dengan komunitas skateboard dan hip-hop, kini menjadi simbol identitas urban generasi muda. Lewat TikTok, fashion tak lagi didefinisikan oleh majalah atau merek mewah, tetapi oleh para kreator lokal yang mencampurkan gaya global dengan karakter personal. Hoodie oversized, celana kargo, sneakers nyentrik, atau bucket hat bukan sekadar atribut estetika, melainkan cara mereka berkata, “Ini aku.” Bahkan di Indonesia, artis seperti Jefri Nichol, Vincent Rompies, hingga Iqbaal Ramadhan kerap dijadikan panutan fashion oleh pengikut budaya skena. Brand seperti Supreme dan Off-White berdampingan dengan merek lokal seperti Erigo, Screamous, dan Maternal dalam membentuk selera visual baru. Akun-akun seperti @sastra_silalahii dengan jargon “Gak kek gitu bro!!” atau @bachrul_alam yang menyindir gaya streetwear ‘nanggung’, memperlihatkan bagaimana humor dan kritik ringan menjadi bagian dari proses seleksi kultural internal komunitas ini.
Tak kalah penting dari fashion, musik indie juga menemukan jalur hidupnya yang unik di TikTok. Generasi Z menunjukkan ketertarikan besar terhadap karya-karya yang lebih jujur secara emosional—musik yang tidak selalu dipoles sempurna, tapi terasa nyata. Fiersa Besari dengan April-nya, Fourtwnty lewat lagu Mangu, dan Banda Neira dengan Sampai Jadi Debu, adalah contoh musisi yang karyanya viral karena digunakan sebagai latar dalam video-video personal yang menggambarkan kesedihan, rindu, atau pencarian makna. TikTok memungkinkan karya mereka menjangkau jutaan orang tanpa perlu promosi masif, cukup dengan satu video yang relatable.
Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran selera: dari sesuatu yang mengilap dan massal menjadi sesuatu yang personal dan autentik. Di ruang ini, musik bukan lagi sekadar hiburan, tetapi kanal emosi dan koneksi antarindividu. TikTok menjadi perantara yang mempertemukan pengalaman personal dengan ruang publik, memperkuat rasa keterhubungan yang sebelumnya hanya hadir dalam lingkaran kecil.
Identitas yang dibentuk Generasi Z di media sosial bersifat cair, adaptif, dan lintas batas. Mereka bebas memadukan elemen-elemen dari berbagai budaya: dari musik indie Korea hingga gaya anak jalanan Jakarta, dari gerakan sosial global hingga humor khas daerah. Dalam konten yang viral, kita bisa melihat bagaimana budaya lokal dan global tidak saling meniadakan, melainkan saling menegaskan. Lihat saja akun @aswindaaa yang menggabungkan tarian Jaipong dan Saman dengan musik K-pop atau EDM, menciptakan perpaduan yang unik sekaligus membanggakan. Di tangan kreator seperti ini, budaya tradisional bukan hanya lestari, tetapi tampil keren dan relevan di mata anak muda.
Pada saat yang sama, TikTok juga membuka ruang untuk diskusi sosial yang dulu sulit mendapat tempat. Tren seperti #DirumahAjaChallenge di awal pandemi COVID-19, misalnya, melahirkan konten reflektif tentang ketimpangan sosial, akses pendidikan, dan kondisi hidup sehari-hari. Video dari akun @sosialterkini yang membandingkan “belajar online di rumah mewah vs rumah sempit” menjadi contoh bagaimana kritik sosial bisa dikemas secara ringan namun tetap mengena. Demikian pula akun @nengsari.sunda yang mengajarkan filosofi di balik tari ronggeng atau kebaya tradisional, berhasil menarik perhatian generasi muda terhadap kekayaan budaya warisan yang sebelumnya mereka abaikan.
Namun, tak semua berjalan mulus. Ketika budaya lokal dipertemukan dengan tren global, sering muncul pertanyaan tentang batas antara appreciation dan appropriation budaya. Konten yang mencampuradukkan simbol-simbol tradisional tanpa pemahaman kontekstual bisa menuai kritik. Tapi di sinilah pentingnya literasi budaya dan etika digital—sebuah kesadaran baru yang justru tumbuh melalui perdebatan di ruang digital itu sendiri.
TikTok, streetwear, dan musik indie adalah lebih dari sekadar produk tren atau hiburan sesaat. Ketiganya merepresentasikan lanskap budaya yang sedang terus-menerus dibentuk dan dipertanyakan oleh generasi muda. Lewat layar kecil di tangan mereka, identitas tidak lagi diwariskan secara pasif, tetapi dikurasi dan dibagikan secara aktif. Dalam dunia yang berubah dengan cepat, Generasi Z menunjukkan bahwa menjadi bagian dari budaya bukan berarti mengikuti arus, tetapi menciptakan arus baru—yang lebih inklusif, jujur, dan berani.
Mungkin inilah pelajaran terpenting dari generasi hari ini: bahwa budaya tidak hidup karena diwariskan, tapi karena terus dihidupi. Dengan kreativitas, keberanian, dan kesadaran, mereka membuktikan bahwa setiap ekspresi, sekecil apa pun, punya daya untuk mengubah cara kita memandang dunia. []
Tentang Penulis
Galuh Tirta Juan Farera adalah mahasiswa Pendidikan Seni di Universitas Syiah Kuala yang dikenal penuh semangat dan ceria. Ia memiliki ketertarikan kuat pada dunia seni dan budaya, khususnya musik dan tarik suara, yang menjadi ruang ekspresi sekaligus refleksi emosional baginya. Terbuka pada pengalaman dan eksplorasi kreatif, Galuh meyakini bahwa seni bukan sekadar hiburan, melainkan medium untuk memahami dunia dan membangun jembatan antarbudaya.
Editor:
Ari J. Palawi