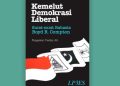Oleh: Fuad Mardhatillah UY.Tiba
Dosen UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
I. Iftitah: Islam, Konstelasi Ajaran Sosial bagi Budaya Damai dan Anti-Kekerasan
Sungguh, dalam konteks maqashid syar’iyyah, bahwa perumusan, pelembagaan, dan penerapan actual-positivistic hukum-hukum material dan formal Syariat Islam, bukanlah sesuatu untuk memenuhi tujuan atau tuntutan dari kepentingan politik dan kekuasan tertentu, dimana isus-isu syariat Islam tampak telah menjadi komoditas politik banyak orang di Aceh, di semua kalangan dan level.
Akan tetapi usaha positivisme hukum Islam itu haruslah senantiasa dipahami sebagai upaya menjalankan tuntutan sunnah kesejarahan manusia bersama ajaran Islam yang harus terus mampu bergerak dinamis, dialektis, transformative, produktif, solutif dan mencerahkan, bagi membangun dan menghasilkan sebuah exemplar peradaban dunia, yang mulia dan agung.[1]
Dalam konteks itu, hukum merupakan suatu perangkat lunak (soft-ware) sekaligus menjadi soft-power yang memiliki kekuatan memaksa (coercive power) untuk menyadarkan semua subjek hukum bagi terbentuknya suatu pola pikir, perilaku dan tatanan sosial yang benar, jujur, adil dan terbuka. Agar kemudian mampu menggerakkan prilaku warga secara massif, baik sebagai objek maupun subjek hukumnya, sesuai dengan tuntutan sunnatullah alam, bersifat fitriah dan sesuai kodrat penciptaan manusia.[1]
Sehingga secara terencana, sistematis dan terarah, positivisme hukum tersebut diyakini dapat menumbuhkan mendorong dan merekayasa perubahan pola pikir, jenis mentalitas dan warna pandangan dunia (worldview) tentang segala sesuatu, dalam semesta mikro dan makro kosmos. Di saat yang nyaris sama, positivism hukum Islam itu sekaligus mampu membentuk realitas kehidupan sosial-politik-ekonomi-budaya dan agama warga muslim Aceh, bersama perubahan hukum yang telah diusahakan bersama, melalui qanun-qanun Aceh, menjadi pekerjaan bersama untuk membentuk tatanan sosial masyarakat Aceh yang mendamaikan.
Maka semestinya, Qanun-Qanun Aceh itulah yang seharusnya merupakan jawaban kontekstual syar’iyyah, bersama kandungan nilai dan sifat adil, luhur dan mulia yang ada dalam ajaran Islam, dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia secara umum dan khususnya masyarakat lokal Aceh hari ini, ke depan dan generasi-generasi Aceh penerusnya.
Sementara rumusan hukumnya, dapat pula disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang perlu diadakan dalam upaya menata tatanan kehidupan masyarakat, untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan bersama secara adil. Disini dialektika antara persoalan-persoalan yang setiap saat bisa bermunculan secara dinamis dan kontinyu, niscaya membutuhkan jawaban-jawaban hukum yang cerdas dan realistis, yang secara legal formal dan sosiologis berfungsi membina tatanan kehidupan masyarakat penggunanya menjadi terus semakin lebih baik secara berkelanjutan.[2]
Dari konsep dan konstruksi pemahaman hukum yang bercita-cita untuk mendidik umat bagi terbentuknya realitas sosial masyarakat muslim yang berperadaban mulia dan luhur tersebut, para manusia pengamalnya akan terbina semangat, mentalitas dan pola pikir untuk senantiasa siap berjuang mewujudkan suatu peri kehidupan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kedamaian, saling menghargai dan tolong menolong. Namun, tuntutan ini hanya mungkin diwujudkan jika Islam benar-benar dipahami dan dihayati oleh para pemeluknya sebagai ajaran ketuhanan yang bersifat rasional-transendental. Dimana kearifan, keikhlasan, keindahan dan kebermanfaatan sosial diri para pemeluknya menjadi élan vital dari dimensi pesan utama religiusitasnya. Sehingga hidupnya rela diabdikan untuk menebarkan rahmat bagi semua, baik bagi sesama manusia, maupun bagi binatang, tumbuhan dan alam lingkungan habitatnya.
Tegasnya, jika keberislaman yang dianut, dipahami dan diamalkan seorang muslim berlangsung secara benar, sungguh dapat dipastikan, bahwa dirinya tidak akan pernah mengarah menjadi pribadi yang egosentris, yang secara ekstrim hanya cendrung mementingkan diri sendiri belaka. Tetapi seorang muslim yang benar, dapat dilihat pada kehendak dan pilihan bebasnya untuk membangun harmoni dan keseimbangan dinamis yang terpolarisasi antara kutub-kutub kepentingan individual dan kepentingan sosial.[3]
Maka, kehadiran seorang muslim di muka bumi ini, harus dipahami sebagai the divine presence[4] yang menghadirkan keseimbangan, dari takdir Allah dalam penciptaan manusia, dengan segala konstanta aksiomatik, maxim, dan code of conduct-nya. Dalam konteks the divine presence ini, adalah suatu kewajiban yang melekat pada eksistensi manusia, setelah ia dianugerahkan Allah berbagai potensi, akal budi, qalbu dan nafsu, untuk berusaha dan berjuang membangun kapasitas diri secara maksimal menuju insan kamil, dalam suatu tatanan keseimbangan antara nalar (pemikiran), rasa (penghayatan) dan asa (pencapaian). Kapasitas bermanusia ini diperlukan untuk digunakan seoptimal mungkin, sehingga dirinya menjadi meaningful dengan mampu memberi faedah dan manfaat secara optimal dan berkelanjutan bagi sebanyak mungkin orang-orang lain.[5]
Sebenarnya, semua tuntutan fitrah kemanusiaan itu, telah terkandung dalam lima asas prinsipil arkaanul-Islam.[6] Secara konfiguratif, masing-masing dari lima asas itu membentuk suatu kosmologi pemahaman, penyadaran, pengamalan dan penghayatan terhadap ajaran Islam, yang secara dialektis, dinamis dan transformatif memproduksi prilaku sosial kebudayaan yang hanif dan bersifat merahmati. Ini berlangsung secara rela, simultan dan integral dalam kehidupan beragama umat Islam, dalam seluruh aspeknya. Dan konflik-konflik yang terjadi dalam dialektika dan dinamika sosialnya, senantiasa secara sadar harus diselesaikan lewat dialog, perdebatan kritis-argumentatif-rasional dan bermusyawarah untuk mendapatkan konsensus demi kemaslahatan bersama, dengan metode yang senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip ahsan.[7] Semua itu diorientasikan untuk mendapatkan jawaban atas segala problema, krisis dan konflik sosial yang bersifat mendamaikan semua pihak yang ada dalam masyarakat Islam dan juga dalam masyarakat semajemuk apapun.
Asas-asas tersebut secara konfiguratif tersusun berlapis-lapis, membungkus kokoh eksistensi kepribadian seorang muslim. Yakni pribadi yang selalu punya niat dan tekad yang tidak ingin merugikan orang lain dalam bentuk apapun, kapanpun dan walau dengan alasan apapun. Bahkan pengembangan eksistensi diri hingga ke tingkat yang paling prima, atau dalam istilah Islam: “Insan Kamil,” justru sepenuhnya dimaksudkan untuk semakin membuat diri menjadi seorang muslim yang bermakna dan berharga bagi orang-orang dan makhluk lain, dalam konteks semesta tatanan hidup bersama, antara manusia dengan seluruh makhluk hidup, yang adil, seimbang dan moderat.[8]
Dalam konteks ini, semua bentuk perwujudan amal dan perbuatan nyatanya, umat Islam niscaya akan bergerak ke arah berlangsungnya transformasi kultural, dari suatu kultur yang rendah derajat ilmiahnya (jahil, primitive dan picik) menuju kultur yang semakin tinggi derajat ilmiahnya (sophisticated). Ketika umat Islam telah mampu menempatkan akal-budi secara optimal untuk memikirkan nilai-nilai kebenaran dan teori-teori yang secara metodologis dapat dioperasionalisasikan secara nyata, maka ini akan menghasilkan secara konstruktif bagi perwujudan tatanan kehidupan umat Islam dan non-Islam, yang berpegang teguh pada nilai-nilai prinsipil Islam, akan memberikan kehidupan bagi semua species makhluk hidup yang ada. Dari sini akan pula merekonstruksi sendi-sendi rasional suatu peradaban, yang mengemban tugas membina kehidupan sosial yang adil dan damai.
Akan tetapi, substansi keadilan dan kedamaian ini hanya mungkin dijalankan jika ada proses-proses rasionalisasi dan transendentalisasi ajaran yang dapat mencerahkan pikiran dan perasaan,[9] yang kemudian melahirkan kesadaran hidup, untuk secara ilmiah menolak segala bentuk pemaksaan dan aksi-aksi kekerasan. Karena segala aktualisasi pengamalan Islamnya harus berlangsung secara sadar, rela, nirkekerasan dan berhikmah, namun harus dicari dalam penghayatannya atas suatu peristiwa.
Selanjutnya, asas-asas anti-pemaksaan dan anti-kekerasan ini tidak terbentuk begitu saja deengan sendirinya, sehingga menjadi kepribadian kultural seorang muslim, jika modus dan derajat keislaman yang dimilikinya hanya berasal dari suatu proses pewarisan (given) atau nyaris tidak dilatari oleh proses-proses panjang pencaharian substansi kebenaran beserta penghayatannya terhadap ajaran Islam. Atau bisa pula berasal dari sekedar praktek keber-agama-an yang hanya bersifat meniru dan mengikuti, simbolis-formal, ritual-seremonial dan menjadi sebuah rutinitas peribadatan belaka, tanpa pendalaman dan kering akan penghayatan makna substansial ajarannya.
Jadi, asas kemusliman yang membentuk sikap dan kepribadian sosial yang anti-kekerasan ini, adalah hasil bentukan (constructed) setelah melalui proses belajar yang panjang dan lama untuk “menjadi” (becoming), dengan memanfaatkan soft power yang ada pada manusia, berupa akal, qalbu dan panca indera. Maka untuk “menjadi,” proses pencapaiannya berlangsung secara gradual, setelah melalui proses-proses pembelajaran, pencarian, penemuan, pemahaman, pembuktian dan pengujian, serta meyakininya sebagai substansi makna-makna kebenaran ajaran dalam aktualisasi sosial sebagai refleksi dari pengamalan Syariat Islam. Untuk kemudian direalisasikan ke dalam system dan praktek dalam kehidupan sosial sehari-hari dari pribadi-pribadi muslimin-muslimat.
Asas-asas ini, secara esensial dan substansial, mensyaratkan bahwa penerapan syari’at Islam dalam konteks individual adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, rela, jujur dan ikhlas. Dan kapasitas seperti ini, hanya akan lebih dapat terbentuk lewat pendekatan pendidikan yang mencerahkan, bukan lewat penerapan hukum positif syariat Islam.
Sehingga nilai-nilai dan ajaran ritual keagamaan itu dapat tumbuh berkembang dan diamalkan para muslim-muslimah menjadi world-view keislaman yang jauh dari dimensi paksa-memaksa dan aneka bentuk tindak kekerasan lainnya. Proses yang tidak memaksa dan berorientasi pada kesadaran akal-budi manusia ini,[10] seharusnya juga telah mulai berlangsung dalam seluruh rangkaian proses pembentukan kepribadian seorang muslim, sejak dini hingga dewasa dan tanpa berhenti, melalui upaya-upaya pendidikan formal, informal dan nonformal.[11]
II. Rukun Islam: Konfigurasi Peradaban Islam
Berikut ini marilah kita elaborasi satu per satu susunan asas-asas yang menjadi pilar-pilar utama bangunan peradaban Islam, yang secara kumulatif dan mencerahkan, adalah blue-print prilaku personal muslim dan merupakan grand scenario desain rancang-bangun wajah peradaban Islam.
Lingkaran konfigurasi pertama yang merupakan asas cognitive menyangkut pemahaman dan kesadaran seorang muslim, serta dorongan kinetis pengamalan prinsip-prinsip tauhid yang menyatukan antara yang dicipta (makhluq) dengan yang mencipta (khaliq), dalam suatu semesta pemahaman (kosmologi) tunggal, universal, bebas dan terbatas. Sementara antara sesama ciptaan, baik secara individual maupun social, semuanya dipahami berada dalam semesta ketetapan ilahi, untuk satu sama lain haruslah melangsungkan kehidupan dalam relasi mutual simbiosis, resiprokalistik (timbal-balik) dan interaktif-produktif dan solutif, yang merahmati pikiran untuk hidup dalam jalinan kasih saying, individual dan social.[12]
Kesadaran tauhid semacam itu diperlukan untuk menjadikan seorang muslim benar-benar mampu bersikap merdeka, mandiri, otonom dan terbebaskan dari segala bentuk prilaku menyembah dirinya (deifikasi) terhadap entitas apapun selain Allah (la ma’buuda illallaah).[13] Sikap dan karakter kebebasan ini terbentuk setelah qalbu dan intelektualitas rasionalnya mampu memverifikasi, menfalsifikasi, mengaffirmasi dan akhirnya bersaksi mengakui kebenaran diktum laa ilaaha illallaah.[14]
Sedangkan diktum asyhaadu anna muhammadar rasulullah merupakan persaksian kebenaran, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang figure utusan Allah yang menjadi rujukan sempurna, par excellent, untuk keteladanan terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah umat manusia di dunia. Dan penyaksinya sendiri selalu rela menyiapkan diri untuk niscaya ikhlas berjuang mensejarahkan kembali segala keteladanan Nabi itu ke dalam realitas sejarah kebudayaan dan peri-kehidupan sehari-harinya, yang visi-misi utamanya adalah membangun kedamaian hidup bagi semua. Bukan sekedar membaca salawat dalam berbagai kesempatan yang hanya bersifat ritualis dan seremonial belaka, yang justru menjadi ajang silaturrahmi dengan masyarakat Aceh.
Tetapi, semua perwujudan dari suri keteladanan Nabi tersebut dilakukan secara kritis, cerdas, rasional, ikhlas, sabar, istiqamah, kreatif, mandiri dan kontinyu, dengan motivasi utama adalah untuk mencari ridha Allah, dengan menebar dan menabur rahmat dan manfaat bagi semua. Di samping terus menerus bersedia melakukan “muhasabah” (menghitung diri) dan “tazkiyatun-nafs” (pensucian diri), serta selalu merindukan ilmu, nasehat dan kritik, yang diharapkan berguna untuk memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan yang niscaya melekat pada eksistensi setiap manusia, tanpa kecuali.
Lingkaran konfigurasi ke-dua adalah karakter yang terbentuk dari rangkaian proses ritualitas penegakan ibadah shalat yang mencerahkan.[15] Proses ini dihayati sebagai proses dialog yang mendialektikakan semesta persoalan kehidupan manusia dan alam kepada Allah, dan selalu merasa dekat dan butuh akan petunjuk (hidayah) dan perlindungan (inayah) Nya.
Ini merupakan wujud pengakuan kehambaan yang sadar benar akan serba kelemahan dan keterbatasan dirinya. Karakter utama yang akan dibentuk dari proses dialog dan penghambaan diri semacam ini adalah karakter dan sikap rendah hati, terbuka, bersih, disiplin, bertanggung-jawab, dinamis, penghargaan atas sesama yang saling berbeda dan kesediaan untuk terus belajar. Sehingga menghilangkan segala bentuk ketakabburan, kemubaziran dan kesombongan, dimana semua sifat ini menjadi sumber bagi merebaknya berbagai tindak kekerasan. Baik itu kesombongan vertikal, berupa sikap-sikap yang menganggap mengambil alih hak-hak dan peran Tuhan, atau bahkan kelakuan yang mencitrakan dirinya seolah Tuhan.
Seperti misalnya, keinginan untuk menghakimi keberagamaan orang lain secara monolitik, atau tindakan membunuh kehidupan makhluk hidup, atau cara-cara yang penuh pemaksaan, agar seseorang mutlak harus menerima apa saja keinginan, pemikiran dan perbuatannya. Maupun kesombongan horizontal antar sesama yang berkasta-kasta, dimana dirinya merasa lebih tinggi, sehingga selalu merasa butuh pujian, di samping segera menjadi murka jika dikritik, apalagi dicaci, dan sekaligus memandang orang-orang lain rendah, hina dan tercela.[16]
Adapun lingkaran konfigurasi asas ke-tiga adalah perintah melaksanakan ibadah puasa di Bulan Ramadhan. Dari ibadah puasa ini, jika dilaksanakan secara rela dan benar serta dihayati implikasi intrinsic dari substansi perpuasaannya, maka akan terbentuk kepribadian yang empatik dan dipenuhi sifat kasih sayang dan rasa keadilan terhadap sesama makhluk Tuhan, yang merupakan perwujudan dari sifat-sifat ar-Rahman dan ar-Rahimnya Allah. Sasaran utama ibadah perpuasaan ini adalah membentuk kepribadian muslim yang ta’at azas, khidmat dan komit terhadap sunnatullah dan penegakan hukum, serta bersedia meminimalisir segala bentuk cinta-diri sendiri (egosentrisme) yang berlebihan. Karena dari egosentrisme inilah akan niscaya berdampak merugikan orang-orang lain dan terbitnya berbagai tindak pemaksaan dan kekerasan.[17]
Selanjutnya, lingkaran konfigurasi asas ke-empat yaitu mengeluarkan zakat. Ibadah ini akan membentuk kepribadian yang penuh persaudaraan, yang tumbuh akibat dari adanya pemahaman substansial tentang ajaran zakat, sebagai sebuah keharusan konsekuensial logis sebagai makhluk sosial.[18] Yakni, bahwa membayar zakat adalah wujud pengakuan jujur dirinya yang merasa tidak mungkin bisa memenuhi sendiri segala kebutuhan dalam hidup dan kehidupannya, tanpa bantuan atau keterlibatan orang-orang lain dalam proses pengadaan, penyiapan dan pemenuhan kebutuhannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Jadi, penghayatan terhadap pelaksanaan ajaran zakat, dipastikan mampu melahirkan kesadaran untuk menjalin kerjasama sosial yang rela memisahkan hak-hak orang lain dalam harta-hartanya secara adil. Karena pemerolehannya diakui secara sadar hanya akibat adanya kerja sama dan bantuan orang-orang lain, langsung atau tidak, dalam setiap perjuangan memenuhi segala bentuk kebutuhan alamiah hidupnya.[2]
Sementara hidup itu sendiri sepenuhnya dipahami sebagai sebuah anugerah yang harus dipelihara dan disucikan kualitasnya menuju kepada suatu standar hidup insani yang wajar, sehat dan bermartabat, sesuai dengan patronasi nilai-nilai fitrah-kodrati, yang egaliter dan menghilangkan kesenjangan sosial dan segala prilaku sehari-hari yang tidak-manusiawi.[19] Kesadaran yang terbentuk pada lapis konfigurasi ini, juga menjauhkan para muslimun dari orientasi, pola-pikir, mentalitas dan prilaku kekerasan.
Sementara lingkaran konfigurasi ke-lima adalah melaksanakan ibadah haji. Dari penghayatan ibadah haji ini, dipastikan akan terbentuk kepribadian yang membangun cita-cita kehidupan di bawah cahaya terang dan semangat universalitas dan kesederajatan (egalitarianisme) manusia. Artinya ibadah haji, juga membentuk cita-cita dan visi hidup bersama yang berlandaskan pada kebenaran universal qur’ani vis a vis egosentrisme diri, anti-diskriminasi serta pengakuan dan kesadaran tentang kesederajatan ummat manusia sedunia. Berbagai perbedaan kemakhlukan yang terdapat disana-sini, dipahami sebagai suatu yang wajar dan alamiah belaka, baik itu perbedaan yang bersifat fisis atau nonfisis, maupun perbedaan yang merupakan hasil konstruksi sosial, yang terbentuk setelah seseorang mengalami pemolaan-pemolaan intelektual, emosional dan spiritual melalui proses-proses pendidikan/ pengajaran dan sosial-budayanya di sekolah dan di lingkungan sosialnya.
Tegasnya, bahwa kepribadian seorang muslim setelah melalui proses mencari dan beraktualisasi diri dalam kehidupan sosial, dimana nilai-nilai luhur keagamaan dipahami dan dijalankan secara benar, rasional dan meta-rasional, niscaya pasti akan terbebas dari segala sikap pemberhalaan (terhadap produk-produk pemikiran manusia, seperti peraturan, uang, kekuasaan, sistem atau ideologi misalnya). Di samping juga memiliki karakter-karakter kepribadian yang rendah hati, dinamis, kreatif, produktif, penuh makna, manfaat dan kasih sayang, persaudaraan, pemaaf, saling menghargai, egaliter dan adil serta anti-kekerasan.
Itulah yang menjadi modal dan esensi utama bagi latar-belakang aktualisasi seorang muslim yang benar-benar memahami pesan terdalam ajaran Islam. Tujuan kontekstual ukhrawinya adalah untuk membangun kehidupan bersama yang damai di tengah pluralitas masyarakat manusia sedunia, dimana umat Islam semestinya dapat secara mentalitas dan mayoritas, berlomba untuk menjadi “pribadi-pribadi yang bertangan di atas.” Setelah menyelesaikan dengan baik seluruh pekerjaan di dunia dalam konteks ukhrawi semacam itu, barulah kemudian ia berhak dan pantas akan syurga Allah.
III. Perubahan Paradigma: Taubat Ilmiah
Diakui atau tidak, bahwa realitas sosial ummat Islam bersama ajaran syariat positivistiknya hari ini, khususnya di Aceh, ternyata masih belum menjawab secara mendasar berbagai problema social, politik, budaya, ekonomi dan pemerintahan umat. Maka tentu saja diperlukan suatu pemikiran dan peninjauan ulang tentang formalisasi dan positivasi Syariat Islam dan pengamalannya, dalam konteks pembelajaran ajaran Islam secara keseluruhan, universal, kompleks, mendalam dan meluas.
Secara epistemologis, kiranya diperlukan suatu perubahan pembelajaran dan pemahaman melalui jalur ilmu pengetahuan (scientific track), sejak dari pemilihan dataran paradigma dalam memahami perintah Tuhan agar setiap muslim punya cita-cita menjadi ‘ulul albab, sebagaimana diwahyukan dalam al-Quran.[20] Disini dimensi rasionalitas manusia adalah sebuah anugerah, dan merupakan bagian dari entitas ketuhanan yang harus dimanfaatkan maksimal dalam memahami ajaran, hukum-hukum dan pesan-pesan universal Islam.[21]
Kemudian, ekspresi amal keagamaan yang selama ini secara dominan cendrung melahirkan aksi-aksi kekerasan dan penuh pemaksaan, semestinya tidak terbentuk menjadi pola pikir dan mentalitas keberislaman. Karena jelas dan tegas, bahwa aksi-aksi kekerasa dan pemaksaan dalam segala bentuknya itu bertentangan secara diametral dari standard asasi dari karakter religiositas Islam yang bersifat mendamaikan dan nirkekerasan. Maka karakter mendamaikan pribadi muslim yang terdidik, semestinya telah terbentuk secara bertahap seiring ia mengalami dan menghayati rangkaian panjang proses rekayasa pendidikan dan social modeling yang ada di sekitar kehidupannya.
Ketidak hadiran realitas kemusliman yang rahmatan itu hari ini, kiranya menjadi bukti indikatif tentang adanya kesalahan secara mendasar dalam pendidikan keislaman, yang perlu disadari, diakui dan ditaubati. Fenomena kegagalan yang terlihat pada kenyataan sosial sebagai hasil yang terbentuk (outcome) hari ini, kiranya sangat erat hubungannya dengan teologi pemahaman dan kesadaran keislaman yang selama ini dimiliki dan dilakoni.
Dalam dimensi ilmiah, tampak umat telah kehilangan dimensi otentisitasnya, kreatif, produktif dan inovatifnya dalam menghadapi dunia yang terus berkembang, bersama seribu satu masalah, tingkat urgensi yang semakin genting dan kompleksitas persoalan yang semakin semrawut.[22] Sehingga mendesak diperlukan upaya untuk segera memperbaiki, merubah, dan menata kembali sistem pendidikan dan sistem pengetahuan keagamaan masyarakat, melalui proses.
Perubahan utamanya adalah menyangkut paradigma pola-pikir dan corak prilaku keberagamaan yang tampak tidak lebih memberi tempat yang terhormat bagi aqal untuk secara bebas dan mandiri mengembangkan potensi rasionalitasnya. Akan tetapi mayoritas muslim, khususnya mereka yang berkuasa, baik secara politik maupun akademik, tampak masih lebih didominasi oleh sikap-sikap irrasionalitas-dogmatis, ritualis dan simbolik. Bahkan, mereka dan sebagian besar umat Islam masih sangat cendrung melihat agama sebagai wilayah yang irrasional, sehingga banyak sekali ajaran yang dianggap tidak bisa dipertanyakan lagi oleh akal-sehat manusia. Padahal banyak sekali ayat-ayat Quran yang justru memerintahkan manusia untuk senantiasa berpikir dan berpikir.[23]
Konsekuensi logisnya, para muslim selama ini tampak gagal dalam memahami dan menangkap esensi dan substansi terdalam yang terkandung dalam makna-makna denotatif “kedamaian” dalam kata-kata: salama, yaslimu dan silmuna, yang semuanya merupakan akar dari kata “Islam.” Disini, ajaran Islam secara eksplisit dan terang bermakna sebuah sistem hidup yang apabila dipahami dengan benar dan dilaksanakan dengan metodologi yang juga tepat, baik dan benar, maka keselamatan dan kedamaian adalah hasil akhirnya, sebagai suatu konsekuensi logis yang pasti diperoleh oleh masyarakat, baik muslim maupun non-muslim.[24]
Namun jika selama ini, Islam dan Muslim sering dilabeli dengan label-label yang berkonotasi negatif, sebagai agama yang dalam realisasi ajaran oleh umatnya dilihat mengandung dan mengundang kekerasan dan ketidak-damaian. Hal itu di satu pihak hanya merupakan sebuah kesimpulan dini yang sekedar didasarkan pada aktualisasi sebagian umat Islam yang telah terprovokasi amarahnya akibat berbagai kekecewaannya dan keterbelakangan wawasan intelelektualitasnya.
Sehingga mereka seolah telah kehabisan akal-sehat untuk memahami persoalan internal dan eksternal dirinya dan masyarakatnya, agar dapat mengeluarkan diri dari lingkaran hegemoni politik-ekonomi kapitalisme Barat, yang tampaknya seolah dibenci, tetapi dalam praktek sehari-hari justru diamalkan. Apalagi juga politik kapitalisme pemerintahan muslim sendiri, yang dirasa memang sangat menindas dan menjajah masyarakatnya sendiri, walau kini bank-bank Islam sudah berdiri. Namun tidak berdampak pada meningkatnya kemampuan ekonomi umat.
Oleh karenanya, kekerasan yang terjadi di kalangan internal umat Islam sendiri, agaknya lebih didorong oleh adanya faktor-faktor eksternal yang dihadapi umat Islam. Seolah, penegakan ajaran Islam dengan seluruh syari’atnya hanya mungkin terwujudkan jika dilakukan dengan penuh pemaksaan dan melalui tindak kekerasan. Seolah pula, Islam bukanlah sebuah agama yang ajaran-ajarannya didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan akal sehat. Ironis memang!
Di lain pihak, secara internal kekerasan demi kekerasan itupun terus sering terjadi, ketika seorang muslim didorong oleh keinginan untuk menampakkan komitmen keshalehan dan ghirah keberagamaannya dalam menentang kemungkaran dan kezaliman yang dihadapinya. Disini, citra kesalehan dan pengabdian kepada Tuhan ingin ditunjukkan melalui sikap-sikap keras dan dalam kobaran kegarangan, seperti yang sering terekspresikan saat meneriakkan yel-yel jihad: “Allahu akbar!.” Kesan sakral coba dibangun lewat lafadz Allahu Akbar, tetapi aksinya cendrung bersifat memaksa orang lain untuk harus bersepakat dengan apa yang ia pahami, sebagai sesuatu yang benar dalam perspektif politik Islam mereka. Ini seringkali terjadi dalam interaksi antar sesama muslim sendiri maupun dari kalangan non-muslim, dimanapun ia berada.[25]
Ada beberapa alasan faktorial internal dan eksternal yang dapat diutarakan disini yang kiranya merupakan penyebab yang merangsang atau memicu terjadinya tindak kekerasan di kalangan sesama muslim, juga dalam pergaulan dan persentuhannya dengan kalangan non-muslim, yaitu antara lain:
(1). Kegagalan epistemologis mayoritas kalangan kaum terpelajar dan terdidik muslim dalam memahami secara kritis dan operasional, terhadap nilai-nilai universalitas dalam ajaran Islam, seperti: keadilan, kejujuran, kesejatian dan fungsi-fungsi rahmatannya, sehingga gagal pula memahami, apalagi solusi terhadap berbagai permasalahan nyata di berbagai sektor kehidupan masyarakat muslim;[26]
(2). Ketidak-mampuan umumnya masyakat muslim dalam menghargai perbedaan, merupakan kelemahan warisan politik rezim otoriter Orba yang penuh pemaksaan dan kekerasan, akibat telah terbentuknya pola-pikir tunggal, bersifat binary opposition, yang hitam-putih tanpa tersedia alternatif dan bersifat searah dan monolitik. Sehingga melihat kebenaran lebih dengan cara klaim membenarkan diri sendiri semata, sebatas informasi yang telah diketahui dari para guru mereka, tanpa mau mencoba memikirkan, mengkaji memahami kembali, berbagai pemikiran orang lain yang beragam dan berbeda, tetapi kemudian berani menyimpulkan bahwa pendapatnya mutlak benar. Dan lantas memaksa orang-orang lain untuk menerimanya;[27]
(3). Keterjeratan mayoritas umat dalam elegy romantisme historis umat Islam yang cendrung terpukau terhadap masa lalu, dan kemudian coba menambatkan masa depannya pada kejayaan masa lalu. Tapi gagal menangkap nilai-nilai referensial-objektif yang kiranya berguna untuk konteks tuntutan masa kini, dalam coba mereaktualisasikan perintah dan ajaran Islam; [28]
(4). Massifnya realitas umat Islam yang miskin, tertinggal intelektualitasnya dan tertindas aktualitas sosialnya oleh hegemoni mazhab pemikiran social, ekonomi dan politik sekular dunia Barat, tanpa transendensi, melalui penetrasi artifak teknologinya, yang nyaris mempengaruhi tatanan nilai di segala sektor kehidupan umat Islam, secara tak terelakkan;[29] Namun kini, resistensi politik sekalangan umat untuk seolah sedang berjihad melawan hegemoni secular Barat, agaknya menjadi semacam ghirah yang memuarakan radikalisme dan berujung terorisme;
(5). Terjadinya ketidak-adilan sosial dalam distribusi sumber-sumber daya kehidupan, baik ditingkat nasional oleh pemerintahan umat Islam sendiri, maupun dirtingkat global yang dirajai super power Barat. Situasi ini menyebabkan kemiskinan massif masyarakat muslim, meskipun banyak Negara muslim yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Namun masyarakatnya tidak mampu mengeksploitasi sendiri kekayaan alam negerinya secara produktif, dan juga tidak memiliki wawasan menjaga kelestarian keseimbangan alam, akibat keterbelakangan ilmu dan teknologi;
(6). Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi umat Islam, yang kemudian membuat ketergantungan berkepanjangan banyak pemerintahan umat Islam kepada Iptek Barat yang justru sekedar membuat jurang kesenjangan sosial yang lebih dalam. Ini lebih merupakan akibat logis dari sistem pendidikan umat Islam yang bersifat menghapal, monolog, beku, jemu dan menindas. Kebebasan peserta didiknya dicabut di satu pihak oleh penguasa pendidik. Sementara di sisi lain, kebebasan pun seolah ditolak, jika itu untuk orang lain. Tetapi diri sendiri menganggap bebas melakukan apapun atas nama kebenaran;
(7). Berurat berakarnya paham kapitalisme Barat di tengah-tengah masyarakat muslim, yang bersifat menghisap dan menindas yang kemudian melembagakan budaya korupsi sebagai sebuah kelaziman baru. Di samping sector ekonomi ril di negera-negara muslim tidak menjadi tumpuan investasi, yang nantinya bisanya menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produksi.
(8) Adanya ketidak-sadaran mayoritas muslim terhadap bentuk dan cara perusakan moralnya yang dilakukan oleh para donatur dan pemberi bantuan asing, dengan membiarkan pengelolaan uang-uang bantuan dan pinjamannya kepada mayarakat muslim tanpa adanya stressing terhadap keharusan akuntabilitas dan transparansi public terhadap stakeholders dan konstituen, bukan sekedar laporan keuangan bagi donatur. Sehingga budaya transparan, partisipasi konstruktif dan akuntabilitas public tidak terbangun secara memadai.
Semua faktor tersebut, merupakan sebab-sebab yang menjadi sumber-sumber terjadinya konflik dan kekerasan yang terus berkelanjutan di dunia Islam. Lebih jauh, fenomena itu juga telah membuat para muslim terlena oleh fatamorgana materialisme-hedonisme barat, yang sebenarnya hanya melahirkan sengketa antar muslim. Sekaligus menggagalkan dirinya dalam menangkap pemahaman substansial ajaran Islam yang bersifat mendamai-sejahterakan, sejak di dunia hingga akhirat.
Padahal, jika umat Islam memahami secara persis dan mendalam pesan-pesan ilahiyah dalam al-Quran seperti yang akan kita kutip di bawah ini, sebenarnya memberi petunjuk tentang motivasi dasar dalam membangun kehidupan, bersama kewajiban berprilaku tanpa kekerasan, yang sungguh musti dijadikan exemplaar bagi prilaku dan akhlaq dalam misi penyebaran peradaban hidup Islami. Perhatikan pesan-pesan qurani dalam surah An-Nahl:125-128 berikut ini:
1. “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik (rasional). Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya, dan Dialah pula yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (16:125)
Ayat ini, menunjuk suatu perintah aktualisasi ajaran Islam yang benar-benar didasarkan pada azas produktifitas manfaat (hikmah), dan yang sama sekali tidak mengandung kekerasan apapun, walau sekedar sebuah sikap memaksa dalam menyerukan kebenaran kepada siapapun. Metode yang dianjurkan disini adalah metode dialektik (tanya jawab dua arah) yang menggunakan akal sehat dan argument-argumen rasional melalui orientasi kependidikan, pengajaran, penalaran, dimana “hikmah” dan “hasanah” (kebaikan) bagi semua pihak menjadi tolok ukur utama dan indikator utama bagi keberhasilan tujuan hidup kemuslimannya dan menjadi sandaran bagi niyat dan orientasi dasarnya.
2. “Dan jika kamu memberikan balasan (terhadap perbuatan buruk seseorang), maka balaslah dengan balasan yang setimpal, akan tetapi jika kamu bersabar, maka itulah lebih baik bagi orang-orang bersabar.” (16:126)
Pada ayat ini, memang ada kebolehan untuk membalas tindakan seorang lawan secara terukur, terbatas dan sebanding dengan apa yang diderita seorang muslim dari perlakuan orang lain (non-muslim) terhadap dirinya. Tetapi, kesediaan bersabar menjadi sesuatu yang lebih disukai Allah. Artinya, kekerasan yang barangkali diterima seorang muslim dari seseorang memang diizinkan untuk dibalas secara sebanding. Tetapi membalasnya itu bukan dengan cara-cara kekerasan adalah sesuatu yang lebih tinggi nilainya, dan sekaligus akan lebih membawa kesuksesan dalam misi dakwah Islamiyah. Bukankah senjata utama yang menjadi andalan Nabi Muhammad dan membuat misi dakwahnya sukses besar adalah akhlaq yang mulia?
3. “Bersabarlah (hai Muhammad), dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan” (16:127)
Disini, Allah menegaskan bahwa sikap shabar adalah suatu anugerah ilahi, yang pelakunya berkualifikasi berjiwa besar. Artinya, kesabaran disini adalah sebuah kekuatan jiwa untuk tidak bersedih dan tidak mengalami kesempitan hati dan pikiran, dalam menghadapi sikap orang-orang yang zalim dan kufur akan kebenaran. Jelaslah disini, bahwa ajaran tentang prilaku anti-kekerasan merupakan esensi dari aktualisasi prilaku Islam yang berasal dari kesabaran, kejernihan hati, kejujuran intelektual dan kelapangan dada dalam menerima pluralitas perbedaan dan dalam memahami visi dan misi universal kemanusiaan.
4. “Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa dan orang-orang berbuat kebajikan.” (16:128)
Jelas disini, bahwa Allah ingin menegaskan bahwa Ia selalu menghidupkan harapan-harapan dan semangat-semangat baru bagi hamba-hambanya yang berkenan menggunakan rasio dan qalbunya untuk mendukung terbinanya ketaqwaan, dalam membangun kehidupan yang berlumur kasih-sayang dalam dada-dada yang lapang. Ini semua bertujuan untuk mengenyahkan rasa kecewa, frustrasi dan pesimisme dalam perjuangan yang pasti akan sangat melelahkan serta penuh tantangan/hambatan, untuk cita-cita mewujudkan tatanan kehidupan umat manusia yang diliputi kedamaian sebagai rahmat dan manfaat dari misi universal kehadiran agama Islam bagi seluruh warga dunia.
Akhirnya perlu ditegaskan disini, bahwa untuk mencapai kebenderangan situasi realitas sosial kehidupan umat Islam yang jaya, sejahtera dan damai, kiranya haruslah diyakini hanya akan berhasil dibangun jika umat Islam, khususnya kaum terdidik dan terpelajar, agar dapat melakukan Taubat Keilmuan. Taubat ini dilaksanakan dengan memikirkan, mengkaji dan meneliti ulang nilai-nilai dan exposure keagamaan harus lebih dalam dimensi rasionalitas. Tanpa optimalisasi peran rasio atau aqal ini, dapat dipastikan ilmu tidak berkembang dan peradaban agama pun pelan-pelan kembali menjadi primitive dan menuju ke masa-masa jahilayah yang penuh kegelapan.
IV. Jihad Fi Sabilillah
Atas dasar semiotika dan hermeneutika sosiologis dalam penafsiran esensi qurani di atas, maka asosiasi pemikiran umat Islam terhadap “Jihad fi Sabilillah” (berjuang di jalan Allah) sama sekali harus dijauhkan dari pengertian-pengertian sempit yang sekedar tersimpul pada pengertian “perang” yang mempersyaratkan perlunya aneka tindak kekerasan, dengan hanya menggunakan berbagai kekuatan otot atau fisik/senjata tajam/api. Motivasi dasar dari peperangan itu sendiri, tampak lebih didorong oleh niat-niat dan semangat menaklukkan, mengalahkan dan bahkan memusnahkan lawan-lawan, sebagai manusia-manusia yang dianggap penghalang dan penentang pemikiran dan keinginannya. Jihad model ini tidak potensial untuk menghasilkan rahmatan.
Sementara pertimbangan yang melatari usaha penaklukan itu, kiranya lebih didorong oleh berbagai bentuk kepentingan sempit politik praktisnya. Atau boleh jadi demi memelihara otoritas dan kewenangan parochial, dalam suatu kontinum keinginan untuk berkuasa atau menguasai dan menundukkan lawan-lawan dan sumber-sumber dayanya di bawah hegemoni politik dan aliran pemikirannya.
Akan tetapi, sewajibnya umat Islam harus memahami bahwa jihad adalah sebuah perjuangan untuk menciptakan perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh pesan terdalam dari agama Islam itu sendiri. Artinya, tidak berlaku disini diktum: “si pacem para bellum” (jika ingin damai, bersiaplah untuk berperang). Tetapi, si pacem para pacem” (jika ingin damai, bersiaplah untuk berdamai).
Perdamaian adalah suatu produk dari aksi damai, bukan produk dari aksi perang. Sementara perdamaian itu sendiri harus dimulai sejak dari dalam pikiran yang membentuk pemahaman secara luas, lintas dimensional kehidupan manusia, yang bukan sekedar tidak adanya peperangan. Tetapi semua itu mencakup tegaknya keadilan, adanya kepastian hukum dan penghargaan atas segala hak-hak dasariah kemanusiaan.[30]
Jadi, jihad fi sabiilillah haruslah dipahami ke dalam suatu konteks dan bingkai perjuangan untuk menjabar-rumuskan praksis metodologis, agar seluruh nilai dan ajaran Islam itu dapat secara operasional dilaksanakan secara bersama dan kongkrit di lapangan. Semua rumusan metodologis itu kemudian akan menjadi sistem-sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya, yang dapat menjamin terselenggarakannya penegakan hukum, keadilan, kesetaraan gender dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia.
Namun, dalam menghadapi realitas sosial-politik umat manusia yang kini penuh kemungkaran, kezaliman dan kesalingan membantai dan memusnahkan, baik yang dilakukan oleh kalangan muslim atau non-muslim, maka sikap yang tepat yang harus diambil oleh seorang muslim yang baik dan yang direstui Allah adalah:
- Hadapi kekerasan secara terukur dan setimpal, dalam artian untuk mengimbangi saja, dengan lebih menekan misi-misi kemanusiaan, pendidikan, pengajaran dan jalinan komunikasi yang interaktif antar semua komponen masyarakat.
- Jadikan hukum qishas dan hukum hudud sebagai batas atas maksimal dari suatu rentangan vonis hukum, serta hanya merupakan suatu konsekwensi logis belaka dari pelanggaran yang dilakukan seseorang. Bukan hukuman yang dimotivisir oleh semangat pelampiasan dendam umat Islam.
- Namun jadikan sikap membangun kesabaran yang aktif dan kesediaan memberi maaf sebagai sumber-sumber kekuatan yang akan lebih membuat lawan sadar akan kesalahannya dan takluk pada kebenaran Islam. Disinilah orientasi ketinggian ajaran Islam harus segera mulai menjadi cita-cita yang perlu dimasyarakatkan, dimana ilmu pengetahuan, organisasi yang kompak dan strategi yang terbuka, terpercaya dan anti-kekerasan merupakan unsur-unsur penting dalam menggapai kemenangan.
- Tingkatkan dialog-dialog antar aneka ragam perbedaan, seraya terus menerus coba mengembangkan berbagai kesalingan yang konstruktif, jujur dan adil dalam membina kepercayaan, pengertian, penghargaan dan mutual simbiosis.
- Akhiri pola-pola pikir keberislaman yang hitam-putih (oposisi, sekedar bermain pada level formalisme, simbolisme dan seremonialisme, yang seringkali menjadi sumber kemunafikan sosiologis, politis dan teologis).
- Lepaskan tambatan hidup keagamaan pada pola-pola orientasi dan romantisasi kepada masa lalu, namun jadikan masa lalu sebagai tempat kita belajar banyak dalam membangun masa depan yang penuh ketidak-pastian, tantangan dan godaan.
- Sebarkan nilai-nilai Islam secara lebih substansial dalam mengkounter seluruh struktur, sistem dan relasi kerjasama sosial yang bersifat menindas, eksploitatif, diskriminatif dan tidak adil, yang merupakan menjadi biang kerok bagi terciptanya kesenjangan sosial-politik dan ekonomi, yang memuarakan berbagai konflik dan kekerasan destruktif selama ini.
- Membangun dan mengembangkan kembali pola-pola relasi, interaksi dan komunikasi yang lebih otentik, jujur, adil, lapang, kritis, berbasis data dan demi kebenaran serta kemaslahatan orang banyak.
V. Khatimah
Mengakhiri tulisan ini, maka perlu kiranya kita tegaskan, bahwa pemberlakuan dan penerapan hukum positive Syariat Islam oleh pemerintahan Aceh, semestinya dapat lebih dulu serius dipikirkan substansi materinya yang urgen, ranah intervensi yang harus lebih dulu dikenali dan aspek-aspek kebutuhan hukum masyarakat serta aspek-aspek transformatifnya yang memerlukan intervensi pemerintah dalam konteks syariat Islam.
Seiring elaborasi operasional aspek hukum tersebut, persoalan aktualisasi sosial seorang muslim dalam bingkai syariat, dengan menggali nilai-nilai dan sifat-sifat luhurnya, haruslah juga menjadi program pemerintah dan masyarakat secara mainstreaming lintas sektoral. Sehingga nantinya, penerapan Syariat Islam di Aceh itu mampu memberi kontribusi positif dan optimal dalam:
- Menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan umat dalam berbagai sektor
kehidupan, yang selama ini telah mendegradasikan derajat kemuliaan manusia.
- Mendorong terjadinya perubahan sosial masyarakat Aceh, yang diarahkan kepada terbentuknya kesadaran hukum masyarakat muslim Aceh dan menolak segala bentuk kekerasan dan main hakim sendiri.
- Membangun budaya keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehari-harinya.
- Meningkatkan kecerdasan dan kesadaran rasional masyarakat dalam menjalankan ajaran agama secara ikhlas dan selalu punya semangat dan kemauan untuk berintrospeksi, demi membangun peri kehidupan yang lebih berwawasan ilmiah.
Dengan demikian, tudingan-tudingan atau label-label negative dari sementara pihak dalam konteks penerapan Syariat Islam di Aceh, seperti: terorisme, fundamentalisme, radikalisme dan militanisme, misalnya, terhadap ajaran Islam dan Umatnya, kiranya secara bertahap dapat berubah, sekaligus membangun citra dan kenyataan sosial baru yang penuh makna dan akan lebih melahirkan suasana damai.
Disinilah tantangan kita bersama, untuk membuktikan bahwa umat Islam di Aceh adalah benar-benar sebagai “khaira ummatin,” sebagaimana yang telah direncanakan Allah dengan diturunkannya Agama Islam. Untuk itu, upaya pengejaran ketertinggalan yang jauh dalam soal penguasaan Iptek perlu menjadi cita-cita bersama masyarakat muslim khususnya di Aceh. Dengan catatan, bahwa konsep dan muatan esensial iptek yang akan dibangun umat Islam disini adalah iptek yang akan dapat melestarikan keseimbangan ekosistem alam dan manfaat yang terus dapat terjaga. Kemudian, dapat pula membangun kesehatan jiwa umat yang pandai menghargai, berterima kasih dan saling menghargai. Sekaligus terjadi penyembuhan dari segala sifat buruk yang merusak kebersamaan dan keseimbangan ekosistem, seperti: iri hati, dengki, khianat, mubazir, angkuh, serakah dan tamak dari umat Islam itu sendiri.
Tegasnya, kejayaan Islam memang hanya akan dapat terwujud melalui proses-proses aktualisasi akal sehat dan moralitas yang menebar manfaat bagi semua. Maka, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala aspek kehidupan, bersama segala kriteria normatif moralis diatas, haruslah menjadi cita-cita muslim di Aceh, sekaligus menjadi modalitas sosial suci bagi kebangkitannya.
Oleh karena itu, dimensi kebudayaan dan peradaban yang semestinya terbangun akibat pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, haruslah mampu membangun kesadaran, bahwa tanpa “Ilmu” kita tak akan pernah “Beriman.” Tanpa “Iman” kita tak akan pernah “Bermoral.” Tanpa “Moral” kita pasti akan kehilangan “Kasih Sayang.” Dan tanpa “Kasih Sayang” kita hanya akan “terhina dan musnah”…
Catatan Kaki:
[1] Peradaban Dunia yang penulis coba bayangkan melalui penerapan positivism hukum Islam di Aceh itu, dapatlah dipandang sebagai The Divine Presence. Suatu kehadiran transcendental manusia di muka bumi, baik sebagai ‘abdullah maupun khalifatullah, yang memerankan keseimbangan kepentingan “Aku dan Orang Lain”. Lebih lanjut tentang pembahasan mendalamnya soal the devine presence ini, baca, misalnya, William C. Chittick, Ibn al-‘Arabi’s Metaphysics of Imagination, Thed Sufi Path of Knowledge, (Albany, NY: SUNY Press), 1989, hal. 3-4
[1] Logika hukum seperti itu mengikuti perspektif filsafat hukum alam fisik dan hukum alam moral, yang memiliki dasar atau akar yang kuat dalam aturan alam semesta (die seinsordnung). Karena alam semesta tercipta dalam suatu perhitungan Allah yang ajeg dan terukur dalam qadar, teratur dalam system hukum dan seimbang antar factor dan unsur alam yang saling kait mengait. Maka berbagai aturan yang mutlak berlaku di dalamnya, merupakan konstanta hukum yang perlu dipahami dengan baik ketika manusia mencoba menjabarkan lebih lanjut secara dinamis hukum-hukum positif yang berfungsi mengatur prilaku manusia yang senantiasa menjaga secara seimbang antara kepentingan pribadi manusia, kepentingan umum dan kelestarian keseimbangan alam. Inilah juga yang harus disadari ketika Syariat Islam diterjemahkan menjadi hukum positif di Aceh. Untuk bacaan lebih lanjut mengenai perspektif filsafat hukum yang memandang hukum positif yang dijabarkan manusia harus sesuai dengan hukum alam, baca misalnya, Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1986), hal. 252-256.
[2] Dalam konteks hukum sebagai suatu kekuatan transformative, diperlukan suatu tatanan yang mengatur keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, sehingga pemberlakuannya tidak kemudian ada pihak yang dirugikan. Dan secara sistematis akan mengkonstruk suatu tatanan kehidupan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban, baik secara individual maupun secara kolektif. Disinilah peran Negara sebagai pemegang kewenangan coercive power harus bertindak bijaksana mengatur dan menjaga keseimbangan antara interest individu dan kolektif. Lebih lanjut baca, misalnya, Dr. Abdoerraoef, SH, Al-Quran dan Ilmu Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka, 1970), hal. 289-294.
[3] Salah satu hadis yang kiranya cukup popular diwacanakan oleh para da’i, yang menunjukkan tabiat dasar keberislaman adalah: “la yu’minu ahadukum hatta yuhibbu liakhihi kama yuhibbu li nafsihi.” Ini bermakna keyakinan kepada ajaran Islam tidak terwujud saat seorang pemeluk Islam hanya mencintai diri sendiri.
[4] Salah satu perwujudan The Divine Presence , yang merupakan suatu kehadiran dalam dimensi ilahiyah yang disyariatkan kepada manusia adalah berupa sebuah tugas suci untuk dapat menjadikan diri seorang muslim sebagai manusia yang hidupnya senantiasa menebar rahmat dan berguna bagi sesama. Untuk bacaan lebih detil menyangkut kajian The Divine Presence ini, baca misalnya, William C. Chittick, Ibn ‘Arab’s Metaphysics of Imangination, The Sufi Path of Knowledge, (New York: SUNY Press, 1989), hal. 3-30.
[5] Pemahaman ini didasarkan pada pesan sosial nabi Muhammad, yang dalam sebuah hadisnya berpesan: “khairun-nas man yanfa’u lin-nas” (sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain). Anehnya, meskipun hadis ini sudah cukup dikenal dan telah menjadi common sense umat Islam yang tak terbantahkan, namun kurang sekali dielaborasi lebih mendalam dan meluas pemahaman aktualnya dalam ritual dakwah Islamiah dan dalam praktek social politik umat Islam itu sendiri, khususnya di Aceh. Sehingga kandungan maknanya luput dari pemahanan praxis ajaran sosial Islam. Bahkan sebagian besar umat Islam, khususnya para elit ulama dan cendekia muslim, justru sering memahami ajaran sosialisme secara konotatif dipandang adalah juga sebuah varian pemikiran yang sama atau mirip dengan komunisme. Realitas umumnya umat Islam yang tekstualis terhadap trauma komunisme Indonesia, kiranya telah menjadi sebab sehingga ajaran social Islam tidak mendapat konteks dalam menyelesaikan secara substansial berbagai problema, krisis dan konflik ekonomi, social dan politik dalam masyarakat Islam, baik di Aceh, maupun di Indonesia. Karenanya, umat Islam tampak gagal berdialektika antara realitas teks yang ada dalam al-Quran dan realitas konteks yang ada dalam kehidupan nyata umatnya. Sehingga seolah islam tidak memiliki greget ajaran sosialnya, walau padahal 60% lebih kandungan Al-Quran merupakan ajaran sosial. Untuk bacaan lebih lanjut dalam hubungan dengan kesadaran teks versus kesadaran konteks, baca misalnya, Nasr Hamid Abu Zaid, (terj.), Tekstualitas Al-Quran, kritik terhadap Ulumul Qur’an, (Jogjakarta: LKIS, 2005), khususnya hal. 1-64.
[6] Ini merupakan pilar-pilar asasi dalam amaliah seorang muslim, sebagai perwujudan kongkrit kebenaran Islam, yang meliputi: 1. Mengucapkan dua kalimat syahadat; 2. Menegakkan shalat; 3. Melaksanakan ibadh puasa Ramadhan; 4. Mengeluarkan zakat dan 5. melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ke lima asas prinsipil perlu dibaca dan dilihat dalam perspektif social yang bisa melahirkan theomorphic ethics, atau ada semacam etika ketuhanan yang setiap harinya menghiasi akhlaq para penganut dan pengamal rukun Islam tersebut. Untuk kajian theomorphic ethic ini, baca, ibid, William C. Chittick, Ibn ‘Arabi’s Metaphysic…, hal. 22-26.
[7] Perhatikan dan camkan pemahaman mendalam dan kontekstual dalam mengahadapi dan menyelesaikan konflik sebagaimana ditegaskan dalam Quran: 16: 125 yang semestinya menjadi pedoman umat Islam. Disini, kosa kata ahsan harus dipahami dalam prinsip-prinsip kebaikan, kebenaran, kearifan dan keindahan. UNtuk mendapatkan ruhnya, baca misalnya, Yusuf Ali, The Qur’an, (mushaf Al-Madinah-An-Nabawiah), English Translation and the Meanings and Commentary, (Riyadh: King Fahd Holy Quran Printing Complex), footnote 2161, hal. 770.
[8] Dalam konteks filsafat eksistensialisme, para filosofnya, seperti Jean Paul Sartre, manusia dipahami sebagai suatu entitas yang padanya melekat berbagai potensi yang bersifat pour moi (given) yang kemudian baru dipandang eksis, jika manusia dapat menggunakan segala potensi itu untuk berproses menjadi pour soi (becoming) atau “menjadi.” Tanpa proses “menjadi” hingga suatu taraf pencapaian puncak, manusia dipandang gagal bereksistensi. Jadi disini tujuan bereksistensi adalah hanya untuk mencapai kemampuan tertinggi demi diri itu sendiri. Untuk kajian filsafat Eksistensialisme, baca misalnya, DR. Bernard Delfgaauw, (terj.), Filsafat Abad 20, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1972), hal. 139-152. Sementara dalam Filsafat Islam, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa optimalisasi potensi yang ada dalam diri manusia melalui berbagai upaya pendidikan, adalah justru ditujukan untuk memaksimalkan kemampuan diri seorang muslim untuk memberi manfaat bagi sebanyak mungkin orang-orang lain.
[9] Untuk memperoleh ketercerahan pikiran dan perasaan ini, maka ada sejumlah jenis kecerdasan yang perlu mendapat pembinaan sejak dini bagi setiap muslim, meliputi kecerdasan-kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, transcendental, social, interpersonal, menejerial, financial hingga kecerdasan seksual. Tetapi sedikitnya dari tiga kecerdasan yang meliputi Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan Emosional (EQ), Kecerdasan Spiritual (SQ), diharapkan seorang muslim akan menjadi mudah tercerahkan dan mengeliminir hingga batas-batas optimal kemungkinan penggunaan kekerasan sebagai metode menghadapi problema kehidupan beragamanya. Salah satu buku yang bagus untuk dibaca dalam konteks pencerahan ini Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, (Jakarta: Penerbit Arga, 2001).
[10] Untuk memahami lebih jauh tentang kedahsyatan kekuatan akal-budi yang ada pada manusia ini, baca misalnya, Syahmuharnis dan Harry Sidharta, Transendental Quotient, (Jakarta: Penerbit Republika, 2006), hal. 25-36.
[11] Disini, prinsip utama yang harus ditanamkan oleh proses pendidikan adalah: keyakinan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia dari segenap makhluk lainnya yang ada di jagat raya ini. Ada sejumlah prinsip dasar lain yang semestinya dibangun dalam konteks keberislaman, agar ia bias menjadi orang yang berguna. Untuk penjelasan lengkap tentang prinsip-prinsip kemanusia yang harus dibangun melalui kerja pendidikan yang akan mendukung terbentuknya masyarakat Islam yang benar, baca Prof. Dr. Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibani, (terj.), Falsafah Pendidikan Islam, (Jakarta: Balai Pustaka, 1979), hal. 101-161.
[12] Dalam kehidupan social-budaya seorang muslim, “Tauhid” harus dilihat dalam world view yang secara logis dapat ditarik pengertian bahwa penciptaan Allah adalah esa. Maka ia menolak segala bentuk diskriminasi (ras, warna kulit, kelas, garis keturnan, kekayaan dan kekuasaan). Dalam prinsip tauhid ini menempatkan seluruh umat manusia sebagai makhluk egaliter, dan menyatukan antara manusia dan alam yang senantiasa harus dijaga kelestarian keseimbangannya. Keesaan Tuhan juga keesaan kehidupan yang tidak memisahkan antara dimensi keagamaan dengan kleduniawian. Dengan memahami seluruh aspek kehidupan yang diatur oleh satu hukum dan tujuan seluruh muslim untuk bersatu di dalam kehendak Allah. Baca, Toshio Kurada, (ed), Islam Jiten (Tokyo: Tokyodo Shuppan, 1983), hal. 15.
[13] Dalam kontek ketauhidan yang membebaskan manusia dari segala bentuk deifikasi atau penyembahan selain Allah, yang boleh jadi sesembahan simbolis terhadap makhluk itu sendiri, baca misalnya, Fuad Mardhatillah, “Islam Protestan: Sebuah Paradigma Pemikiran Islam, Membangun Spirit Perlawanan” dalam Jurnal Gelombang Baru, (Banda Aceh: Tikar Pandan, 2008), hal.. 63-102.
[14] Tugas dan sikap beragama secara kritis dan berakal sehat seperti itu, sungguh amat sesuai dengan perintah Allah dalam Surah Ali Imran: 191, dimana setiap pencari akan sampai pada pembuktian dan pengakuan yang haqqul yaqin tentang kemahaciptaan Allah. Baca juga, Idrus Shahab, Beragama dengan Akal Jernih: Bukti-Bukti Kebenaran Iman dalam Bingkai Logika dan Matematika, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), hal. 128-159.
[15] Untuk memperkaya varian pemahaman tentang ibadah shalah, perlu pula dibaca Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, hal. 204-217.
[16] Shalat yang dalam ajaran Islam menempati ibadah yang paling utama, kiranya perlu dipahami dan dihayati dalam konteks dan perspektik ilmu social profetik, yang tidak saja membahas fenomena-fenomena social dan usaha-usaha mengubahnya, tetapi juga memberi arah tentang kemana arah perubahan yang harus dituju dan dicapai, oleh siapa dan untuk apa perubahan itu. Sehingga shalat benar-benar fungsional dalam mencegah para mushallin dari prilaku merusak, penuh kekerasan, keji dan mungkar. Untuk pembahasan ilmu social profetik baca misalnya, Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 2006), hal. 86-88.
[17] Sebuah petunjuk yang ditegaskan Allah dalam Qur’an, Al-baqarah: 183, bahwa ujung pencapaian dari puasa yang benar itu adalah ketaqwaan, harus pula dipahami dalam konteks ilmu social profetik. Sehingga pelaksanaan ibadah puasa itu akan membentuk pribadi-pribadi yang transformative menuju masyarakat yang memiliki kesabaran, kepedulian dan solidaritas sosial.
[18] Kesadaran sebagai makhluk social memberi implikasi betapa seorang manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya orang-lain di sekeliling dirinya. Bahkan ketika seorang anak manusia yang diisolasi atau dialienasi oleh komunitasnya dapat berdampak ekstrim dengan melakukan bunuh diri oleh orang yang diisolasi tersebut. Atau ada juga gejala orang-orang yang menyendiri, takut keramaian, dan mengasingkan diri dari komunitasnya. Maka orang tersebut divonis oleh masyarakat dan oleh kajian psychologis sebagai orang menderita gangguan kejiwaan (mental disorder). Untuk memahami gejala asosial dan menyangkut kajian fenomena ekstrim berupa tindakan bunuh diri dan ketika sebagai makhluk social salah mempersepsikan kehadiran orang lain terhadap dirinya. Baca misalnya, Emile Durkheim, Suicide: A Study in Sociology, (New York: The Free Press, 1951), khususnya bab Social Element of Suicide, hal. 297-325.
[19] Ajaran Zakat ini pun adalah juga bagian dari proses transformasi dan purifikasi diri seorang anak manusia yang menyadari kelemahan dirinya dan butuh kehadiran orang-orang lain untuk membantu dirinya.
[20] Perhatikan dan pahami pesan-pesan implicit dalam Quran, Ali Imran: 190-200.
[21] Untuk maksimalisasi fungsi aqal dalam memahami ajaran Islam yang menghendaki adanya perubahan paradigma, ini berarti konsep teologi negatif dalam melihat Tuhan sebagai suatu entitas yang menakutkan dengan azab neraka yang maha mengerikan, perlu dirubah dengan perspektif teologi positif yang melihat dalam kebaikan dan keindahan yang penuh kasih saying. Pemahaman teologi positif ini dapat diamalkan dengan memahami pesan-pesan intrinsic yang terkandung dalam nama-nama Allah (al-asma ul husna). Untuk pengembangan wawasan metodologis dalam konteks tuntutan perubahan paradigma teologis dan perdebatannya, baca misalnya, Hans Kung dan david Tracy, Paradigm Change in Theology, (New York: Cross Road Publishing Company, 1989), hal. 3-112.
[22] Untuk kajian bagaimana manusia dapat memanfaatkan potensi aqliyahnya dalam mengembangkan rasionalitas kreatif dalam menghadapi kehidupan yang terus semakin kompleks yang membutuhkan terobosan-terobosan cerdas dan kreatifitas. Kreatifitas pemikiran semacam inilah yang juga amat diperlukan dalam memahami ajaran Islam yang kaaaffah yang nyaris tak terbatas, hingga penjabaran metodologi operasionalnya yang realistis-kontekstual, sesuai dengan tuntutan realitas. Maka baca misalnya Conny R. Semiawan, dkk, Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu, (Bandung: Rosda Karya, 2004).
[23] Untuk sikap mental yang menempatkan aqal sebagai sesuatu yang tak dapat digunakan semaksimal mungkin dalam memahami ajaran Islam, kiranya menjadi mirip dengan sikap mental umat Katholik yang tidak boleh mempertanyakan secara tyerus menerus berbagai doktrin ajarannya. Maka kepada umat Islam kiranya perlu merenungkan pesan-pesan yang terkandung dalam Quran, Surah al-Kahfi: 103-105. Lihat pula Yusuf Ali, The Qur’an, (mushaf Al-Madinah-An-Nabawiah), English Translation and the Meanings and Commentary, catatan kaki no. 2448 dan 2449.
[24] Untuk mencapai hal semacam itu, umat Islam perlu terus menerus mengasah daya jelajah keilmuannya secara kritis dan mengembangkan nalar-nalar ijtihad kreatifnya. Lebih lanjut, baca misalnya Ali harb, Kritik Kebenaran, (Jogjakarta: LKiS, 1995), hal. 86-90
[25] Pertanyaannya disini, apakah kesucian dapat berdampingan dengan kekerasan, dalam alasan apapun? Saya cendrung ingin mengutip pesan Allah dalam Al Quran, surah al-Ankabut: 2-3 yang mempertanyakan: “apakah manusia itu dibiarkan saja mengatakankami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta.”
[26] Untuk membuka wawasan nilai-nilai universal dari ajaran Islam, baca misalnya, M. Syafi’i Anwar, dkk, Islam and Universal Values, (Jakarta: ICIP, 2008).
[27] Sebenarnya, Islam bukanlah agama yang didirikan di atas doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran dogmatis. Tetapi Islam adalah agama yang didesain secara penuh perhitungan yang dapat dibuktikan kebenaran ajarannya. secara ilmiah, melalui nalar-nalar rasional yang bersifat empiris dan nalar metarasional yang tidak membutuhkan dimensi empiris. Sehingga ilmu-ilmu Islam dapat disusun menjadi landasan teori bagi rancang bangun systemik, agar kemudian yang dapat dilaksanakan secara operasional di dunia nyata. Untuk ini baca misalnya, Dr. H. Nasuka, Teori Sistem, Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2005), khususnya hal. 61-90.
[28] Manusia sebagai makhluk historis, kiranya harus memahami sejarah sebagai pengalaman orang-orang terdahulu, yang kemudian menjadi tempat dimana para generasi pelanjut dapat berguru untuk menemukan pelajaran dan hikmah dalam membangun masa depan yang lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Barangkali tepat, jika sejarah eksistensi suatu kaum beragama misalnya, dielaborasi pemahaman yang lebih komprehensif melalui tinjauan perspektif Filsafat Perennial. Ini diperlukan untuk menemukan “benang-merah” nilai-nilai keluhuran, baik yang bersifat particular maupun universal, yang merupakan warisan yang bersifat abadi dan perlu terus dikembangkan dalam menata kehidupan di masa depan oleh generasi yang dating kemudian. Untuk kajian apa dan mengapa Filsafat Perennial, baca misalnya Komaruddin Hidayan dan Mohd. Wahyu Nafis, Agama Masa Depan, Perspektif Filsafat Perennial, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995), hal. 1-14.
[29] Disini jelas tidak ada masalah dengan produk teknologinya sendiri. Yang bermasalah adalah penggunaan dan penyikapan yang diberikan umat Islam yang akhirnya hanya menempatkan dirinya hanya sebagai konsumen pemakai yang pasif dan tak mampu melakukan perlawanan secara cerdas terhadap aliran informasi yang mengalir lewat teknologi informasi hai ini.
[30] Karenanya agama Islam harus benar-benar dielaborasi seluruh kekuatan ajarannya untuk menghindari segala bentuk kekerasan, untuk kemudian dapat membangun perdamaian. Dalam hubungan ini, baca misalnya, Chaiwat Satha Anand, Agama dan Budaya Perdamaian, (Jogjakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama, Universitas Gadjah Mada, 2001), hal 26-38.