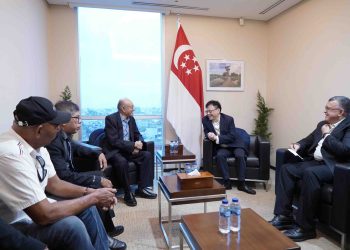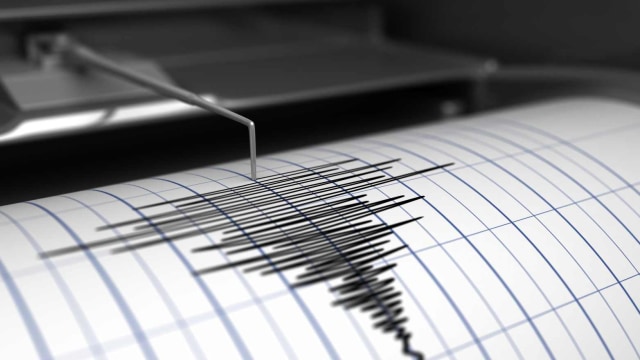Oleh: Affan Ramli
Praktisi Pendidikan Kritis di Masyarakat Adat.
Sebulan setelah mengasingkan diri ke Arab Saudi pada April 2017, Habib Rizieq menyampaikan harapannya suatu hari ketika pulang ke Indonesia ia akan disambut seperti Ayatollah Khomeini. Tentu, yang ia maksudkan kepulangan Khomeini ke Iran pada Januari 1979 dari pengasingannya di Francis. Tiga tahun kemudian sejak hasrat itu diutarakan, Rizieq benar-benar disambut jutaan massa pada 10 November 2020. Mungkin melebihi penyambutan Khomeini.
Bagi rezim Jokowi, menyeret nama Khomeini pada momen ini adalah suatu pesan. Rizieq dan massa FPI menginginkan revolusi Islam. Setidaknya itu mulai kelihatan, sejak Pangdam Jaya lansung ke garis depan membungkam Front Pembela Islam (FPI). Satpol PP dan Polda Metro Jaya tampak tak dapat diandalkan. Situasi sebenarnya, pasti tidak seserius itu. Dibanding revolusi, FPI sekedar menyasar Pilkada. Paling jauh, Pilpres berikutnya.
Berbeda dari nasib Khomeini, kampanye politik Rizieq terlalu mudah dibungkam. Dalam waktu kurang dari dua bulan, gerakan FPI nyaris sepenuhnya berhasil dihentikan. Rizieq ditahan sebagai tersangka kasus kerumunan massa pelanggar Prokes Covid-19, FPI dibubarkan dua minggu kemudian. Kasus chat mesum Rizieq dan Firza Husein pun dibuka kembali setelah sempat dihentikan (SP3).
Jika kita meletakan kisah pertarungan FPI melawan rezim kali ini sebagai kelanjutan drama lama, kontestasi antara islamisme dan nasionalisme yang sudah dimulai sejak awal pendirian Republik Indonesia, buat sementara waktu dapat dikatakan kekuatan nasionalis sudah memenangkan pertarungan jenis ini untuk kesekian kalinya. Sekarang kaum nasionalis merayakan tahun baru 2021 dengan hati lebih gembira. Tahun baru, tahun tanpa FPI.
Pun begitu, memposisikan FPI sebagai representasi kekuatan islamisme Indonesia terkini mungkin juga berlebihan. Mengingat FPI awalnya lahir hanya bagian dari inisiasi Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (PAM Swakarsa) untuk membantu TNI menyukseskan Sidang Istimewa MPR pada November 1998 (ISAI, 2000). Pada periode-periode berikutnya, militer menggunakan FPI untuk melawan organisasi-organisasi masyarakat sipil progresif yang mengusik rezim dan aparatusnya.
Tetapi dalam perkembangannya sulit diabaikan, FPI cukup lantang menyuarakan gagasan ‘NKRI Bersyariah’. Kelantangan ini melampaui tingkat keberanian PKS yang mungkin punya aspirasi politik mirip-mirip. Sementara dua Ormas Islam terbesar kita, NU dan Muhammadiah, tidak tertarik sama sekali pada gagasan islamisme. Bagi NU dan Muhammadiah, Islam adalah agama, kebudayaan, dan sumber ide moral. Islam bukan ideologi politik bernegara. Dapat dikatakan, NKRI Bersyariah versi FPI satu bentuk ideologi islamisme Indonesia terkini setelah ideologi Negara-Islamnya DI/TII dan khilafah-islamiahnya HTI yang telah lebih duluan dipasarkan di Indonesia. Terkadang, FPI mencampur ide ‘NKRI Bersyariah’ dan ‘Khilafah Islamiah’ dalam doktrin ideologi mereka.
NKRI Bersyariah sebagai gagasan politik sangat sederhana. Itu seperti memperluas model Aceh saat ini ke seluruh Indonesia. Tidak perlu diumbar, Aceh pada faktanya telah kembali ke Piagam Jakarta, atau Pancasila versi 22 Juni 1945. Secara defacto, kalimat ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemluk-pemeluknya’ sudah dihidupkan kembali di Aceh dalam dua dekade terakhir.
Jika Pemerintah Indonesia dapat berkompromi menghidupkan Piagam Jakarta untuk Aceh tanpa perlu mengubah teks Pancasila, kenapa kompromi yang sama tidak bisa dilakukan dengan FPI? Setidaknya membiarkan saja FPI bersuara. Dugaan saya, FPI dibubarkan tidak terkait ideologi islamismenya. Lebih pada pertimbangan kontestasi kuasa dan hitungan risiko gangguan terhadap rezim oligarki saat ini.
Itu tidak bermakna saya menginginkan model Aceh bersyariat diperluas ke Indonesia. Justru sebaliknya, jika kiyai-kiyai NU menolak kekacauan ide NKRI Bersyariah, kenapa Aceh tidak diselamatkan dari kekacauan yang sama? Toh faktanya, persoalan-persoalan utama penataan ‘ruang hidup bersama’ di negara ini seperti kapitalisme, militerisme, dan budaya korup, malah tidak terselesaikan sama sekali dengan jalan bersyariat model Aceh. Dibanding menyelesaikan persoalan-persoalan utama itu, NKRI Bersyariah model Aceh lebih banyak menambah persoalan-persoalan baru.
Islamisme?
Abdulkarim Soroush memberi kita jalan terobos kebuntuan tak berkesudahan dalam gelanggang tarung hampir seabad antara narasi islamisme dan nasionalisme bernegara. Bahwa ruang-ruang hidup bersama (ruang publik) di negara ini dapat diatur dengan ide-ide baik yang terseleksi melalui sebuah perdebatan keilmuan yang fair di tengah publik, dengan memperlakukan sumber-sumber ide itu di posisi setara, terbuka peluang dari gagasan-gagasan yang ditangkap manusia dari agama. Ruang publik kita dengan demikian, tidak boleh anti-agama. Ide-ide syariah jika ditarik dari ruang personal ke ruang publik, tetap diperlakukan sama tidak sucinya. Setara ide-ide lain dari sumber-sumber non-agama, seperti filsafat, penemuan keilmuan sosial, keilmuan alam, tradisi masyarakat adat, atau tradisi hukum kolonial yang masih dominan di Indonesia saat ini.
Bagaimanapun, ide-ide syariah yang dibawa paksa ke ruang publik sudah pasti bukan syariah itu sendiri. Pengembangan ide-ide syariah bila hendak dimenangkan menjadi ‘aturan main’ di ruang publik harus melalui ‘proses-peras’ berkali-kali, minimal dalam tiga tahapan. Pertama, pemindahan ide-ide itu dari teks suci ke penyimpulan pengetahuan personal (mekanisme ushul fiqh), ke dua, pemindahan dari kesimpulan-kesimpulan pengetahuan personal ke sistem dan konten perundangan (mekanisme ushul taqnin), dan ke tiga, pemindahan ide dari perundangan (qanun) ke kerangka-kerja praktis pelaksanaannya di ruang publik (mekanisme ushul tadhbiq). Maka ketika ‘aturan main’ di ruang publik ditentukan, semua ide didalamnya sama sekali bukan ide suci, sekalipun ide-ide itu bersumber dari agama.
Bila tidak melalui perdebatan publik yang fair, gagasan-gagasan yang diklaim berasal dari agama (syariah) terlalu cepat dianggap berkualitas suci dan diklaim bernilai benar pada tingkat aksioma. Padahal tidak ada pengetahuan agama yang suci dan aksioma. Sebuah pemahaman adalah peristiwa manusiawi yang profan melibatkan terlalu banyak unsur ketaksuciannya, sekalipun terhadap teks-teks suci. Jika tiga tahapan ‘proses-peras’ di atas dilompati atau dilakukan tanpa kesadaran epistemik, maka sebagian warga merasa dapat mengubah pengetahuannya yang suci menjadi undang-undang publik dengan serta merta. Fantasi seperti ini yang kebanyakan diyakini dalam gerakan-gerakan islamisme di Indonesia.
Kekacauan epistemik itu pula yang menyebabkan qanun-qanun syariat di Aceh dipandang sama sucinya dengan syariat (agama). Ruang-ruang perdebatan dan diskusi publik tidak dibuka sekondusif mungkin. Kritik-kritik terhadap qanun dipandang sebagai anti-syariat, dengan sendirinya anti-Islam. Sekolompok masyarakat sipil yang hendak mendiskusikan ulang dan mengusulkan perubahan tatacara eksekusi cambuk dapat dinilai anti-syariat. Penghakiman serupa terjadi pada diskusi-diskusi lain sejenis, seperti advokasi perubahan uqubat (hukuman) tindak kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, dan pendiskusian ulang kerangka-kerja penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Implikasi lainnya dari islamisme demikian bisa lebih fatal. Pertama, membatasi kegiatan pengaturan ruang publik menjadi otoritas ekslusif pemuka agama. Ruang-ruang dialog dan komunikasi deliberatif-inklusif, sebagaimana dibayangkan Habermas, dengan sendirinya tergusur. Serikat-serikat rakyat dianggap terlalu awam memahami syariat, apalagi memindahkannya menjadi undang-undang.
Ke dua, kelompok-kelompok elit pemegang otoritas keagamaan dapat menjustifikasi kelembagaan dan praktek-praktek ekonomi kapitalisme atas nama syariat. Pembenaran yang sama bisa dilakukan memperkuat militerisme dan kekerasan komunal yang cenderung menguat. Para pengelola urusan dan harta publik yang korup kemungkinan besar tidak akan tersentuh karena islamisme Indonesia biasanya fokus pada urusan-urusan kemaksiatan personal, bahkan di ruang-ruang privat. Kecendrungan ini dapat dibaca dan dibuktikan dari pola razia-razia FPI dan kelompok islamis lain selama ini.
Gerakan islamisme kita seringkali mendapat tepukan tangan, apresiasi, dan dukungan kekuatan imperialisme dunia. Kepalsuan islamisme Indonesia ditandai dengan itu. Selain tidak paham urusan-urusan kerakyatan, pada saat yang sama tidak menganggu kekuatan-kekuatan eksploitatif jejaring gurita kaum pemodal. []