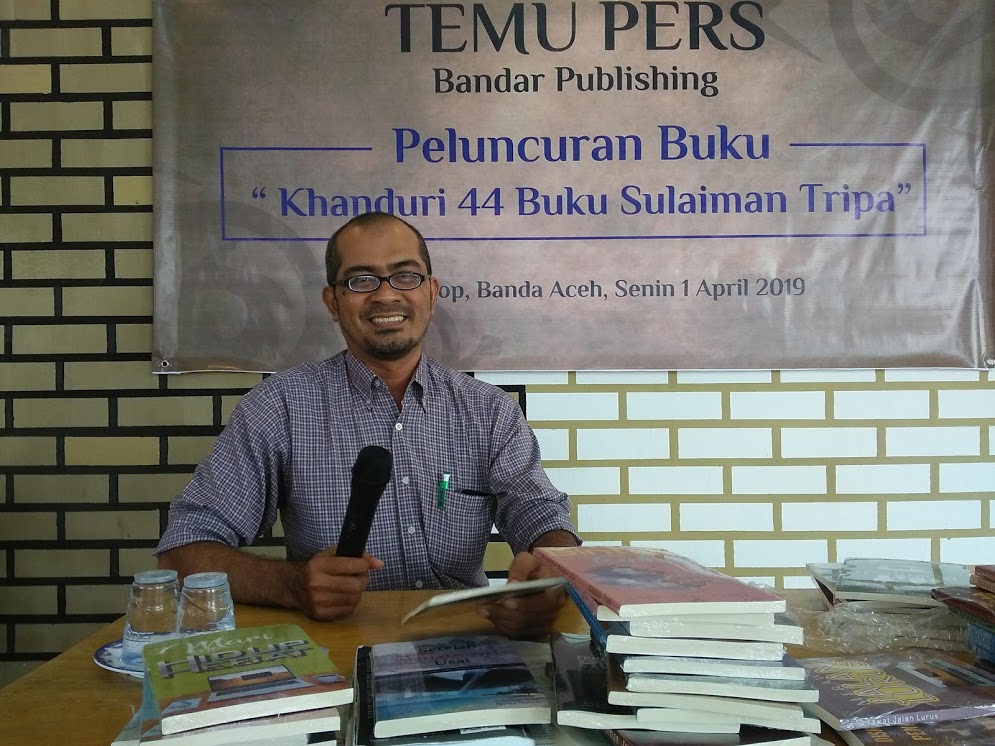Oleh: Sulaiman Tripa.
Penekun Kajian Hukum dan Masyarakat.
Dua dekade yang lalu, seorang penulis dari Selatan, Martin Khor (2001) mengungkapkan bahwa salah satu dilema terbesar negeri-negeri yang sedang berkembang masa kini adalah mereka harus membuka diri terhadap globalisasi. Membuka diri tersebut, sebenarnya sangat berkaitan dengan harapan akan memperoleh beberapa keuntungan bagi negara yang bersangkutan. Atau paling tidak –kalaupun bukan keuntungan—akan memilih berhati-hati untuk menghindari berbagai risiko; yang paling berat disebut Khor adalah kritik institusi-institusi mainstream yang kemudian akan mengkuliahi negara-negara yang sedang berkembang dengan penekanan bahwa negara-negara tersebut akan tertingga apabila tidak mengikuti proses globalisasi.
Pertanyaannya adalah apakah globalisasi akan menjamin tidak ada kesenjangan kesejahteraan dan ekonomi antara negara-negara maju dan negara-negara yang sedang berkembang? Pertanyaan ini pun bukan baru muncul sekarang. Ia sudah menjadi diskursus sejak isu globalisasi muncul.
Pertanyaan (yang seharusnya tak perlu) tersebut, dipertanyakan hanya untuk meneguhkan pernyataan bahwa ada kesenjangan yang luar biasa antara negara-negara maju dan negara-negara yang sedang berkembang, dalam konteks ekonomi dan kesejahteraan –yang dihiasi pula oleh dominasi politik yang sangat berlebihan. Tak pelak, perdebatan tentang keuntungan ekonomi menjadi suatu yang dominan dalam konteks globalisasi –yang pernah digambarkan oleh mantan Presiden Soeharto sebagai sesuatu yang mau tidak mau, senang atau tidak senang, akan dihadapi oleh semua negara di dunia.
Ketimpangan muncul. Lalu mengapa, kesenjangan yang luar biasa itu ternyata kian menganga dari tahun ke tahun?
Perilaku mencari sumber ekonomi sebenarnya sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Lahirnya penjajahan di atas muka bumi, faktor terbesarnya disebabkan oleh karena penguasaan sumber-sumber ekonomi. Membaca buku-buku tentang sejarah Aceh memperlihatkan bagaimana berbagai negara di dunia berusaha menjangkau bahkan untuk kawasan yang tidak terjangkau. Kemauan orang-orang di negara maju untuk mengelilingi dunia pada abad-abad silam, adalah sebagian besar juga disebabkan oleh rangsangan ini.
Nah, bukankah sebenarnya proses sejarah memang berulang-ulang sebagaimana pernah dipermaklumkan oleh Ibnu Khaldun –dengan bentuk dan warna yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman?
Tentang ini, diingatkan Khor (2001), dengan mengatakan bahwa tantangan dalam hal membuka diri terhadap proses globalisasi, adalah apakah negara-negara berkembang dapat mengambil keuntungan dari proses yang hakikatnya berlangsung liberalisasi yang sampai tahapan tertentu didorong oleh kekuatan-kekuatan eksternal, dan pada saat yang sama harus menghindari atau meminimalkan konsekuensi-konsekuensi buruk pada perekonomian dan masyarakat mereka.
Apa yang diingatkan Khor, memperjelas bahwa dominannya memang ekonomi. Akan tetapi globalisasi ternyata juga mengharuskan adanya perubahan di semua lini. Yang lebih penting adalah kebijakan nasional yang mendukung proses globalisasi tersebut.
Ketika melewati penjelasan ini, maka persoalan menjadi kompleks. Banyak tatanan yang ternyata harus berubah. Memang ini menyangkut dari kemampuan negara-negara dalam mengelola globalisasi dan liberalisasi melalui penyusunan kebijakan nasional di negara masing-masing.
Hal ini tentu berkaitan dengan paradigma pembangunan ekonomi, hukum, dan keadilan sosial. Pada kenyataannya, paradigma ekonomi semata –sebagaimana harapan keuntungan dari ikutserta dalam proses globalisasi—sama sekali tak menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Masalah akhir-akhir ini yang muncul, ketimpangan secara ekonomi secara global justru kian menjadi-jadi.
Di sinilah pentingnya kekuatan nasional –yang ikut atau tidak ikut dalam proses globalisasi—untuk memperjuangkan terwujudnya pengelolaan tingkat nasional dengan memadukan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial (keadilan sosial) dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksudkan Khor. Tetapi selama ini, negara-negara sedang berkembang seperti tidak berdaya. Di banyak negara berkembang, persoalan lingkungan terjadi secara besar-besaran dengan permasalahan sosial yang juga berselimak. Masyarakat terus menjadi korban terus dalam memperoleh keuntungan ekonomi lewat berbagai kepungan pundi-pundi kekuatan pasar.
Pada akhirnya kesenjangan tetap merupakan sebuah kenyataan, yang memberi kesangsian bahwa globalisasi dapat memperoleh keuntungan ekonomi akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan. Mari kita merenungi kawasan vital nasional di Aceh yang ternyata tidak menyelesaikan masalah kesejahteraan. Bahkan kemiskinan menganga justru muncul di pinggir perusahaan-perusahaan multinasional?
Ada keuntungan dari globalisasi, namun globalisasi bukan tak melahirkan implikasi negatif yang luar biasa. Seperti keharusan negara-negara sedang berkembang untuk terus mengkampanyekan bahwa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itu merupakan sebuah kenyataan. Masalahnya, bila prosea itu pun diikuti, bagaimana implikasi negatifnya akan dihindari?
Selain ketergantungan ekonomi, ada persoalan lain yang lebih besar. Samuel Huntington (2003) mengatakan sumber-sumber identitas dan sistem otoritas yang telah mapan menjadi “kacau” yang terpengaruh dengan munculnya kebangkitan global. Menurut Huntington, proses modernisasi sudah melanda dunia pada paro abad ke-20. Orang-orang dari pinggiran menuju kota, terpisah dari tradisi dan mendapatkan pekerjaan baru atau menjadi penganggur. Francis Fukuyama (2002) menyebutkan bahwa perubahan terpenting dalam masyarakat masa kini adalah menngkatnya individualisme.
Dalam hal-hal tertentu, proses ini bisa dikatakan terwakili lewat modernisasi. Dalam Jeane Patrick (2005), Samuel Huntington mengetahui bahwa modernisasi (yang lebih dekat dengan westernisasi) –jika dipahami secara luas—dan ia dapat mengakibatkan serangan balik dan permusuhan yang sengit. Ia juga mengetahui betapa kuat momentum moderen, cara kerja sains Barat, teknologi, demokrasi, dan pasar bebas. Tapi ada satu pertanyaan besar yang diketahui Huntington adalah apakah negara-negara yang non-Barat tu dapat menjadi moderen tanpa menjadi Barat?
Inilah persoalan besar. Proses globalisasi tak hanya berlangsung dalam aspek ekonomi, tapi juga tatanan lainnya. Sungguh kompleks. Negara-negara maju sepertinya sedang mempermaklumkan bahwa negara-negara yang sedang berkembang berada dalam genggaman mereka. Barangkali tidak secara teritorial. Sebuah negara yang menguasai negara lain, akan dikatakan sebagai penjajahan. Tetapi ketika negara berkembang disapih dengan cara lain, akan disebut sebagai kemurahan hati negara maju.
Negara mana yang sudah berdiri tegap untuk menyampaikan bahwa sedang berlangsung pencaplokan negara-negara besar terhadap negara-negara kecil yang tidak berdaya? Lalu di tempat kita, siapa yang sudah berdiri tegap untuk menyampaikan bahwa ada beberapa penguasaan yang terjadi lewat penetrasi gelombang-gelombang modal besar dari perusahaan dunia, atas nama kesejahteraan dan pembangunan?
Negara-negara maju masih menjadi pemegang remote ekonomi sekaligus budaya. Kebanyakan akan boleh dimiliki oleh negara-negara berkembang, tapi remote penguasaan, sama sekali tidak. Negara pemilik kekayaan biasanya hanya mendapat sebagian kecil saja. Di luar itu, hampir tak ada negara di dunia yang berhasil mempertahankan tradisi dan identitasnya karena alasan modernisasi sebagai bagian dari globalisasi.[]