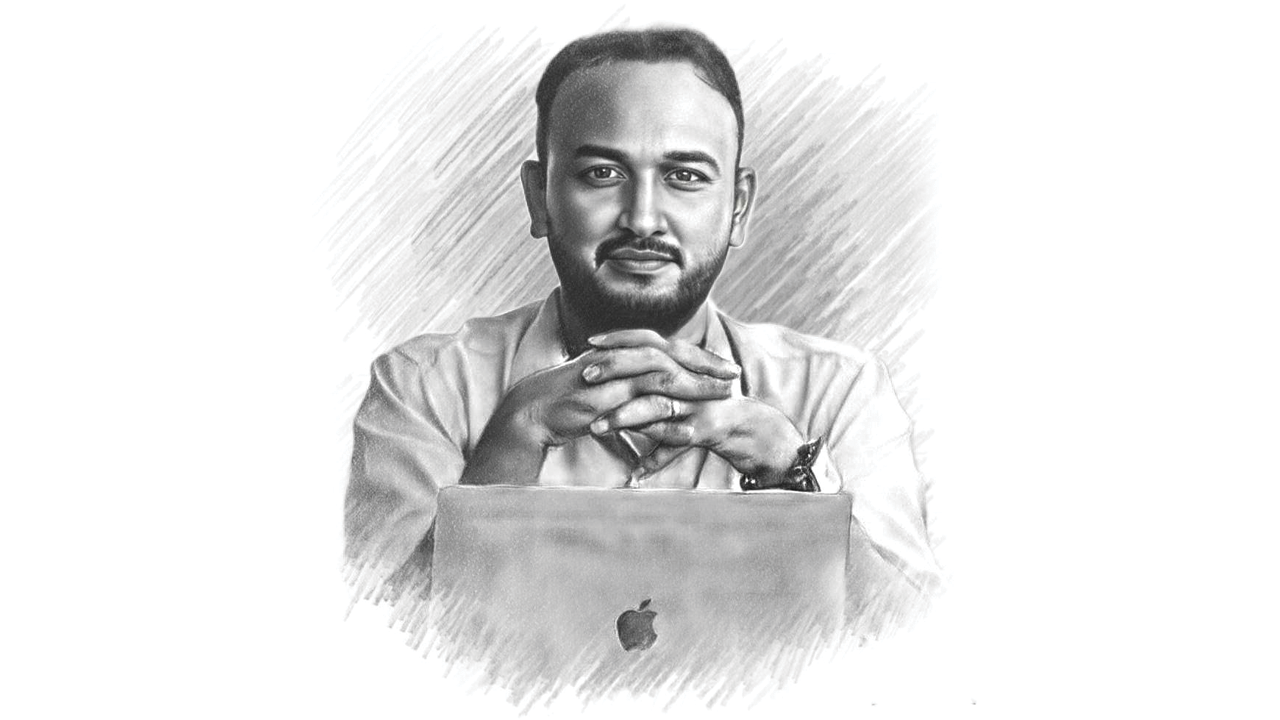Oleh: Mukhlisuddin Ilyas
Direktur Bandar Publishing
Tulisan ini memaparkan tentang kontestasi aktor di Aceh paska MoU Helsinki. Salah satu akibat dari kontestasi aktor lokal di Aceh adalah pudarnya gerakan baru berbasis nasionalisme Aceh. Kontestasi aktor lokal yang akan dibahas dalam kajian ini, antara lain adalah terdiri dari kontestasi aktor politik, kontestasi aktor kombatan dan kontestasi aktor agama. Tulisan ini melihat bahwa ruang sosial kontestasi aktor lokal di Aceh berakibat pada menurunnya rasa nasionalisme keacehan. Karena masyarakat tersadar, bahwa akhir dari semua kontestasi, berujung pada penguasaan kapital, perebutan pengaruh dan perebutan sumber daya alam oleh para elit lokal di Aceh.
Dalam sejarahnya, kehidupan sosial di Aceh pernah digerakkan melalui spirit nasionalisme ke-acehan. Setelah Indonesia Mardeka pada tahun 1945, gerakan nasionalisme Aceh pernah tampil di puncak selama dua kali. Pertama, terjadi pada tahun 1953 ketika Pemerintah RI mengabaikan aspirasi kultural (DI/TII), yakni keinginan untuk melaksanakan syariat Islam, yang kemudian memunculkan perlawanan dari Daud Bereueuh. Kedua, munculnya sebagian kelompok masyarakat Aceh untuk membentuk organisasi berbasis etnis seperti GAM tahun 1976. Mereka menuntut pemisahan diri dari pemerintah Republik Indonesia, yang kemudian dihadapi oleh pemerintah melalui penerapan Daerah Operasi Militer DOM, sehingga makin menguatkan munculnya sentimen keetnisan di Aceh, dimana ruang tarungnya mencapai puncak pada tahun 1998.
Menurut Otto Syamsuddin Ishak, dinamika kehidupan paska konflik di Aceh sangat dipengaruhi oleh 4 peristiwa besar. [1] Pertama adalah keberhasilan gerakan Reformasi 1998 secara nasional, yang mencerminkan keberdayaan sebuah gerakan sosial yang bisa melampaui kedigdayaan sebuah rezim yang sudah bertahan hidup hingga 3 dasawarsa. Fenomena ini merupakan awal kebangkitan gerakan masyarakat sipil di Aceh, yang merefleksikan kebangkitan gerakan sosial di daerah terhadap kebijakan politik rezim pusat sehingga. Kedua, muncul tuntutan pencabutan status Aceh yang dikenal secara publik sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) atau dalam sandi militer sebagai Daerah Operasi Jaring Merah (OJM) yang juga digelar di Timor Timur dan Papua. Ketiga, bencana alam gempa tsunami (2004) yang membangkitkan solidaritas kemanusiaan dunia terhadap kondisi kemanusiaan di Aceh, yang mencerminkan kesatuan aksi kolektif lintas bangsa dan keyakinan untuk hal-hal yang bersifat kemanusiaan pada level lokal. Keempat, tercapainya kesepahaman bersama untuk menciptakan perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia (RI) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, yang telah dirintis sejak awal pada tahun 2000, yang dikondisikan oleh sebuah pengakuan dunia bahwa pembangunan (rehabilitasi dan rekonstruksi) hanya bisa dilakukan pada situasi yang damai.
NASIONALISME ACEH
Sejarah nasionalisme Aceh terhadap bangsa Indonesia selalu di catat dalam banyak arsip. Salah satu catatan arsip itu adalah keterlibatan orang-orang Aceh dalam Perang Medan Area di Sumatera Utara, sumbangan pesawat Seulawah 01 dan Seulawah 02 yang disumbangkan rakyat Aceh kepada Republik, dan beragam catatan lainnya. Semuanya itu dapat dirangkum dalam sebuah frase bahwa rasa dan sikap nasionalisme orang-orang Aceh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bergelora tinggi dan berdinamika. Beberapa tokoh Aceh kontemporer, yang awalnya seorang republiken sejati, seperti halnya Daud Beureueh dan Hasan Tiro kemudian malah berontak dengan basis tagline nasionalisme Aceh.
Sebenarnya, nasionalisme sebagai suatu bentuk pemikiran dan cara pandang yang menganggap bangsa sebagai bentuk organisasi politik yang ideal. Suatu kelompok manusia dapat disatukan menjadi bangsa karena unsur-unsur pengalaman sejarah yang sama, dalam arti pengalaman penderitaan atau kejayaan bersama.[2]Nasionalisme adalah suatu identitas kelompok kolektif yang secara emosional mengikat banyak orang menjadi satu bangsa. Bangsa menjadi sumber rujukan dan ketaatan tertinggi bagi setiap individu sekaligus identitas nasional.[3]
Terminologi nasionalisme memiliki perbedaan dengan patriotisme, chauvinisme dan primordialisme. Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya atau semangat cinta tanah air. Chauvinisme adalah paham (ajaran) cinta tanah air secara berlebih-lebihan. Meskipun demikian, antara nasionalisme, patriotisme dan chauvinisme sama-sama berkaitan dengan paham cinta tanah air atau bangsa/negaranya dalam konteks lembaga negara bangsa (nation-state).
Nasionalisme Aceh adalah bagian dalam perbincangan nasionalisme itu sendiri, yang bercirikan lokal. Nasionalisme Aceh, dalam ruang konflik vertikal, lebih popular disebut dengan kajian etnonasionalisme. Etnonasionalisme merupakan terminologi yang berada dibawah bahasan nasionalisme. Dengan kata lain, etnonasionalisme merupakan nasionalisme tingkat lokal yang biasanya muncul untuk menentang nasionalisme pusat. Apabila seseorang berada dalam suatu kontestasi yang tidak berimbang dan adil, maka orang tersebut akan berusaha mempertahankan dirinya dengan mencari identas budayanya atau sering disebut dengan ethnic identity.[4]
Peter M. Leslie, menyebutkan bahwa etnonasionalisme merupakan suatu kebudayaan yang meliputi pencapaian artistik, alat dan gaya pernyataan diri, dan seluruh sistem nilai sosial agama yang mendefinisikan suatu komunitas—menjadi kontribusi pada formasi sebuah masyarakat yang berbeda, hidup berdampingan dengan yang lainnya dalam batas-batas suatu negara.[5] Dapat dikatakan bahwa etnonasionalisme merupakan bentuk solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas merujuk pada perasaan subyektif yang memisahkan satu kelompok tertentu dengan kelompok lain dalam sebuah komunitas.[6]
Sentimen etnonasionalisme merupakan fenomena positif bagi rasa keanggotaan komunitas dan bagi perkembangan pribadi mereka, yang tidak dapat terjadi dalam konteks sosial lain yang lebih luas. Etnonasionalisme dapat mengisi kebutuhan individu atas dimensi kolektif yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan pribadi. Etnonasionalisme berakar dari adanya kehendak untuk mengubah apa yang tadinya bernama etnosentrisme menjadi entitas politik. Tujuannya memang untuk membangun masa depan bersama dari penduduk yang mendiami wilayah tertentu, yang secara ekonomi, politik, dan kultural merasa merupakan suatu komunitas yang mempunyai rasa solidaritas yang erat.[7]
Terkait dengan kebangkitan sentimen etnis menurut Joseph Rothscild terdapat dua alasan mengapa sebuah kelompok etnis yang semula berkehendak membentuk bangsa kemudian dalam perjalanannya menjadi kehilangan orientasi nasionalismenya. Pertama hal itu disebabkan adanya kompetisi dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang tidak imbang, dimana kemudian mendorong menguatnya identitas suatu kelompok etnis. Kedua adanya aktor yang menggerakkan anggota kelompok etnis, sehingga memiliki sentimen keetnisan yang kemudian mengarah pada pembentukan sebuah bangsa yang mandiri.[8]
Etnonasionalisme digerakkan dan muncul berbasis pada etnis. Namun tidak berarti setiap etnis akan menggerakkan etnonasionalisme.[9] Etnonasionalisme juga tumbuh dari faktor kesejarahan, yakni orang-orang di daerah tertentu mempertahankan ingatan mereka terhadap kontribusi etnisnya dalam perang kemerdekaan dan itu membentuk suatu sikap superior yang misalnya diungkapkan dengan kalimat: “Kalau dulu tidak ada suku kami membantu perang mengusir penjajah, mungkin saat ini Indonesia masih dijajah!” Sentimen seperti ini biasanya menolak usulan “penyetaraan”, bahwa semua daerah harus diperlakukan secara setara.
Etnonasionalisme dirajut oleh kesamaan asal-usul, sedangkan nasionalisme diikat oleh kesamaan tujuan. Jika negara gagal mengembangkan nasionalisme kewarganegaraan, maka etnonasionalisme sebagai salah satu ekspresi politik identitas lokal, akan dengan mudah muncul ke permukaan melalui aktor-aktornya. Disinilah perlu ketegasan aktor nasional dalam memainkan peranannya yang kondusif.
ORIENTASI AKTOR
Emirbayer dan Mische, membedakan tiga orientasi aktor sosial dalam sebuah situasi.[10] Pertama, orentasi agensi interaksional. Aktor sosial model ini menggunakan tindakannya secara selektif untuk diterapkan pada kondisi sosial tertentu yang dipadukan dengan aktivitas praktis mereka. Kedua, orientasi proyektif, aktor model ini membanyangkan tindakan yang mungkin dilakukan untuk masa depan pribadi dan kelompoknya. Ketiga, orientasi praktis-evaluatif, aktor model ini berusaha untuk menilai sesuatu dalam situasi tertentu untuk bisa terus bersikap yang berubah-rubah.
Beranjak dari pemikiran Emirbayem dan Mische, sudah momentumnya masyarakat Aceh paska MoU Helsinki untuk membangun “situasi interaksional” antarwarga. Supaya masyarakat Aceh dapat mengambil peran dalam kesejahteraan rakyat Aceh. Aktor-aktor di Aceh harus melempar ide-ide gerakan, bukan selalu berpikir pada kepentingan dan kekuasan jangka pendek.
Setelah MoU Helsinki, sejumlah aktor lokal terus bergerak di Aceh. Mereka mengambil keuntungan dari situasi tidak solidnya para aktor lokal. Situasi terpecahnya elit lokal di Aceh, menampilkan broker-broker elit lokal yang bergerak dalam 3 bagian.
Bagian pertama, munculnya elit lokal di Aceh yang fokus pada kerja-kerja pengurasan sumber daya alam (SDA) secara agresif dan sistematis, mulai dari hutan, tambang, dan perikanan. Dalam sektor ini, para elit lokal bekerjasama dengan elit nasional supaya eksistennya berjangka panjang.
Bagian kedua, terkurasnya modal sosial orang Aceh. Para elit saling memecah belah para aktor lokal. Hubungan satu aktor lokal dengan aktor lokal lainnya dibuat seseram mungkin, menenggelamkan aktor yang berkarakter dan mendukung aktor yang lemah leadership. Seolah-olah akan menjadi penyelamat dan membawa keberkahan bagi kelanjutan pembangunan Aceh. Para elit mengelola kelemahan para aktor untuk eksistensi misinya di Aceh.
Bagian ketiga, terkurasnya modal kelembagaan lokal. Hampir tidak ada lembaga keistimewaan di Aceh yang memiliki reputasi sebagai penjaga stabilitas lokal. Setiap permasalahan yang diperbedebatkan antar elit lokal di Aceh, bukan diselesaikan di Aceh. Melainkan bersama-sama menjari penyelesaian kepada Pemerintah Pusat. Situasi ini terus dipelihara oleh elit tertentu, supaya wibawa antar lembaga di Aceh tidak stabil. Tampilnya broker-broker elit lokal di Aceh mendapat dukungan dari tenaga-tenaga ahli yang memiliki reputasi pada bidangnya. Baik yang berasal dari Aceh maupun luar Aceh. Semunya berjalan dibawah nilai-nilai moral.
Jacques Bertrand mengatakan bahwa integritas moral, terutama pascakonflik menjadi hal penting, karena secara filosofis, integritas moral harus didukung oleh ideologi personal aktor. Menurutnya, pemberontakan yang terus menerus terjadi di Aceh dulunya dapat dipahami sebagai konsekuensi dari konteks mengelola identitas, kekuasaan dan distribusi ekonomi.[11]
Menurut Jacques Bertrand, arti pentingnya integritas moral dalam perspektif Aceh mulai ditinggalkan. Para aktor di Aceh, mempertontonkan terma-terma lama dalam kondisi kontemporer. Misalnya terma “jahannam”, “pengkhianat”, “pungo”, “sesat”, dan lainnya, ditambah janji-janji yang tidak rasional. Munculnya terma-terma ini membuktikan rapuhnya sendi-sendi integritas moral, kohesi sosial, serta hilangnya nilai-nilai persaudaraan dan kesetiakawanan antar aktor di Aceh.
KONTESTASI AKTOR
Era kebebasan dan keterbukaan Aceh pasca konflik dan tsunami Aceh merupakan simbol baru bagi identitas masyarakat Aceh. Sekaligus indikator penanda terjadinya pergeseran pada ranah suprastruktur, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai ke- Aceh-an yang kini sedang menemui masalah disorientasi, dan elit-elit lokalnya. Berbagai bentuk struktur nilai-nilai, keagamaan, keadatan, hingga pada sub-kultur masyarakat Aceh kini sedang mengalami redefinisi atau apa yang kerapkali disebut sebagai transformasi secara meluas. Kebebasan pasca-konflik juga dipahami sebagai pembudayaan nilai baru yang terkadang berhadap-hadapan dengan nilai-nilai asli (indegenius values). [12]
Lebih lanjut Ibnu Mujib, Irwan Abdullah, Heru Nugroho, (2014) mengatakan bahwa setidaknya terdapat tiga kegelisahan empiris yang mengispirasi kebangkitan Aceh. Pertama, kerinduan akan Aceh yang damai dan kondusif, tidak lagi ada konflik, apalagi konflik baru yang diciptakan melalui situasi yang tidak kondusif pasca tsunami. Kedua, harapan kolektif masyarakat Aceh yang tidak lagi ingin dijajah oleh rezim apapun, tekanan- tekanan politik, termasuk para agensi global yang meraup kepentingan lewat jalur-jalur kapitalisme yang demikian ekstreem. Ketiga, kurang adanya perjuangan bersama, sebuah perjuangan yang berpihak pada kecerdasan lokal. Hal ini tidak berarti kekuatan global tidak diizinkan menjamah pada ranah lokal, tetapi kecerdasan global harus beroperasi melalui mekanisme yang ditentukan oleh dan atas negosiasi di antara kekuatan-kekuatan berbagai pihak yang berkepentingan. Ketiga bentuk kegelisahan inilah yang kemudian menginspirasi pembantukan gagasan Aceh baru, sebagaimana yang saat ini sedang dibangkitkan kembali di Aceh. Oleh karena itu, selanjutnya dibutuhkan rekomendasi- rekomendasi yang mengarah pada perjuangan aksi-aksi dari dalam yang akan terumuskan melalui isu reaktualisasi ruang publik dan transformasi identitas keacehan.
Disadari atau tidak bahwa perkembangan Aceh tidak saja diciptakan oleh masyarakat Aceh sendiri, pelibatan global juga mewariskan pengembangan Aceh yang lebih efektif, cepat, dan bahkan strategis. Meski dalam batas yang lain, globalisasi seringkali melewati batas-batas teritori kultural yang sudah ditentukan sebagai arena kontestasi dalam masyarakat.[13] Kontestasi elit lokal harus dipahami sebagai sebuah respon dalam dinamikan transformasi masyarakat sosial.
Kontestasi Aktor di Aceh paska MoU Helsinki, terutama dalam merebut otoritas harus memperkuat pemahaman dan kewaspadaan bersama. Terutama menyangkut tiga hal. Pertama isu potensi konflik dan pembangunan; kedua pembangunan sebagai konflik; ketiga adalah sektor ekonomi penyebab konflik.
Pertama menyangkut konflik dan pembangunan. Sering diwacanakan dalam perspektif faktor kebencian dan sejarah. Konflik selalu berkaitan dengan fakta empiris, ekonomi dan pembangunan dalam spektrum ekonomi, politik dan sosial budaya.
Menurut Bank Dunia, konflik dan pembangunan selalu bermuara kepada tiga hal: Pertama, konflik memperlambat pembangunan; Kedua, pengembangan mengarah kepada konflik, dan; Ketiga konflik terjadi karena kurangnya pembangunan.[14] Dalam setiap kontestasi, semua aktor politik harus mempertimbangkannya secara mendalam, termasuk kualitas intelektual pribadinya, supaya kehadirannya kemudian tidak menimbulkan benturan baru bagi Aceh.
Menurut Bates dalam suatu kawasan pascakonflik, pada awalnya kekerasan dan peningkatan kesejahteraan berjalan beriringan, tetapi menurun sesudahnya.[15] Perkataan Bates, benar-benar aktual bagi kondisi Aceh mejelang 10 tahun MoU Helsinki. Peningkatan kesejahteraan dapat mendorong perilaku predator dalam bentuk kekerasan oleh orang yang kurang beruntung. Jadi, konflik dan pembangunan harus benar-benar menjadi kewaspadaan bersama oleh para aktor.
Kedua adalah pembangunan sebagai konflik. Dalam domain ini, menurut Huntington menyebutkan bahwa pembangunan adalah proses inheren dengan konflik.[16] Untuk itu, kontestasi politik di Aceh paska MoU Helsinki harus dikelola untuk mencapai nilai-nilai positif dan non-kekerasan. Setiap ketimpangan yang terjadi, harus didistribusi dalam proses pembagunan dengan bentuk-bentuk politik non kekerasan.
Asumsi dasar bahwa pembangunan sebagai konflik adalah pembangunan tidak selalu berjalan dengan baik. Pembangunan selalu memiliki dampak seperti tidak direncanakan. Pada sisi lain, pembangunan dapat memicu dan mempertahankan konflik. Pembangunan juga pada dasarnya adalah sebuah proses yang tidak merata. Spektrum pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dapat ditargetkan dengan cara membantu rekonstruksi pasca-konflik dan rekonsiliasi.[17] Pembangunan sebagai konflik harusnya berjalan setara, karena tidak semua pembangunan memili korelasi positif dari segi perekonomian, terutama untuk jangka pendek.
Dan ketiga adalah sektor ekonomi sebagai penyebab konflik. Setidaknya memiliki tiga unsur utama dalam isu ini. Pertama adalah unsur keserakahan (greed), terutama oleh para aktor politik dan aktor birokrat. Perebutan sumber daya alam sering sekali menjadi contoh dalam keserakahan yang mengakibatkan menjadi konflik. Keserakahan ini selalu bermuara pada keuangan, pendapatan, rekrutmen sumber daya manusia. Unsur kedua adalah keluhan (grievance). Keluhan dalam unsur ini adalah berkaitan keadilan. Motivasi mencari keadilan untuk kemaslahatan semua elemen.
Unsur ketiga adalah kontrak sosial (social contract). Kontrak sosial biasanya bersifat vertikal, antara pemerintah lokal dengan pemerintah pusat (sentralisasi), atau kontrak sosial bersifat horizontal antara daerah atau sesama masyarakat (desentralisasi). Ketiga unsur ini harus benar-benar diaktualisasi dalam setiap kontestasi politik di Aceh, supaya penguatan ekonomi tidak menjadikan sumber daya alam sebagai arena konflik baru.
KONTESTASI AKTOR KOMBATAN
Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pemerintah Aceh, memberi kesempatan bagi mantan kombatan GAM untuk membentuk partai lokal dan memiliki kesempatan berkontestasi merebut kekuasaan politik, untuk menjadi Gubernur, Bupati/Wali Kota sampai dengan Kepala Desa (Keuchik). Peluang dan kesempatan ini, dimanfaatkan dengan baik oleh mantan GAM untuk berkontestasi.
Beberapa kombatan berhasil berebut kekuasaan politik. Baik pada level Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil walikota, DPR Aceh, DPR Kabupaten/Kota, hingga elit kombatan menjadi Kepala Desa (Keuchik). Dalam proses kontestasi merebut kekuasaan politik pask MoU Helsinki, sering sekali menghilangkan akal sehat, kadang-kadang berujung pada pembunuhan sesama mantan kombatan. Akibat dari kontestasi elit politik kombatan, hilangnya rasa kebersamaan dan cenderung berfikir praktis tidak lagi bersandar pada ideologis gerakannya.
Pudarnya sikap ideologis aktor kombatan dalam merebut kekuasaan, dikarenakan kehilangan tokoh pemersatu dalam merangkul semua elit politik kombatan. Sebenarnya, dalam setiap periode konflik dan pembangunan di Aceh, selalu lahir sosok perekat. Baik itu dengan sentimentil etnonasionalisme maupun dengan sentimen etnosentrisme. Lahirnya perekat menjadi “pemicu” dalam mengisi pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh elemen rakyat Aceh. Sejumlah aktor pernah menjadi perekat dalam kedua nasionalisme tersebut, sebut saja seperti Daud Beureueh, Hasan Tiro, A Hasjmy, Ibrahim Hasan, dan lainnya.
Dalam kontestasi politik kombatan pada Pilada 2017 misalnya, terlihat bahwa masyarakat Aceh kehilangan perekat yang dapat dijadikan panutan dalam memasang harapan untuk mengisi kesejahteraan. Masyarakat Aceh seperti kehilangan sosok man of inspiration, sosok yang dapat menginspirasi banyak orang, untuk terlibat dalam mengisi pembangunan Aceh.
Semula, setelah ditinggal Hasan Tiro, sosok man of inspiration dialamatkan kepada Malik Mahmud. Tapi, sosok ini kualitasnya jauh dari harapan banyak pihak. Jangankan mengisi pembangunan Aceh, “mendamaikan” eksponen kombatan saja tidak berhasil. Bukan tidak mungkin, setelah 2017-2022 nanti, mereka yang memiliki latar belakang GAM akan menjadi “korban” dalam setiap kontestasi kekuasaan. Mereka terhempas dari panggung politik, akibat dari ketidakmampuan menjadi perekat dan hilangnya sosok man of inspiration.[18]
Ke depan, akan lahir sosok man of inspiration dari kalangan nasionalis di Aceh. Jika ini terjadi, maka pada tahun 2022 nanti, Aceh kembali dalam sejuta aksi, layaknya Ibrahim Hasan. Baru kemudian pada 2027 Aceh kembali melahirkan sosok man of inspiration. Tapi untuk apalagi sosok man of inspiration, Aceh sudah tidak lagi mendapat dana Otsus. Sebagaimana diketahui, selama 2008-2022 Aceh mendapat dana otsus setara 2% dana alokasi umum Nasional, sementara pada 2023-2027 hanya mendapat setara 1% pagu dana alokasi umum Republik Indonesia.
Satu akibat tidak hadirnya sosok perekat atau man of inspiration dalam masyarakat Aceh saat ini, lahirlah politisi-politisi radikal dan sandiwara (humoris). Politisi radikal dan lucu-lucuan, lahir karena basis intelektualitas yang tidak mumpuni. Tensi politik selalu meninggi karena perilaku aktor politik yang berujung pada sikap radikalisme, agresif dan saling menyalahkan.[19]
Sikap politisi radikal dan humoris bisa kita lihat dari debat kandidat pada Pilkada Aceh pada 22 Desember 2016 lalu di Hermes Palace. Kesimpulan debat menampilkan dua hal; radikal dan humoris. Maka tidak mengherankan, terdapat kontestan dalam Pilkada Aceh 2017 yang selalu bersikap ekstrim dan jenaka. Sikap ekstrem diwujudkan dalam kata-kata seperi penghianat, laknat, dan klaim sejenisnya.
Sikap ekstrem dalam perilaku politik seringkali berbeda yang dikatakan dengan yang dikerjakan. Satu sisi memperjuangkan kepentingan tertentu, tapi sisi lain melecehkan tujuan tersebut. Begitu juga kontestan humoris, terkesan natural dengan basis keacehan yang mengental. Tapi sesungguhnya selalu memuat sikap radikal, meuyoe dipubloe, ta bloe (kalau mereka jual, kita beli). Artinya simbolisme sosok politisi itu bukan pada ucapan para politisi, tapi harus dilihat dari perbuatan masa lalu dan masa kini.
Secara umum kondisi Aceh selalu mendapat pantauan, maka diperlukan sistem politik yang kuat, supaya Aceh tidak melahirkan politisi-politisi radikal. Harus diakui, sistem politik Aceh di bawah kepemimpinan eksponen GAM sangat rapuh, situasi politik di Aceh terkadang mempengaruhi aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Hal ini dapat dibuktikan periode paska MoU Helsinki, terdapat gerakan-gerakan keagamaan yang menggunakan agama sebagai alat kekerasan yang mengarah pada aksi-aksi radikalisme. Lebih lanjut setelah diteliti ditemukan bahwa setidaknya radikalisme dalam beragama di Aceh dipicu oleh perilaku dan sikap politisi-politisi Aceh itu sendiri.
Pemerintah Aceh di bawah kendali eksponen GAM sama sekali tidak memiliki formula yang ampuh dalam menyelesaikan perpecahan di kalangan umat beragama. Ini bisa jadi karena Aceh kehilangan sosok perekat atau man of inspiration seperti digambarkan di atas. Ditambah penanganan masalah keagamaan di Aceh belum dilakukan melalui kebijakan yang komprehensif. Satu penyebabnya adalah karena banyaknya distribusi “radikalisme politik” yang tersebar merata di seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Kontestasi elit mantan kombatan terpecah belah. Data “prestasi” hasil dari kontestasi merebut kekuasaan di Aceh. Bila ditelaah lebih lanjut karena hilangnya sosok perekat di Aceh dalam menjalankan kekuasaannya. Wali Nanggroe Malik Mahmud yang digadang-gadang menjadi simbol baru sebagai perekat, malah menjadi “kutukan” bagi para kombatan GAM. Mereka terpecah-pecah, saling mempertontonkan keluguan dan kelucuan dalam setiap kontestasi.
KONTESTASI AGAMA
Aceh paska MoU Helsinki 2005, menjadi penanda munculnya dominasi elit agama di Aceh dari dayah. Posisi dayah paska DI/TII sering “diwarnai” dalam setiap kontestasi. Sebaliknya paska MoU Helsinki, dayah di Aceh “mewarnai” setiap elit di Aceh.
Dominasi elit agama dari dayah di Aceh, dapat dilihat dari keberedaanya dalam struktur Tuha Peut Wali Nanggroe, Majelis Ulama Aceh (MPU) dan sejumlah kader-kader dayah telah berhasil menduduki posisi puncak dalam struktur lembaga pemerintah. Beberapa lembaga sosial, politik dan lembaga pemerintah terdapat pengaruh dari personal dari dayah. Misalnya, dominasi dayah di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Tuha Peut Wali Nanggroe, terdapat perwakilan di DPRA dan DPRK, Kanwil Kementerian Agama, Kantor Gubernur, menjadi birokrat di Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah, dan banyak alumni yang bergelar magister dan doktor yang berkecimpung di kampus seperti Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), UIN Ar-Raniry, Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Universitas Samudera (Unsam) Langsa, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, di kampus-kampus swasta seperti IAI Al-Aziziyah Samalanga Bireun, dan lain-lain.[20]
Aktor agama dari dayah menjadi kelompok besar saat ini di Aceh, setelah kelompok GAM mulai menurun eksistensinya. Sepuluh tahun ke depan, belum terindentifikasi kelompok lain di Aceh yang memiliki akar dan pengaruh seperti dayah saat ini. Kampus di Aceh dengan segala dinamikanya dan eksponen GAM dengan segala kelemahan dan romantismenya akan menjadi kelompok pendukung dalam organ pengendali Aceh.
Aktor dayah di Aceh dapat dilihat dalam beragam perspektif. Mulai dari hal relegius, sejarah kebudayaan, pertahanan keamanan, politik elektoral, perdamaian, perekonomian sampai dengan potensi dayah menjadi pengendali Aceh masa depan. Kenapa dayah bisa dilihat dalam beragam pandangan. Karena dayah sebagai sebuah organisasi (organ) yang mengakar dalam tradisi masyarakat Aceh. Sejak masa klasik terus berkembang pada abad 17-20, sampai dengan era revolusi industri 4.0 saat ini, dayah beserta instrumennya tidak pernah absen memainkan kontestasinya dalam setiap perjalanan keagamaan dan sosial politik di Aceh. Tidak ada alasan untuk tidak menyebutkan dayah dalam melihat masa depan Aceh. Transformasi dayah kontemporer di Aceh menjadikan kepemimpinannya sebagai alat dalam perluasan otoritas (outrech authority). Pelan-pelan, organ dayah menjadi orang-orang yang mempengaruhi setiap kontestasi keagamaan di Aceh.
Namun demikian, secara geneologi keberadaan dayah di Aceh, esensinya bukan lagi berbasis pada gerakan politik. Tapi geneologi dayah di Aceh saat ini, dominan berakar dengan filosofi beut dan seumeubeut (belajar dan mengajar). Filosofi ini pula yang sekarang diwarisi oleh Dayah MUDI Mesra Samalanga, melalui Abon Aziz dan Abu Mudi. Jadi, secara umum, dayah di Aceh fokus sebagai basis organisasi pendidikan dan dakwah, makanya menghasilkan alumni yang berkontribusi pada institusi vertikal maupun horizontal di Aceh dan Sumatera Utara.[21]
Kemampuan dayah dalam melahirkan pemimpin telah teruji, dayah di Aceh bukan sebatas agent of change (agen perubahan), tetapi sudah menjadi agent of modernization (agen pembaruan). Manifestasi nilai-nilai dayah untuk masa depan sangat menentukan situasi politik dan sosial keagamaan di Aceh.
Terlepas upaya progresif yang mulai dilakukan aktor dayah di Aceh. Secara umum, terdapat kontestasi dalam merebut otoritas keberagaman di Aceh. Seperti misalnya kontestasi jaringan dayah. Munculnya jaringan dayah baru di Aceh, seperti “Al Aziziyah”, “Mudawaliyah” “Darussaadah” “Muhammadiyah” dalam beberapa bagian di Aceh menjadi korban dalam kontestasi beragama. Akibatnya kemaslahatan beragama menjadi terganggu akibat adanya kontestasi sunyi ini.
Kontestasi aktor agama yang terjadi saat ini, terjadi karena ruang politik di Aceh yang sangat terbuka. Perebutan pengaruh dalam berbagai perspektif, mendorong aktor agama di Aceh ikut serta di dalamnya. Dalam konteks ini, upaya pelaksanaan syariat Islam terkadang menjadi dalil dari upaya kontestasi elit agama. Beberapa kejadian, imbas dari kontestasi mengarah kepada intoleransi dalam beragama. Seperti terjadi di Sangso Samalanga Bireun. Seharusnya elit agama harus bersinergi menyelesaikan setiap kemelut dengan kebijaksanaan. Supaya kontestasi dalam beragama tetap dijalankan dengan rasional. Elit agama di Aceh harus meninggalkan labeling kepada kelompok tertentu di Aceh. Supaya agama menjadi rahmat bagi pemeluknya.
DIBALIK KONTESTASI
Hakikat MoU Helsinki adaah membuka ruang bagi semua aktor di Aceh, untuk dapat terlibat memberi berkontribusi bagi kemajuan peradaban Aceh. Apalagi Aceh saat ini menjadi daerah termiskin di Sumatera. MoU Helsinki antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) harus menjadi “pelajaran” bersama yang harus disyukuri. Karena esensi perdamaian Aceh adalah dapat membawa masyarakat hidup dalam suasana tenang dan saling menghargai dalam perbedaan.
Ditengah harapan mengisi perdamaian, selalu muncul kontestasi. Dibalik kontestasi aktor di Aceh, selalu berujung pada perebutan sumber daya ekonomi. Akibatnya, rasa nasionalisme Aceh menipis dari generasi baru. Karena genarasi baru melihat aktor-aktor Aceh selalu dikendalikan, bukan mengendalikan.
Namun, dibalik kontestasi selalu tersemai harapan, supaya Aceh selalu menjadikan “damai” sebagai “jalan hidup” semua aktor di Aceh. Artinya membangun ruang-ruang diskursus perdamaian tidak boleh stagnan. Paul Collier, Anke Hoeffler and Mans Soderbom mengungkapkan bahwa masyarakat pascakonflik selalu menghadapi dua tantangan yang berbeda, yaitu pemulihan ekonomi dan pengurangan risiko.[22]
Begitu juga dengan Zulfan Tadjoeddin yang mengemukakan bahwa setidaknya terdapat enam resiko pascakonflik di sebuah wilayah, seperti Aceh, yaitu: (1) Pengangguran; (2) Distribusi pembangunan yang tidak merata; (3) Pengelolaan sumber daya alam yang didominasi oleh pemain baru; (4) Kontrak sosial; (5) Transformasi sosial; dan (6) Biaya yang tinggi untuk kelas baru.[23]
Situasi Aceh saat ini, dibalik kontestasi aktor lokal dalam setiap periode Aceh Paska MoU Helsinki, dapat dilihat dalam lima situasi: Pertama, penikmat damai. Orang Aceh kebanyakan menjadi penikmat damai walau kemiskinan menderanya. Penikmat damai tidak mengenal latar belakang, bisa saja mereka eksponen GAM, TNI/Polri, ASN, dan LSM. Semuanya menikmati hidup damai tanpa permusuhan, apalagi kembali ikut vertikal skala nasional.
Kedua, menghindari konflik horizontal. Fokus utama dalam potensi konflik ini adalah konflik etnik. Secara prinsip konflik etnis adalah perdebatan atau perselisihan antar kelompok etnis terkait dengan masalah politik, ekonomi, sosial budaya atau wilayah. Indikasi konflik ini juga dapat dilihat munculnya kaum terpelajar tapi miskin dari daerah tertentu di Aceh.
Ketiga, kekerasan rutin. Di Aceh dikenal dengan kekerasan rutin, di mana kekerasan rutin dapat digambarkan seperti kekerasan main hakim sendiri, kekerasan terkait dengan frustasi sosial, kekerasan akibat pengangguran, dan kekerasan disebabkan sosial ekonomi.
Keempat, konflik Pilkada/Pilpres. Pilkada/Pilpres telah menjadi kekerasan model baru yang selalu dialami oleh para kontestan ataupun para tim pemenangannya. Konflik Pilkada/Pilpres di Aceh masih bisa dikendalikan. Karena ruang tarungnya masih berada di area-area keramaian. Mendorong kebebasan masyarakat menentukan pilihan secara demokratis tanpa harus bermusuhan. Kontestasi politik harus diartikan sebagai kepentingan bersama untuk mencari yang terbaik.[24]
Kelima, konflik inter-agama di Aceh, indikasi konflik inter-agama (Islam) sudah mulai terjadi di Aceh. Berbarengan meningkatnya potensi konflik sesama penganut Islam, karena perbedaan amaliah mengarah kepada “meningkatnya” intoleransi di berbagai daerah di Aceh.
Persoalan perdamaian bukan saja mengakhiri konflik, tapi bagaimana perdamaian dapat membawa berkah dengan cara melibatkan diri dalam merawat dan membangun diskursus-diskursus baru untuk Aceh. Harus menjadi ingatan bersama bahwa kemunculan konflik gaya baru di Aceh bukan tidak musykil. Satu-satunya strategi menghindari konflik adalah dengan merekatnya para aktor lokal di Aceh.
Dalam kajian global, konflik etnis, kekerasan seperti terorisme, perang konvensional, epidemi, kecelakaan nuklir, senjata pemusnah massal dan kejahatan terorganisir, semuanya termasuk dalam daftar konflik yang berbahaya. Namun dari semua itu, situasi ekonomi dan pengangguran menjadi titik sentral terjadinya konflik yang menghambat kemakmuran manusia.[25]
Konflik dan damai bagian dari kehidupan masyarakat Aceh. Konflik atau kekerasan di Aceh sudah berlangsung lama, malah sebelum era kolonialisme. Dalam sejarahnya, sebelum 1873 level konflik dan damai Aceh itu bercitarasa internasional seperti berkonflik dengan Portugis, Inggris, Prancis serta bersahabat dengan Turki. Secara terus-menerus masyarakat Aceh sangat bangga membangun diskursus literasinya bahwa Kesultanan Aceh tidak pernah dijajah Belanda sebelum abad xx.
PENUTUP: KESADARAN KOLEKTIF
Kemunculan aktor-aktor lokal dalam konfigurasi perebutan kekuasan dalam berbagai konteks di Aceh, harus ditempatkan sebagai suatu yang tidak eksploitatif. Ini adalah tantangan bagi setiap aktor lain di Aceh untuk tampil humanis. Supaya setiap lahirnya suatu perbedaan, di respon dengan kemaslahatan. Ini penting dilakukan oleh para aktor lokal di Aceh dalam membangun kesadaran kolektif terhadap sebuah penderitaan, menuju kemenangan bersama-sama.
Aktor-aktor lokal di Aceh, harus menjaga keseimbangan atas segala pendapat dan pendapatannya. Supaya perdamaian Aceh benar-benar berkelanjutan. Paul Collier dalam penelitiannya telah mengingatkan bahwa 50 persen konflik bersenjata asimetris kembali kambuh setelah 5-10 tahun pascadamai.[26] Jadi secara esensial, walaupun perdamaian Aceh telah melewati pendapat Collier. Tetap perlu kewaspadaan munculnya konflik varian baru di Aceh. Peranan para aktor lokal di Aceh sangat diperlukan untuk saling bergandengan tangan; terutama antar aktor partai politik, antar aktor kombatan dan antar aktor agama.
Harapannya, Aceh kedepan, tidak hanya dikendalikan oleh aktor politik, aktor kombatan dan aktor agamawan, tapi semua aktor harus berperan dalam mengisi pembangunan Aceh. Pembangunan yang dilakukan bersama-sama, akan menjadikan energi baru bagi Aceh. Perbedaan cara pandang, sesama orang Aceh dalam mengisi pembangunan, tidak kemudian menyebutkan mereka sebagai pengkhianat. Tetapi harus disebut sebagi aktor-aktor yang memiliki niat baik untuk mengisi pembangunan Aceh. Sebagai bagian dari kesadaran kolektif para aktor lokal di Aceh.
Harus disadari bahwa perkembangan Aceh tidak saja diciptakan oleh aktor-aktor Aceh itu sendiri. Setidaknya terdapat juga kecenderungan adanya keberpihakan pihak lain pada kekuatan-kekuatan lokal di Aceh. Seharusnya, kekuatan-kekuatan elit lokal harus mampu menerjemahkan dukungan itu untuk membangun bersama-sama menuju perubahan Aceh. Kedepan, para elit di Aceh harus bergerat dengan kedaulatan dan kestimewaan yang dimilikinya, secara bersama-sama. Kentingan untuk sebuah perubahan lokal yang terus dilekatkan pada kedaulatan lokal, baik berbasis pada adat istiadat, agama maupun, kearifan lokal. Dengan demikian transformasi identitas keacehan yang diagendakan tidak keluar begitu saja dari aspek-aspek lokalitas keacehan.
Demikian beberapa uraian tentang kontestasi aktor lokal di Aceh. Tidak bisa juga dilupakan bahwa paska damai MoU Helsinki, proses kontestasi aktor lokal di Aceh sangat “ditentukan” juga oleh aktor militer dan aktor ekonomi. Karena Aceh selalu memiliki aura untuk diperebutkan.
[1] Otto Syamsuddin Ishak, 2013. Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme, Banda Aceh: Bandar Publishing. Hal 37
[2] Soemarsono Mestoko. 1988. Indonesia dan Hubungan Antar Bangsa, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 76
[3] Walter S.Jones, 1993. Terj. Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 182
[4] Cut Maya Aprita Sari dkk, “Imagined Community of Indonesia: Pertentangan Nasionalisme Indonesia Vs Etnonasionalisme Bangsa Aceh dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM)”. AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science. Hal 139
[5] Peter M. Leslie, “Ethnonasionalism in a Federal State: The Case of Canada” dalam Joseph R. Rudolph, Jr dan Robert J. Thompson, Ethnoterritorial Politics, Policy, and the Western World, (Boulder, Colorodao: Lynne Rienner Publishers, 1989), hal. 45-48.
[6] Peter M. Leslie. Hal. 181
[7] Wiratmadinata dan Bisma Yadhi Putra, 2016, Nasionalisme Vs Etnonasionalisme di Aceh. Banda Aceh: Bandar Publishing. Hal 64.
[8] Rothscild, Joseph. 1993, Ethnopolitics A Conceptual Framework. New York: Columbia University Press. Hal 21
[9] Wiratmadinata dan Bisma Yadhi Putra, 2016, Nasionalisme Vs Etnonasionalisme di Aceh. Banda Aceh: Bandar Publishing. Hal 46.
[10] Emirbayer dan Mische, What Is Agency?, The American Journal of Sociology, Vol. 103, No. 4. (Jan., 1998), pp. 962-1023.
[11] Jacques Bertrand, 2012. Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia. Yogyakarta; Ombak. Hal 262
[12] Ibnu Mujib, Irwan Abdullah, Heru Nugroho, “Gagasan Aceh Baru: Pembentukan Identitas Aceh dari dalam Reaktualisasi Ruang Publik bagi Aksi Pengelolaan Kearifan Lokal Pasca-Konflik dan Tsunami”. Jurnal Kawistara, Vol. 4, No. 1, April 2014: 49-62
[13] Cohen, Anthony. 2000. Discriminating Relation: Identity, Boundary, and Authenticity, in Cohen.A.P (ed) signifying Identity, Londong: Routladge. Hal 2-3.
[14] Mukhlisuddin Ilyas, Aceh Menuju 2017, Banda Aceh: Serambi Indonesia, Senin 27 Juli 2015. Hal 8.
[15] Bates, Robert H. 2001. Prosperity and Violence: The Political Economy of Development. W.W. Norton&Campany. Hal 63
[16] Huntington, 1973 (seventh printing). Political order in Changing Societies, New Haven and London: Yale University Press. Hal 7.
[17] Mac Ginty, R & A. Williams 2009. Conflict and Development, London & New York: Routledge (Introductory chapter). Hal 26
[18] Mukhlisuddin Ilyas, 2016. Aceh Tanpa Perekat, Serambi Indonesia, Kamis 29 Desember 2016. Hal 8
[19] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme diberi makna sebagai satu sikap ekstrem dalam aliran politik.
[20] Mukhlisuddin Ilyas, (2018), Dayah Masa Depan Aceh, Serambi Indonesia, Kamis 25 Oktober 2018. Halaman 8.
[21] Mukhlisuddin Ilyas, and Abdul Muin Sibuea. 2019. “Leadership Transformation: Study of Islamic Boarding School (Dayah) in Aceh Province of Indonesia” Journal of Entrepreneurship Education 22 (2): 1–5.
[22] Paul Collier, Anke Hoeffler and Mans Soderbom (2006), Post-Conflict Risks, Centre for the Study of African Economies, Department of Economics, University of Oxford. Hal 2.
[23] Tadjoeddin,Z. and M. Murshed (2007), ‘Socioeconomic Determinants of Everyday Violence in Indonesia: An Empirical Investigation of Javanese Districts, 1994-2003,’ Journal of Peace Research 44(6): 689-709.
[24] Mahfud MD, Sudah berkembang politik Identitas Serang Kelompok Lain tapi Klaim Penjaga Pridordial. Harian Kompas, 2 April 2019.
[25] Frances Stewart, (2004), Development and Security. Journal Conflict, Security & Development. Taylor & Francis. 2004. Volume 4. Issue 3. Page 261-288.
[26] Paul Collier, Anke Hoeffler and Mans Soderbom (2006), Post-Conflict Risks, Centre for the Study of African Economies, Department of Economics, University of Oxford. Hall 23.