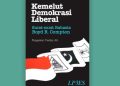Oleh: Asrul Sidiq*
Semenjak disahkannya Peraturan Daerah atau yang disebut di Aceh dengan Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS) nomor 11 tahun 2018, seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh termasuk bank dan non-bank, hingga seluruh transaksi keuangan di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
Di dalam Qanun ini juga diatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada setiap individu atau lembaga yang melanggar ketentuan tersebut. Sanksi ini dapat berlaku kepada setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melaksanakan transaksi keuangan di Aceh, orang yang beragama bukan Islam yang melakukan transaksi keuangan di Aceh, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah daerah di Aceh, LKS yang menjalankan usaha di Aceh, serta LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.
Paradoks
Dalam perjalanan penerapan Qanun ini, ketiadaan lembaga keuangan konvensional hanya berwujud simbol yang tampak di permukaan sebagai identitas, tanpa menyentuh esensi yang mendasar. Secara umum, saya melihat ada dua paradoks besar.
Paradoks pertama, kebijakan yang abai pada digitalisasi. Dalam Qanun LKS mengatur mengenai teknologi finansial (fintech) yang dapat beroperasi di Aceh harus sesuai dengan prinsip syariah, termasuk di dalamnya platform Peer to Peer (P2P), ziswaf, transfer, investasi, dan crowdfunding.
Digitalisasi lembaga keuangan baik itu syariah dan konvensional membuat segala sesuatunya baik dari buka rekening, transaksi, pinjam, deposito, hingga berbagai macam instrumen investasi bisa dilakukan secara online. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah melarang logo konvensional di tembok namun membiarkan akses melalui gawai merupakan kebijakan yang konsisten? Mungkinkah aturan ini dapat mengatur lembaga keuangan konvensional untuk tidak beroperasi di Aceh dalam ranah digital?
Secara nasional, digitalisasi telah membuat jumlah kantor cabang dan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terus berkurang. Sementara dalam konteks Aceh dengan literasi dan akses keuangan yang masih rendah membuat tantangannya menjadi lebih berat.
Paradoks kedua, aset perbankan (syariah) yang rendah di Aceh. Berdasarkan data Bank Indonesia, aset perbankan syariah di Aceh per Maret 2025 hanya sebesar Rp 61,3 triliun rupiah. Nominal tersebut hanya sekitar 6,4% dari total aset perbankan syariah di Indonesia.
Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh sepanjang tahun 2024 sejumlah Rp 243,2 triliun, maka rasio aset perbankan Aceh terhadap PDRB hanya sebesar 25,2%, jauh di bawah angka ideal. Secara nasional, rasio tersebut berada di angka sekitar 60% dan masih dirasa kurang, apalagi jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang sudah di atas 100%. Rendahnya rasio ini umumnya menunjukkan bahwa sektor perbankan belum maksimal dalam mendukung perekonomian.
Data menunjukkan masih kurangnya peran lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Aceh, yaitu sebagai penyedia modal dan memudahkan transaksi bagi lapangan usaha lainnya. Dalam rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi dalam PDRB triwulan I tahun 2025 hanya sekitar 1,63%, menurun dibandingkan data tahun 2019 yaitu sebesar 2,14%. Bahkan jauh di bawah rata-rata nasional di angka 4,25%.
Dengan rendahnya rasio-rasio tersebut, tentu menjadi pertanyaan bagaimana Aceh dapat bertahan dengan data yang mengkhawatirkan tersebut? Dari pengamatan di lapangan justru saya melihat “tau sama tau” bahwa banyak pihak baik itu individu bahkan lembaga publik yang melanggar aturan dalam Qanun ini dengan masih memiliki akun dan bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional.
Dikarenakan segala keterbatasan dan realita yang ada, maka terjadi pelanggaran terhadap sebuah aturan yang ada kata syariah dalam judulnya agar bisa selamat sebagai sebuah daerah. Bukankah ini mengarah ke arah kemunafikan kolektif yang dilegitimasi oleh institusi negara?
Aceh dengan kontribusi ekonominya terhadap Pulau Sumatra di angka 4,91% sedang mengisolasi diri dari sistem yang dianut secara global dan nasional. Disaat secara nasional dan global menganut dual banking system (konvensional dan syariah), lalu apakah mungkin ada daerah yang memilih single banking system (hanya syariah atau hanya konvensional) saja?
Uji coba pertama di dunia kebijakan seperti di Aceh ini seharusnya tidak dilakukan tanpa ada kajian mendalam. Kalau kita lihat Malaysia yang menjadi peringkat teratas selama sepuluh tahun berturut-turut negara dengan perkembangan ekonomi Islam terbaik di dunia tidak menerapkan single banking system. Bahkan Kelantan sebagai salah satu negara bagian di Malaysia yang menerapkan Syariat Islam juga tidak menerapkan kebijakan seperti ini.
Apakah di Makkah/Madinah hanya ada lembaga keuangan syariah berbeda dengan negaranya Arab Saudi yang menerapkan dual banking system? Sepengetahuan saya tidak. Apakah berbagai Universitas Islam di Indonesia dan dunia yang mengajarkan dan mengembangkan Ekonomi Islam melarang ada ATM atau fintech lembaga keuangan konvensional di dalam area kampusnya?
Masa Depan
Perbankan syariah memiliki keunggulan dari perbankan konvensional salah satunya terbukti dari ketahanan yang kuat dalam masa pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dengan peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan aset dari perbankan syariah.
Salah satu tujuan substansial dari penerapan Qanun LKS ini adalah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian yang islami serta peningkatan inklusi keuangan syariah. Namun, outcome nya dapat berbeda dengan tujuan utamanya jika berfokus hanya pada output berupa ketiadaan lembaga keuangan konvensional.
Revisi Qanun LKS diperlukan agar fokus pada tujuan substansial seperti peningkatan inklusi dan literasi serta penguatan lembaga keuangan syariah, bukan semata simbol ketiadaan bank konvensional. Syariah seharusnya hadir sebagai solusi, bukan sekadar “simbol”. Alih-alih “mengusir” sistem lain yang saat ini digunakan secara global dan nasional yang kita menjadi bagian di dalamnya, mari kita fokus pada “membangun” sesuatu yang bisa menjadi contoh dunia. Seperti Grameen Bank di Bangladesh misalnya, bisakah Aceh melahirkan model lembaga keuangan syariah yang diakui global? Sejarah akan mencatat pilihan kita hari ini. []
*Asrul Sidiq, mahasiswa PhD di Crawford School of Public Policy, The Australian National University