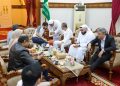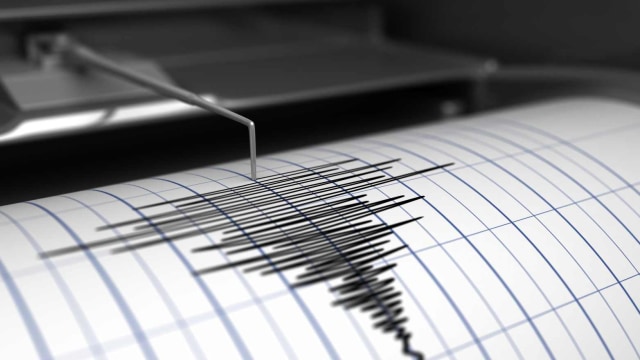Oleh: Ari Palawi
Beberapa waktu lalu, dalam sebuah percakapan daring yang singkat namun bermakna, saya bertanya kepada Mukhlisuddin Ilyas—seorang ilmuwan, kandidat guru besar, sekaligus pemikir yang konsisten bicara soal moral publik dan masa depan Aceh:
“Kira-kira isu apa lagi yang prioritas untuk kebaikan Aceh sekarang dan ke depan?”
Jawaban beliau hanya satu kalimat, namun menghentak dan dalam maknanya:
“Terlalu banyak masalah Aceh kita. Prioritasnya harus banyak orang bergerak memberi solusi setiap saat dan pejabat publik sadar itu.”
Di antara begitu banyak wacana yang berputar-putar pada siapa salah dan siapa lalai, kalimat ini justru meletakkan sorotan pada dua simpul utama:
- Banyaknya masalah yang tak selesai bukan karena kurangnya data atau wacana, tapi karena kurangnya “gerakan kolektif warga yang konsisten”, dan
- Lemahnya kesadaran pejabat publik terhadap kebutuhan mendesak akan solusi nyata, bukan hanya administrasi reaktif.
Kalimat itu bukan keluhan biasa. Ia adalah tamparan sunyi: bahwa Aceh tidak sedang kekurangan ide, proposal, atau regulasi. Yang kurang adalah “kemauan untuk terlibat, dari sebanyak mungkin pihak”, secara terus-menerus, lintas sektor, lintas generasi.
Kita sering menunggu “aktor besar” datang menyelesaikan segalanya: gubernur, bupati, anggota DPR, atau lembaga donor internasional. Namun sejarah membuktikan, peradaban dibangun oleh banyak tangan kecil yang bekerja dalam kesadaran bersama, bukan oleh satu-dua nama besar yang tampil di baliho.
Maka, ketika Mukhlisuddin Ilyas menekankan bahwa “harus banyak orang bergerak setiap saat”, ini bukan hanya seruan moral. Ini adalah rumus kultural. Tanpa gerakan dari banyak orang – petani, guru, ibu rumah tangga, pemuda desa, seniman jalanan, dosen, santri, dan buruh – Aceh akan terus berputar dalam siklus krisis dan ilusi solusi.
Yang menjadi soal hari ini adalah:
Apakah kita masih punya energi dan keberanian untuk “bergerak bersama”, bukan sekadar “mengomentari dari kejauhan?”
Dan lebih penting lagi:
“Apakah para pejabat publik masih bersedia membuka telinga dan hati untuk menyadari bahwa kekuasaan mereka tidak cukup berarti jika tidak seiring dengan gerakan warga yang hidup, kreatif, dan mandiri?”
Masalah Aceh: Bukan Satu, Tapi Berlapis dan Terstruktur
Aceh adalah salah satu provinsi dengan anggaran otonomi khusus terbesar di Indonesia. Namun paradoksnya, provinsi ini tetap mencatat angka kemiskinan tertinggi di Sumatera. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Aceh mencapai 14,23% pada Maret 2024—menurun tipis dari 14,45% pada Maret 2023. Di wilayah perdesaan, angka kemiskinan turun dari 16,92% menjadi 16,75%, sementara di perkotaan dari 9,79% menjadi 9,60%. Penurunan ini patut dicatat, namun tetap belum cukup untuk mengubah posisi Aceh yang secara nasional masih berada di urutan kedua dalam hal jumlah penduduk miskin. Itu berarti, lebih dari 800 ribu orang di Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Angka ini bukan sekadar statistik. Ia menyiratkan piring-piring kosong di meja makan, anak-anak yang harus putus sekolah, dan ibu-ibu yang memikul beban ganda antara dapur dan ladang. Sering kali kita dengar bahwa anggaran Aceh “besar”, tetapi jika besarnya anggaran tidak berbanding lurus dengan keadilan distribusi, transparansi pelaksanaan, dan keberpihakan pada yang paling membutuhkan, maka besar itu justru menjadi sumber luka kolektif—luka yang diam-diam diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Di bidang pendidikan, tantangan tak kalah serius hadir dalam bentuk yang tak selalu tampak: kekerasan psikososial di ruang belajar. Hasil Asesmen Nasional 2022 menunjukkan bahwa sekitar sepertiga peserta didik di Aceh—lebih dari 30%—mengalami risiko perundungan (bullying). Ini bukan angka kecil. Ini berarti bahwa di setiap tiga anak yang duduk di bangku sekolah, setidaknya satu di antaranya berpotensi menjadi korban kekerasan verbal, sosial, bahkan fisik.
Risiko ini tak hanya merusak kenyamanan belajar, tapi juga menggerus rasa aman yang seharusnya menjadi fondasi dunia pendidikan. Dalam jangka panjang, perundungan dapat melukai keberanian untuk berpikir kritis, menghambat partisipasi aktif, bahkan memicu putus sekolah. Maka, memperbaiki kualitas pendidikan di Aceh tak cukup hanya dengan membangun infrastruktur atau menambah anggaran. Iia juga mensyaratkan perubahan budaya relasi di sekolah: dari hierarkis ke partisipatif, dari represif ke suportif.
“Lalu, bagaimana kita bisa membayangkan masa depan Aceh yang lebih cerdas, jika hari ini saja anak-anak kita belajar dalam ketakutan dan luka psikis?”
Sementara itu, kerusakan lingkungan menambah lapisan krisis yang mengancam masa depan Aceh. Tahun 2023 mencatat hilangnya tutupan hutan seluas 8.906 hektar, dan dari jumlah itu, 4.854 hektar berada di jantung Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)—salah satu paru-paru dunia yang tak tergantikan. Ini bukan sekadar statistik ekologis; ini adalah peringatan keras bahwa keserakahan telah mengalahkan akal sehat, bahwa kebijakan konservasi kerap kali dikompromikan demi kepentingan jangka pendek dan keuntungan segelintir pihak.
Dan jangan lupakan bahwa hutan-hutan itu bukan hanya habitat gajah, harimau, atau orangutan. Ia juga rumah bagi masyarakat adat yang hidup dalam harmoni dengan alam, sumber air bersih yang mengalir ke sawah dan rumah-rumah, serta benteng terakhir dari bencana ekologis yang sewaktu-waktu bisa meluluhlantakkan desa-desa. Ketika hutan ditebang, yang hilang bukan hanya pepohonan, tapi juga masa depan, identitas, dan ketahanan hidup komunitas di akar rumput.
Dalam aspek tata kelola, kita berhadapan dengan persoalan korupsi yang sistemik dan mengakar. Antara tahun 2021 dan 2022, tercatat 27 kasus tindak pidana korupsi di Aceh, dengan 44,4% pelakunya berasal dari aparatur sipil negara. Ini mencerminkan sebuah ironi yang menyakitkan: sebagian dari mereka yang seharusnya menjadi penjaga kepercayaan publik justru menjadi bagian dari penyakit itu sendiri. Lebih memilukan lagi, kinerja penegakan hukum pun masih jauh dari harapan—pada tahun 2021, hanya 20% dari target kasus korupsi yang berhasil dituntaskan oleh kepolisian. Ketika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, kepercayaan publik pelan-pelan terkikis, dan demokrasi hanya tinggal nama.
“Apa arti semua ini?”
Artinya, masalah Aceh tidak berdiri sendiri. Mereka saling menopang dalam jaring krisis yang terstruktur: kemiskinan yang dipelihara oleh korupsi, pendidikan yang tercederai oleh kekerasan simbolik dan struktural, ekologi yang dihancurkan demi proyek sesaat, serta tata kelola yang lumpuh oleh kompromi kepentingan.
Jika semua ini adalah lapisan-lapisan luka, maka solusi tak cukup dengan perban temporer. Kita membutuhkan pemulihan yang menyeluruh, sistemik, dan berkelanjutan. Dan untuk itu, kita butuh lebih dari sekadar satu orang baik di pemerintahan. Kita butuh banyak orang yang sadar, bergerak, dan bersuara—di kampung, di kampus, di masjid, di kafe, di media sosial, dan di ruang-ruang diskusi yang hidup.
Pertanyaannya kini adalah:
“Berapa banyak dari kita yang masih percaya bahwa Aceh bisa berubah—jika kita tidak lagi menyerah?”
Gerakan Solusi: Bukan Elite Saja, Tapi Banyak Orang
Dalam banyak peristiwa sejarah Aceh, solusi sering lahir bukan dari atas, tetapi dari bawah. Komunitas adat yang mengelola tanah ulayatnya secara mandiri, para seniman muda yang berkarya tanpa subsidi, kelompok pemuda yang mengarsipkan sejarah lokal, perempuan yang membentuk koperasi ekonomi berbasis syariah—semua ini adalah bukti bahwa “banyak orang” memang sedang bergerak, meski tidak selalu terdeteksi oleh radar kekuasaan atau headline berita utama.
Kita punya contoh konkret:
- Komunitas adat Mukim Kunyet di Aceh Besar, yang memprakarsai perlindungan kawasan hutan adat dan melakukan patroli rutin berbasis kearifan lokal.
- Gerakan Pustaka Jalanan di Banda Aceh dan Lhokseumawe, yang membuka akses literasi untuk anak-anak pinggiran kota dan desa-desa terpencil.
- Komunitas seperti Sejagat Rangkang Seni Jauhari dan Festival Panen Kopi Gayo, yang menghidupkan narasi kebudayaan di luar institusi resmi dan pasar kesenian.
- Inisiatif koperasi perempuan di Aceh Tamiang dan Pidie Jaya, yang menciptakan sirkulasi ekonomi mikro berbasis prinsip keadilan dan gotong royong.
Gerakan-gerakan ini sejatinya adalah oasis dalam gurun birokrasi, tetapi mereka kerap maju-mundur, bahkan kerap berumur pendek. Bukan karena mereka kurang ide atau semangat, melainkan karena kurangnya dukungan kebijakan, akses pembiayaan yang berkeadilan, atau bahkan represi simbolik yang memarjinalkan mereka sebagai “bukan bagian dari program resmi.”
Ini menciptakan paradoks besar! Rakyat bergerak, tapi negara tidak hadir dalam bentuk yang mendukung.
Akibatnya, yang kita saksikan adalah pulau-pulau inisiatif, bukan jaringan yang saling menopang. Banyak orang bergerak, tapi dalam isolasi. Banyak gagasan lahir, tapi tidak masuk ke sistem kebijakan. Banyak solusi bermunculan, tapi dipatahkan oleh logika proyek jangka pendek yang hanya menilai dari angka realisasi, bukan transformasi sosial.
Maka yang kita butuhkan bukan hanya “gerakan sporadis,” melainkan konsistensi, kolaborasi, dan pengakuan publik. Kita butuh ruang dan kebijakan yang memberi nafas panjang bagi inisiatif rakyat. Perluasan akses terhadap Dana Otonomi Khusus berbasis merit dan keberlanjutan gerakan akar rumput, misalnya, bisa menjadi langkah awal. Perlu audit bukan hanya terhadap angka pengeluaran, tetapi terhadap siapa yang diberi kesempatan berkontribusi.
Dalam dunia yang semakin digerakkan oleh jejaring, Aceh tak bisa terus-menerus mengandalkan elite dan struktur vertikal. Gerakan horizontal, yang kolaboratif, setara, dan lintas sektor, adalah nadi baru perubahan.
Kita bisa mulai dengan bertanya:
- Apakah lembaga pendidikan telah membuka ruang untuk inisiatif lokal?
- Apakah media massa memberi panggung yang cukup bagi suara komunitas akar rumput?
- Apakah pemerintah daerah menyalurkan anggaran berdasarkan kebutuhan nyata, bukan semata usulan atas dasar kedekatan?
Jika tidak, maka kita sedang gagal memanen apa yang sudah tumbuh di kebun rakyat.
Kesadaran Pejabat Publik: Dari Simbolik ke Etis
Frasa “pejabat publik sadar itu” menyentil kenyataan yang menyakitkan. Banyak pemimpin di Aceh sibuk membentuk citra daripada memperkuat struktur. Mereka lebih peka terhadap suara elite politik ketimbang suara warga kampung yang mencoba hidup dari hasil tani, kerajinan, atau kesenian. Gimmick lebih mudah viral ketimbang kerja senyap membenahi sistem irigasi, koperasi, atau kurikulum sekolah dasar.
Sementara itu, kehidupan nyata terus berjalan dengan luka-lukanya sendiri.
Menurut BPS, 60,24% penduduk miskin di Aceh tinggal di pedesaan. Artinya, problem utama tidak berada di kantor-kantor Dinas, tetapi di sawah, ladang, dan kampung pesisir. Namun, sejauh mana struktur pemerintahan benar-benar hadir di sana? Apakah pejabat pernah datang bukan sekadar untuk “kunjungan kerja,” melainkan untuk belajar dan menyerap aspirasi dengan rendah hati?
“Apa arti menjadi pejabat publik jika tak mau mendengar warganya sendiri?”
Tugas seorang pejabat bukan sekadar mengurus administrasi atau menjalankan program. Ia memikul tanggung jawab etis, untuk menjawab gerakan warga, bukan sekadar mengumumkan agenda dari balik meja.
Pejabat yang sadar adalah mereka yang bersedia mendengar, mau belajar, dan membuka diri terhadap partisipasi masyarakat. Bukan hanya datang saat peresmian, lalu pergi saat masalah mulai tampak. Bukan hanya memamerkan angka, tetapi menyelami kenyataan di lapangan.
Karena kepercayaan publik tidak dibangun dari baliho atau siaran pers, tapi dari keberanian melibatkan warga dalam proses yang jujur dan bermakna. Bukan karena rakyat tidak mengerti, tapi karena mereka terlalu sering tidak diajak bicara sejak awal.
Kesadaran publik itu tidak lahir dari rapat-rapat tertutup, tetapi dari pertemuan dengan kenyataan:
- Banjir yang tak kunjung selesai karena hutan gundul tapi izin terus dikeluarkan.
- Tambang yang meluas ke kawasan pangan dan adat, sementara rakyat dituduh menghambat pembangunan.
- Generasi muda yang perlahan kabur dari Aceh, karena kampung halaman tak lagi bisa memberi harapan kerja, ekspresi, dan penghidupan yang layak.
Jika pejabat hanya menjawab masalah dengan press release, bukan dengan kebijakan yang memihak pada kehidupan, maka kita akan terus terjebak dalam siklus simbol tanpa substansi.
Pejabat publik harus menyadari bahwa posisi mereka bukan pusat segala solusi, tapi simpul dari sistem yang harus melayani – bukan mengendalikan – inisiatif rakyat. Dan kesadaran semacam ini bukan produk pelatihan, melainkan hasil dari keberanian memelihara empati, mendekat ke realitas, dan menanggalkan ego struktural.
Dari Masalah ke Jalan Bersama
Masalah Aceh terlalu banyak, terlalu dalam, terlalu menahun. Tapi bukan berarti kita kehabisan harapan. Sebagaimana diskusi awal bersama ilmuwan di atas, yang konsisten menyuarakan moral publik. “Yang kita butuhkan bukan hanya solusi atas satu-dua isu, tapi banyak orang yang terus bergerak dan pejabat yang sadar diri”.
“Dan mungkin, di situlah letak pintu keluarnya”.
Bukan pada program yang penuh jargon, melainkan pada keterlibatan yang tulus. Bukan pada pencitraan, tapi pada kerja senyap yang terus menyala. Jika suara rakyat diberi ruang, jika inisiatif akar rumput tidak dianggap ancaman, dan jika pejabat lebih sibuk mendengar daripada menggenggam mikrofon, maka kita sedang menapaki jalan perubahan yang sesungguhnya.
Karena Aceh tidak hanya butuh kebijakan yang baik, tapi keberpihakan yang nyata. Tidak cukup dengan anggaran yang besar, jika tidak ada kejujuran dalam mengelolanya. Tidak cukup satu orang baik di pucuk, jika tak ada gerakan bersama dari akar.
“Mungkin inilah saatnya”:
Kita tidak lagi bertanya apa prioritas Aceh, Tapi “siapa saja” yang mau terus bergerak!
“Dengan kepala jernih dan hati yang terjaga.” []
Penulis adalah Pendiri Geunta Seni Jauhari. Ia menulis, meneliti, dan mencipta karya yang menghubungkan penciptaan artistik, pengabdian budaya, dan kebijakan publik. Fokusnya banyak pada wilayah-wilayah non-sentral dan suara komunitas.