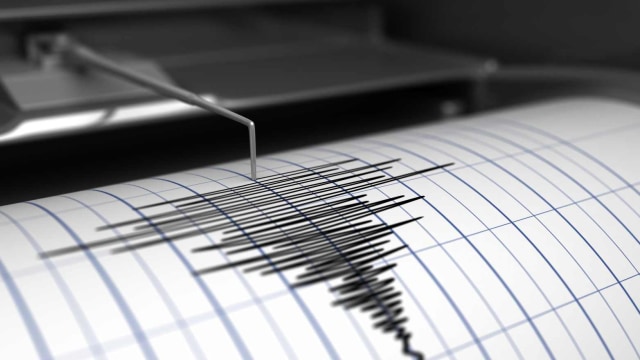Oleh: Risman Rachman.
Pemerhati Politik dan Pemerintahan di Aceh.
“Bek keu loen, neujok keu ureung laen mantong,” kata MM.
Melihat Teuku Raja Muda D-Bentara meminta seorang penulis untuk membubuhkan tanda tangan di bukunya, saya pun ikut memintanya.
Sebuah tanda tangan dengan tinta merah akhirnya melekat dihalaman cover dalam. Tanda tangan itu milik Mirza Ardi. Buku “Aceh 2024” ditulis oleh 18 orang, dan Muhammad Mirza Ardi menyuguhkan tulisan dengan judul “Demokrasi, Oligarki dan Politik Pengarusutamaan Kriteria.”
Mirza, usai mencermati politik kekinian Indonesia yang melahirkan calon cacat etik, langsung menggugat: Masih relevankan berimajinasi memiliki politik yang bermartabat?
Saya terdiam lama, hingga berhenti membaca lebih lanjut. Denyut nadi saya melemah, hingga harus menyulut sebatang rokok dan berbincang dengan kepulan asap yang lewat di depan mata.
Rasanya, rakyat dan kaum terdidik hanya bisa berimajinasi tentang demokrasi yang ideal. Selebihnya, imajinasi itu dijadikan retorika politik oleh mereka yang disebut oleh Mirza sebagai komplotan orang kaya, yang pada masa lalu sukses memanen kekayaan dari kuasa otoriter.
Saya berhenti lagi membaca seraya membayangkan rakyat yang bebas memilih. Tapi, yang dipilihnya sudah ditentukan baik oleh partai maupun oleh partai lewat suatu proses yang mencederai nilai-nilai.
Jika ada yang berkata, kita memang bebas memilih, memilih untuk diterkam harimau, atau diterkam oleh serigala. Sebab, itulah pilihan yang ada.
Akhirnya Mirza Ardi menyimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia berbasis uang, dan massa. Inilah pemandangan yang sedang kita lihat.
Uang itu di wilayah yang massanya ramai, yaitu Jawa (konsep 50 persen plus 1) menari-nari dengan terang, bahkan hingga dilakonkan oleh tokoh agama yang dulunya mengecam politik uang.
Karena politik kita tidak menganut kemenangan di 2/3 wilayah Indonesia, maka di Aceh uang tidak ditebar, tapi diganti dengan tebaran isu-isu yang berpotensi membelah massa menjadi kumpulan-kumpulan.
Misalnya, mereka yang mendukung pengusiran pengungsi Rohingya akan memilih si B karena si A menerima pengungsi dan si C tidak becus memindahkan pengungsi.
Sementara di Jawa dengan pemilih yang berpuluh-puluh juta, yang sudah terbiasa dengan politik orang kaya, saling bernegosiasi dengan retorika kelompok, nasab, identitas dan lain-lainnya.
Maka, masing-masing berlomba memperlihatkan kegembiraan mereka lewat berbagai cara, ada konser nyanyi, konser selawatan, hingga tarian gemoy ala Pilpres Filipina.
Kita? Dengan isu yang tajam menukit, harus menjaga pantai, menggelar demo, memvisualkan penolakan, dan akhirnya meudakwa bak warong hingga bak live tiktok troeh jelang suboh (saling berdebat di warung kopi sampai live di tiktok sampai subuh).
Di sela-sela itu, terdengar diksi kepentingan Aceh seraya hilang ingatan bahwa lawan bangsa Aceh adalah nanggroe penganiaya, bukan ureung teraniaya. []